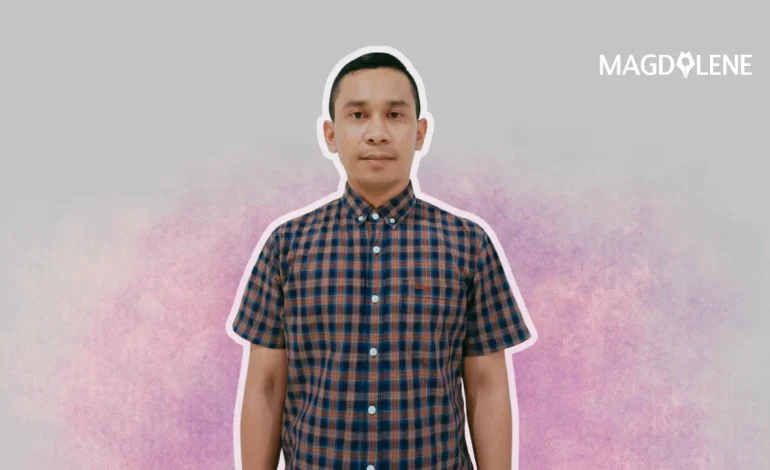Dilema Utang Kereta Whoosh: Kejar Kecepatan, Ancam Kedaulatan

Kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh menjadi proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dinarasikan sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia.
Pada Oktober 2023, Jokowi dengan bangga meresmikannya dan mengatakan bahwa Whoosh hadir sebagai bukti Indonesia mampu bersaing dalam teknologi transportasi modern.
Namun, di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, masalah Whoosh mulai bermunculan, terutama terkait pembayaran utang ke Cina yang mencapai US$ 7,27 miliar atau Rp110-113 triliun).
Problematika ini mencerminkan realita bahwa kecepatan yang ditawarkan Whoosh telah menyebabkan ketergantungan baru dalam sistem ekonomi global, alih-alih mencerminkan kemajuan teknologi nasional.
Baca Juga: #TanahAirKrisisAir: Proyek ‘Beach Club’ Raffi Ahmad, Bukti Abainya Pemerintah pada Lingkungan
Tumpukan Utang di Balik Modernitas
Proyek Whoosh memang mengesankan. Dengan kecepatan mencapai 350 kilometer per jam, ia menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara—hasil kerja sama perusahaan Indonesia dan Cina.

Namun, secara ekonomi, proyek ini menghadirkan paradoks yang sulit diabaikan. Biaya yang semula diperkirakan sekitar $6 miliar (Rp99,4 triliun) kini melonjak hingga lebih dari $7,3 miliar (Rp120,9 triliun).
Pemerintah pun harus melakukan negosiasi ulang dengan Cina, yang diwakili oleh China Development Bank dan sejumlah perusahaan milik negara dalam konsorsium proyek Whoosh, untuk menyesuaikan skema utang yang kian membebani keuangan proyek.
Fakta ini memperlihatkan bahwa proyek infrastruktur besar tidak hanya mencakup teknologi dan konektivitas, melainkan juga relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan arah politik pembangunan.
Selama dua tahun beroperasi, Whoosh mencatatkan angka penumpang yang cukup tinggi, lebih dari 12 juta penumpang hingga Oktober 2025. Rekor hariannya mencapai 26 ribu penumpang.
Capaian ini patut diapresiasi sebagai kemajuan nyata dalam sistem transportasi nasional. Namun, angka tersebut ternyata belum cukup untuk menutupi beban finansial yang ditimbulkan.
Pendapatan dari tiket belum sebanding dengan biaya operasional dan pembayaran bunga utang.
Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini berpotensi menjadi beban bagi keuangan publik, apalagi jika tidak disertai perencanaan ekonomi yang matang.
Ketika proyek besar semacam Whoosh menghadapi tekanan finansial, lagi-lagi rakyat yang kemungkinan besar akan menanggung konsekuensinya.
Baca Juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Tak Penuhi Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Ketergantungan Global
Pembangunan seperti Whoosh tidak berlangsung di ruang yang netral, tetapi merupakan hasil dari proses negosiasi antara kebutuhan domestik dan kepentingan global.

Dalam dunia yang semakin terhubung, kerja sama ekonomi lintas negara menjadi hal yang tak terelakkan, tetapi hubungan tersebut jarang bersifat setara.
Modal, teknologi, dan keahlian sering kali datang dari pusat kekuatan ekonomi, sementara negara berkembang menyediakan pasar, sumber daya, dan ruang ekspansi.
Kemitraan untuk pembangunan kadang tampak sebagai kolaborasi, tetapi pada dasarnya menciptakan struktur ketergantungan yang baru.
Indonesia tentu membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap modal dan teknologi eksternal dapat melemahkan kemandirian nasional dalam jangka panjang.
Ketika kemampuan produksi domestik tidak dikembangkan secara bersamaan, kemajuan yang tercipta hanya bersifat simbolik seolah cepat di permukaan, padahal fondasinya rapuh.
Pembangunan sejati seharusnya menciptakan kapasitas baru, kemampuan suatu negara untuk merancang, mengelola, dan memperluas teknologi sendiri tanpa harus terus bergantung pada pihak luar.
Ujian bagi Kedaulatan Indonesia
Proyek Whoosh seharusnya dibaca bukan hanya sebagai simbol kemajuan, tetapi juga sebagai ujian bagi kemampuan Indonesia menegosiasikan kedaulatannya.

Pemerintah memiliki peluang untuk menjadikan renegosiasi utang dengan Cina sebagai momentum memperkuat posisi strategis nasional. Langkah tersebut tidak semata soal menyesuaikan bunga pinjaman atau memperpanjang tenor, tetapi juga memastikan adanya transfer teknologi, pelibatan industri lokal, serta pengawasan publik yang lebih transparan.
Tanpa upaya itu, Whoosh berisiko menjadi proyek yang hanya memperindah citra tanpa memperkuat kapasitas nasional.
Dalam jangka panjang, keberlanjutan proyek ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan negara mengelola relasi internasionalnya secara cerdas dan berdaulat.
Pada dasarnya, infrastruktur selalu memiliki dimensi politik. Ia menentukan arah distribusi sumber daya, prioritas pembangunan, dan relasi antara negara serta masyarakatnya.
Kebanggaan terhadap pembangunan yang tidak disertai refleksi kritis bisa berbahaya, banyak risiko ekonomi dan sosial yang akan muncul, termasuk menumpuknya utang negara.
Dua Mata Pisau Modernitas
Modernitas selalu datang dengan wajah ganda. Di satu sisi, ia membuka peluang bagi inovasi dan pertumbuhan. Di sisi lain, ia menuntut penyesuaian terhadap struktur global yang sering kali tidak adil.

Kereta cepat Whoosh mencerminkan dilema ini. Ia melambangkan tekad Indonesia untuk maju, tetapi juga mengingatkan bahwa kemajuan sejati tidak dapat dibeli hanya dengan kecepatan dan investasi asing.
Kemajuan sejati menuntut kemampuan untuk menentukan arah, bukan sekadar mengikuti arus. Whoosh bukan sekadar kisah tentang transportasi, melainkan juga tentang kedaulatan. Ia mengajarkan bahwa pembangunan yang hanya mengejar kecepatan tanpa arah akan kehilangan makna.
Tugas besar Indonesia hari ini bukan hanya memastikan keretanya berjalan, tetapi memastikan bahwa bangsa ini benar-benar mengendalikan ke mana rel sejarahnya mengarah.
Aniello Iannone, Indonesianists | Research Fellow at the research centre Geopolitica.info | Lecturer, Universitas Diponegoro.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.