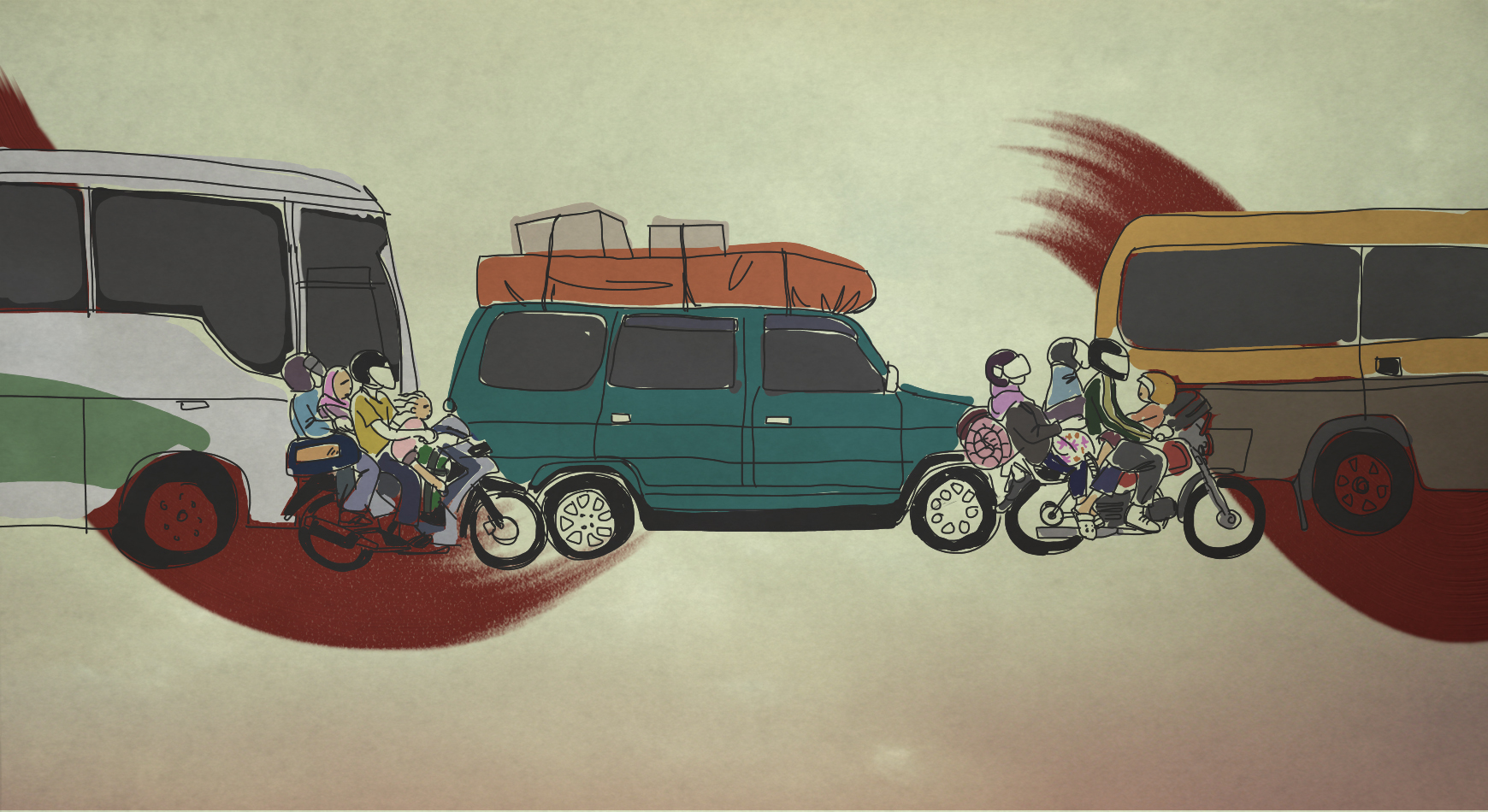Bukan Cuma Negara yang Homofobik, Media juga
Apa yang bisa dilakukan ketika media massa membombardir kita dengan berita-berita tak inklusif soal LGBT?
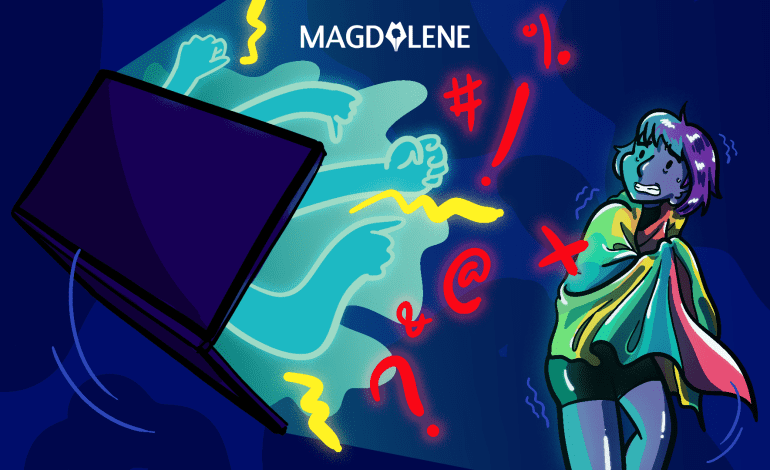
Bukan saya satu-satunya orang yang marah saat media kaliber Kumparan merilis Liputan Khusus (Lipsus) bertajuk “Jalan Tobat LGBT”. (27/3). Seorang kawan yang dulu sama-sama di pers mahasiswa ikut misuh-misuh. Kok bisa ya media yang semangat awalnya tampak progresif, mendadak layu dan merilis artikel macam ini? Ruang redaksi kami ribut, komentarnya sama: Kecewa.
Ada dua artikel yang mereka buat di Lipsus tersebut. Pertama menceritakan kisah pertobatan beberapa kawan LGBT menjadi heteroseksual. Ya betul, diksi “pertobatan” sengaja dipilih jurnalis Kumparan untuk menunjukkan bahwa kawan-kawan LGBT telah sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan itu—persis sesuai definisi tobat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Di antara narasumber yang diwawancara adalah orang-orang yang mengaku sudah kembali ke jalan yang benar, jalan heteroseksual. Cerita pergumulan batin dan pertemuan mereka dengan orang yang “menyadarkan” ini diurai, lengkap dengan apa yang mereka klaim sebagai keberhasilan, seperti menikah dengan lawan jenis, punya anak, ketenangan hati, kelegaan bisa lepas dari era kegelapan menuju aufklarung.
Artikel kedua memuat tentang betapa waswasnya orang tua di Indonesia dengan propaganda LGBT di berbagai produk budaya populer, dari film, serial TV, juga konten-konten di media sosial. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dikutip pendapatnya soal larangan LGBT, “Saya tidak pernah melihat ayam jago kawin sama ayam jago.” Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah menegur beberapa tontonan, buku ajar yang menurut hemat mereka mempromosikan LGBT.
Celaka dua belas, Kumparan bukan media tunggal yang membuat angle berita macam ini. Jika mencari dengan kata kunci “LGBT” di Google, akan diperoleh sejumlah hasil pemberitaan bernada serupa. Tak cuma tercermin dari judul, narasumber, data yang dikutip, hingga gambar pendukung pun entah sengaja atau tak sengaja, dipilih untuk mendukung angle tersebut.
Baca juga: Kepanikan Moral dan Persekusi atas Minoritas Seksual di Indonesia
Dalam hal ini saya harus mengamini analisis Eduard Lazarus Tjiadarma di Remotivi. Dalam artikelnya bertajuk “Kepanikan Moral di Balik Perbincangan tentang LGBT” (2016), ia bilang, media-media termasuk Republika, kerap pakai gambar ilustrasi orang yang ramai-ramai mengangkat panji pelangi. Bahkan untuk isi pemberitaan yang tak sesuai sekalipun. Seperti sopir taksi yang mengantar penumpang gay atau pendapat tokoh politik tentang LGBT. Seolah ingin mendudukkan LGBT sebagai sebuah gerakan. Bahaya. Meresahkan.
Sekarang mari kita lihat pemberitaan di Republika. Beberapa kali ia bikin artikel tentang LGBT, seperti “LGBT yang Makin Meresahkan”, “Tolak Segala Kampanye LGBT di Indonesia, ICMI: Penyakit Sosial Membahayakan”, “Di Hadapan Ormas Islam, Ketua MUI Dorong Hukuman Berat untuk Pelaku LGBT”, “Awas, Lagu Kerispatih ini Ternyata Lagu Gay”, “KPAI Punya Instrumen untuk Cegah Promosi LGBT”, hingga “Melonjak, Penularan HIV/ AIDS pada LGBT di Indonesia”.
Radar Bogor menulis “Waspada! LGBT Masuk Pelosok Desa di Kabupaten Bogor, Ini Buktinya”, “LGBT Jadi Pemicu Banyak Janda Baru di Kota Bogor”, dan “39 Lokasi Sarang LGBT”.
Sementara, Tribunnews pakai judul, “LGBT Perbuatan Maksiat Paling Dibenci Allah, Ini Azab Pedih yang Pernah Ditimpakan”, “Enyahkan LGBT dari Bumi ABS-SBK, Nurnas: Revisi Perda Mendesak”, “Video Viral LGBT Pangku-pangkuan di Kafe Wow, Pemilik Sebut Warung Jadi Sarang Homo adalah Fitnah”, dan “Selain Kesehatan, Inilah 4 Bahaya LGBT Bagi Lingkungan, Masih Didukung?”
Maraknya pemberitaan dengan angle demikian bakal membuat kawan-kawan LGBT semakin rentan oleh diskriminasi dan represi. Kondisi ini diperburuk dengan berbagai kebijakan anti-LGBT dari negara, seperti yang kini tengah digodok di Garut dan Makassar. Pun, pernyataan tajam dari pejabat publik, pegiat pendidikan, serta pesohor lain, termasuk aktivis gerakan mahasiswa yang cenderung memusuhi keberadaan LGBT.
Kita tentu masih ingat beberapa pencekalan LGBT di kampus-kampus Indonesia. Atau kesulitan kelompok LGBT di Bogor dalam pemenuhan hajat paling dasar: Tinggal aman di kos yang mau menerima mereka, dan mengisi perut tanpa takut dipersekusi. Khususnya setelah Peraturan Daerah (Perda) Penyimpangan Seksual Kota Bogor diteken. Belum lagi kasus perundungan, kekerasan, dan pencerabutan hak lain yang menimpa LGBT hari-hari ini.
Merujuk pada catatan Arus Pelangi pada 2013, sebanyak 89,3 persen LGBT pernah mengalami kekerasan. Rinciannya, 46,3 persen mengalami kekerasan fisik, dan 26,3 persen dalam bentuk kekerasan ekonomi, tulis Tempo.
Berbagai dampak bahaya untuk kawan-kawan LGBT ini sayangnya tak menjadi perhatian negara, akademisi, bahkan fatalnya media. Padahal media berperan untuk memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas, mengutip Bill Kovach dan Rossentiels dalam “The Elements of Journalism” (2001). Alih-alih ajeg mempromosikan sentimen negatif terhadap kelompok LGBT yang notabene dipinggirkan di Indonesia.
Baca juga: Al-Qur’an Tak Ajarkan Membenci Kelompok LGBT: Akademisi Muslim
Kenapa Media Tunjukkan Wajah Homofobia?
Yang dilakukan oleh sejumlah media di atas bisa dikategorikan sebagai politik homofobia. Antropolog Universitas California Tom Boellstorff dalam tulisannya berjudul “The emergence of political homophobia in Indonesia: masculinity and national belonging” (2016) yang dikutip Muhammad Ammar Hidayahtulloh di The Conversation menjelaskan soal ini. Politik homofobia didefinisikan sebagai logika budaya baru yang menghubungkan antara kelompok LGBT di ruang publik dan ancaman mereka terhadap norma maskulinitas dan masa depan bangsa. Logika inilah yang belakangan dipakai sebagai alat gebuk LGBT yang berupaya merebut ruang publik.
Pertanyaannya, kenapa media yang notabene diisi oleh orang-orang yang terliterasi tapi justru menulis liputan macam ini?
Sebenarnya ada beberapa faktor penyebab. Pertama, kita tahu media adalah sebuah bangunan besar dengan sistem yang dibuat dan dikontrol oleh pemilik modal, biasanya oligark yang juga punya bisnis lainnya. Hary Tanoe dengan kerajaan MNC Group, Surya Paloh dengan Media Group, atau Aburizal Bakrie dengan Bakrie Group misalnya. Kalau pun ada media yang didirikan dengan semangat pembaharuan atau progresifitas, ujung-ujungnya bakal tergulung persaingan, sehingga bisa saja menerima suntikan modal dari oligark.
Dampak ketika media dikuasai oligark yang isi kepalanya soal mengejar profit, adalah berita-berita yang dihasilkan akan cenderung bias, partisan, dangkal, dan tak berkualitas. Atas nama cuan juga, media bakal menyulap artikelnya agar lebih sensasional, clickbait, dan laris manis di pasaran. Ini senada dengan tesis Vincent Mosco dalam bukunya “The Political Economy of Communication” (1996). Ia bilang, media melakukan praktik komodifikasi atau transformasi hubungan, dari yang mulanya bebas dari hal-hal yang bisa diperjualbelikan, menjadi hubungan yang murni komersial. Baik komodifikasi konten, khalayak, maupun pekerja.
Komodifikasi konten misalnya dilakukan dengan membuat judul-judul berita tentang LGBT dengan bingkai sensasional, menghakimi, dan bersentimen negatif. Lihat saja judul-judul berita di atas.
Baca juga: Sejarah Gerakan dan Perjuangan Hak-hak LGBT di Indonesia
Nyatanya, hal ini sudah pernah dikuliti oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), dan organisasi non-pemerintah yang membela hak kelompok LGBT, Arus Pelangi. Dari 113 berita media lokal dan nasional sepanjang Januari dan Februari 2023, 100 di antaranya tak berperspektif gender, lima netral, dan cuma delapan yang punya perspektif gender, demikian dilansir dari laman AJI.
Media yang didata tiga organisasi itu pun kerap mengutip pernyataan diskriminatif dari tokoh organisasi massa sebanyak 35 kali, 31 anggota DPRD, 25 kali wali kota, bupati, dan wakil bupati, serta 16 kali kepala dinas dan kepala bidang. Penggunaan narasumber otoritatif ini membenarkan tesis Peter Vanderwicken dalam “Why the News is Not The Truth” (1995) yang terbit di Harvard Business Review. Bahwa jurnalis dan otoritas terperangkap dalam jaringan kebohongan yang menyesatkan publik. Di satu sisi jurnalis perlu mendramatisasi berita, sedangkan otoritas harus terlihat seperti merespons krisis, kendati kadang-kadang krisis bisa saja direkayasa. Kali ini krisis itu bernama LGBT.
Kedua, ini terkait minimnya perspektif gender dan inklusivitas di ruang redaksi. Ini sekaligus menjawab kenapa wartawan masih senang menggunakan diksi yang cenderung menggiring publik pada kebencian terhadap kelompok LGBT, seperti “penyakit sosial”, “meresahkan”, “bahaya”, “menyimpang”. Boro-boro repot memikirkan apakah berita yang dibuat justru melanggengkan stereotip atau tidak, wartawan bekerja berdasarkan logika mencari cuan.
Masalahnya, di ekosistem media yang mengejar klik saat ini, wartawan jadi tak punya banyak pilihan untuk melawan. Jadi jika kamu bertanya kenapa Lipsus Kumparan bisa lolos tayang, kenapa berita tentang kota janda, atlet perempuan cantik, mayat cantik bisa terbit, semua karena wartawan tak punya posisi tawar di media besar, khususnya yang dikuasai oligark.
“Bisa jadi wartawan-wartawan di redaksi ini paham perspektif gender. Mereka sadar dirinya salah ketika buat peliputan yang menyudutkan kelompok minoritas, tapi atas nama profit perusahaan media, wartawan pun tak bisa berkutik,” tutur Mustaqim, wartawan Kompas TV dalam liputan Magdalene sebelumnya.
Jika Media Besar Tak Mau Berubah, Kita Harus Apa?
Sejumlah media independen sebenarnya sudah menyadari problem ini, dan silih berganti berusaha menghadirkan konten jurnalisme yang berkualitas, alih-alih stereotipikal. Mereka berupaya mengubah pola pikir saat mendekati pemodal bahwa angka bukan indikator tunggal, ada yang namanya kualitas dan kedalaman berita misalnya. Berita-berita inklusif pun ditulis dengan harapan itu bakal memberikan dampak lebih baik, khususnya buat kelompok minoritas.
Langkah ini perlu diapresiasi karena tak banyak media yang sadar untuk melakukannya. Pun, untuk berjuang di jalan ini, butuh energi relatif besar buat media-media kecil alternatif. Sebab, biasanya para pemodal sudah punya target yang semuanya diukur dengan angka dan jangka waktu tertentu. Biasanya diskursus dampak tak cukup kuat meyakinkan pemodal untuk memberikan dana. karena itulah, yang bisa dilakukan media alternatif kini adalah menjaga konsistensi dan berkolaborasi agar semakin kuat.
Sementara buat publik, yang harus dilakukan adalah meliterasi diri. Mengingat sejauh ini sentimen negatif dan homofobia, selain dipromosikan media, juga diamplifikasi dalam percakapan di media sosial oleh warganet. Misalnya, jika kamu iseng cek komentar warganet, maka diksi-diksi stereotipikal akan sangat mudah ditemukan. Dalam postingan Lipsus Kumparan di Instagram misalnya, sejumlah orang masih berkomentar bahwa LGBT adalah penyakit, gangguan jiwa, disuruh bertobat menjadi lelaki atau perempuan seutuhnya, didoakan dapat hidayah, dan lainnya.
Karena itulah, selemah-lemahnya iman, yang bisa kita lakukan ketika menyaksikan parade kebodohan di mana berita-berita tak inklusif, adalah berhenti membacanya. Berhenti mengeklik. Dengan begitu, kita sudah andil dalam cara paling sederhana, untuk tak mereporduksi sentimen negatif terhadap kelompok LGBT.