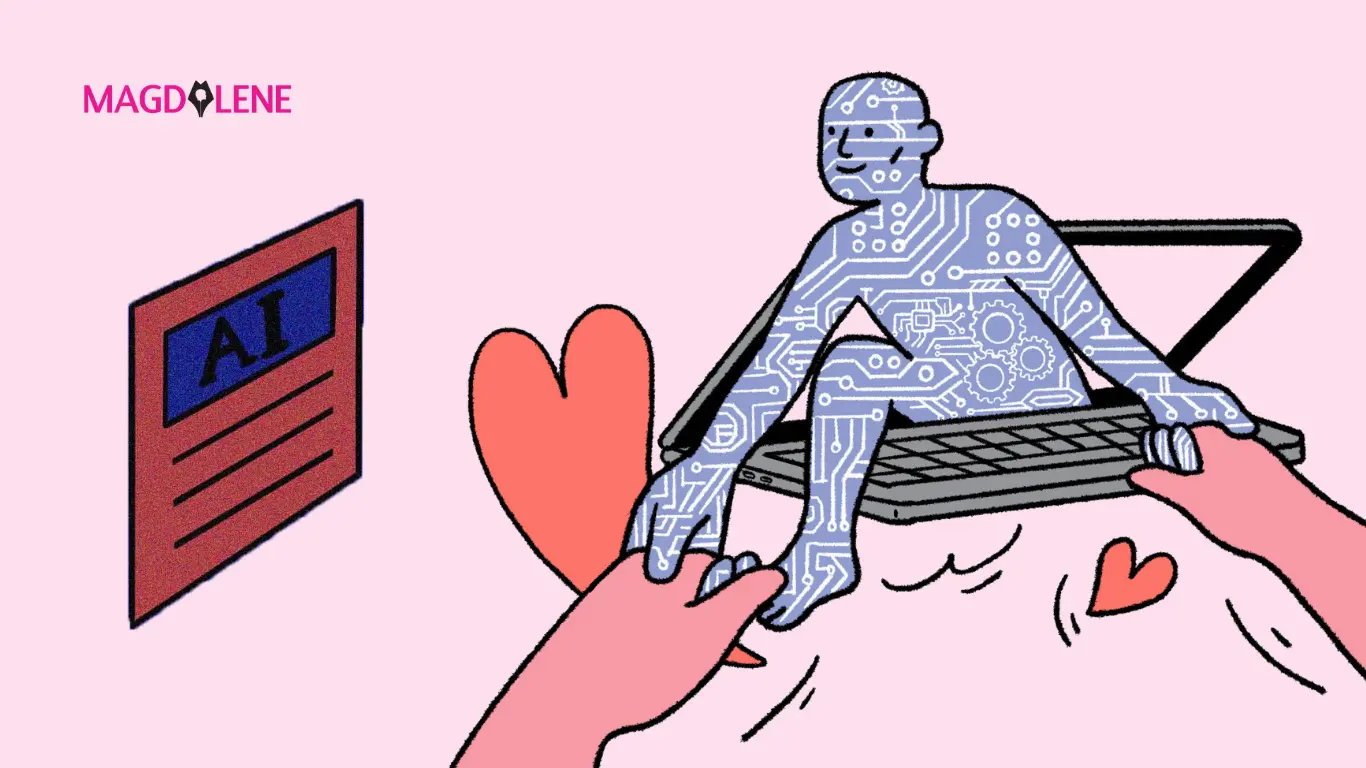Tujuh Belas Mei

Malam ini aku nelangsa. Berlayar sendu dalam rindu yang bukannya kian tenteram, malah semakin gaduh mengacau rasa.
Kekasihku sedang jauh di lereng gunung, memadu kasih dengan alam, bertemu dengan para sahabatnya sembari menyusun beberapa langkah penting untuk melanjut rawat bumi. Tampaknya ia begitu sibuk sejak pagi tadi hingga lupa memberi kabar. Ah, sejujurnya ia memang tak terlalu pandai berkabar kata lewat udara.
Sebetulnya bukan rindu yang membuatku nelangsa. Aku selalu mendukung dan bangga atas apapun yang dikerjakannya. Rindu hanya sepercik kesedihan, kegetiran serta kenikmatan yang singgah bersamaan sejenak, untuk sekedar menguji hasrat dan cinta. Cinta yang baru dua belas hari kami sadari dan alami, tapi tentu tak kurang cukup kadarnya untuk disebut cinta.
Fina, kekasihku, berangkat kemarin malam bersama tiga teman sekelompoknya. Sekecup cium dan peluk hangat kulekatkan di bibir dan keningnya agar ia bisa bepergian dengan tenang. Juga agar aku yang ditinggal sejenak, tak terlalu kalut menunggu dalam rindu. Jadi sesungguhnya tak ada yang perlu terlalu kukhawatirkan tentangnya. Nelangsa ini bukan karenanya.
Aku nelangsa sebab esok adalah tujuh belas Mei. Begitu cepat waktu berlalu. Sudah 26 tahun sejak Badan Kesehatan Dunia (WHO) menghapus homoseksualitas dari klasifikasi internasional mengenai penyakit, tapi sampai sekarang masih banyak yang menganggap dan mengatai kami sakit jiwa.
Tiga hari yang lalu, saat aku merangkul mesra kekasihku yang kepalanya pusing karena suhu dingin bus Transjakarta, segera saja banyak mata sinis tertuju seakan hendak menikam jantung kami berdua.
“Mereka tak bermaksud sinis, hanya penasaran. Tak perlu dipikirkan,” bujuk Fina.
Aku sering merasa risih setiap kali orang-orang menatap dengan kasar. Aku merasa tak pernah mengganggu mereka sedikitpun.
Hingga hari ini, setiap pakaian yang kurasa nyaman kukenakan di luar rumah, yang menambah percaya diri dan kepuasan berekspresi, pun selalu jadi alasan orang-orang bertanya setengah mendikte. “Eh, kamu perempuan atau laki-laki?. “Eh, ini toilet perempuan. Laki-laki di sebelah sana,”
Belum lagi ingar-bingar cuitan rendahan para penguasa negara soal isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender/Transeksual, Interseksual dan Queer (LGBTIQ), yang sejak tiga bulan lalu mendominasi wacana tingkat nasional.
Padahal menurutku itu tak lebih dari sekedar pengalihan tatapan rakyat pada kemiskinan, dan kemelaratan yang kian hari kian menyedihkan, atau perpecahan suara antar warga dalam menimbang kebijakan reklamasi Teluk Jakarta, atau penggusuran demi penggusuran warga miskin kota dengan cara yang tak manusiawi, atau penderitaan orang-orang Papua yang tak mendapat perhatian apa-apa kecuali janji-janji palsu, ibu-ibu Pegunungan Kendeng pembela bumi, atau korupsi yang sudah terlalu biasa, hingga tak laku jual lagi di halaman depan media massa, atau bahkan perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang memang sepertinya sejak dulu negara tak terlampau minat membahas dan mendalami materinya.
Sepuluh hari yang lalu suruhan ‘mereka’ berdemo membawa spanduk yang isinya agak lucu dan di luar akal sehat. Tolak komunis, tolak LGBT dan tolak gerakan separatis Papua, kata mereka. Ah, gampang sekali mengenali siapa yang mengutus anak-anak muda tak berdosa itu.
Kami mewakili masyarakat dan mahasiswa Muslim, katanya pula. Penamaan yang aneh. Entah sejak kapan mahasiswa menjadi bukan masyarakat. Bikin nama kelompok kok asal-asalan. Asal jadi, yang penting dapat nasi.
Kekasih dan sahabat-sahabatku pun banyak sekali yang Muslim, dan aku selalu takjub pada cinta tak berbatas serta kecerdasan berpikir mereka yang tak bisa diragukan, yang tentu selalu mengutamakan kasih dan solidaritas.
Jelang tujuh belas Mei, perasaan memang selalu bercampur-aduk. Entah karena tiap pojok pasti akan penuh warna dan bahagia, atau justru karena goresan duka oleh negara yang tak kunjung reda. Semoga saja kita semua tetap teguh dalam kata, laku dan cinta.
Sambil merindu dan menunggu kekasihku pulang, aku membongkar-bongkar foto lama di satu folder bernama RUNS. Rainbow United of North Sumatera. Tepat tiga tahun lalu, aku berdansa dan menari bersama sahabat-sahabat seperjuanganku merayakan International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT) paling meriah di Kota Medan.
Seperti julukan harinya, seluruh foto kami penuh warna-warni, antusias, ceria dan membawa bahagia, bahkan hingga malam ini pun masih terasa.
Sayang tahun ini sepertinya Medan tak akan ramai di tujuh belas Mei. Sahabatku seperjuanganku bilang, kondisi di sana sedang tak kondusif. Rapat-rapat organisasi pun kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena takut mereka sedang diintai. Sekretariat yang biasanya tanpa jeda kegiatan, kini semakin terbatas, senyap dalam suara dan aktivitas.
Belum lama ini rektor universitas mengeluarkan ancaman pemecatan mahasiswa yang terlibat dalam gerakan LGBTIQ. Aku sendiri menyarankan teman-temanku untuk istirahat saja sejenak. Aku hanya tidak ingin mereka menjadi korban keganasan dan ketololan yang dipelihara sejak lama, bahkan sekalipun di lingkungan akademis.
Rindu sekali aku pada masa-masa tiga tahun lalu itu. Entah kapan kami akan mengorganisir pesta perayaan IDAHOT lagi. Pesta yang riuhnya tak pernah hilang dari ingatan kami.
Malam hampir larut saat tiba-tiba keponakan perempuanku menelepon sambil menangis.
“Ada apa?” tanyaku. Ia sesenggukan, tak mau bicara.
“Apa yang terjadi?” tanyaku lagi. Ia jawab setelah beberapa menit berdiam diri. Aku menunggu dalam sabar.
“Aku ingin mati,” jawabnya.
“Kamu kenapa?” aku bertanya lebih lembut, takut ia segera menutup teleponnya.
“Pokoknya aku ingin mati!” ia jawab sambil teriak. Lalu menangis lagi. Aku tak berani bertanya lagi.
Kami butuh waktu lama untuk berdiam diri sambil aku meraba ada apa gerangan yang sedang terjadi padanya. Jauh sekali ia berada saat ini, percuma kupaksakan diri membayangkan aku sedang berada di sana. Kami terpisah laut, juga jarak daratan.
“Anxiety attacked me since last night,” ucapnya lirih. Aku menangis. Aku tahu pasti yang ia alami. Setiap kali ia sebut mati, aku tahu itu karena ia telah kehabisan daya bahkan untuk hanya mencoba berdiri.
“Tarik napas dalam-dalam ya, tiga kali,” pintaku. Kudengar di ujung telepon ia berusaha melakukan apa yang kuminta meski dengan napas terbata-bata.
“Hold on, dear. I’m here for you,” ucapku sungguh-sungguh. Aku tak kuat menahan perih di hatiku.
Keponakanku ini cantik sekali, dan sangat ceria, sebelum akhirnya ayah sahabatnya menggerayangi tubuhnya yang mungil di kamar kecil itu. Sejak saat itu ia berubah menjadi murung, gelisah dan tak tentu arah. Setiap kali masa itu terbayang olehnya, ia hanya bisa bilang mau mati.
“Sahabatku cerita pada ayahnya tentang aku yang suka sama sesama perempuan. Lalu esok harinya saat main ke rumahnya, ia membisikkan sesuatu di telingaku, sambil meremas perut dan payudaraku,” ceritanya dua bulan lalu.
Kejadian itu bahkan terjadi dua tahun lalu. Ia baru punya keberanian menceritakan hal itu padaku saat aku berkunjung ke desa.
Aku bahkan tak sanggup bertanya saat itu, tapi kupaksakan dengan kemarahan yang amat kutahan.
“Dia membisikkan apa, Nak?”
“Ia bilang mau bikin aku ‘sembuh’,” jawabnya polos.
Sudah dua bulan ini aku mencari keberadaan lelaki itu. Aku ingin sekali sekedar bicara padanya sebagai sesama manusia. Ingin sekali kutemui dia dalam jiwa seorang bapak yang memiliki anak perempuan. Tapi hingga kini aku tak pernah menemukannya.
Ia menghilang setelah melecehkan keponakanku dua tahun lalu. Entah, mungkin dia sudah mati dimakan ular, atau sekarat terlempar truk ke dalam jurang..
Malam ini jiwaku penat sekali. Apalagi kekasihku baru saja berkabar, katanya kepulangannya ditunda satu hari lagi, sebab ada rapat mendesak yang harus mereka tuntaskan malam ini. Padahal rasanya sudah tak sanggup lagi hati ini menanggung rindu, beban serta gelisah untuk sekedar melewati malam. Tapi aku sadar setiap orang tentu harus siap dan tegar menanggung kuk di bahunya masing-masing.
Terlalu banyak ingatan yang belum pulih setiap menjelang tujuh belas Mei. Ah, aku ingin sekali tidur dalam damai.
***
Bersyukurlah sebab pagi telah tiba. Aku terbangun karena Fina membuka pintu kamar dengan senyum manis di wajahnya.
“Selamat pagi. Bagaimana kabarmu, Sayang?” tanyanya bersemangat.
“Hmm, perfect! Aku merasa sepenuhnya dilupakan,” ucapku tersenyum getir, sedikit menyindir. Ia tertawa.
Lalu segera ia peluk aku paling lekat, jauh melebihi 20 detik seperti biasa, sebab itu sangat ampuh memberi efek harapan hidup yang amat panjang. Ia belajar itu dari aku. Kutenggelamkan diriku dalam pelukannya yang erat, sambil menangis sejadinya.
“Ada apa? Apakah terjadi sesuatu?” tanyanya. Aku menggeleng, tapi masih terus menangis.
“Sejak kemarin aku tanya kabarmu, tapi kamu nggak jawab. Malah bilang nggak ingin mengusik ketenanganku di sana. Ada apa?” tanyanya lagi, sedikit memaksa.
Kupandangi wajah dan sekujur tubuhnya yang tampak letih. Dua malam ini dia tidur beralas bambu dan bermantelkan udara dingin. Begitu banyak beban yang ingin sekali segera kubagi, tapi bahkan energinya pun belum pulih sehabis digerogoti angin. Kuurungkan niat untuk bicara.
“Tidak ada apa-apa. Nanti kita cerita. Ayo kamu sarapan dulu,” jawabku. Kuhapus air mata yang seperti tak ingin berhenti mengaliri pipiku.
“You sure, Dear? Ayo dong cerita,” ia terus meminta.
“Iya, nanti aku cerita. Sarapan dulu, lalu istirahat. Sore nanti kita persiapan untuk acara IDAHOT besok. Tapi kalau kamu nggak kuat, lanjut istirahat saja ya,”
“Nggak mau! Ikut!”
“Hmm.. Ya udah, oke kalau begitu sarapan dulu.” Kuusap rambut tipis di ujung kepalanya.
Meski sangat lelah, tak pernah ia kurang menarik dalam membangkitkan gairah. Kuraih ujung dagunya agar segera kukecup bibir tipisnya yang diam dan malu-malu. Kunikmati setiap helai perjumpaan napas kami berdua yang menghangatkan wajah, pun menghangatkan jiwa.
“Kamu kemarin jadi olahraga?” tanyanya membuyarkan konsentrasiku.
“Belum, aku sibuk. Memangnya kenapa?” jawabku.
“Ah, kamu kan terakhir kali kram setelah bercinta,” jawabnya lantang, tertawa lepas. Lalu ia lepaskan kecupan bibirku, berlari kecil menggoda dari jauh, membuatku harus olahraga instan sebelum kutenggelamkan diriku dalam pelukan cintanya.
Saat kekasihku tidur dengan lelap, aku berdoa berbisik kepada Tuhan. Semoga kelak selalu ada kekuatan untuk kami bertahan meski dalam kegetiran, kegelisahan dan kebimbangan. Meski pasti jalan ini akan selalu sulit, semakin sulit, tapi bukankah justru kita terbentuk semakin kuat lewat masa-masa sulit?
Setiap orang mesti bangkit dari rasa sakit, lalu berjuang, dan terus berjuang.
Semoga.
Pamulang, 16 Mei 2016
Febbry Lovina adalah lulusan Antropologi Sosial dari Universitas Sumatera Utara. Tinggal di Pamulang Timur, saat ini ia menjadi relawan di Perempuan Berbagi. Ia mencintai anjing dan buku. Sebagaimana Pramudya, ia pun percaya, bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian.