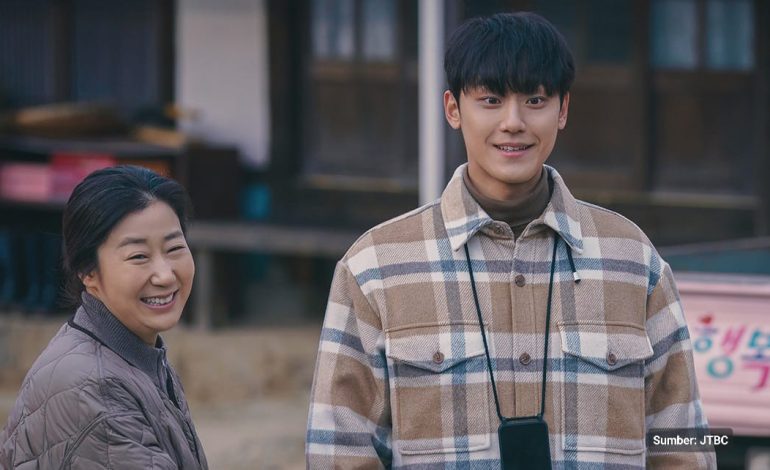Ulasan ‘The Little Mermaid’ yang Perlu Dibaca Reviewer Rasis

Percakapan ini sudah pernah terjadi. Tahun lalu, komentar rasis menyerbu Halle Bailey, saat trailer The Little Mermaid versi live action ini dirilis Disney. Beberapa komentar muncul dengan dalih sama: “Ariel kulit hitam merusak masa kecil” mereka.
Argumen serupa muncul pertama kali tiga tahun lalu, saat Halle Bailey pertama kali diumumkan akan memerankan Ariel versi film ini. Tagar #NotMyAriel muncul dari para rasis yang mempermasalahkan warna kulit sang aktor. Tahun lalu, seorang TikToker bahkan mengolok-olok trailer The Little Mermaid dengan melakukan blackface.
Blackface sendiri punya sejarah panjang di Amerika Serikat. Praktik ini dulu dipakai orang-orang teater untuk merias aktor mereka (yang biasanya orang kulit putih) agar bisa memerankan orang kulit hitam. Ia berangkat dari sejarah kelam politik segregasi AS yang rasis dan menindas orang-orang kulit hitam.
Baca juga: Heboh Trailer ‘The Little Mermaid’: Masih Banyak Komen Rasis
Praktik ini meninggalkan luka besar buat orang kulit hitam dan generasi Afrika-Amerika, yang kini sudah jadi kesadaran global. Terutama semenjak rasisme pada orang kulit gelap (colorism) masuk jadi diskursus arus utama di media dan budaya populer.
Lagi-lagi Pakai Argumen Anti-diversity
Tahun ini, percakapan serupa ramai lagi saat seorang reviewer menyebut plot Ariel yang diselamatkan telanjang dari laut tak masuk akal. Argumennya: “Mana ada orang sebaik (nelayan yang menyelamatkan Ariel) itu, sampe nganterin ke kastil, apalagi Ariel kulit hitam. Yang ada diperkosa dan human-trafficking kali.”
Menurutnya, plot itu tidak masuk akal. Garisbawahi kata “masuk akal”. Argumen begini selalu muncul saat para rasis berargumen tentang ketidaksetujuan mereka pada Halle Bailey sebagai Ariel.
Jurnalis dan ahli drama Amanda-Rae Presscot telah meneliti dan mencatat, ada pola copy-paste (menyadur) komentar yang dilakukan para fans rasis ini di internet. “Orang-orang yang marah tentang ratu kulit hitam dan bangsawan Asia Selatan di Bridgerton (Netflix) adalah orang yang sama yang marah-marah tentang peri, penyihir, dan duyung yang diperankan orang kulit berwarna,” kata Presscot pada Vox.
“Forced diversity”—alasan yang juga jadi intro di video TikTok si reviewer rasis—adalah yang paling sering muncul saat debat tentang Ariel kulit hitam ini muncul. Tujuannya untuk mengalihkan percakapan dari isu sebenarnya: rasisme.
Baca juga: Putri Duyung Disney Berkulit Hitam, Kenapa Tidak?
Lantas kenapa argumen yang sama muncul juga dari para indons—alias beberapa contoh di atas? Alasan utamanya adalah peninggalan kolonialisme. Logika sesat orang kulit putih tentang segregasi berdasarkan warna kulit telah tertinggal di setiap tanah yang pernah mereka jejaki. Termasuk Indonesia, yang pernah juga jadi lahan basah langganan jajahan bangsa Kaukasia, dari Spanyol, Inggris, sampai Belanda.
Jadi, seperti kata Aja Romano di Vox, argumen tentang “forced diversity” ini amat dangkal karena datang dari ketidaktahuan sejarah penindasan pada kelompok minoritas. Terutama karena kebanyakan para rasis tidak sadar kalau yang dilakukannya adalah hal politis dan membahayakan.
Betulkah Mengkritik Film dengan Pandangan Bias Sah-sah Saja?
Belakangan, saat review berdurasi 6 menitan itu jadi percakapan ramai di Twitter, beberapa orang membelanya dengan argumen: “Kritik film itu subjektif”. Saya sendiri sepakat dengan poin tersebut. Karya dan kritik atas karya tersebut tentu saja dibangun dari sudut pandang subjektif pembuatnya.
Namun, gagasan-gagasan atau imajinasi yang tampil pada karya atau kritik kita tentu tidak datang dari ruang hampa. Pengalaman dan pengetahuan sang pembuat jadi salah satu faktor besar yang memengaruhinya.
Mengimajinasikan perempuan kulit hitam diperkosa karena ditemukan telanjang di laut jelas bukan sesuatu yang datang dari ruang kosong. Pengalaman, bahan bacaan, tontonan, atau secuil pengetahuan dari sumber apa pun adalah yang memengaruhi si reviewer melempar argumen itu. Masalahnya, argumen itu tidak datang dengan sentimen tepat.
Di dunia nyata, perempuan kulit hitam memang termasuk dalam kelompok paling rentan. Namun, reviewer yang sering menggunakan argumen “tidak masuk akal” saat mengkritik, sering kali lupa kalau film tidak harus selalu masuk akal. Bahkan sering kali yang terjadi di film memang versi berlebihan, dramatis, eksplotitatif, dan ekstra dari yang terjadi di hidup. Terutama saat kita bicara tentang The Little Mermaid, cerita tentang makhluk fantasi, bernama duyung.
Argumen yang sama sempat ramai di Twitter, saat foto-foto behind the scene The Little Mermaid muncul di internet sebelum film ini tayang di bioskop. Beberapa orang bilang, foto Halle Bailey naik kereta kuda mengingatkan mereka pada masa-masa perbudakan di Amerika Serikat, dan plot ini bisa dipakai di The Little Mermaid versi live action. Meski terdengar seperti gagasan harmless buat sebagian orang, penyataan itu sebenarnya preseden buruk yang mengandung rasisme. Seolah-olah orang kulit hitam di film hanya boleh tampil dengan cerita-cerita gelap perbudakan dan sejarah kelam yang mereka alami di dunia nyata.
Argumen demikian mengindikasikan bahwa orang-orang kulit hitam tak boleh keluar dari kotak “masuk akal” karena akan melawan keabsahan sejarah. Padahal, dalam film, dunia bisa dikontruksi olang, diimajinasikan ulang. Dan lewatnya, banyak orang-orang teropresi di dunia nyata bisa mencari eskapisme dari kekejaman di dunia nyata.
Itu sebabnya, kritik yang baik harusnya adalah kritik yang sensitif dan tidak malah makin membebankan mereka yang diopresi di dunia nyata.
Baca juga: Merebut Takdir bersama Elsa, Maleficent, dan Merida
Film-film live action Disney—yang muncul beberapa tahun terakhir—sendiri lahir dari proses otokritik mereka. Film-film animasi Disney’s Princess banyak dikritik berdampak buruk bagi anak perempuan dan dianggap bukan representasi baik. Itu sebabnya, dalam versi live action, ada plot-plot kecil yang diubah agar karakter-karakter canon ini jadi lebih baik dan sesuai dengan konteks sekarang.
Dalam The Little Mermaid, ada dialog-dialog Ariel yang diganti agar motivasinya tentang ingin bertualang ke daratan lebih kuat, ketimbang hasratnya ingin hidup bersama Pangeran Eric. Mereka bahkan menambahkan beberapa lagu baru untuk mempertebal karakter Ariel yang lebih pemberani dan memberdayakan.
Itu yang bikin mengkritik warna kulit Ariel baru dengan alasan forced diversity atau agenda keberagaman yang terlalu dipaksakan jadi—bukan hanya keliru, tapi konyol. Hollywood belum pernah betul-betul beragam. Dominasi orang kulit putih dan kaya raya di sana masih memengaruhi jenis film-film yang mereka produksi. Artinya, konsep forced diversity tak betul-betul nyata alias karangan belaka.
Meski, kini makin banyak produksi film-film mereka yang mempekerjakan aktor kulit hitam dan kuliat berwarna, atau minoritas gender, atau aktor disabilitas, tapi representasinya masih timpang.
Sebetulnya, ketimbang mengkritisi diversity yang di permukaan tampak beragam di Hollywood, energi kita bisa dipakai untuk menyoroti tingkah problematik lainnya Disney dan perusahaan raksasa serupa. Dalam upaya mereka memberikan tontonan beragam, perusahaan-perusahaan ini sering kali menjual slogan “representation matters” dalam film-film yang mereka produksi.
Tak banyak orang sadar, alih-alih memproduksi cerita baru yang memang ditulis, diproduksi, dan mempekerjakan orang-orang minoritas, Disney lebih sering melakukan reboot atau remake.
Memproduksi ulang film-film lama adalah strategi bisnis yang baik, karena mereka bisa mengeksploitasi intelectual property (IP) sendiri sehingga lebih hemat, sekaligus lebih menguntungkan. Ketimbang membuat cerita-cerita baru yang lebih beragam dan memang dibikin oleh para kreator minoritas.
Baca Juga: Ada Internalisasi Rasisme di Balik Komentar Orang Indonesia pada ‘The Little Mermaid’
Gagasan “representation matters” juga sebetulnya bermasalah, karena tetap melakukan penyaringan dalam prosesnya. Orang-orang minoritas yang dipilih jadi pemeran utama, misalnya, cuma dipilih untuk menggenapi kuota keberagaman yang telah ditentukan. Cerita-cerita yang diproduksi juga sering kali masih memakai white gaze sebagai minoritas, sehingga penggambaran orang-orang minoritas tetap jadi yang dipinggirkan, dianiaya, atau menderita. Jika bermimpi pun, keinginan mereka sering kali masih mirip-mirip karakter-karakter kulit putih di film-film kulit putih yang sudah pernah dibikin.
Kalau betul-betul mau mengkritik The Little Mermaid, kita bisa menggugat bagaimana film ini hanya menguliti representasi di atas permukaan warna kulit saja. Halle Bailey tampil memukau dengan akting dan kualitas prima suaranya, poin-poin feminisme Ariel makin kuat, gagasan tentang Ariel yang jatuh cinta pada dunia manusia sebelum jatuh hati pada Eric makin tegas, tapi narasinya cuma sampai di sana.
Keputusan Disney setia pada cerita original membuat film ini kehilangan kesempatan mengeksplor kisah fantasi legendaris ini. Ada ruang besar yang mereka bisa pakai untuk membuka diskursus lebih dalam tentang masa lalu Triton-Ursula, kenapa ibu Ariel bisa mati di daratan, enam saudari Ariel yang beragam, dan kenapa Triton membenci manusia dan bagaimana Selina dan kerajaannya membenci bangsa Mer.