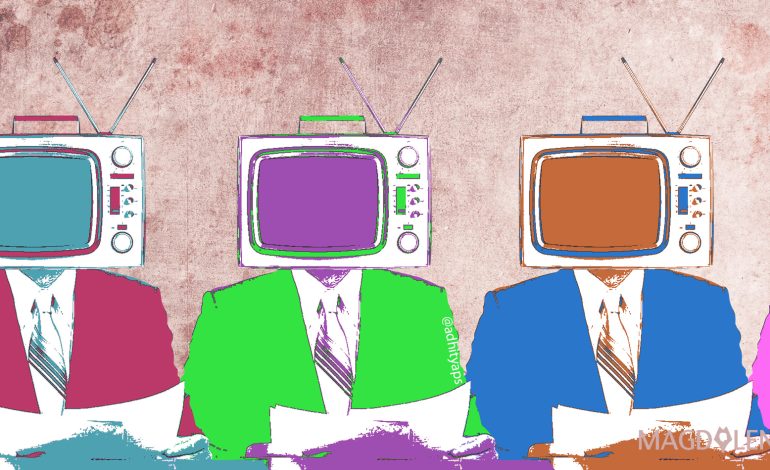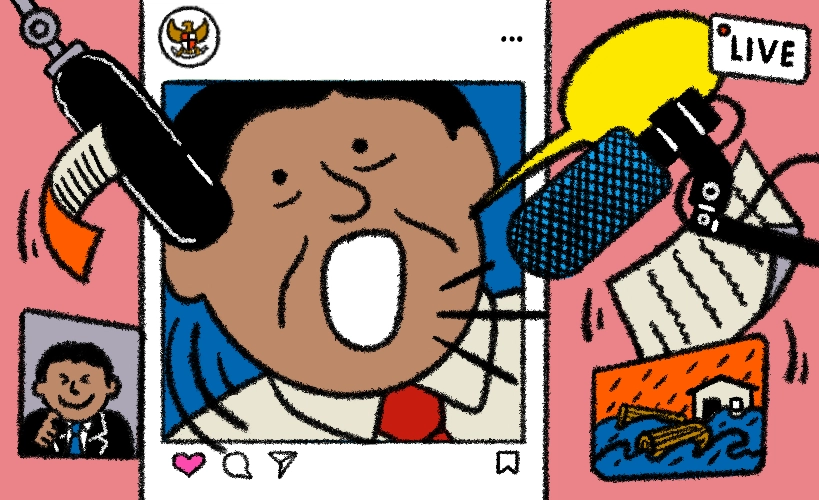Perempuan dan Pernikahan dalam ‘Ini Kisah Tiga Dara’

Dalam masyarakat kita, perempuan dan pernikahan sering dipahami sebagai sebuah jukstaposisi. Setidaknya, itu yang saya rasakan setelah menonton Ini Kisah Tiga Dara. Film garapan Nia Dinata ini memang menyebut perkara pernikahan sebagai ukuran keberhasilan seorang perempuan. Menariknya, tema tersebut didedah dan digarap dengan tetap menempatkan perempuan sebagai entitas yang sadar dan berdaya atas pilihan-pilihan yang hendak mereka jalani.
Saya selalu percaya bahwa menjadi feminis tidak serta merta menafikkan lembaga pernikahan. Tidak ada alasan untuk menolak lembaga pernikahan, selama pernikahan tersebut mampu mewadahi nilai-nilai pribadi kedua belah pihak, tidak digunakan untuk melegalisasi kekerasan dan tidak untuk mengopresi salah satu pihak. Dalam Ten Ways You’re Wrong about Feminism, Devi Asmarani menjelaskan bahwa yang ditolak para feminis adalah ketika masyarakat menilai pernikahan sebagai “tempat yang lebih baik” untuk perempuan, memberi hukuman sosial untuk mereka yang tidak menikah atau bercerai, dan ketika pernikahan digunakan sebagai cara mengontrol perempuan.
Ini Kisah Tiga Dara dimulai dari premis pernikahan sebagai “tempat yang lebih baik” untuk perempuan. Premis tersebut yang sepanjang cerita dibawa oleh Oma (Titiek Puspa) dalam menghadapi kehidupan sosial tiga cucu perempuannya: Gendis (Shanty Paredes), Ella (Tara Basro), dan Bebe (Tatyana Akman). Dari awal film, Oma bersikap tidak nyaman dengan umur Gedis yang sudah 32 tahun dan belum mendapat jodoh – belum berpacaran dan belum menikah. Film ini berlanjut pada usaha-usaha Oma untuk mencarikan jodoh untuk Gendis, mulai dari mengenalkan Gendhis dengan teman-teman pengusaha ayah Gendis sampai pendekatan personal dengan Yudha (Rio Dewanto), satu laki-laki mapan yang tengah bermalam di hotel keluarga mereka di Maumere. Konflik dimulai saat Ella, cucu kedua mulai lebih agresif dan mencoba ‘mengambil’ Yudha yang semula dijodohkan dengan Gendis. Oma, sebagai generasi old fashioned yang juga konservatif, tentu saja menentang hal tersebut, dan bersikeras untuk menikahkan Gendhis terlebih dahulu, “Kalau kamu bersikeras melangkahi, Gendis akan menjadi perawan tua,” Kata Oma kepada Ella.
Sekilas, tampak jelas bahwa film ini memang fokus menggarap pernikahan dari sisi perempuan – berikut mitos-mitos yang tumbuh di sekitarnya. Nia Dinata sepertinya ingin mendokumentasikan kekhawatiran keluarga (Indonesia) perihal pernikahan yang selama ini hidup dalam jargon (kalau sudah klise jika disebut sebagai pertanyaan) “Kapan nikah?”.
Menariknya, bentuk dokumentasi tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai yang tengah bertumbuh dewasa ini. Sebut saja perihal kedaulatan tubuh perempuan dan kesadaran sebagai perempuan progresif. Dua hal tersebut dihidupkan dalam banyak adegan di Ini Kisah Tiga Dara. Salah satunya, melalui karakter Gendis, si cucu pertama.
Adalah karakternya yang mandiri tapi penyayang, keras tapi pengalah terhadap adik-adiknya, perfeksionis, paling idealis dan kecenderungannya untuk tidak mau dikontrol. Karakter tersebut semakin berkembang ketika Gendis harus berhadapan dengan Yudha. Di adegan ini, penonton bisa melihat bahwa usaha Omanya dan ketertarikan Yudha tidak cukup berarti untuk memosisikan Gendis sebagai objek – yang bisa direpresi oleh subjek-subjeknya – dalam pembangunan sebuah relasi. Dalam banyak adegan, Nia Dinata sengaja memposisikan Gendis sebagai perempuan yang tidak terjangkau oleh siapapun. Yang mana posisi tersebut, setidaknya menjelaskan bahwa faktor usia, faktor keluarga, kemapanan, dan sebagainya bukan merupakan alasan berarti yang membuat perempuan berkomitmen dengan hal sesakral pernikahan.
Barangkali Gendis bersepakat dengan saya. Ketika saya sudah mantab berkomitmen hanya dengan satu orang, berarti saat itu saya sudah siap menjadi lebih kompromis dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya. Dan ketika saya sudah memutuskan menikah, berarti saat itu saya sudah merasa diri saya matang secara emosional, siap berkomitmen seumur hidup dengan orang tersebut, berikut menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang pasti akan terjadi. Dan yang paling penting, dua proses tersebut, memilih satu orang dan memutuskan menikah, sebisa mungkin dijalani bukan semata-mata untuk memberi kepuasan orang lain, misalnya: keluarga.
Film ini nyatanya mampu menjembatani dua jenis perempuan: Omanya yang konservatif, yang masih bersetia dengan mitos dan aturan masa lalu, serta Gendis yang mencerminkan perempuan progresif yang mandiri dan bebas. Yang menjadi catatan adalah, karakter Oma terlalu mendominasi, baik untuk kehidupan tiga dara tersebut maupun pengaruhnya untuk konstruksi cerita. Tidak bisa dipungkiri, dominasi Oma, yang di dalam film disebut juga dengan istilah matriarki, melahirkan kembali mitos-mitos konservatis dalam porsi yang tidak sedikit. Mitos tersebut misalnya hadir dari pernyataan-pernyataan Oma yang menggambarkan bahwa tingkat kebahagiaan perempuan masih diukur dari seberapa berhasil dia ‘mendapatkan’ laki-laki.
Terlepas dari itu, perlu diapresiasi juga usaha Nia Dinata untuk mengubah stigma masa lalu perempuan terhadap dua ruang: dapur dan kasur. Nilai-nilai masa lalu kerap menyebut dapur dan kasur adalah takdir perempuan – sebuah pernyataan yang membatasi ruang gerak dan hak-hak yang dimiliki perempuan. Di Ini Kisah Tiga Dara, Nia Dinata dengan berani memvisualisasikan sekaligus memberi definisi yang lebih luas perihal dua ruang tersebut. Dapur sebagai ruang kerja Gendis, diperluas maknanya menjadi ruang perempuan mengekspresikan hak-hak personalnya, pengekspresian karakternya yang mandiri, perfeksionis, dan idealis.
Adalah ruang kedua yang juga didedah Nia Dinata dengan kedalaman dan keberaniannya sendiri. Kasur mencerminkan karakter Bebe, cucu terakhir yang paling pemberontak. Hal ini semakin dijelaskan pada dialog terakhir Bebe dengan Erick, pacarnya. “Aku hamil, tapi aku tak ingin kamu menikahiku karena aku hamil. Aku tidak ingin kamu kejebak,”
Satu lagi pernyataan perihal pernikahan, yang dari sana menjelaskan bahwa ada lebih banyak hal yang di masa lalu bisa digunakan untuk mengontrol perempuan dan saat ini tidak bisa. Sebuah pergeseran nilai yang nyatanya kita tengah rasakan, yang sengaja Nia Dinata tanamkan di sepanjang filmnya. Pun dengan adegan penutup yang semakin mengamini visi misi sutradara. Adalah adegan pernikahan, tetapi bukan pernikahan dari ketiga dara tersebut. Akhir yang bukan saja mengejutkan, tetapi juga menjelaskan bahwa pernikahan bukan puncak keberhasilan seseorang, bukan pula akhir dari perjalanan seseorang, dan bukan jenis akhir bahagia untuk sebuah film layar lebar. Di atas segalanya, pernikahan bukan alat untuk mengukur pencapaian seorang perempuan, bukan?

Yulaika Ramadhani selalu percaya bahwa cerita-cerita adalah media terbaik untuk belajar (menjadi) manusia. Oleh karenanya, ia sangat cinta membaca buku, menonton drama dan dokumenter, dan bermain dengan siapa saja. Kadang-kadang menulis di Cinema Poetica. Bekerja sebagai Asisten Peneliti di LIPI. Sekali-kali bermain di Tempo Institute dan Community for Interfaith and Intercultural Dialogue Indonesia (CINTA_ID). Dia menulis di yulaside.com