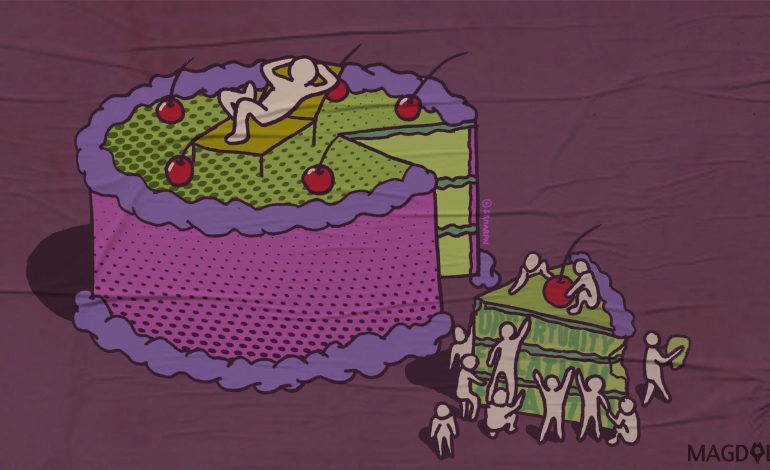Yang Baik dan Yang Buruk dari ‘Avatar: The Last Airbender’ 2024
Avatar: The Legend of Aang (2005) bukan cuma nostalgia dan tontonan masa kecil, buat mereka yang menggemari kartun Nickelodeon ini. Melanie McFarland, kritikus dari Salon.com, bahkan berargumen bahwa ATLA adalah salah satu tontonan paling anti-fasis terbaik yang pernah dibikin. Ia tidak mengajarkan perang dilihat dengan solusi-solusi pasifis, tapi juga malah memperlihatkan bagaimana perlawanan dengan kekerasan adalah sesuatu yang diperlukan. Terutama dalam upaya pembebasan.
ATLA sendiri bercerita tentang Aang, bocah 12 tahun yang tertidur selama 100 tahun, lalu mendapati dirinya sebagai korban genosida. Seluruh sukunya, Suku Udara Nomad, telah digenosida Negara Api yang sedang mengkolonisasi dunia. Selain bangun jadi korban genosida, Aang harus belajar tiga elemen lain karena dirinya adalah Avatar, master pengendalian empat elemen.
Kita bukan cuma menonton petualangan sang Avatar melawan perang 100 tahun, fasisme, dan traumanya sendiri, tapi juga sebuah worldbuilding megah dengan pengembangan karakter-karakter kokoh.
Baca juga: 5 Perbedaan Besar dalam ‘Avatar: The Last Airbender’ Series 2024 dengan Animenya
Saat Netflix mengumumkan akan membuat versi live action Avatar: The Last Airbender (2005-2008), para fans terbelah. Ada yang excited karena kartun masa kecil mereka akan diadaptasi jadi versi baru. Banyak pula yang buru-buru sangsi dengan kualitas adaptasi ini kelak. Pasalnya, anime ini pernah diadaptasi M. Shyamalan jadi film pada 2010, dan berakhir jadi tontonan live action dengan cap terburuk.
Film itu betul-betul mengobrak-abrik banyak hal penting yang membuat Avatar: The Last Airbender jadi tontonan favorit generasinya. Contohnya, mengubah pelafalan nama Aang, mengganti semua karakter utama dengan aktor kulit putih, membuat pengendali api hanya bisa mengendalikan api jika ada api di dekat mereka. Sampai special effect yang jelek dan koreografi pengendalian elemen yang terbilang konyol.
Paling parah, Shyamalan gagal menangkap roh asli ATLA yang bisa menggambarkan perlawanan pada rezim fasis dengan amat baik. Itu sebabnya, di titik ini sebuah live action tidak bisa lagi salah mengadaptasi nilai-nilai utama yang jadi roh, kekuatan, dan alasan fans mencintai kisah ini.
Format 8 Episode yang Menantang
Salah satu tantangan terbesar adaptasi anime adalah memadatkan jumlah episode ke dalam format lebih ringkas, tanpa harus bikin fans marah. Proses eliminasi karakter, subplot, dan perintilan kecil yang mungkin amat penting bagi fans pasti susah terhindarkan. Hal ini juga terjadi dalam ATLA versi Netflix.
Dalam dua episode pertama, susah rasanya menampik efek mual-eksposisi karena serial ini perlu menciptakan dunia Avatar dan empat bangsa di dalamnya dengan cepat. Eksposisi sendiri adalah cara penulis untuk membeberkan informasi-informasi penting yang diharapkan dapat membantu penonton atau pembaca untuk mengerti alur, karakter, dan/atau dunia yang sedang dibangun. Menerjemahkan 20 episodes dalam The Book I: Water animenya ke dalam format 8 episode saja, tentulah pekerjaan menantang.
Namun, versi Netflix memutuskan memasukkan sejumlah adegan tambahan yang dilewatkan dalam versi aslinya. Seperti adegan genosida Negara Api di Kuil Suku Udara Nomad, atau sebagian besar plot Azula dan Ozai.
Berbeda dari anime originalnya, latar belakang antagonis utama series ini, Azula (Elizabeth Yu) dan Ozai (Daniel Kim) diberi porsi besar. Kita akan disuguhkan plot-plot tambahan tentang bagaimana dua karakter ini berkembang sepanjang series. Plot-plot tersebut sama sekali tidak hadir dalam animenya, dan membuat karakter Azula dan Ozai terasa makin bengis.
Sementara, dalam versi adaptasi Netflix ini, kita bisa melihat Ozai lebih banyak dan melihat sendiri bagaimana dia memanipulasi Azula untuk jadi bengis. Banyak materi plot ini diambil dari komik Avatar: The Last Aibender, sehingga tetap setia pada cerita originalnya.
Meski mual eksposisi ini lumayan menganggu, tapi penulisan dalam versi Netflix tetap setia pada materi originalnya. Bahkan dalam karakterisasi Zuko, mereka berhasil memperluas sekaligus memperdalam pergulatan batin sang pangeran terbuang.
Plot Zuko (Dallas Liu) yang dibenci lalu disayang kru kapalnya juga hadir dalam series berisi 8 episode ini. Bedanya, mereka memperkenalkan Batalion 41 atau 41st Division, sebuah divisi khusus yang ditugaskan menemani sang pangeran dalam pengasingannya.
Baca juga: Anti-Imperialism and Cultural Representation Behind Avatar: The Last Airbender
Konon, kru kapal Zuko ini adalah divisi perang yang ingin ditumbalkan Ozai, si raja api dalam peperangan. Zuko yang masih muda dan pertama kali ikut rapat strategi membantah Ozai, dan bilang taktik itu tidak etis. Ia tidak ingin divisi itu dikorbankan demi nama perang. Berang dengan pendapat putranya, Ozai menantang Zuko untuk melakukan Agni Kai, sebuah tradisi duel satu lawan satu di negara api.
Dalam pertandingan itu pula, kita tahu dari mana luka bakar di mata kiri Zuko berasal.
Penambahan plot Batalion 41 nyatanya bikin plot si pangeran eksil makin kuat dan bikin kita makin berempati pada kisahnya.
Adegan Laga yang Terhalang CGI
Selain worldbuilding, karakter-karakter kuat, dan cerita yang memikat, ATLA original terkenal punya adegan tarung yang detail, keren, dan… superkeren. Gerakan tarung mereka punya makna dan selalu memperdalam karakterisasi atau memperdalam pengetahuan kita tentang dunia Avatar yang dibangun.
Misalnya pada Aang, sang Avatar sekaligus pengendali udara terakhir.
Meski sempat terjebak dalam dunia energi selama 100 tahun, dan kembali saat seluruh bangsanya habis digenosida Negara Api, Aang tetap menjalani ajaran Suku Udara Nomad. Kultur suku mereka sendiri diinspirasi dari Tibetan, Buddhisme, dan Hinduisme. Termasuk filosofi anti-kekerasan dan cinta sesama yang diteladani Aang. Ini yang juga memengaruhi teknik pengendalian udara. Teknik itu dalam anime terinspirasi dari seni bela diri Bagua atau Circle Walking (Gerakan Melingkar) dari Cina, yang fokus pada teknik bertahan diri atau mengelak.
Baca juga: ‘One Piece’ Versi Netflix: 5 Plot yang Beda dari Manga-nya
Gerakan ini sering dipakai untuk menghindari serangan lawan, sekaligus mencari tahu kelemahan mereka. Itu yang bikin Aang lebih sering loncat ke belakang lawannya, dan memilih tidak menyerang duluan.
Koreografi tarung dalam anime ini juga selalu menambah makna plot. Ia tidak pernah benar-benar terpisah dari penceritaan. Sehingga tugas Netflix mengadaptasi adegan-adegan laganya jadi penting. Sejauh 8 episode, tugas itu rasanya belum khatam ditunaikan kecanggihan CGI mereka. Ada banyak adegan laga yang diperingkas. Banyak yang setia pada materi original, tapi lebih banyak lagi yang dipangkas.
Saking banyaknya kekurangan yang muncul karena keterbatasan format 8 episode ini, rasanya wajar muncul pertanyaan: Apakah pemotongan-pemotongan ini gagal menangkap kompleksitas serial aslinya? Buat saya pribadi, jawabannya lumayan. Serial aslinya terlalu sakral. Tiap episodenya bukan cuma indah, tapi juga penuh kedalaman.
Tapi, di titik ini, versi adaptasi Netflix masih setia pada roh utama versi originalnya. Apakah ia sempurna? Jelas tidak. Yang paling bikin saya girang ketika adaptasi ini dibuat adalah kemungkinan orang-orang membicarakan lagi ATLA versi original, dan kemungkinan ia menambah penggemar baru. Sehingga kisah ini akan kita ingat lebih lama.