Usaha Kecil ini Bisa Hentikan Masalah Besar Pernikahan Anak di NTB
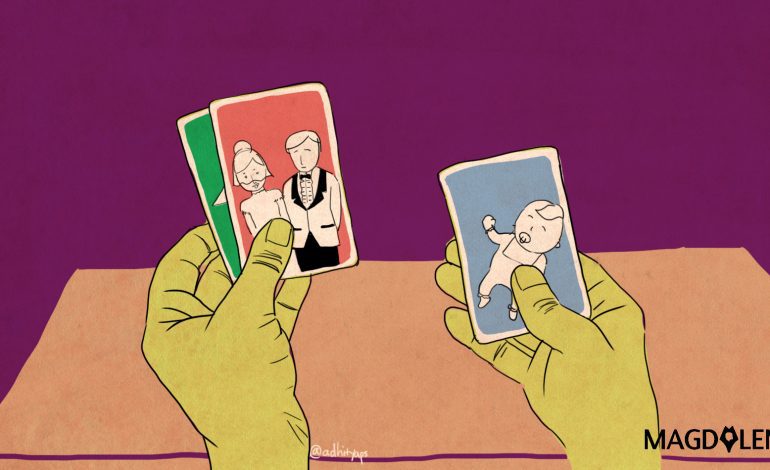
Konselor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Lombok Barat, Rusmiati mendapat tugas menangani kasus perkawinan anak pada awal 2024. Menurutnya, kasus semacam ini sering terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB): Anak perempuan diculik oleh anak laki-laki untuk dinikahkan, atau biasa disebut merarik.
Setelah mencocokkan informasi pengaduan dan kejadian di lapangan, dia mengintervensi dan berdiskusi dengan keluarga dari kedua belah pihak. Rusmiati memberi pemahaman kepada mereka bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pernikahan anak masuk ke dalam pelanggaran hukum.
Saat dimediasi, keluarga sepakat untuk membatalkan pernikahan tersebut. UPT PPA akhirnya menempatkan anak perempuan di rumah aman selama dua minggu untuk diberikan pembinaan dan rehabilitasi psikologi. Pun demikian, tiga hari setelah anak perempuan dipulangkan, Rusmiati yang datang ke rumahnya untuk melakukan evaluasi menemukan fakta pahit.
“Pada saat kita follow-up kita tanya, ‘mana anaknya?’ keluarganya berbohong, bilang ‘dia pergi’. Kebetulan ada adiknya di sana yang keceplosan lah ngomong, ‘dia kawin’. Baru kita cari tahu ke kantor dusun. Di sana juga kaget, mereka ternyata dinikahkan secara diam-diam,” ujar Rusmiati pada (20/1).
Baca juga: ‘Demi Hindari Zina’: Gus Zizan dan Sesat Pikir Perkawinan Anak
Langkah Hukum
Dia kemudian berkonsultasi dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Joko Jumadi terkait langkah paling ideal yang bisa diambil. Setelah mendengar, Joko melihat penegakan hukum bisa membawa perubahan berarti dalam menangani kasus pernikahan anak.
Sebab, Pasal 10 ayat 1 UU TPKS menyatakan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana, sedangkan ayat 2 menyertakan perkawinan anak sebagai salah satu definisi pemaksaan perkawinan. Dia menyarankan UPT PPA untuk melaporkan kasus ini ke polisi.
“Dengan yang menjadi pelapor adalah UPTD PPA,” kata Joko pada (17/1).
“Karena menurut saya memenuhi unsur pidana, akhirnya mereka melaporkan dan saya diminta jadi saksi ahli untuk kasus ini, dengan kapasitas sebagai akademisi,” lanjutnya yang juga dosen di Universitas Mataram (Unram).
Meski begitu, terdapat celah hukum di Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memungkinkan anak di bawah umur untuk menikah asal orang tua meminta “dispensasi kepada Pengadilan…”
Untungnya, dispensasi tak terjadi dalam kasus ini, membuat argumen Joko semakin kuat. “Perkawinan anak itu saya tafsirkan sebagai perkawinan yang salah satu atau kedua mempelainya di bawah usia 19 tahun dan tidak melalui proses dispensasi,” ujarnya.
Laporan ini diproses di Polda NTB pada Agustus 2024, hingga penyidik menetapkan ayah kedua anak sebagai tersangka pada November. Sebelumnya, Joko menemukan tantangan dalam meyakinkan penegak hukum, yakni penyidik di Polda dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahwa kasus ini memenuhi unsur pidana. Dia tak bisa menemukan contoh penerapan Pasal 10 UU TPKS, karena tidak pernah yang melakukannya.
Baca juga: Kisah Resi Mencegah Perkawinan Anak di Kampungnya
Mengubah Pola Pikir Sebagai Pintu Masuk
Serupa dengan Rusmiati, Ketua NGO Senyum Puan, Ade Lativa Fitri yang kerap dipanggil Adel juga punya pengalaman mengintervensi pernikahan anak. Perbedaannya, kasus yang ditangani Adel berawal dari pemerkosaan, hingga pelaku mengajak keluarga korban berdamai.
Orang tua awalnya membuat laporan ke polisi bahwa anak mereka yang disabilitas rungu wicara menjadi korban pemerkosaan hingga hamil. Berbagai upaya dilakukan pelaku, termasuk memberi uang dan berjanji menikahi sang anak, agar mereka mau berdamai. Karena merasa putus asa, tawaran itu hampir saja diterima.
“Bahkan keluarganya sempat kayak, ‘masa sih ada yang mau sama anak saya? Anak saya kan cacat’. Dari pemikiran itu kita berusaha membangun kembali pikiran yang lebih positif,” ungkap Adel pada (9/1).
“Mereka juga khawatir, ‘anak saya ini kalau nanti melahirkan gimana, enggak ada bapaknya?’ dan itu hampir bersedia berdamai, karena merasa bahwa, ‘ya udah anak saya dengan kondisi seperti itu syukur-syukur ada yang mau, ya dinikahkan saja’,” tambahnya.
Untungnya, sebelum orang tua korban menyerah, seorang tetangga yang mengetahui kasus ini melaporkan ke Adel. Dia kemudian datang untuk berdiskusi dengan orang tua dan menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak mau menikahkan anaknya dengan pelaku. Namun, usia kehamilan yang sudah lima bulan mendorong mereka untuk melakukannya.
Berbagai opsi Adel elaborasi di depan orang tua korban, hingga mereka akhinya setuju untuk melanjutkan proses hukum. “Mereka awalnya tidak bisa berpikir karena tidak tahu solusi lain. Setelah kita berikan pemahaman bahwa anak dalam kandungan kalau mau dirawat sendiri silakan, tapi kalau tidak sanggup karena faktor ekonomi, bisa libatkan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya.
Diskusi panjang itu pun harus dilapisi dengan pendampingan rutin. Adel tetap harus menjaga komunikasi dengan keluarga walau nampak sudah paham dan setuju. Komunikasi rutin, jelasnya, adalah cara supaya pikiran orang tua tidak berubah-ubah selama proses hukum. “Akhirnya tidak jadi, dan pelaku sudah menjadi terdakwa,” pungkas Adel.
Baca juga: Ramai-ramai Matikan Alarm Darurat Perkawinan Anak
Masalah yang Mengakar
Kasus yang ditangani Rusmiati dan Joko; serta Adel, berasal dari sumber yang sama: Perspektif masyarakat yang melihat pernikahan sebagai solusi. Kasus yang mereka hadapi hanya dua upaya intervensi dari banyak pernikahan anak yang berhasil diejawantahkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memotret NTB sebagai provinsi dengan perkawinan anak tertinggi pada 2023, dengan angka 17,32 persen, lebih besar dari dua kali angka nasional, yakni 6,92 persen. Joko mengatakan banyak orang tua di NTB, melihat anak sebagai beban finansial. Maka, untuk melepas beban, orang tua menikahkan anak mereka.
“Meskipun akhirnya yang terjadi sebaliknya. Kemiskinan menyebabkan perkawinan anak, di sisi lain perkawinan anak juga menyebabkan kemiskinan,” terang Joko.
Selain faktor ekonomi, hubungan yang dianggap ‘aib’ oleh masyarakat juga menjadi salah satu alasan orang tua menikahkan anak. “Apalagi sampai hamil. Enggak ada ceritanya di NTB kalau anak hamil dibiarkan saja dan diasuh sendiri, pasti dicari siapa yang menghamili lalu kemudian dinikahkan,” lanjutnya.
Anggapan ‘aib’ untuk hubungan romansa remaja dan korban pemerkosaan ini adalah produk dari peraturan adat di Lombok atau biasa disebut Awik-Awik. Terdapat beberapa larangan dalam Awik-Awik yang mengikat penduduk bahkan untuk hal yang sangat mikro, seperti pulang terlalu larut dengan lawan jenis. Hukuman untuk perilaku tersebut misalnya, adalah menikahkan pelanggar.
Meski penerapannya sudah tidak terlalu ketat, Adel mengungkap, Awik-Awik menyublim di benak masyarakat dan menjadi peraturan tidak tertulis. “Walaupun sebenarnya sudah enggak banyak ada di desa-desa, tapi pada akhirnya bergeser jadi masalah sosial, di mana masyarakat kita dapat dengan mudah melihat sesuatu sebagai aib, penghakminan terhadap seseorang menjadi sangat tinggi,” kata Adel.
Di tengah normalisasi perkawinan sebagai solusi dan hukuman untuk anak, upaya intervensi memiliki urgensi yang tinggi. Proses pendampingan untuk merubah pola pikir seperti yang dilakukan Adel, harus lebih banyak dilakukan. Alih-alih menerima tawaran damai, pelaku harus dibawa ke tempat yang seharusnya: Meja hijau.
Sementara itu, kasus yang ditangani Rusmiati dan Joko, masih dalam proses penyidikan. “Penyidikan kasus ini masih terus berjalan,” ucap kasubdit Renakta Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati pada Jumat (17/1), dilansir dari Rri.co.id. Jika berhasil, Joko berharap, intervensi hukum yang sedang dilakukannya bisa menjadi terobosan untuk kasus-kasus perkawinan anak ke depan.






















