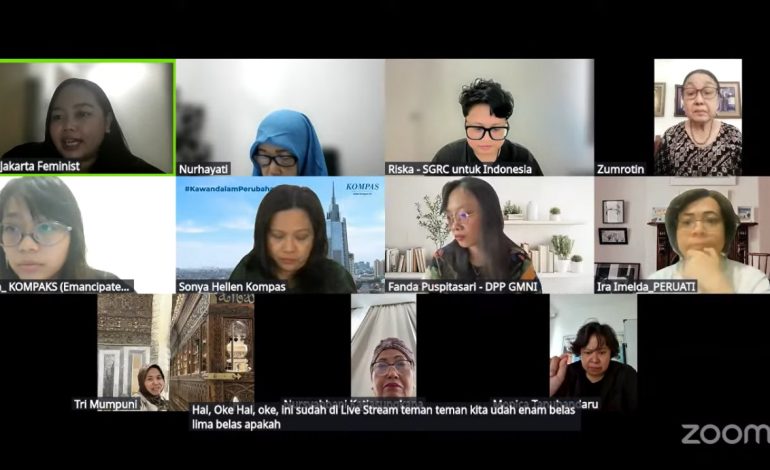Logika Neoliberal Joko Anwar dalam ‘Pengepungan di Bukit Duri’

“Kalau ditanya bagaimana agar kita tidak menuju 2027 lewat film ini, tentu kita buat film ini tidak untuk menyelamatkan dunia. Kita buat film ini untuk membuka mata, that’s it,” ucap Joko Anwar di siaran Space ‘Percakapan Setelah Pengepungan’ lewat akun pribadi X-nya (22/4).

Pernyataan itu hanya satu dari banyak pembelaan yang dia jabarkan selama hampir seminggu—di minggu pertama filmnya rilis—siaran live di X. Di sana, ia coba merangkum respons penonton setelah menonton film itu, sekaligus memberi jawaban buat mereka yang membawanya sepulang dari bioskop. Sesuatu yang tak banyak dilakukan sutradara.
Joko tampaknya sadar bahwa Pengepungan di Bukit Duri tidak menyediakan jawaban atas permasalahan kemanusiaan yang ia resahkan. Dan ingin terus berdiskusi dengan penonton agar bisa memahami yang ingin ia sampaikan lewat film itu. Tapi, kenapa?
Baca juga: ‘Pengepungan di Bukit Duri’: Ada Kritik Atas Heteronormativitas dan Peran Ayah yang Gagal
Ada Apa dengan Etnis Tionghoa dalam Film Joko?
Sosiolog Johan Galtung dalam Peace by Peaceful Means pernah bilang, “Death and mortality contradict survival needs; misery and morbidity negate well-being needs; alienation negates identification needs; and repression negates freedom needs.” Galtung menegaskan bahwa kekerasan bukan hanya tentang darah dan korban jiwa, tetapi juga tentang sistem yang secara konsisten mengingkari kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak, diakui, dan merdeka.
Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa kekerasan pada etnis Tionghoa di Indonesia sudah terjadi sejak masa kolonialisme. Kekerasan ini bukan semata lahir dari dominasi mereka di sektor tertentu. Negara secara aktif membentuk struktur sosial-politik yang membuat posisi etnis Tionghoa tampak menonjol dan terasing. Posisi ini membuka ruang untuk sentimen dan mewujud dalam berbagai bentuk kekerasan (Dahana, 2004).
Ignasius Loyola Adhi Bhaskara, dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, menyatakan bahwa regulasi-regulasi yang mendiskriminasi warga keturunan Tionghoa merupakan bagian dari kekerasan struktural yang dilakukan oleh negara. Narasi dominasi ekonomi etnis Tionghoa tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang menciptakan ketimpangan, sekaligus menjadikan mereka kambing hitam saat krisis melanda.
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, segregasi struktural dirancang sedemikian rupa dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling. Ia membagi penduduk Hindia-Belanda jadi golongan Eropa, Bumiputera, dan Timur Asing. Golongan Timur Asing kemudian dibagi atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa seperti Arab dan India (Suhardana, 2001 dalam Priyanti, 2019).
Simanjuntak (1999), seperti dikutip dalam Lailawati (2020), menyebut strategi ini sebagai “politik pembodohan” agar penduduk menerima hierarki dan sekat-sekat sosial yang menguntungkan penjajah. Kelompok Tionghoa, lewat kebijakan Wijkenstelsel, dipaksa tinggal dalam pemukiman yang terpisah (kampung pecinan), dan dikenakan Passenstelsel, yaitu kewajiban memiliki izin khusus untuk bepergian (Martinus et al., 2018).
Alih-alih menghapus diskriminasi warisan kolonial, pemerintah era Orde Baru justru melanggengkannya. Giblin (2003) dalam studinya mencatat, lewat kebijakan asimilasi, rezim Soeharto menuntut etnis Tionghoa untuk melebur ke dalam identitas nasional yang didefinisikan secara sempit.
Instruksi Presiden No 14 Tahun 1967 melarang segala bentuk ekspresi budaya Tionghoa di ruang publik, dari perayaan keagamaan, penggunaan aksara Mandarin, hingga penerbitan media berbahasa Tionghoa. Sementara Keputusan Presiden No 240 Tahun 1967 mendorong penggantian nama-nama Tionghoa dengan nama “Indonesia” sebagai simbol integrasi. Pemerintah pun membatasi akses mereka ke universitas negeri dan menutup sekolah-sekolah swasta berbasis budaya Tionghoa.
Diskriminasi yang dibiarkan menumpuk selama puluhan tahun ini akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan massal. Purdey (2006) dalam Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996-1999 mencatat Tragedi Kerusuhan Mei 1998 sebagai puncak kekerasan anti-Tionghoa dalam sejarah Indonesia. Penjarahan, pembakaran, pemerkosaan massal, dan pembunuhan yang dilakukan terhadap warga keturunan Tionghoa sampai saat ini tidak pernah diproses secara hukum.
Konteks di atas tidak hadir baik dalam teks maupun konteks dalam Pengepungan di Bukit Duri. Meski begitu, elemen historis 1998 ini dipinjam film itu sebagai inspirasi untuk menampilkan kekerasan dan sinisme pada etnis Tionghoa.
Joko, yang dalam promo-promo film ini, menyebut mengalami Tragedi Kerusuhan Mei 1998 secara langsung. Ia merasa ada keengganan di tengah masyarakat untuk membicarakan peristiwa ini. Rasa enggan itu ia nilai merawat sentimen terhadap warga keturunan Tionghoa sampai sekarang. Film ini ia harap dapat membuka lagi percakapan-percakapan atas “hal yang belum selesai”.
Tapi, muncul pertanyaan: percakapan apa yang akhirnya muncul?
Baca juga: Edwin Tidak Sendiri: Luka, Politik Identitas, dan Sinema yang Berpihak
Neoliberalisme dan Komodifikasi Trauma
Revrisond Baswir, pakar Ekonomi Kerakyatan, menilai sejak masa penjajahan, Indonesia telah diwarisi struktur sosial dan politik yang timpang. Kekuasaan dan kekayaan di negeri ini terkonsentrasi di tangan segelintir elite. Warisan kolonial ini tidak hanya membentuk relasi kuasa antara penguasa modal dan rakyat, tetapi juga menanamkan fondasi bagi sistem ekonomi yang eksploitatif.
Corak perekonomian bercita rasa kolonial terus berlanjut bahkan setelah kemerdekaan. Pada rezim Orde Baru, ideologi pembangunan-isme menyerap prinsip-prinsip kapitalisme global seperti swastanisasi, pembukaan pasar, dan pelemahan peran negara dalam menjamin kesejahteraan. Negara tidak lagi diposisikan sebagai pelindung kepentingan publik, melainkan sebagai fasilitator bagi kepentingan modal.
Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia mencatat krisis ekonomi 1997 menjadi titik krusial neoliberalisme, melalui tekanan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, mulai diterapkan secara sistematis. Atas nama pemulihan ekonomi, pemerintah menjalankan kebijakan liberalisasi sektor keuangan, privatisasi BUMN, dan penghapusan berbagai subsidi sosial (Majidi & Rizky, 2008).
Globalisasi sering dijadikan kendaraan utama penyebaran agenda neoliberalisme secara kultural maupun ekonomi. Ia meresap ke dalam kebijakan makro, sekaligus membentuk nilai, budaya, dan cara berpikir masyarakat, terutama dalam melihat dunia sebagai pasar tunggal tempat individu dituntut terus bersaing.
Dalam budaya populer, pengalaman personal, terutama trauma, bisa dengan mudah diserap oleh sistem kapitalis dan dijauhkan dari makna politiknya. Lebih dalam lagi, proses ini tidak lagi hanya soal depolitisasi trauma dan menjualnya, tapi menyangkut cara neoliberalisme bekerja dan menata ulang cara kita memahami pengalaman.
Alison Phipps, seorang profesor sosiologi dari Newcastle University, dalam esai Neoliberalism and the commodification of experience menyebut bahwa neoliberalisme “individualises, interiorises, and neutralises“. Neoliberalisme mendorong kita untuk memandang luka dan penderitaan sebagai sesuatu yang harus ditangani secara individual, bukan dibaca sebagai bagian dari kekerasan struktural yang sistemik.
Trauma dan penderitaan yang direpresentasikan di media seperti film dan televisi, menurut Lilie Chouliarki dalam The Spectatorship of Suffering, memungkinkan terciptanya spectator–sufferer relationships atau hubungan kuasa antara sutradara dan penonton. Kisahnya diproduksi sedemikian rupa untuk menggerakkan simpati penonton sebagai pusat afeksi. Oleh karenanya, penderitaan orang lain harus di-render secara emosional agar dapat diterima secara etis oleh penonton yang jauh secara geografis dan historis dari subjek penderitaan itu.
Pengepungan di Bukit Duri secara sadar bergerak dalam logika ini. Dalam sebuah wawancara, Joko menyebutkan, “Kenapa nggak dikupas banget [soal tragedi ‘98], karena akan se-segmented itu. Filmnya nggak akan bisa merangkul banyak penonton. Maka, kita susupi ke genre yang populer, yaitu thriller dan action.”
Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam upayanya memediasi sejarah, film ini lebih memilih menyesuaikan diri pada selera pasar ketimbang mendorong pembacaan kritis terhadap akar struktural dari kekerasan yang diangkat. Praktik ini memperkuat cengkraman neoliberalisme dalam ranah budaya dan produksi pengetahuan.
Lingkaran Kekerasan di Ruang Pendidikan
Dalam Pengepungan di Bukit Duri, latar waktu dibentangkan dari tahun 2009—saat Edwin (Morgan Oey) masih pelajar SMP dan menyaksikan kerusuhan—lalu lompat ke 2027, saat ia menjadi guru dan mengalami kerusuhan kembali.
Perjalanan hidup Edwin, dari siswa menjadi guru, menunjukkan betapa erat kaitannya antara pendidikan dan kekerasan struktural. Joko Anwar, dalam komentarnya, mengamini gagasan bahwa sistem pendidikan kita menyimpan lingkaran kekerasan (circle of violence) yang terus-menerus diwariskan. Ia pun menyebut budaya korupsi dan kekerasan yang menggerogoti negara ini, salah satunya akibat kegagalan sistem pendidikan.
SMA Bukit Duri adalah potret kecil dari masyarakat yang dibiarkan gagal oleh sistem. Di bawah logika neoliberalisme, sistem yang terpusat pada pasar hanya akan menciptakan orang yang lebih tertarik pada pencapaian individu yang terpisah dari nilai-nilai kolektif. Menurut Anggi Afriansyah, peneliti Sosiologi Pendidikan, narasi dominan dalam pendidikan di Indonesia pasca-Reformasi adalah narasi investasi untuk menghasilkan manusia-manusia “siap kerja” sesuai kebutuhan industri, bukan sebagai ruang emansipasi.
Salah satu yang disebut Anggi sebagai salah kelola pencerdasan di negeri ini, yaitu penekanan pada pendisiplinan siswa. Kebiasaan seperti merazia rambut, menghukum siswa karena seragam tidak sesuai, atau mewajibkan hormat pada simbol tanpa memahami maknanya, mencerminkan pola discipline and punish milik Foucault. Ini bukti sekolah lebih menekankan kepatuhan ketimbang pembentukan karakter yang utuh. Sekolah, sebagai alat pembinaan yang teknokratik, tidak membentuk warga negara yang mampu berpikir mandiri, memahami sejarah bangsanya secara utuh, dan berdaya secara sosial-politik.
Akhirnya, pendidikan dijadikan alat untuk mempertahankan relasi produksi yang tidak adil. Dalam suasana pendidikan yang terpinggirkan dan terisolasi seperti di SMA Bukit Duri, hal ini justru merawat kekerasan. Dalam film ini, Joko sepertinya merasa tak perlu membongkar kenapa sistem pendidikan kita diracuni neoliberalisme, dan repot-repot meramu obat penawarnya dalam film ini. Dalam banyak hal, ia justru meneruskan logika neoliberalisme ini sebagai perangkat naratif agar dunia dalam Pengepungan di Bukit Duri jadi cerminan dunia nyata.
Misalnya, bagaimana SMA Bukit Duri didesain seperti penjara buat anak-anak “bermasalah”. Kekerasan, dalam film ini, jadi satu-satunya jalan keluar yang dipahami dan warisi murid-murid di sana. Sehingga melawan guru, tidak menurut saat di kelas, atau bahkan berkata kotor pada guru, jadi lumrah dalam logika Pengepungan di Bukit Duri. Di titik ini, naskah Joko bahkan terasa mendramatisasi logika neoliberal itu agar kenakalan ekstrem murid-murid itu terasa wajar.
Di satu adegan, Jefri (Omara Esteghlal) tertangkap melakukan percobaan penusukan ke Edwin pada malam hari, sepulangnya Edwin dari bar di Pecinan. Ketika tahu Edwin akan melaporkannya ke Kepala Sekolah, Diana (Hana Pitrashata Malasan), rekan gurunya, berusaha menghentikan Edwin. “Harusnya dari awal kamu gak usah ladenin dia,” kata Diana.
Yang dikatakan sang Kepala Sekolah (Landung Simatupang) pada Jefri dalam adegan selanjutnya lebih menyakitkan. Saat tahu Jefri menusuk Edwin, ia mengeluarkan Jefri dari sekolah dan bilang, “Seharusnya orang tua kamu tidak usah pernah melahirkan kamu.”
Dari sikap Diana yang memilih jalur aman, menghindar, membiarkan kekerasan berlangsung, sampai Kepala Sekolah yang menganggap kekerasan Jefri adalah kesalahan individu, film makin terasa memanfaatkan logika kekerasan sebagai bagian dari pembangunan semesta (worldbuilding).
Sekolah membiarkan relasi kuasa antara siswa beroperasi tanpa intervensi, sehingga kekerasan remaja cuma dibaca sebatas “kenakalan remaja”, bukan produk struktur.
Seperti yang Joko sebut di salah satu siaran live-nya di X, film memang tidak punya beban untuk memberi solusi. Itu sebabnya, usaha Joko memotret realitas dan mendramatisasinya bisa dibaca sebagai bentuk kritik terhadap logika neoliberalisme dalam pendidikan yang dapat menelurkan dan memelihara kekerasan.
Film Indonesia yang Dikepung dan Dibingkai Buat Mata Pasar Neoliberal
Jika melihat para pendahulunya dalam kategori film bertema kekerasan, The Raid (2011) dan The Raid 2: Berandal (2014) menonjol sebagai contoh ekstrem bagaimana kekerasan ditampilkan dengan gaya yang estetis dan koreografis.
Produser film The Raid, Ario Sagantoro, pada Viva menyatakan film ini memikat distributor Amerika Serikat, Sony Picture Classics, karena film ini “orisinal dan eksotik” dengan silat menjadi daya tariknya. Sekuelnya, The Raid 2: Berandal, bahkan tidak hanya dibeli oleh distributor yang sama, tetapi juga berhasil menembus Sundance Film Festival 2014, memperkuat posisinya sebagai komoditas budaya yang laku di pasar global.

Dalam konteks ini, budaya diposisikan sebagai aset yang dapat dikapitalisasi. bell hooks dalam esainya Eating the Other: Desire and Resistance menyoroti bahwa ketika budaya liyan dikomodifikasi, pesan-pesan sosial dan sejarah yang melekat padanya sering kali diabaikan atau disederhanakan. Hal ini menciptakan ilusi bahwa keberagaman dihargai, padahal sebenarnya hanya dimanfaatkan untuk memenuhi hasrat pasar tanpa memberikan ruang bagi pemahaman yang mendalam.
Fenomena serupa dapat dilihat dalam Pengepungan di Bukit Duri, yang kolaborasi produksinya melibatkan Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), salah satu studio besar Hollywood. Hollywood gemar mengemas narasi dari dunia ketiga yang menyorot kemiskinan, ketidakstabilan sosial, atau konflik etnis sebagai produk eksotik yang bisa dikonsumsi.
Ini adalah manifestasi dari logika neoliberal sebagaimana dijelaskan Alison Phipps, di mana budaya dan penderitaan pun menjadi komoditas, selama ia tidak mengganggu status quo global.
Namun, di balik keberhasilannya menembus pasar internasional, kekerasan brutal yang ditampilkan dalam film-film ini menyimpan dampak serius di dalam negeri. Penelitian Gumay (2016) menunjukkan adanya pengaruh signifikan paparan kekerasan dalam The Raid 2: Berandal terhadap meningkatnya agresivitas siswa-siswi sebuah SMA di Samarinda. Agresivitas di sini merujuk pada tindakan yang bersifat negatif, keras, kasar, dan merusak, tanpa memperhitungkan konteks atau alasan di baliknya.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Eyal et al. (2006), bahwa remaja yang secara rutin mengonsumsi media, dalam konteks ini tayangan televisi, penuh kekerasan cenderung lebih mendukung solusi represif terhadap isu-isu sosial dan politik. Misalnya, dukungan terhadap hukuman fisik yang keras, tindakan militer terhadap kelompok sipil, atau pembatasan kebebasan sipil.

Meskipun Pengepungan di Bukit Duri memiliki konteks kritik sosial, jika tidak dikritisi secara aktif, film ini berisiko dimaknai secara dangkal hanya sebagai tontonan aksi yang seru dan penuh adrenalin. Kekhawatiran saya kian meninggi ketika Joko, dalam masa promosi film, mem-posting video sekelompok anak STM yang menonton bersama film Pengepungan di Bukit Duri.
Kita tahu dalam berbagai pemberitaan, anak STM sering muncul dalam konteks demonstrasi yang ricuh atau bentrok antarpelajar. Anak-anak STM yang telah lama termarjinalkan dan dicap negatif bisa jadi justru mengidentifikasi diri dengan representasi kekerasan dalam film, melihatnya sebagai bentuk pembenaran atas kemarahan sosial mereka. Ini adalah risiko nyata yang harus dihadapi, mengingat betapa film bisa berperan dalam membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu (Gupta et al., 2024).
Relasi Kuasa dan Politik Penafsiran dalam Film
Menurut saya, di sini letak potensi yang dilewatkan oleh Joko Anwar sebagai sutradara: Alih-alih menelusuri jejak kekuasaan yang menciptakan dan memelihara kekerasan, ia justru membiarkan narasi konflik berputar di antara korban. Ia membiarkan warga sipil sebagai karakternya “bermain” dalam parade kekerasan tanpa menunjukkan sumber konfliknya.
Misalnya, ada adegan ketika warga memprovokasi dengan teriakan rasis seperti “Babi” dan “Cina” ke arah massa aksi yang memegang spanduk bertuliskan “Say No to Racism” di depan stasiun kereta. Atau ketika poster “Stop Rasisme” ditemukan di dalam kereta. Di momen lain, Edwin terlihat menonton siaran berita dengan headline “Bahaya Konflik Horizontal Semakin Tinggi”. Detail kecil seperti itu yang justru membangun kesan bahwa akar dari kekerasan tersebut adalah intoleransi individual semata.
Saya ingat dalam beberapa siaran live di Space-nya, Joko mengakui bahwa kekerasan dalam Pengepungan di Bukit Duri bukan sekadar konflik horizontal antarsipil, tapi sesuatu yang diciptakan dan dipelihara oleh sistem untuk dimanfaatkan sewaktu-waktu. Sayangnya, kesadaran itu tidak terpancar dalam filmnya.
Dalam struktur relasi kuasa, posisi Joko sebagai pembuat film bukanlah netral. Ia punya agensi dan akses untuk menentukan arah kritik. Namun dalam Pengepungan di Bukit Duri, kekuasaan struktural nyaris tak hadir, seolah-olah kekerasan adalah keniscayaan sosial, bawaan masyarakat bukan hasil produksi politik.
Ketika neoliberalisme merasuk ke semua lini kehidupan, termasuk cara kita membuat, menonton, dan memaknai film, maka sinema juga bisa menjadi alat perlawanan, tapi dengan catatan: Ia harus sadar diri dan tahu medan yang dilawannya.
Pengepungan di Bukit Duri beredar dalam sirkuit distribusi bioskop yang masih diatur oleh logika pasar. Promosi yang mengandalkan respons viral dan kritik sosial yang dibingkai sebagai bagian dari nilai jual adalah ekosistem neoliberal yang mendaur ulang kekritisan menjadi komoditas. Kritik menjadi tontonan. Trauma menjadi hiburan intelektual. Dan ruang gugatan menjadi performatif, bukan transformatif.
Tak seperti Pengepungan di Bukit Duri, La Haine (1995) karya Mathieu Kassovitz menolak logika komodifikasi. Ia hitam putih, tidak menyenangkan, tidak menawarkan resolusi, dan penuh rasa tidak nyaman. Tapi justru karena itu ia berhasil memancing kesadaran politis.
La Haine mengikuti tiga pemuda dari pinggiran kota Paris (banlieue): Vinz (Yahudi), Saïd (Arab), dan Hubert (Afro-Prancis). Mereka hidup dalam kemiskinan, ketegangan rasial, dan kekerasan struktural setelah kerusuhan yang dipicu oleh kebrutalan polisi.
Konflik vertikal dalam La Haine adalah cerminan ketegangan antara warga sipil yang terpinggirkan dan institusi negara yang seharusnya melindungi mereka. Kedua pihak ada di layar: yang tertindas dan yang menindas. Dalam wawancara dengan France 24, Kassovitz menggambarkan La Haine lebih sebagai “reportase sinematik” daripada fiksi, dengan tujuan menampilkan kondisi nyata masyarakat yang sering diabaikan oleh media arus utama.
Pengepungan di Bukit Duri, di lain sisi, justru menciptakan bentuk alienasi baru yang pasif, gamang, dan permisif. Saya melihat yang terjadi dengan film ini, tanggung jawab untuk memahami, mengolah, dan menggugat diserahkan seluruhnya kepada publik yang sebagian besar tidak memiliki akses terhadap wacana dan literasi sejarah. Ketika banyak kritik masuk soal pembacaan sejarahnya, Joko menyerahkan beban tafsir kepada publik sambil menjaga jarak aman dari posisi ideologis.
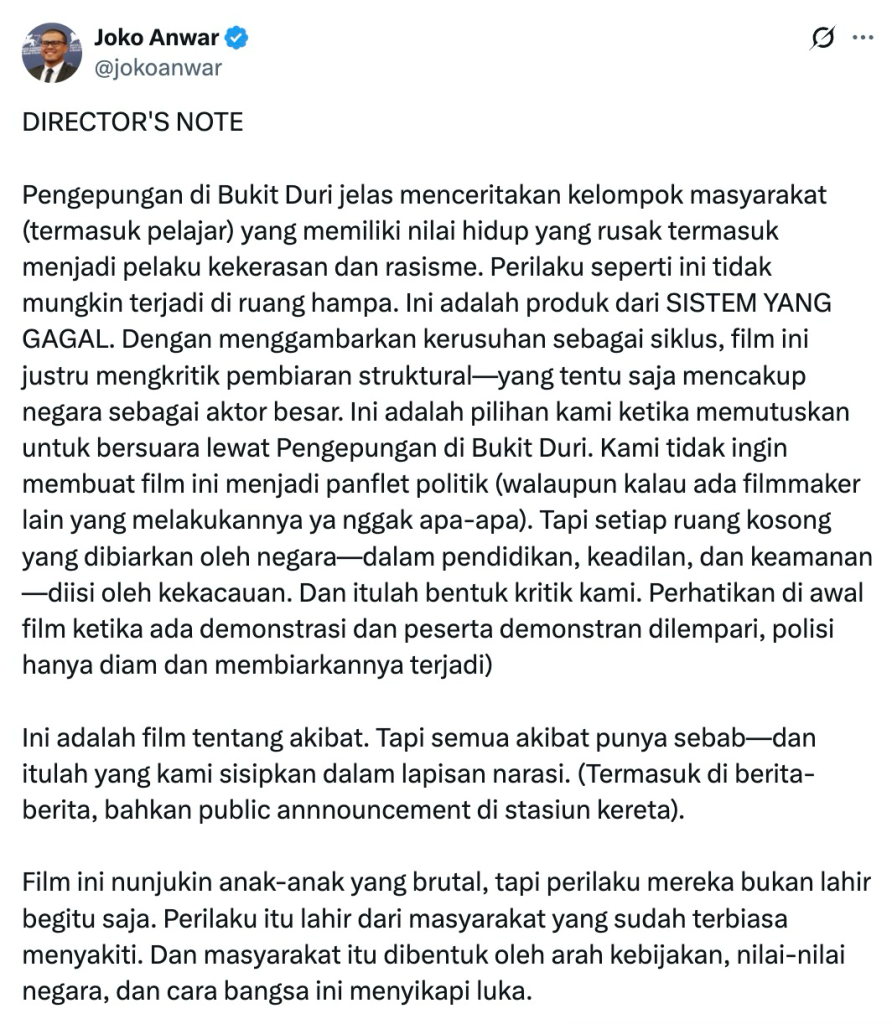
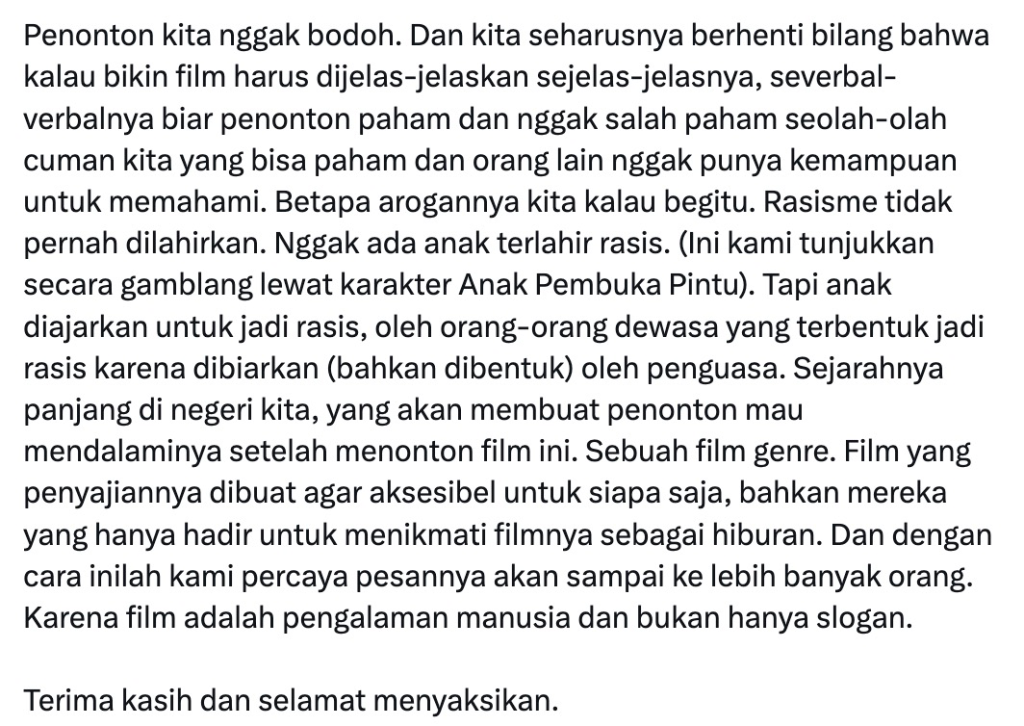
Pada saat posisinya sebagai sutradara digugat, Joko merilis director’s note di akun X-nya yang justru menuntun interpretasi penonton pada bacaan tertentu. Ia menolak didaktisme, menolak menjelaskan “severbal-verbalnya”, tapi juga menyuguhkan banyak informasi visual dan naratif yang cukup eksplisit memperjelas konteks sosial yang ingin disampaikan.
Dalam hal ini, Joko tampaknya luput menyadari bahwa gugatan dari penonton sebetulnya adalah respons langsung dari ajakannya sendiri: untuk membicarakan hal-hal yang ia sebut sebagai “tidak nyaman” bagi bangsa ini. Alih-alih membiarkan wacana itu tumbuh secara kolektif dan organik, ia malah menempatkan dirinya dalam posisi yang nyaris mirip dengan institusi negara, sebagai kurator atas bagaimana luka sejarah bisa dan boleh diakses publik.
Joko menutup film ini dengan suara penyiar radio 98.5 FM di tengah kerusuhan, “Tidak ada yang benar-benar tahu kenapa ini bisa terjadi.” Di saat kita, penonton, dan Joko, sebetulnya sama-sama tahu negara lah aktor utama yang merancang dan memperpanjang rantai kekerasan terhadap etnis Tionghoa ini. Kita bisa lihat Aksi Kamisan, misalnya, yang terus berlangsung setelah 27 tahun reformasi, sebagai bukti bahwa negaralah yang aktif sebagai arsitek kekerasan. Aksi damai itu berlangsung berdekade-dekade, tanpa kekerasan, sekaligus tanpa perhatian negara.
Ketika filmnya mengaburkan peran negara dalam sejarah panjang kekerasan terhadap etnis Tionghoa, Joko justru mereproduksi sikap abai yang selama ini dipraktikkan oleh negara itu sendiri. Sinema seharusnya dapat menjadi ruang tanding bagi narasi dominan.
Sebagai pembanding, film pendek Laut Bercerita (2017) karya sutradara Pritagita Arianegara yang diangkat dari novel karya Leila S. Chudori sama-sama berlatar kekerasan politik 1998. Namun, film pendek itu menawarkan pendekatan yang jauh lebih reflektif. Meskipun fiksi, film ini disadari oleh para pembuatnya sebagai produk dari keputusan politik, bukan semata keputusan estetika.
Dalam sebuah sesi pemutaran, produser Laut Bercerita secara eksplisit menolak untuk memutar film ini di platform streaming atau kanal distribusi massal, karena merasa bertanggung jawab untuk selalu menyertai pemutaran dengan diskusi. Praktik ini menunjukkan kesadaran akan relasi kuasa antara film, pembuatnya, dan penonton, bahwa narasi trauma tidak bisa dilepas begitu saja ke publik tanpa kerangka pembacaan yang kritis.
Di tengah rezim yang terus berupaya menghapus sejarah, representasi menjadi medan penting bagi perebutan makna dan ingatan. Keputusan Joko Anwar untuk menempatkan konflik horizontal Pengepungan di Bukit Duri dalam genre populer bukanlah tindakan yang bebas nilai. Ia mungkin bisa merakit cara kita mengingat, tapi tidak cara kita menggugat.