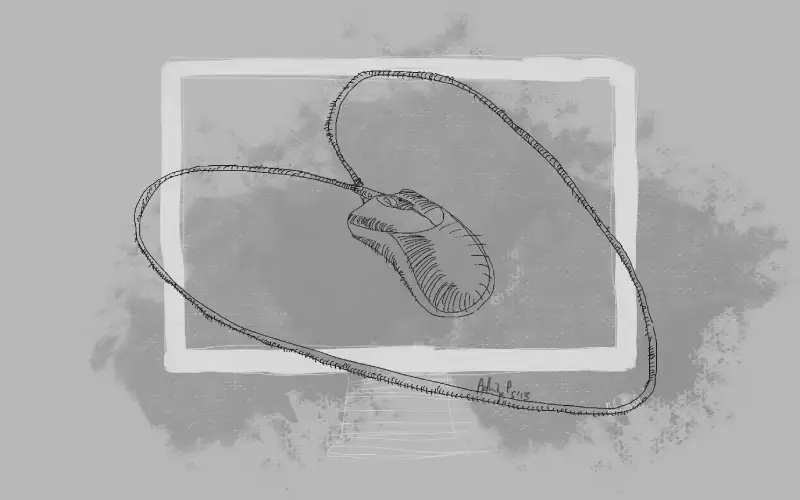Cinta Bukan Strategi: Menelisik Standar Relasi ala TikTok
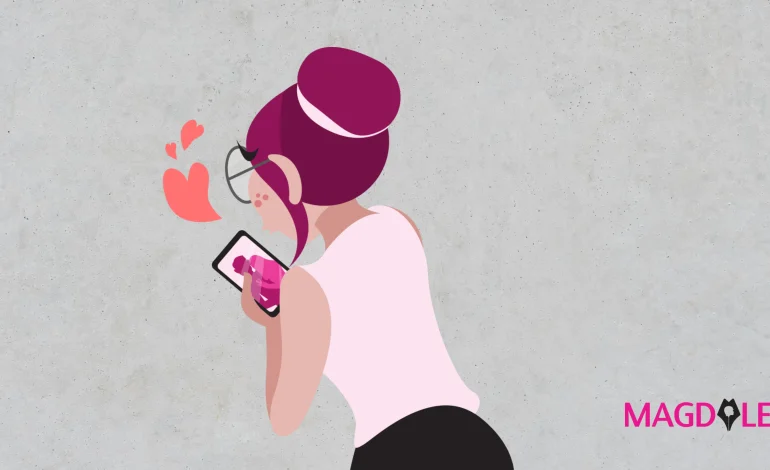
Butuh waktu lama bagi saya untuk mencerna berbagai standar hubungan yang beredar di media sosial. Belakangan ini, cara kita merawat relasi romantis tampak diwarnai oleh norma-norma baru yang tidak tertulis dan tak jarang justru dipopulerkan lewat TikTok dan lini masa media sosial lain.
Salah satunya muncul dari seorang influencer yang muncul di beranda saya. Dengan nada yakin, ia menyatakan bahwa perempuan harus memastikan laki-laki mengeluarkan banyak materi demi hubungan. Tujuannya agar si laki-laki merasa rugi kalau harus melepaskan hubungan tersebut.
Awalnya, pernyataan ini tak begitu mengganggu. Namun makin saya pikirkan, semakin absurd rasanya menjadikan hubungan sebagai strategi ekonomi. Menurut sang influencer, hubungan romantis merupakan investasi layaknya bisnis. Semakin banyak uang yang dikeluarkan laki-laki, semakin besar peluang perempuan “mempertahankan” hubungan itu. Tapi, benarkah cinta bekerja seperti itu?
Logika transaksional dan komodifikasi cinta
Sebuah artikel berjudul “Love is a commodity” (2025) di laman University of California, Irvine, menyebut bahwa cinta kini semakin dilihat dari kacamata transaksi. Keseriusan dan kedalaman cinta diukur berdasarkan nilai materi yang diberikan. Orang yang tepat adalah dia yang menunjukkan effort dalam bentuk uang, hadiah, atau gestur besar lainnya.
Hal serupa dibahas dalam riset The Commodification of Love in Neoliberalism: Affect, Attachment, and Desire (2025). Riset ini menyatakan bahwa di era sekarang, cinta telah bertransformasi menjadi komoditas. Ia dikelola dengan logika persaingan dan strategi, bukan sekadar soal perasaan. Cinta menjadi sesuatu yang bisa “dipasarkan” atau bahkan “dipertukarkan”.
Dalam konteks ini, wajar jika tren media sosial mendorong narasi bahwa kasih sayang harus dibuktikan melalui pemberian materi, baik itu bunga, cincin, hadiah valentine, atau sekadar gestur romantis viral. Ukuran keberhasilan kencan pun jadi seberapa besar “nilai tukar” yang diterima perempuan.
Namun ketika standar ini diarahkan secara sepihak kepada perempuan, terselip beban gendered emotional labor. Riset tadi menyebut, di media sosial, perempuan kerap jadi pihak yang harus “mengelola” kualitas hubungan. Perempuan lah yang dituntut memastikan pria memberikan effort, dan perempuan juga yang harus tahu kapan hubungan butuh “investasi lebih”. Seolah keberhasilan hubungan hanya terletak di pundak perempuan.
Baca juga: ‘Bibit Bebet Bobot’ Plus Anti-Kekerasan: Kriteria Tambahan Perempuan Mencari Pasangan
Adakah cara terbaik untuk mencintai?
Di tengah tren cinta yang dikomodifikasi ini, pemikiran Erich Fromm dalam bukunya The Art of Loving (1965) terasa akurat. Fromm mengkritik cara cinta dipahami sebagai sesuatu yang bisa dimiliki, dijual, atau dimenangkan. Menurutnya, cinta bukan soal strategi untuk dicintai balik, melainkan soal kapasitas untuk mencintai.
Ia menyebut bahwa mencintai adalah seni, bukan transaksi. Sebuah relasi yang sehat tumbuh dari empati, penghormatan, tanggung jawab, dan kesabaran. Cinta bukan tentang seberapa besar hadiah yang diberikan, tapi seberapa jauh kita berkembang dalam hubungan itu, baik terhadap diri sendiri maupun pasangan.
Senada dengan Fromm, Alain de Botton dalam Essays in Love (2014) juga menyatakan bahwa cinta tak selalu membawa kepuasan sempurna. Justru di dalamnya ada ketidaksempurnaan, proses belajar, dan ruang untuk tumbuh bersama. Cinta bukan pengejaran atas kebahagiaan ideal, tapi keberanian untuk hadir dan bertumbuh dengan orang lain dalam realitas yang kompleks.
Baca juga: ‘Nge-date In This Economy’: Rela Kurangi ‘Budget’ Kencan demi Masa Depan
Kita boleh saja menikmati konten TikTok yang lucu atau relatable tentang hubungan. Tapi kita juga perlu waspada saat standar-standar ini berubah jadi tuntutan yang merusak relasi itu sendiri. Cinta bukan kompetisi hadiah terbesar atau siapa yang paling banyak berkorban. Ia adalah proses panjang, penuh kompromi dan pemahaman.
Mungkin tak ada satu cara yang paling benar untuk mencintai. Tapi yang pasti, menjadikan cinta sebagai strategi ekonomi bukanlah satu-satunya jalan menuju hubungan yang sehat.