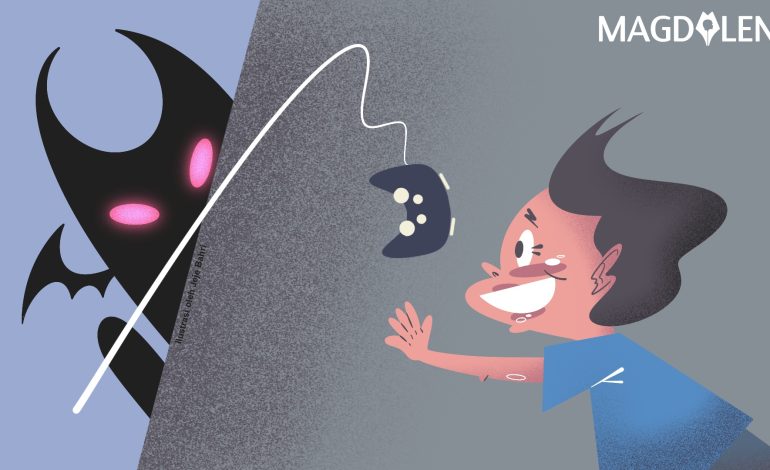Janji di Balik Nikah Siri: Cinta, Celah Hukum, dan Perempuan yang Selalu Dirugikan

Di linimasa kita, nama perempuan sering kali hanya muncul untuk dua hal: dipuji setinggi langit atau dijatuhkan sedalam-dalamnya. Belum lama ini, publik masih terbelah soal Inara Rusli, perempuan yang mencoba bangkit setelah dikhianati sang suami. Belum selesai juga sorotan terhadap Helwa Bachmid, yang mengaku sebagai istri siri seorang tokoh agama, lalu diseret ke jurang penghinaan publik saat hubungannya memburuk.
Dua kasus itu mungkin terlihat seperti kisah berbeda. Namun sesungguhnya, mereka memiliki benang merah yang sama: perempuan sebagai pasangan kedua, laki-laki yang memanfaatkan celah hukum, dan masyarakat yang menjadikan perempuan kambing hitam setiap kali ada konflik rumah tangga.
Masyarakat kita terlalu sering menyederhanakan nikah siri sebagai perkara sah atau tidak sah menurut agama. Padahal, masalahnya jauh lebih kompleks.
Secara hukum, Indonesia memang membuka ruang bagi poligami. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memperbolehkannya dengan syarat: izin istri pertama, izin pengadilan, bukti kemampuan finansial, dan komitmen berlaku adil. Konsepnya tampak ideal: hukum hadir sebagai pelindung perempuan. Namun kenyataan di lapangan berkata lain.
Banyak laki-laki memilih jalan pintas. Cukup akad di ruang tamu dengan saksi seadanya, lalu selembar surat bermeterai sebagai “bukti nikah.” Tak ada pencatatan ke negara. Tak ada perlindungan hukum bagi perempuan.
Kasus Inara menunjukkan sisi rapuh dari skema ini. Saat suaminya menikah siri, ia masih tercatat sebagai suami sah secara hukum. Maka, nikah siri bukan tameng, melainkan senjata. Pasal 284 KUHP tentang perzinaan bisa diberlakukan, dan istri sah memiliki hak penuh untuk melapor. Ironisnya, dalam pusaran konflik, laki-laki bisa “menyesal” sebentar, lalu pulih secara sosial. Tapi perempuan siri akan dihukum berkali lipat—oleh hukum, oleh publik, oleh warganet yang hobi merajam dengan komentar penuh kebencian.
Sementara dalam kasus Helwa, kita melihat sisi gelap lainnya. Saat hubungan berakhir, statusnya sebagai istri tak diakui negara. Ia tak punya dasar hukum untuk menuntut nafkah, hak asuh, apalagi pembagian harta. Semuanya bergantung pada niat baik laki-laki. Ketika cinta usai, pernikahan itu lenyap tanpa jejak, seolah tak pernah ada.
Baca Juga: Ada KDRT di Pernikahan Muda
Nikah siri, perempuan, dan ketimpangan struktural
Dua sisi yang tampak berlawanan—satu dipidana, satu ditinggalkan—sesungguhnya menunjukkan ketimpangan yang sama. Perempuan dalam pernikahan siri nyaris tak punya posisi aman. Jika istri sah diam, mereka tetap tak punya perlindungan. Jika istri sah melapor, mereka bisa masuk penjara. Apa pun yang terjadi, risiko dan kerugian paling besar hampir selalu ditanggung perempuan.
Kerentanan ini bukan hanya menyentuh relasi orang dewasa. Anak yang lahir dari pernikahan tanpa pencatatan sering kali menghadapi hambatan administratif, stigma sosial, dan potensi penelantaran. Potongan film Pangku yang memperlihatkan anak gagal mendaftar sekolah karena tak jelas siapa ayahnya mungkin tampak seperti fiksi. Tapi di balik layar, itu adalah kisah nyata bagi banyak keluarga.
Tulisan ini bukan ingin menyalahkan agama atau mengharamkan cinta. Masalahnya bukan pada iman, melainkan bagaimana dalil sering dipakai sebagai jubah untuk menyembunyikan pernikahan, menghindari tanggung jawab, dan melempar kesalahan ke perempuan ketika semuanya tidak berjalan mulus. Frasa seperti, “Saya sudah talak secara agama, tinggal urus administrasi,” bukan lagi hal asing. Padahal perempuan berhak menjawab, “Kalau belum ada akta cerai dari pengadilan, kamu masih suami orang.”
Baca Juga: Nur Rofiah: Pernikahan yang Patriarkal adalah Konsep ‘Jahiliyah’
Perempuan berhak bertanya, meminta bukti, menolak, dan menjaga diri dari relasi yang hanya menawarkan cinta tanpa perlindungan. Kasus-kasus seperti Inara dan Helwa menunjukkan bahwa nikah siri bukan semata keputusan spiritual, melainkan zona abu-abu hukum dan budaya yang lebih sering menguntungkan laki-laki. Ketika aturan negara tidak cukup ketat dan norma sosial tetap memihak laki-laki, perempuan terus menjadi penanggung utama luka-lukanya.
Jika kita sungguh ingin perubahan, langkah pertama adalah mengakui bahwa nikah siri menyimpan risiko struktural. Pencatatan pernikahan tidak boleh dipandang sekadar formalitas. Negara perlu menutup celah hukum yang membiarkan pernikahan tanpa perlindungan berlangsung, sementara masyarakat perlu berhenti menormalisasi relasi yang menggantungkan keselamatan perempuan pada itikad baik satu orang laki-laki.
Memilih nikah siri bisa jadi keputusan personal yang sangat kompleks. Tapi sebelum menjalaninya, penting untuk memahami segala kemungkinan yang menyertainya—dari segi hukum, sosial, maupun emosional. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar langkah yang diambil tidak membutakan diri terhadap risiko yang bisa berdampak panjang, termasuk bagi anak jika kelak ada. Menjaga hak dan perlindungan diri bukan berarti meragukan cinta, tapi bentuk kasih sayang kepada diri sendiri.
Bagi publik yang mudah terpancing untuk menghakimi, mungkin perlu jeda sejenak sebelum mengetik komentar yang menyakitkan. Situasi nikah siri sering jauh lebih rumit daripada sekadar narasi “pelakor” dan “istri sah”. Banyak perempuan yang dijanjikan, dimanipulasi, dan diyakinkan bahwa hubungan mereka sah dan akan dijalani dengan tanggung jawab. Tidak sedikit yang baru menyadari kerentanannya ketika semua sudah telanjur berantakan.
Baca Juga: Nikah Muda karena Agama, Dua Kisah Perempuan
Maka, yang perlu dipertanyakan bukan hanya siapa yang “salah” secara individu, tetapi juga sistem hukum dan budaya yang masih memberi ruang bagi praktik tak setara ini untuk terus terjadi. Kita perlu lebih kritis terhadap struktur yang menyulitkan perempuan, bukan sekadar sibuk mempermalukan mereka.
Kalau kita sungguh ingin menjadi bagian dari perubahan, mungkin langkah awalnya adalah berempati dan belajar lebih dalam—tentang hukum, tentang dinamika kuasa, dan tentang bagaimana memastikan keadilan tidak menjadi hak eksklusif mereka yang lebih berkuasa. Karena pada akhirnya, perempuan, baik dalam hukum maupun budaya, tetap pantas mendapatkan rasa aman dan perlindungan, bukan penghakiman berlapis-lapis.