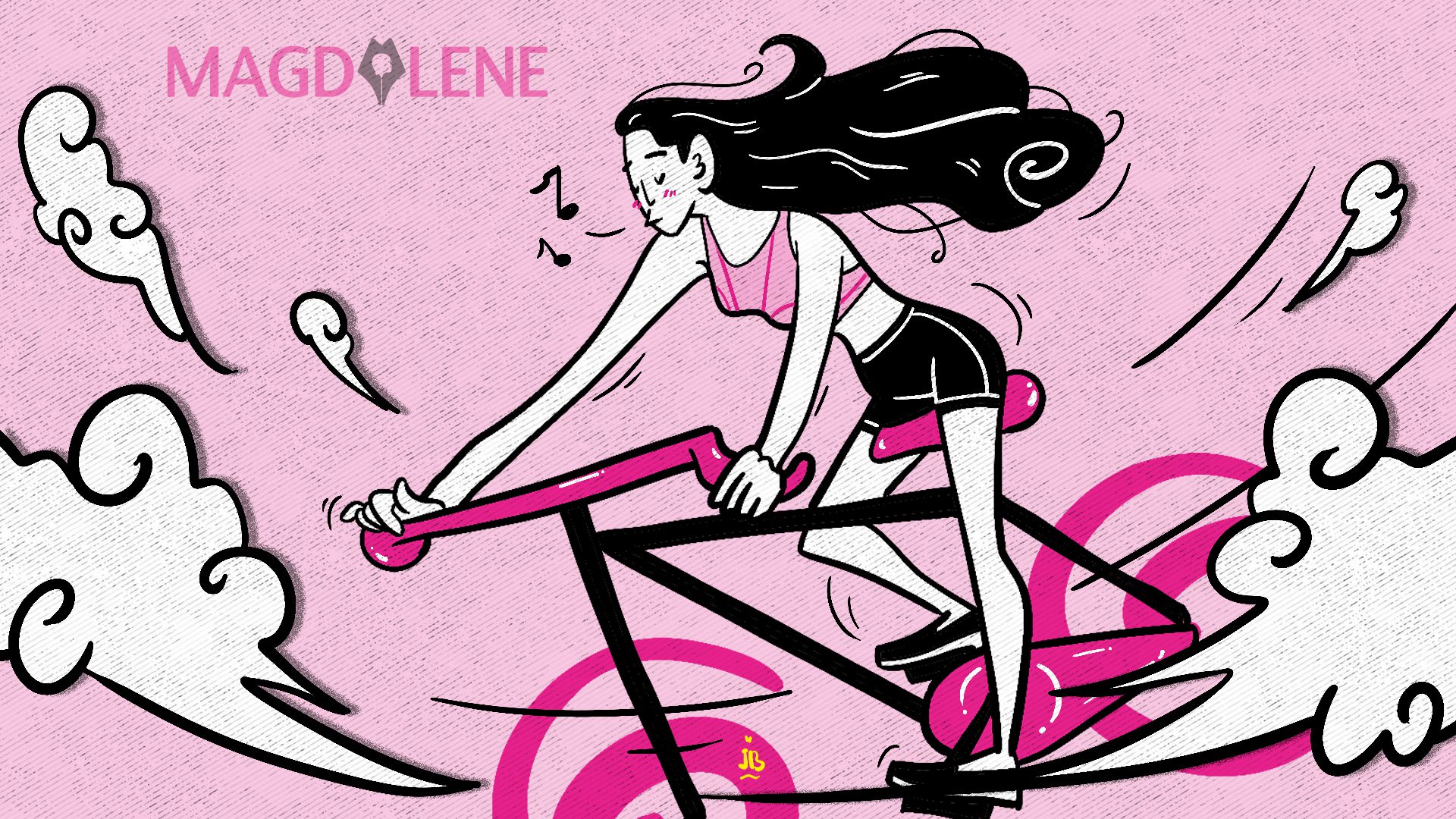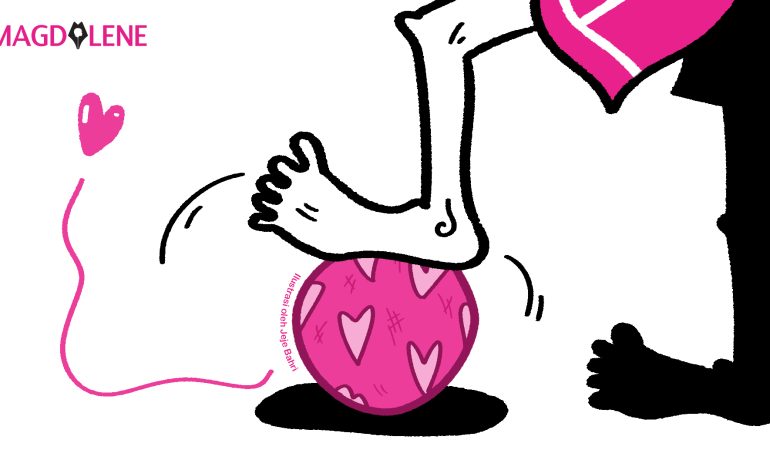
Peringatan pemicu: Tulisan ini membahas kekerasan berbasis gender dan bisa memantik trauma.
Dua tahun lalu, saya menjadi relawan di sebuah ajang sepak bola internasional di Indonesia. Buat saya, ini mimpi kecil yang jadi kenyataan. Saya bisa dekat dengan dunia sepak bola yang saya cintai sejak kecil, ikut membantu di balik layar, dan merasakan atmosfer stadion dari jarak sangat dekat.
Yang tidak pernah saya bayangkan adalah, di tengah euforia gol dan sorak penonton, saya dan banyak perempuan lain justru menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Pelakunya bukan hanya sesama relawan laki-laki, tapi juga penonton, termasuk yang datang dari luar negeri.
Perempuan di dunia sepak bola, entah sebagai pemain, panitia, maupun penonton, masih sering dipandang sebelah mata. Kami dianggap tempelan, bonus visual, atau “penggembira”, bukan subjek yang berhak merasa aman. Sepak bola adalah olahraga pertama yang saya kagumi, tapi juga yang menimbulkan banyak tanda tanya di kepala saya sebagai perempuan penikmat bola.
Beberapa waktu setelah pengalaman itu, sebuah video dari stadion di Indonesia sempat viral. Seorang perempuan terlihat kebingungan di tengah kerumunan laki-laki, entah ia mencari orang, barang, atau pintu keluar. Bukannya ditolong, ia malah disoraki satu stadion. Tidak ada panitia yang sigap datang, tidak ada penonton yang benar-benar turun tangan membantu. Di media sosial, caption dan komentar ikut melecehkan, menertawakan, dan menyalahkan, tanpa ada yang tahu apa sebenarnya yang ia alami.
Momen itu terasa sangat dekat dengan apa yang saya dan kawan-kawan rasakan: perempuan dianggap tontonan, bukan seseorang yang patut dilindungi.
Baca juga: Rolex Buat Sepak Bola, Kesenjangan Buat Atlet dan Cabor Lain
Ketika aturan hanya jadi poster
Secara formal, sepak bola tidak hidup di ruang kosong. Ia terikat hukum domestik dan internasional, juga berbagai regulasi dari badan sepak bola dunia FIFA sebagai induk organisasi, hingga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai anggota. Di atas kertas, semua tampak meyakinkan: ada kampanye No Discrimination yang ditempel di jersey, ada komitmen melawan rasisme, ada dokumen tentang Safeguarding & Child Protection di laman resmi.
Namun di lapangan, aturan itu sering berhenti sebagai teks dan slogan. Ia hadir sebagai patch di lengan pemain, poster di sekitar stadion, atau kalimat manis di pembukaan acara—tanpa diterjemahkan menjadi mekanisme perlindungan nyata, terutama bagi perempuan dan kelompok LGBTQIA+.
Selama rangkaian acara tempat saya menjadi relawan, saya tidak pernah mendengar penjelasan eksplisit tentang prosedur perlindungan perempuan, bagaimana melapor jika mengalami pelecehan, atau siapa yang bisa dihubungi selain sesama teman. Kasus-kasus yang terjadi cenderung ditangani tertutup antara korban, pelaku, dan perwakilan panitia. Tidak pernah betul-betul dibawa ke ranah hukum, jauh dari semangat transparansi yang selama ini dikampanyekan.
Pengalaman buruk yang menimpa saya dan perempuan lain akhirnya dikubur dalam-dalam. Kami didorong untuk melanjutkan tugas seolah tidak terjadi apa-apa. Pada titik itu, rasa aman bukan sesuatu yang dijamin sistem, tapi hal yang harus kami ciptakan sendiri dengan cara-cara yang melelahkan: berpura-pura, berkamuflase, memainkan peran tertentu demi bertahan.
Kekerasan yang kami alami adalah gabungan kekerasan berbasis gender (KBG) dan kekerasan berbasis gender online (KBGO): komentar bernada seksis, pertanyaan personal yang menyudutkan, pesan bernada ancaman, foto vulgar yang dikirimkan laki-laki—baik sesama relawan maupun penonton. Saya sendiri mengalami pelecehan langsung saat bertugas di tribun; pelakunya penonton asing yang menganggap tubuh saya bagian dari hiburan pertandingan.
Sebagai perempuan, kami sering dilabeli lemah dan butuh dilindungi laki-laki. Ironisnya, di stadion itu, justru laki-laki yang menjadi bagian dari ancaman. Di tengah rasa marah dan takut, satu-satunya hal kecil yang bisa saya lakukan adalah menguatkan sesama perempuan. Kami saling mengabari, saling mengawasi, memastikan tidak ada yang berjalan sendirian. Kedengarannya klise, tapi di situasi seperti itu, solidaritas sekecil apa pun terasa penting.
Bentuk “peran” yang kami mainkan juga sangat konkret. Beberapa kawan sengaja memakai cincin seolah-olah sudah menikah, atau mengenakan kalung dan gelang yang seakan jadi tanda “sudah punya pasangan”. Ada yang dengan sadar menciptakan status palsu—mengaku sudah taken—dengan harapan akan lebih dihormati. Bukan karena kami senang berbohong, tapi karena kami tahu, status “sudah jadi milik orang” sering lebih dihargai daripada fakta bahwa kami ini manusia yang semestinya tidak diganggu.
Yang paling menyakitkan adalah ketiadaan disclosure atau penyelesaian yang layak. Peristiwa yang singkat tapi membekas itu dibiarkan menggantung. Tidak ada pemulihan psikologis, tidak ada sanksi jelas pada pelaku, tidak ada pengakuan bahwa sistem telah gagal.
Baca juga: Perempuan Dilarang Suka Sepak Bola dan Musik Keras
Dalam obrolan dengan seorang kolega sesama penikmat bola, ia mengakui bahwa aturan sepak bola, baik di level nasional maupun internasional, masih jarang benar-benar menempatkan perempuan sebagai pusat pertimbangan. Perempuan minim dilibatkan dari proses penyusunan kebijakan sampai pengambilan keputusan dalam turnamen. Tidak heran jika perspektif keamanan perempuan juga ikut hilang dari desain acara.
Pada akhirnya, semua slogan dan peraturan terasa seperti hiasan. Ajang berskala internasional boleh saja terus menggaungkan tagar peduli sesama dan anti-diskriminasi. Tetapi kalau pelaku pelecehan tidak diberi sanksi tegas—misalnya di-blacklist dari seluruh acara sepak bola, dan korban tidak mendapat pendampingan psikologis—maka keamanan perempuan akan tetap menjadi janji yang berhenti di spanduk.
Rasa kagum saya pada dunia sepak bola masih ada, tapi sudah tidak utuh seperti sebelum peristiwa dua tahun lalu. Saya masih mencintai permainan di atas rumput hijau, tetapi saya juga ingin stadion menjadi ruang yang benar-benar aman bagi semua orang.
Semoga suatu hari nanti, perempuan tidak lagi ditempatkan di pinggir lapangan—baik secara harfiah maupun kiasan—melainkan dilibatkan dari hulu ke hilir: dari tribun penonton, ruang ganti panitia, sampai meja penyusun kebijakan.
Divya Sanjay adalah anak tunggal yang tertarik pada isu gender meski tidak menjadikannya konsentrasi studi. Di luar kesibukan, ia senang menghabiskan waktu dengan mendengarkan radio. Ia bisa dihubungi melalui Instagram @divyasanjayb.