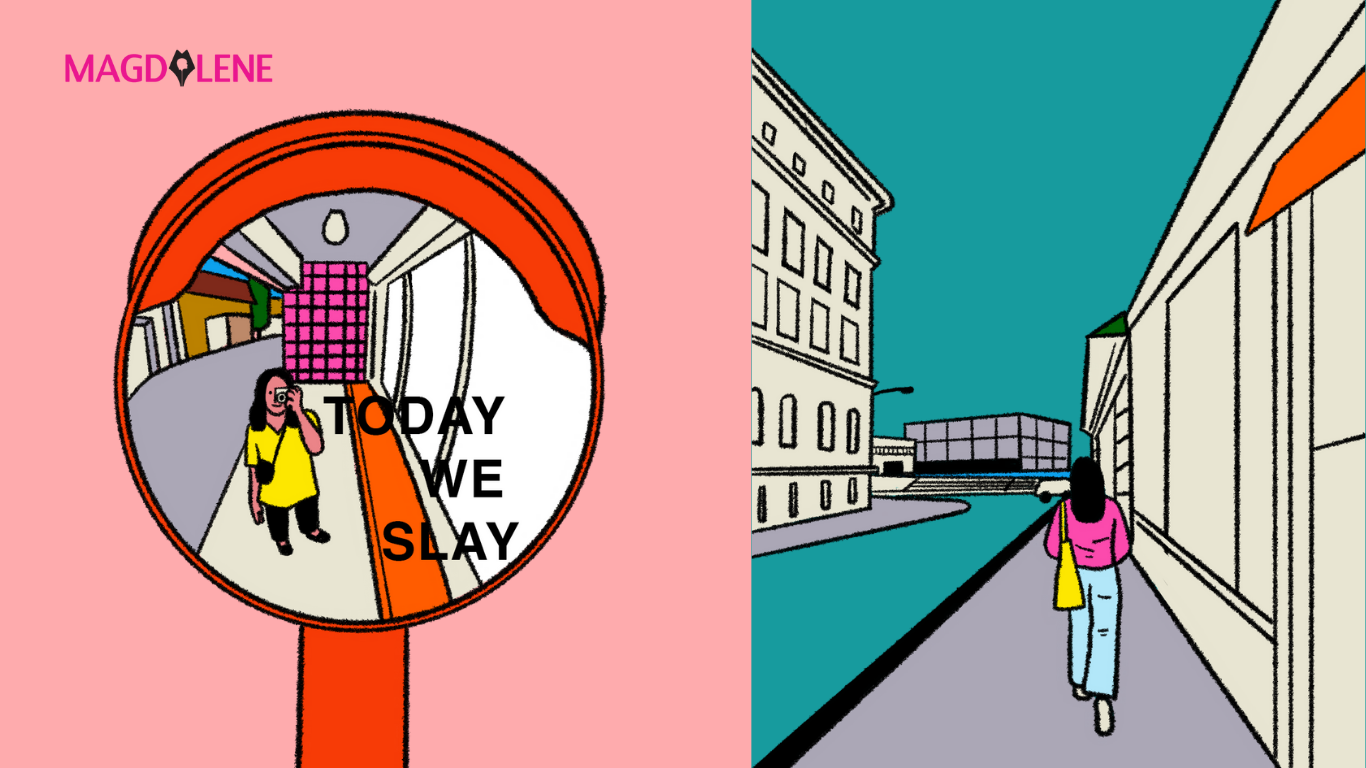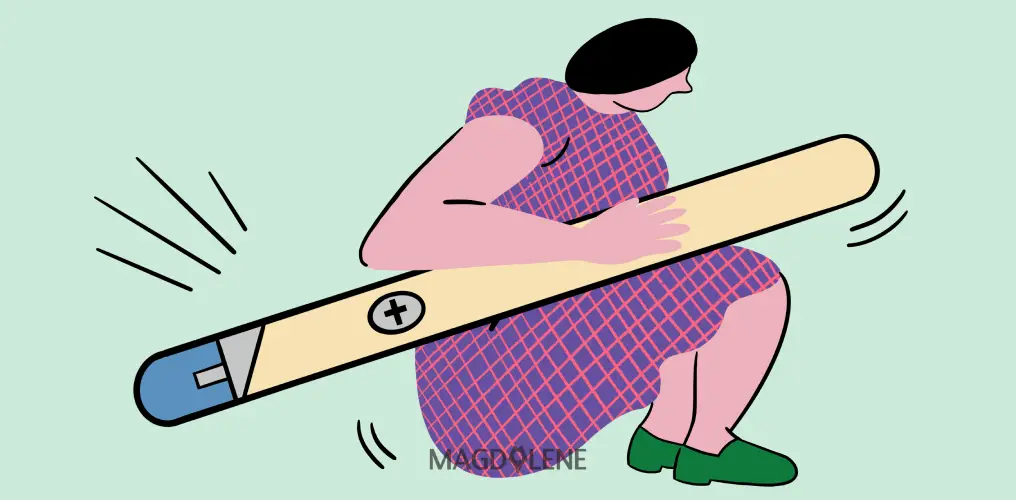Tubuh Perempuan, Tubuh Bumi, dan Banjir Bandang Indonesia

Banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumatera bukan sekadar peristiwa alam. Bencana tersebut adalah penanda krisis yang lebih dalam sekaligus cara kita memandang Bumi, tubuh, dan kehidupan.
Ketika sungai meluap, hutan runtuh, dan desa-desa terendam, yang pertama kali menanggung dampaknya adalah perempuan. Ibu yang kehilangan sumber air bersih, pengasuh yang harus memastikan anak tetap hidup dan sehat, serta tubuh-tubuh perempuan yang dipaksa bertahan di tengah keterbatasan, trauma, dan kehilangan.
Dalam logika pembangunan arus utama (pembangunanisme), bencana kerap direduksi menjadi statistik. Entah berupa jumlah korban, nilai kerugian, dan kecepatan pemulihan infrastruktur. Bagi perempuan, bencana adalah pengalaman yang berlapis karena menyentuh tubuh, relasi sosial, kerja merawat, dan keberlanjutan hidup sehari-hari.
Baca juga: Saat Banjir Tenggelamkan Rak: Arsip Gerakan yang Ikut Hilang
Di saat bencana tubuh perempuan dan tubuh Bumi bertemu. Keduanya sama-sama dieksploitasi, diperlakukan sebagai sumber daya, dan dianggap dapat dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi.
Deforestasi, alih fungsi lahan, tambang, dan perkebunan skala besar di seantero Indonesia telah lama diperingatkan para peneliti dan komunitas lokal sebagai bom waktu ekologis. Ketika hutan digunduli, daya serap tanah hilang, sungai kehilangan penyangga alami, dan banjir bandang menjadi keniscayaan. Perempuan, terutama perempuan miskin, adat, dan pedesaan, mengalami krisis air, pangan, kesehatan reproduksi, dan meningkatnya kekerasan di situasi darurat.
Persis seperti tubuh perempuan, tubuh Bumi kerap diperlakukan tanpa persetujuan, tanpa perlindungan, dan tanpa pemulihan yang adil. Ketika Bumi “dipaksa produktif” melampaui batas daya dukungnya, ketika tubuh perempuan dibebani kerja merawat tanpa pengakuan dan perlindungan, keduanya mengalami luka struktural akibat kebijakan yang abai pada kehidupan.
Dalam perspektif Feminisme Pancasila, krisis ekologis tidak bisa dipisahkan dari krisis etika politik. Politik yang hanya menghitung pertumbuhan, tetapi mengabaikan kerja merawat, relasi sosial, dan keberlanjutan generasi, adalah politik yang kehilangan akar kemanusiaannya. Pancasila—terutama sila kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadaban—menuntut pendekatan yang memuliakan kehidupan, bukan mengorbankannya.
Di sinilah relevansi Musyawarah Ibu Bangsa 2025 menjadi nyata. Musyawarah ini tidak sekadar forum perempuan, melainkan ruang politik yang memindahkan pengalaman hidup perempuan ke pusat perumusan agenda nasional. Salah satu isu strategis yang dibahas adalah keterkaitan antara krisis iklim, lingkungan hidup, dan tubuh perempuan—sebuah pengakuan bahwa bencana ekologis adalah persoalan keadilan, bukan takdir.
Melalui Manifesto Ibu Bangsa 2025, perempuan Indonesia menyerukan perlindungan terhadap tubuh perempuan, Bumi, dan ruang hidup dari perusakan, kekerasan, dan krisis iklim. Seruan ini bukan bahasa simbolik, melainkan tuntutan politik konkret: perubahan arah pembangunan, penegakan hukum lingkungan, pengakuan pengetahuan lokal dan perempuan, serta kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan hidup, bukan kepentingan jangka pendek.
Baca juga: Libur Sekolah dan Kritik Tak Hentikan MBG, Orang Tua: Harusnya Bantu Banjir Sumatera Saja
Manifesto ini juga menegaskan bahwa kerja merawat—yang selama ini dilakukan perempuan dalam situasi bencana—adalah kerja sosial-politik yang menopang bangsa. Saat negara gagal mencegah kerusakan ekologis, perempuanlah yang merawat luka: memasak di pengungsian, merawat yang sakit, menjaga anak-anak, dan memulihkan kehidupan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Ironisnya, kerja inilah yang paling jarang diakui dalam perencanaan kebijakan dan anggaran.
Banjir bandang Sumatera seharusnya menjadi titik balik. Bukan hanya untuk memperbaiki tanggul atau relokasi sementara, tetapi untuk meninjau ulang paradigma pembangunan yang menjauh dari etika merawat kehidupan. Jika tubuh Bumi terus dilukai, tubuh perempuan akan terus menanggung akibatnya. Jika suara perempuan terus diabaikan, krisis ekologis akan berulang dengan skala yang semakin destruktif.
Menuju Indonesia Emas 2045, pilihan kita semakin jelas. Kita bisa melanjutkan pembangunan yang menormalisasi kerusakan dan bencana, atau memilih politik kesetaraan yang berakar—politik yang mendengar pengalaman perempuan, menghormati batas Bumi, dan menempatkan kehidupan sebagai pusat kebijakan. Ibu Bangsa, sebagaimana dimaknai dalam Manifesto 2025, bukan simbol domestik, melainkan subjek politik yang membawa etika merawat ke ruang kekuasaan.
Banjir bandang Sumatera bukan hanya peringatan alam. Ia adalah panggilan politik. Pertanyaannya: apakah negara bersedia belajar dari kebijaksanaan perempuan—dari tubuh yang merawat, dari Bumi yang memberi, dan dari pengalaman hidup yang selama ini diabaikan?