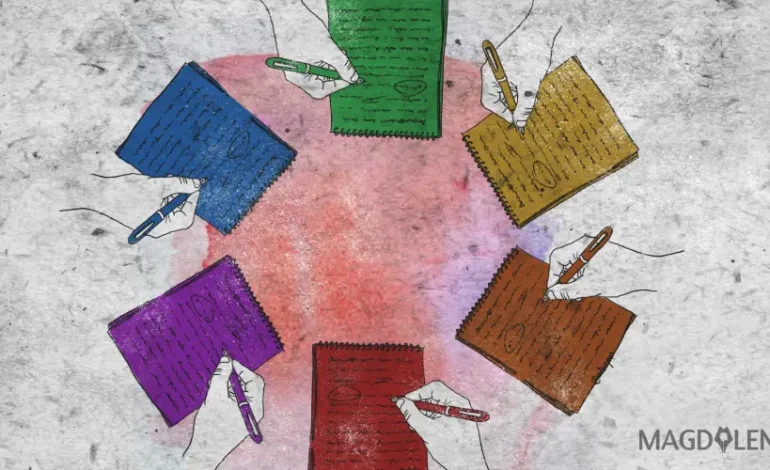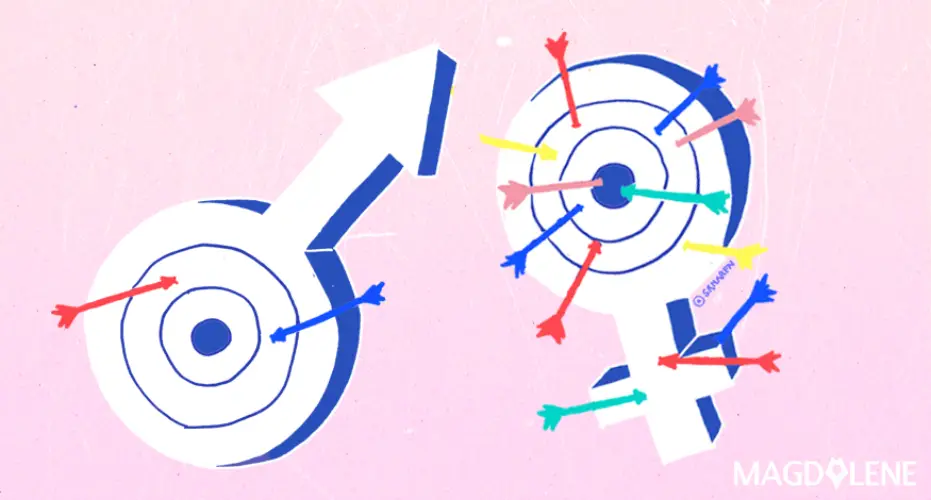Atas Nama Kemuakan pada Patriarki, Maka Kulepas Jilbabku

Sejak dulu pun saya tak pernah menyepakati bahwa jilbab adalah kewajiban bagi muslimah sebagai tanda ketakwaannya pada Allah. Dari dulu saya memang paling enggan menghubung-hubungkan tingkat keimanan dengan jilbab atau cara seseorang berpakaian. Iman adalah persoalan yang sangat pribadi antara Tuhan dengan hamba-Nya, dan tidak ada seorang pun yang berhak menilai atau menghakimi hanya dari hal-hal yang saya nilai tak esensial.
Namun dulu saya masih beranggapan bahwa jilbab adalah sunnah, yang jika dikerjakan berpahala, dan sesuatu yang baik untuk dilakukan sebagai pemacu saya untuk berbuat lebih baik dalam segala hal, karena saya selalu memimpikan sosok perempuan berjilbab yang tidak malu-malu dengan suara tak terdengar seperti kebanyakan halnya dulu. Saya memimpikan sosok perempuan berjilbab yang lantang, berprestasi, nyaris mendekati gambaran saya tentang kesempurnaan.
Setelah berjilbab pada Desember 1999, bulan-bulan pertama saya lalui dengan penuh kenikmatan atas identitas baru saya. Meskipun demikian, tidak ada perubahan pemikiran atau perilaku yang signifikan. Saya tetap “bebas nilai” dan tidak ragu untuk mengenali dan mempelajari semua hal.
Namun tak sampai setahun kemudian, saya mulai mengalami kejenuhan dalam hampir semua aspek kehidupan saya, termasuk soal jilbab. Jilbab yang saya kenakan tidak lagi dapat memotivasi saya untuk melakukan apa pun. Tadinya saya pikir hanya sebatas bosan karena penampilan saya menjadi seperti itu-itu saja, tapi semakin lama motivasi saya berjilbab semakin luntur. Perubahan yang terbaik memang bukan dari luar ke dalam tapi dari dalam ke luar, namun adakah perubahan dari dalam ke luar ini pun harus ditampakkan dengan jilbab? Saya mulai merasa kehilangan alasan kenapa harus memakainya.
Sekian banyak pertanyaan tentang jilbab kembali membanjiri pikiran saya. Kesalahan yang terbesar mungkin adalah pemujaan terhadap hal-hal yang hakikat dan lebih menghargai pertumbuhan rohani daripada perubahan kasat mata. Maka pada satu saat, ketika tidak juga didapat peningkatan spiritual dengan berjilbab, buat apa lagi saya teruskan? Kalau seorang teman pernah mengatakan ia berjilbab untuk meningkatkan kualitas ibadahnya pada Allah, saya tetap melihatnya sebagai hal yang paralel saja. Berjilbab satu hal, meningkatkan kualitas ibadah itu hal lain lagi. Atau mungkin hal itu berlaku untuknya tapi tidak untuk saya.
Di sisi lain baru saya sadari bahwa di samping alasan yang saya katakan sebagai “simbolisasi penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah”, alasan “duniawi” saya mengenakan jilbab dulu adalah agar dapat mengadakan perubahan “dari luar ke dalam” itu tadi. Suatu alasan yang sungguh keliru ternyata, setidaknya buat saya. Jika simbolisasi penyerahan diri saya sepenuhnya pada Allah, mengapa juga harus jilbab? Ketika saya mulai merasa kehilangan makna mengenakan jilbab, saya melakukannya hanya karena perasaan sudah terlanjur basah.
Tidak bisa saya mungkiri bahwa aktivitas saya pada sebuah organisasi hak perempuan memberikan kontribusi terhadap keputusan saya untuk berani melepas jilbab. Pemicunya sebetulnya adalah kemuakan dan kemarahan atas ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat ini. Apalagi dengan maraknya desakan untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Belum apa-apa tindakan zalim itu sudah terjadi. Perempuan yang tak berjilbab digunduli. Perempuan yang pulang malam tanpa mahrom digunduli. Razia terhadap semua perempuan yang masih berada di luar rumah di atas jam 22.00, tapi hal itu tidak berlaku untuk laki-laki.
Beberapa kabupaten di Indonesia sudah menerapkan syariat Islam, atau setidaknya yang mereka sebut sebagai syariah Islam. Namun, alih-alih menyentuh hal yang lebih esensial, hal pertama yang dilakukan adalah mewajibkan perempuan untuk berjilbab. Jika penerapan ekonomi syariat terlalu sulit dilakukan, kenapa tidak mulai dari menjaga kebersihan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, menghapuskan pungutan liar dan uang sogok kepada pegawai pemerintah, memperbaiki kesejahteraan guru dan petugas keamanan? Bukankah itu lebih Islami?
Umat Islam kerap menjalankan ‘perintah’ agama tanpa menggunakan kemampuan mereka untuk berpikir secara esensi kenapa mereka harus melakukan itu.
Asumsi saya, ada dua paradigma yang mungkin melatarbelakangi kenapa pemberlakuan jilbab menjadi primadona di kalangan pemerintah daerah yang ingin menerapkan syariat Islam. Paradigma pertama selalu melihat perempuan sebagai sumber persoalan secara tidak proporsional, seperti pornografi, pemerkosaan, atau kemaksiatan. Kedua, perempuan adalah kelompok yang paling lemah dan mudah dikendalikan sehingga merekalah yang dibebani berbagai macam aturan. Hal serupa kerap terjadi di negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam, seperti Iran pada masa pemerintahan Imam Khomeini sesudah revolusi 1979, atau Afghanistan pada rezim Taliban.
Satu hal yang membuat saya kerap ingin berontak adalah upaya pengkotak-kotakan antara perempuan baik-baik dan tidak baik-baik dengan adanya pembedaan pada pakaian. Seolah-olah jilbab adalah simbol kesucian perempuan, dan saya benci dengan istilah “kesucian”. Karena istilah itu hanya dan memang hanya diperuntukkan untuk perempuan, tidak pernah untuk laki-laki. Padahal baik laki-laki maupun perempuan punya kewajiban untuk memelihara kesucian diri. Namun hanya karena perempuan yang bervagina dianggap punya selaput dara yang dapat rusak, sementara penis laki-laki dianggap tetap saja utuh selama-lamanya, maka beban kesucian itu hanya diberikan pada perempuan.
Seolah itu tak cukup, ada lagi pengkotak-kotakan lain yang membedakan perempuan berjilbab dari caranya berjilbab dan mengukur tingkat keimanannya dari panjang pendeknya jilbabnya. Maka timbullah istilah “Kudung Gaul,” “Berjilbab tapi Telanjang” yang menjadi judul sebuah buku saku. Bacalah buku itu, dengan segala hinaan dan makian di dalamnya yang sama sekali tak Islami itu. Padahal Islam yang saya kenal tidaklah bengis dan buruk dalam berkata-kata.
Salah satu sahabat saya, berjilbab dengan tak bergamis, beberapa tahun yang lalu sempat minder jika harus berkenalan dengan perempuan yang berjilbab dengan gamis, karena merasa derajat jilbabnya lebih rendah. Sahabat yang lain, berjilbab dengan gamis, baru-baru ini bercerita bagaimana teman-teman berjilbab gamis lainnya di sebuah organisasi berbasis Islam menyindir-nyindir bila ia memakai warna jilbab yang terang atau yang pendek sedikit saja, karena perempuan dianggap tidak boleh sampai mengundang pandangan mata sama sekali.
Sementara itu, perempuan lain yang pernah sangat dekat dengan saya, aktivis perempuan katanya, yang senang mengenakan tank top dan selalu siap membela bila ada yang menghina perempuan yang berbaju mini, malah menjadi apriori dan serta merta menunjukkan sikap penolakan terhadap perempuan yang berjilbab dan bergamis. Kapan perempuan mau maju kalau hanya sibuk mengukur panjangnya pakaian sesama perempuan yang sebetulnya hanya peluang untuk saling memecah belah di antara kita?
Kemudian saya menyadari bahwa pengertian aurat adalah sesuatu yang tabu untuk diperlihatkan atau memalukan. Padahal saya tidak pernah merasa saya harus malu dengan rambut saya. Kenapa harus malu pada tubuh sendiri? Kalau laki-laki merasa tidak punya kemampuan mengendalikan hawa nafsu, kenapa kita yang harus jadi bumpernya?
Sering dikatakan bahwa perempuan harus menutup auratnya agar tidak mengalami pelecehan seksual. Alasan yang dikemukakan adalah nafsu syahwat laki-laki lebih besar daripada perempuan. Namun hal ini pun sebetulnya tidak pernah terbukti secara medis.
Menurut cendekiawan Muslim Faqihuddin Abdul Kodir dari Fahmina Institute, persoalan agresivitas dan kepasifan seksual lebih terkait dengan fisik dan mental daripada dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Maka pelabelan seksualitas perempuan pasif dan seksualitas laki-laki agresif adalah menyesatkan dan tidak terbukti secara empiris. Artinya, perempuan dan laki-laki bisa agresif dan bisa juga pasif dalam hal hasrat seksual, tergantung dengan makanan yang dikonsumsi, kondisi fisik, mental dan lingkungan. Dan semua orang juga tahu laki-laki dapat secara bebas mengungkapkan kebutuhan seksualitasnya, sementara perempuan sejak dulu dikondisikan bahwa ia harus pasif dan betapa jalang dirinya jika melihat buku stensilan atau film-film porno sebagaimana laki-laki.
Namun pandangan yang menyesatkan ini ternyata tetap dipertahankan secara luas. Seolah-olah pemerkosaan dan pelecehan hanya persoalan perempuan berpakaian mini. Padahal pemerkosaan terjadi di mana-mana, bahkan di Arab Saudi dan Afghanistan, di mana para perempuannya wajib berjilbab.
Identitas Islam
Ada beberapa surat dalam Alquran yang dijadikan referensi untuk kewajiban berjilbab. Surat Annur ayat 31 menyebutkan, “Hendaklah mereka menahan pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dari padanya. Hendaklah mereka mengulurkan kain kudung ke dadanya.”
Persoalan biasa tidak biasa juga menjadi sangat kontekstual karena yang ‘biasa’ di satu tempat mungkin ‘tidak biasa’ di tempat lain. Maka batasan aurat sendiri dapat sangat beragam tergantung konteks tempat dan waktu pada saat itu. Hal ini justru menunjukkan betapa sebetulnya Islam sangat fleksibel.
Surat Al-Ahzab ayat 59 menyatakan, “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu’min: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”
Ayat itu turun karena perempuan kerap menghadapi pelecehan. Sementara itu, perempuan-perempuan budak tidak diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khatab memarahi seorang perempuan hamba sahaya yang mengenakan jilbab karena jilbab merupakan pakaian perempuan merdeka. Perempuan budak tidak diwajibkan untuk berpakaian demikian karena akan sangat merepotkan mereka dalam bekerja dan beraktivitas. Maka dapat dikatakan jilbab adalah pakaian masyarakat kalangan atas, yang bisa menghindarkan perempuan dari kemungkinan pelecehan ketika itu.
Islam sesungguhnya sangat fleksibel, dan tak mesti disimbolkan dengan jilbab, sorban, gamis dan janggut.
Jilbab sendiri bukan monopoli Islam. Sebelum Islam turun, perempuan Kristiani dan penduduk Yaman sudah ada yang mengenakan jilbab. Jadi ketika kita bicara jilbab sebagai identitas, itu pun masih patut dipertanyakan, benarkah jilbab merupakan identitas Islam? Bila tidak, manakah yang termasuk identitas Islam? Dan apakah Islam butuh punya identitas? Apakah identitas itu harus dicirikan dengan tampilan fisik? Kalau Islam adalah rahmatan lil alamin (agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta), kenapa identitas fisik yang dikenakan hanya mengacu pada satu budaya tertentu?
Apakah esensi dari penggunaan identitas? Apakah kita harus selalu butuh dikenali identitasnya? Apakah dengan demikian pekerjaan mata-mata atau pekerjaan lain yang butuh yang sering menyamar jadi terhitung tidak “Islami”? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai sekarang masih belum bisa saya jawab. Karena bicara jilbab sebagai identitas fisik dan jilbab sebagai kewajiban penutup aurat adalah dua hal yang bisa sangat berbeda. Identitas fisik bisa kita tanggalkan sesuai dengan kebutuhan kita yang tergantung konteks tempat dan waktu namun sepertinya tidak dihalalkan bila dipandang sebagai penutup aurat.
Saya percaya Islam menginginkan baik perempuan maupun laki-laki untuk memelihara auratnya. Namun saya meyakini Islam sesungguhnya sangat fleksibel. Saya menginginkan Islam yang memiliki banyak wajah dan rupa. Islam tak mesti disimbolkan dengan jilbab, sorban, gamis dan janggut (kenapa tidak naik unta juga?).
Menurut saya, umat Islam (Indonesia khususnya) kerap menjalankan “perintah” agama tanpa menggunakan kemampuan mereka untuk berpikir secara esensi kenapa mereka harus melakukan itu. Atas nama menjalankan sunnah Rasul, para laki-laki memanjangkan janggutnya. Mengapa tidak mengambil nilai yang lebih esensial dari sekedar berjanggut?
Pada zaman dulu, semua orang Arab, yang penjahat, pemerkosa, kafir, muslim itu berjanggut. Jadi mana sunnah Rasulnya kalau para penjahat pun melakukan hal yang sama? Bukankah harus kita bedakan mana yang perbuatan Rasul sebagai bagian dari budaya Arab dan mana yang perbuatan Rasul sebagai utusan Allah yang pada dirinya tercermin Alquran yang mulia? Alih-alih berjanggut, kenapa tidak, misalnya, coba meneladani Rasulullah yang sangat getol memperjuangkan keadilan buat perempuan pada zaman itu di mana derajat perempuan demikian direndahkan?
Adalah penting bagi saya untuk mempertanyakan kenapa perempuan harus mengenakan jilbab. Sama dengan mempertanyakan kenapa perempuan harus mengenakan gaun yang terbuka bila ingin disebut modis dan trendi.
Saya sedang bertanya-tanya sebetulnya siapa yang merancang model-model berpakaian itu pada awalnya dan landasan pikiran apa yang membuatnya merancang baju seperti itu. Memang perempuan sebagai orang yang merdeka atas tubuhnya berhak untuk pakai baju apa saja — bikini, rok mini dan baju seseksi apa pun tanpa mendapat pelecehan. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan baju-baju seksi itu sebetulnya didesain untuk memuaskan laki-laki dan bukannya membuat perempuan menjadi merdeka atas tubuhnya, malah membuat laki-laki semakin merdeka menjadikan mereka obyek seks?
Ketika saya berjilbab, sering kali saya menyesal telah melakukan sesuatu tidak murni karena perasaan berdosa kepada Allah. Yang kerap terjadi adalah saya merasa malu kepada orang-orang karena saya berjilbab. Karena jilbab adalah sebuah simbol di mana segenap harapan pada kesucian moral dan kebaikan dibebankan pada bahunya. Menurut saya, itulah salah satu konsekuensi pengkotak-kotakan perempuan dari cara berpakaian. Karena berbeda halnya dengan laki-laki, pakaian buat perempuan tidak hanya ukuran status, kesopanan atau etiket tapi juga persoalan penghakiman moral pada dirinya. Adakah dia perempuan “baik-baik” atau tidak baik-baik, dengan kutub-kutub yang terkadang amat ekstrem.
Namun bukan berarti yang sudah berjilbab, yang diidentikkan masyarakat Indonesia sebagai perempuan baik-baik, pun lepas dari tekanan yang acap kali tak proporsional. Sering kita dengar omongan orang, “Ih percuma berjilbab tapi pelit,” atau “Berjilbab kok judes, percuma saja”.
Ketika seorang perempuan berjilbab berbuat salah ia akan langsung diserang, “Buat apa Anda pakai jilbab?”, seolah perempuan berjilbab tidak boleh salah. Perempuan berjilbab serupa sebuah tiang penyangga bangunan yang harus tetap tegar berdiri sementara tiang-tiang yang lain berubuhan tanpa merasa bersalah. Padahal perempuan dan laki-laki, bergamis, berjenggot, berjas, berjilbab gaul, atau mengenakan rok mini, celana panjang, kulot, wajib berbuat baik dan menjaga tutur katanya agar tak menyakiti orang. Tapi mereka semua juga manusia biasa yang sering kali lupa dan bersalah.
Jadi setelah semuanya lewat, saya kini berefleksi. Adakah saya lebih takut pada harapan dan penilaian orang-orang ataukah pada Allah? Karena sering kali kata-kata kita, manusia, jauh lebih jahat dari Tuhan sendiri. Atau setidaknya kita lebih tidak pemaaf, gemar memberikan label, dan membesar-besarkan persoalan, sementara kecaman Tuhan kerap lebih bijak dan pemaaf.
Manusia memang serba terbatas, termasuk dalam kemampuan melihat melampaui jarak pandangnya. Maka selama jilbab malah menjadi sarana lain penindasan terhadap perempuan oleh peradaban ini, selama sebagian masyarakat berpuas diri dengan hanya berpikir pewajiban berjilbab sudah menyelesaikan separuh permasalahan umat, selama kaum perempuan justru jadi terpecah belah hanya karena pilihan cara berpakaian, selama pengkotak-kotakan moral perempuan membuat masyarakat semakin punya justifikasi untuk mengontrol perempuan atas nama agama, atas semua kemuakan dan jeritan pemberontakan saya terhadap patriarki keparat yang tak kunjung padam dalam dada saya, sudah saya ambil keputusan itu.
Maka, saya buka jilbab saya.