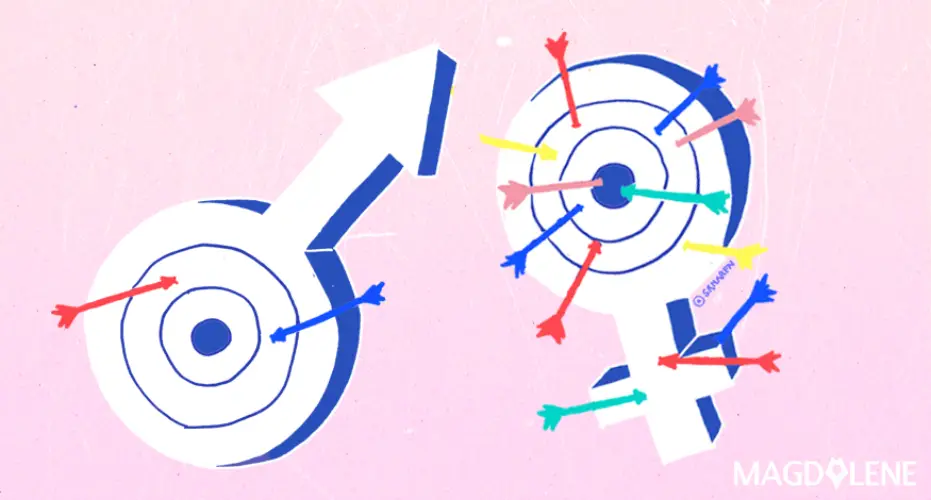Menerima LGBT, ‘Menularkan’ Keragaman Gender dan Seksualitas

Baru-baru ini media memunculkan kembali berita-berita mengenai kelompok LGBT dan bahaya mereka. Siapakah mereka sebenarnya? Benarkah mereka berbahaya? LGBT adalah akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, dan keempat huruf itu mewakili banyak huruf lainnya yang menunjukan keragaman gender dan orientasi seksual.
Kehebohan di tanah air ini bermula dari Amerika Serikat dengan beberapa negara bagiannya yang melegalkan pernikahan sesama jenis dan didukung oleh Mahkamah Agung di negara itu. Berita menggegerkan itu tentu saja sampai di sini dan istilah LGBT pun menjadi marak di Indonesia pada pertengahan 2015 lalu, tanpa memahami artinya. Ucapan seperti “Jangan bergaul dengan si A, dia kan LGBT” muncul, seakan-akan seseorang dapat menjadi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender sekaligus, dan itu tidak masuk akal.
Dua tahun berselang terus muncul larangan dan batasan diseminasi keragaman identitas gender dan minoritas seksual (selanjutnya saya sebut ragam minoritas) di Indonesia, seakan mereka adalah wabah. Sejumlah spanduk di beberapa kota menunjukkan sikap antipati nyaris benci kepada ragam minoritas ini. Kutipan-kutipan tanpa penelitian yang jelas menjadi propaganda yang menyudutkan teman-teman ragam minoritas ini sebagai hal yang menjijikkan dan berbahaya, contohnya:
- ‘LGBT menular, waspadalah!’
- ‘Mereka tidak bisa bereproduksi maka mereka membujuk’
- ‘LGBT adalah penyakit’
- ‘Selamatkan anak-anak kita dari LGBT’
- ‘LGBT karena salah pergaulan’
- ‘LGBT tidak boleh ada di kampus’
- ‘LGBT bisa disembuhkan’
- ‘LGBT bukan budaya Indonesia tapi bawaan globalisasi’
- ‘Hentikan agenda LGBT’
Menyebut gender dan orientasi seksual minoritas sebagai wabah bukanlah hal yang tepat. Mereka bukan virus dimana sekali kedipan mata dapat mengubah jati diri cisgender, atau orang-orang yang merasakan ketertarikan seksual dan secara fisik sejalan dengan apa yang diharapkan norma masyarakat. Bayangkan, berapa banyak cisgender yang akan ‘tertular’ virus LGBT saat ini apabila interaksi sosial dengan teman-teman minoritas saja dapat mengubah akar diri seseorang. Mungkin setengah dari populasi rakyat Indonesia akan ‘terjangkit’.
Namun sebenarnya jumlah orang-orang dari ragam minoritas ini tidak lebih banyak dari 3 persen dari populasi Indonesia, dibandingkan dengan orang-orang yang mengancam eksistensi mereka dan dengan seenaknya menghakimi, sehingga membuat teman-teman minoritas gender takut untuk mengungkapkan jati diri mereka karena ancaman kekerasan. Jumlah 3 persen teman-teman ragam minoritas ini bahkan kemungkinan lebih sedikit daripada itu karena angka tersebut merupakan jumlah total pendukung ragam minoritas. Dengan kata lain, jumlah itu masih harus berbaur dengan cisgender yang tidak ikut mendiskriminasi.
Pernyataan-pernyataan tentang keragaman identitas gender dan orientasi seksual yang dianggap ancaman secara tidak langsung malah mengancam hidup sekelompok kecil manusia ini. Masyarakat menjadi antipati terhadap keberadaan mereka, seakan mereka adalah penyebar sesuatu yang buruk dan makhluk langka yang hanya bisa digosipkan dan dijelekkan, padahal mereka ada di sekitar kita dan sebagian besar menyembunyikan identitas gender dan orientasi seksual mereka.
Yang menyedihkan, sejak 2015 hingga saat ini, beberapa pihak dari berbagai universitas di Indonesia menolak keragaman identitas gender dan inklusi kelompok minoritas seksual dalam bidang pendidikan, seperti dikutip dalam berita-berita berikut ini:
- Rektor Universitas Lampung Hasriadi Mat Akin menyatakan akan memecat mahasiswa atau dosen yang terbukti menyebarkan virus LGBT
- Universitas Indonesia melarang penggunaan nama UI untuk komunitas pendukung LGBT di UI
- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menyatakan larangan LGBT masuk kampus
- Forum Rektor Universitas Negeri Yogyakarta menolak keberadaan LGBT di lingkungan kampus
- Institut Teknologi Bandung membubarkan diskusi tentang LGBT karena dianggap melakukan propaganda
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau melakukan demonstrasi untuk menolak LGBT, yang dianggap menyalahi aturan Islam
- Universitas Tadulako membuat dialog nasional dan deklarasi penolakan LGBT di kampus
- Universitas Garut membuat seminar untuk menolak keras penyebaran LGBT di lingkungan kampus
- Universitas Andalas meminta mahasiswa baru untuk menandatangani lembar pernyataan bukan LGBT
Dan masih ada pernyataan-pernyataan lain yang menjadi kutipan resmi bahkan dari akademisi berilmu tinggi dan pejabat pemangku pemerintahan. Siapa sebenarnya yang melakukan propaganda? Mengapa kita hanya mendengar satu sisi dari pihak kontra? Di mana akademisi yang berani membela calon penerus bangsa dari diskriminasi raksasa?
Lepas dari kontroversi, patutkah teman-teman minoritas gender dan orientasi seksual tidak diberikan haknya sebagai warga negara Indonesia, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C Ayat (1) Amandemen Kedua, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, serta Pasal 31 Ayat (1) Amandemen Keempat yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”?
Apakah itu berarti teman-teman minoritas gender dan seksual tidak berhak pintar, tidak berhak berbeda dan mendapatkan pendidikan yang layak? Atau seorang mahasiswa tidak berhak memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan, mengembangkan intelegensinya dengan mempelajari segala sesuatu yang sebagian masyarakat anggap tabu? Untuk apa sebenarnya globalisasi dan keterbukaan informasi jika sebagian besar masyarakat hanya menegaskan hal-hal yang sudah ada, tidak lagi mempertanyakan dogma, dan menelan bulat-bulat penjelasan masa lampau?
Sebenarnya siapa yang beragenda di sini? Tega sekali beramai-ramai menyudutkan sekelompok kecil manusia sebagai warga negara kelas dua. Selama bertahun-tahun teman-teman ragam minoritas menundukkan kepala, mencoba berbaur dengan sekitar dan hanya karena beberapa dari mereka dengan lantang menerima diri mereka apa adanya dan membiarkan masyarakat mengetahuinya, tiba-tiba saja semua yang mereka lakukan salah, muncullah diskriminasi, sampai pendidikan mereka pun diancam. Sebenarnya siapa yang harus dikecam? Teman-teman minoritas seksual dan ragam gender yang menundukkan kepala bersembunyi dalam lubang ketakutan atau mereka-mereka yang tega memberikan pernyataan diskriminasi bahkan mengupayakan agar diskriminasi dilegalkan?
Tidakkah lebih baik agar teman-teman ragam minoritas belajar mengenai pendidikan seksualitas di pendidikan tinggi, bertemu akademisi yang terbuka dengan topik ini, dan mengkaji benar permasalahan tersebut dengan mereka yang menentukan arah perkembangan ilmu mereka? Bukankah itu tujuan pendidikan tinggi, mempelajari yang tidak diketahui di sekolah dasar hingga menengah atas, membuka cakrawala pendidikan lebih jauh dengan membuka diri pada ilmu pengetahuan dan memusatkannya?
Pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak yang dihormati di kalangan sarjana mengenai bahaya teman-teman ragam minoritas dan menyudutkan mereka sebagai manusia ataupun warga negara, menimbulkan asumsi publik yang timpang akibat akses yang kurang dan rendahnya literasi masyarakat terhadap topik seksualitas. Ditutupnya akses akademisi muda mempelajari segala yang tabu di masyarakat akan membuat perkembangan ilmu pengetahuan jalan di tempat. Dalam ilmu pengetahuan, tabu tidak seharusnya ada.