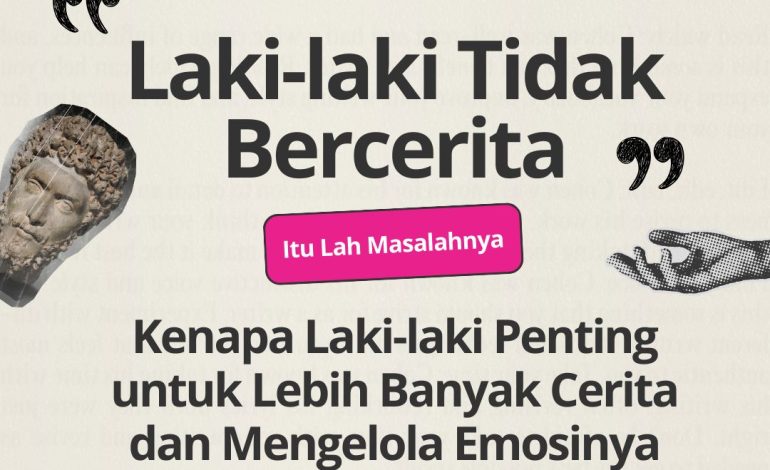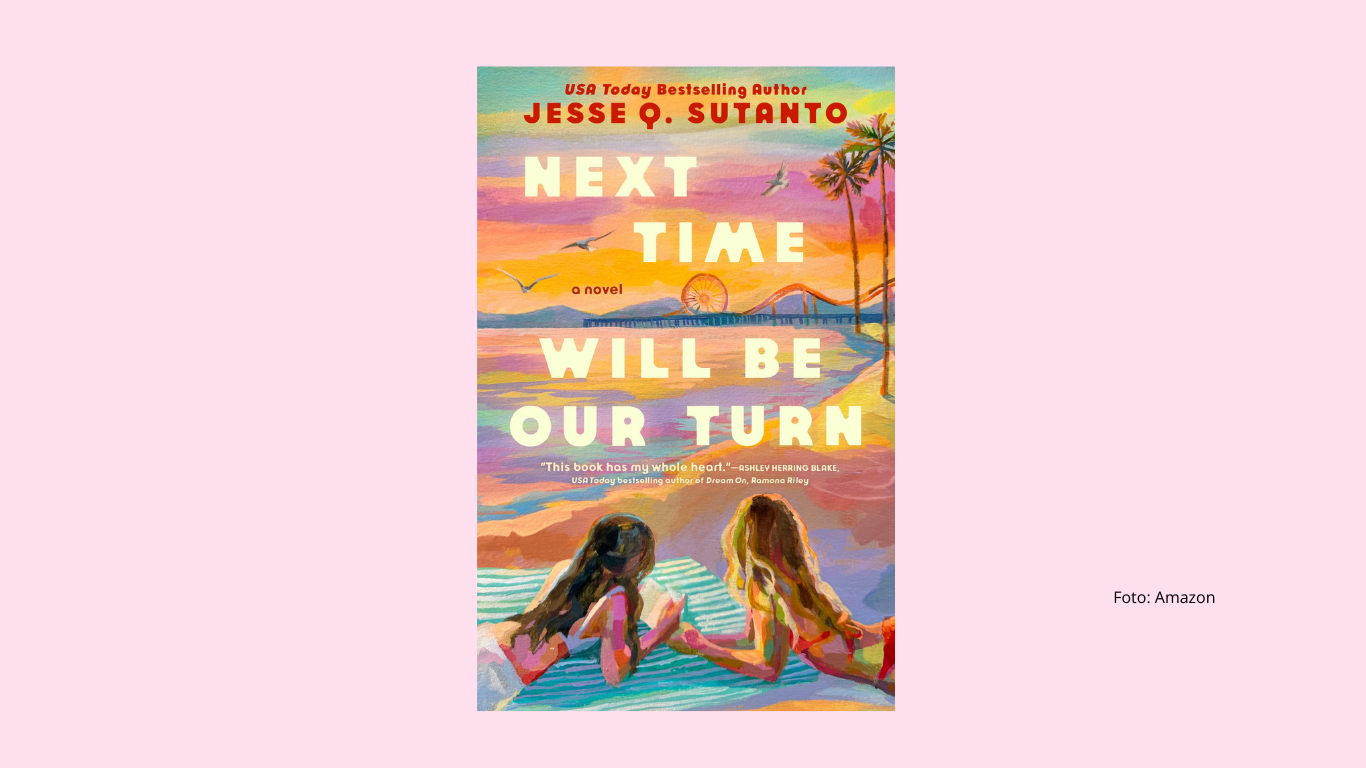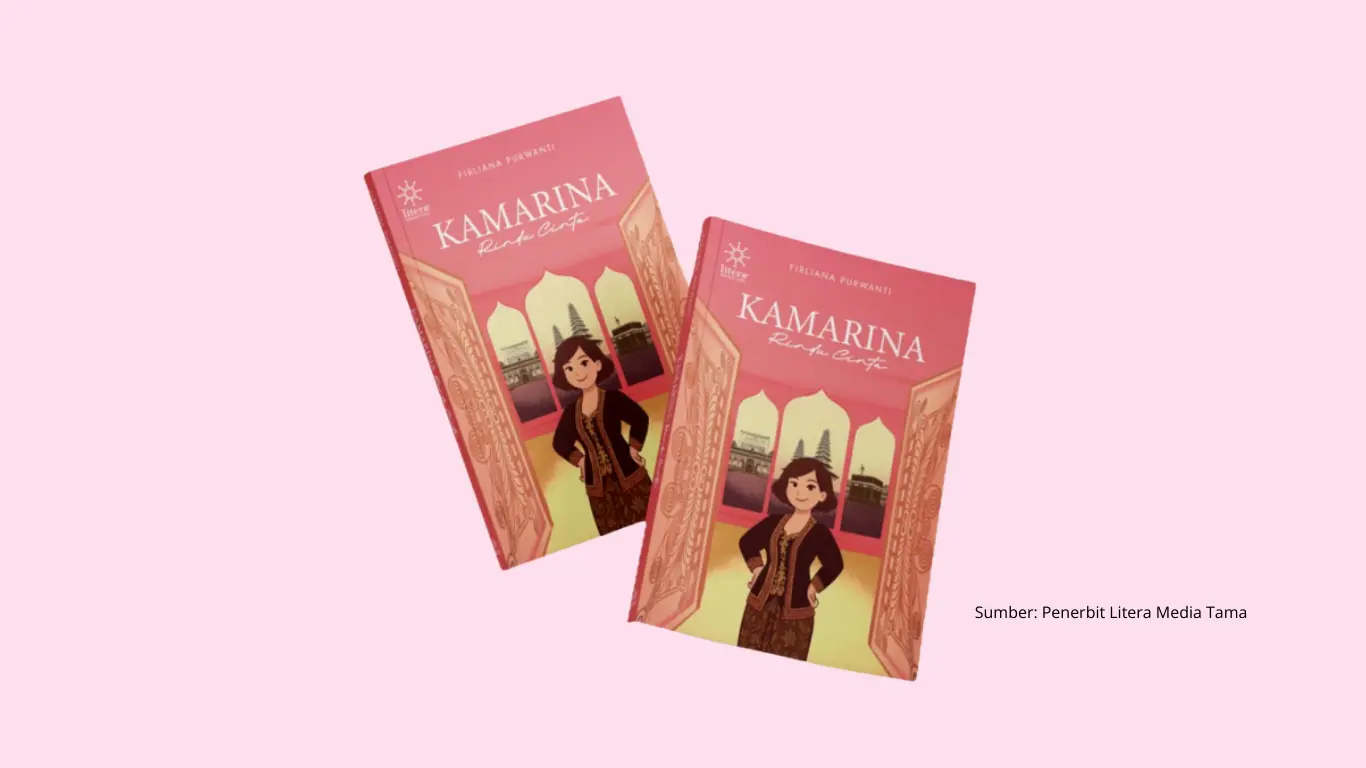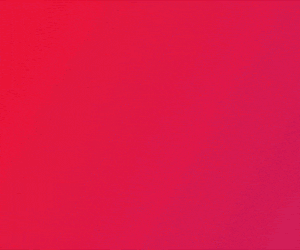Basi-basi THR Ojol: Bukan Solusi, Cuma Basa-basi

Baru-baru ini, pengumuman Presiden Prabowo Subianto tentang pemberian “THR” bagi para pengemudi ojek ‘online’ (ojol) jadi sekadar pepesan kosong. Benar saja, bonus hari raya yang hanya bersifat imbauan berbeda dengan tunjangan hari raya yang merupakan mandatori undang-undang.
Polemik tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi ojol yang terus berulang menandakan, ini bukan cuma sengketa antara aplikator dan pengemudi, melainkan adanya kekosongan regulasi yang dibiarkan. Negara tidak hanya abai mengatur hubungan kerja yang timpang, tetapi juga gagal mengenali kekerasan implisit dalam sistem ketenagakerjaan transportasi daring yang termasuk ekonomi gig (termasuk ojol dan cleaning service).
Kekerasan implisit dalam ekonomi gig terjadi melalui tiga jalur utama: (1) pelabelan pekerja gig sebagai mitra, (2) kerentanan kondisi kerja yang dianggap lumrah atas nama perjuangan mencapai kesejahteraan, dan (3) absennya regulasi dari negara untuk mengatur pekerjaan berbasis platform secara keseluruhan.
“Pak Presiden, yang kamu janjikan ke ojol itu jahat!”
Kekerasan ini—yang membuat mereka berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan hak yang memadai—dialami secara umum oleh pekerja platform, bukan hanya pengemudi ojol.
Terdapat sekitar 430 ribu hingga 2,3 juta orang atau sekitar 0,3-1,7 persen dari total angkatan kerja yang menjadikan aktivitas gig sebagai pekerjaan utamanya. Bahkan menurut Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA, asosiasi pengemudi ojol) total jumlah pengemudi berbagai platform ride-hailing di Indonesia telah mencapai 4 juta.
Jumlah ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menerbitkan aturan yang melindungi pengemudi ojol dan pekerja gig lainnya dari kekerasan.
Baca juga: Driver Ojol, Riwayatmu Kini: Dilecehkan, Rentan Jadi Sasaran Kejahatan
Omzet Jumbo yang Tak Menetes ke Mitra
Per akhir 2024, ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, mencapai US$90 miliar yang setara Rp1.440 triliun dalam bentuk gross merchandise value (GMV) atau nilai transaksi kotor dari seluruh platform per akhir 2024. Dari total GMV itu, layanan transportasi dan pengiriman makanan berkontribusi sebesar USD9 miliar (setara Rp144 triliun)—bisa bertambah hingga US$20 miliar (Rp330,5 triliun) pada 2030—alias terbesar kedua setelah e-commerce.
Ini berarti pengemudi ojol dan kurir makanan berada di garda depan ekonomi digital. Sayangnya, nilai ekonomi fantastis ini tidak tercermin dalam pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Bekerja penuh pada platform digital memang memungkinkan mereka mengumpulkan penghasilan bulanan di atas upah minimum lokal. Namun, untuk mencapai target tersebut para pengemudi harus bekerja dengan jam yang sangat panjang: rata-rata lebih dari 70 jam per minggu. Beberapa bahkan bekerja lebih dari 100 jam per minggu.
Mayoritas aksi unjuk rasa pengemudi ojol antara Maret 2020-Maret 2022 pun menuntut tarif layak, penurunan komisi untuk platform, serta perbaikan upah dan kondisi kerja.
Penetapan harga/tarif transportasi daring sesungguhnya mencerminkan pasar bebas ojek konvensional. Sejak kehadirannya pada 1960-an, tidak pernah ada aturan tarif ojek konvensional. Penetapan harganya diserahkan pada pengemudi. Perusahaan ride-hailing seperti Gojek dan Grab kemudian memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan harga sangat rendah dibanding ojek konvensional.
Perang tarif antara Gojek dan Grab sempat menyentuh harga serendah Rp1.200/km, sampai pemerintah turun tangan memberi panduan tarif menyusul serangkaian protes besar-besaran pengemudi ojol di 2018.
Pola di atas cenderung berulang pada tahun-tahun berikutnya: perang tarif antarplatform ditambah kenaikan harga bahan bakar minyak membuat biaya operasional pengemudi membengkak lebih dari pendapatannya. Pengemudi ojol kemudian melancarkan protes besar, disusul dengan pemerintah mengeluarkan aturan penyesuaian tarif.
Baca juga: Akun Tuyul sampai Joki: Bagaimana Pengemudi Gojek Lawan Eksploitasi Kerja
Status dan Sistem Canggih yang Abaikan Hak
Status pengemudi ojol sebagai “mitra” jadi hulu masalah lemahnya posisi para pengemudi ojek dan taksi online.
Dalam hal perubahan skema insentif, misalnya, platform kerap mengambil keputusan sepihak tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pekerja atau “mitra”. Padahal, perubahan skema insentif ini berdampak besar bagi pengemudi—terutama yang bekerja ‘full-time’ untuk transportasi daring.
Platform juga menerapkan aturan dan algoritma untuk membentuk perilaku pengemudi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya pengemudi dapat menerima bonus berdasarkan poin yang mereka kumpulkan dalam sehari atau pada jam-jam tertentu.
Akumulasi poin tersebut bergantung pada sejumlah kriteria, seperti jumlah pesanan yang diselesaikan, rating dari pelanggan, dan jenis pesanan.
Sementara pengemudi berhadapan dengan risiko skorsing atau penonaktifan jika ikut dalam unjuk rasa. Ini bisa jadi membuat perlawanan yang sempat sengit dari para pengemudi pada periode awal booming platform Gojek, Uber, dan Grab di Indonesia belakangan ini cenderung melunak.
Kini bentuk perlawanan sehari-hari pengemudi ojol adalah dengan memanfaatkan celah sistem platform. Mereka menggunakan aplikasi mod dan titik GPS palsu untuk mengurangi beban kerja, ataupun bekerja di lebih dari satu platform.
Demikian, ketimbang pekerja kerah biru yang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, posisi pekerja platform jauh lebih rentan: Tanpa jaminan terkait pekerjaan, keamanan kerja, perlindungan sosial, dan upah minimum.
Baca juga: Kenapa Istilah “Mitra” Buat Driver Ojol Bermasalah?
Menanti Kehadiran Negara
Aturan ketenagakerjaan Indonesia sebenarnya tidak mengenal istilah ‘kemitraan’. Istilah ini justru berasal dari Undang Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang diterapkan antara klien dan kontraktor independen dengan kedudukan yang setara.
Melalui label “mitra”, pekerja gig diposisikan seolah setara dengan platform digital. Padahal, kenyataannya kendali platform begitu besar atas banyak hal, seperti syarat dan ketentuan kerja, kapan dan bagaimana pekerja dibayar, sistem penilaian (rating), dan algoritma untuk mencocokkan permintaan kerja dengan pekerja.
Beberapa tahun belakangan, persoalan klasifikasi tenaga kerja dan hak-hak pekerja gig/pekerja platform menjadi perbincangan hukum di sejumlah negara.
Sebagai contoh, Keputusan Mahkamah Agung Inggris pada Februari 2021 menegaskan pengemudi Uber adalah pekerja. Waktu kerjanya dihitung sejak mereka masuk (log in) hingga mereka keluar (log out) dari aplikasi.
Sementara itu, awal 2025 ini Singapura memberlakukan Platform Workers Act untuk menjamin hak-hak pekerja platform, tetapi tanpa reklasifikasi pekerja.
Perubahan dinamika dunia kerja menuntut hukum untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Sudah saatnya pemerintah Indonesia mengambil langkah sistematis untuk menjamin pemenuhan hak-hak pekerja platform, alih-alih membiarkan mereka menggantungkan nasib pada belas kasih algoritma.
Klara Esti, Mahasiswa Pascasarjana STF Driyarkara, Senior Research Associate, Centre for Innovation Policy and Governance.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.