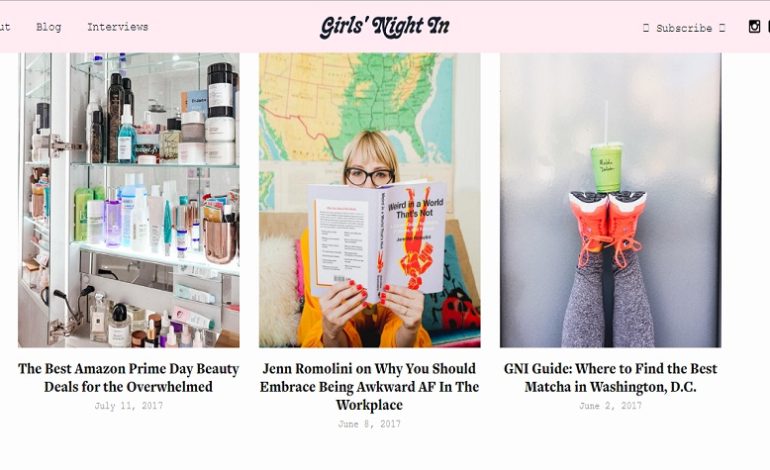De-romantisasi Poligami

“The man is the one who marries, the one who takes a concubine, and the woman is the one who is married, who is taken as a concubine. It is not permissible, to make analogies between things that are different.”
(Al-Umm, K. al-Nafaqat, “Ma ja’a fi ‘adad ma yahill min al-hara’ir wa’l-imma’ wa ma tahill bihi al-furuj,” 5:215. Ali, Kecia. Marriage and Slavery in Early Islam, Harvard University Press, 2010.)
Saya tidak habis pikir, mengapa sebagian masyarakat Muslim di Indonesia sepertinya tak mampu untuk mengalihkan fokus dan energinya kepada isu-isu substantif dan selalu sibuk dengan pergulatan superfisial yang tidak pernah ada habisnya. Perbedaan antara Muslim dan non-Muslim, kontrol terhadap seksualitas liyan dan tubuh perempuan, dan perebutan kuasa politik adalah topik-topik yang selalu menggairahkan sebagian komunitas Muslim di Indonesia. Sementara topik-topik lainnya, terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan dan perdamaian, hampir tak mendapatkan tempat.
Ilmuwan Muslim kenamaan, Khaled Abou El-Fadl, pernah menyatakan bahwa apa yang terjadi pada saat ini di banyak masyarakat Muslim di pelbagai penjuru dunia adalah vulgarisasi Islam. Pada konteks Indonesia, dapat dilihat bahwa vulgarisasi ini terdiri dari dua elemen utama, yakni elemen performatif dan elemen konsumtif. Di tataran performatif, vulgarisasi Islam mengambil bentuk fokus terhadap simbol-simbol eksplisit yang diasosiasikan dengan Islam, terlepas dari benar-tidaknya asosiasi tersebut.
Selayaknya penampilan di atas panggung, apa yang penting dari Islam performatif ini adalah seberapa eksplisit tampilan keislaman yang dapat disajikan. Semakin norak dan menor dandanan keislaman kita, maka semakin ‘Islam’-lah kita. Tak pelak, perdebatan paling sengit yang menyibukkan masyarakat Muslim di Indonesia saat ini berkisar pada hijab, niqab dan janggut, kosakata Arab sebagai media komunikasi, dan berapa banyak istri yang dapat digandeng ke mana-mana.
Di sisi lain, elemen konsumtif dari vulgarisasi Islam melengkapi elemen performatifnya dengan bertindak sebagai pemberi gratifikasi instan dari ‘tampilan keimanan’ yang dihadirkan melalui elemen performatif di atas. Iman bukan lagi sebuah perjalanan spiritual yang harus dilalui seiring dengan meningkatnya empati kemanusiaan. ‘Iman’ adalah rasa superioritas yang datang melanda ketika hijab yang dipakai jauh lebih lebar dari hijab perempuan lainnya; ‘iman’ adalah kebanggaan yang mengalir ketika kita mampu mencampuradukkan Bahasa Indonesia dengan istilah-istilah Arab ala kadarnya; dan ‘iman’ adalah arogansi buta yang berasal dari ketidaktahuan akan apa makna sunnah Nabi sebenarnya.
Karena agama tidak lagi berarti sebagai proses konstruksi keimanan secara terus-menerus (melainkan sebagai aksi teatrikal yang harus menyita perhatian orang banyak), maka ber-’Islam’ di Indonesia tak bisa dilepaskan dari aspek romantisasinya. Layaknya drama murahan, sebagian Muslim di Indonesia menjalankan Islam dalam kerangka khayalan dimana setiap aspek kehidupan beragama, dan setiap individu di dalamnya, direduksi menjadi gambaran-gambaran stereotipikal yang tidak lagi bisa dikenali dari perspektif tradisi Islam itu sendiri.
Salah satu drama murahan Islami yang sedang popular di Indonesia adalah drama poligami Islami. Dalam narasi murahan ‘poligami Islami’ ini, institusi pernikahan – yang tak lebih dari sebentuk kontrak antar-individu dalam perspektif yurisprudensi Islam – menjadi satu-satunya jalan ke surga dan jaminan kebahagiaan. Posisi suami, yang memiliki hak dan juga kewajiban dalam rumah tangga, menjadi lebih suci daripada posisi Tuhan itu sendiri. Sedangkan posisi istri, yang kemanusiaannya diakui sepenuhnya oleh Quran, tak lagi bisa dibedakan dengan posisi budak belian.
Iman bukan lagi sebuah perjalanan spiritual yang harus dilalui seiring dengan meningkatnya empati kemanusiaan. ‘Iman’ adalah rasa superioritas yang datang melanda ketika hijab yang dipakai jauh lebih lebar dari hijab perempuan lainnya.
Elemen performatif dalam vulgarisasi Islam menuntut laku keagamaan untuk dilaksanakan secara ekstrem. Berlebihan adalah kata kunci di sini karena dramatisasi menuntut adanya eksploitasi. Dengan demikian, pernikahan tak bisa lagi ditampilkan apa adanya, yakni kontrak sosial-seksual antara dua orang dewasa yang memiliki posisi sepadan di dalamnya. Pun dengan posisi suami dan istri. Posisi ‘pernikahan’, yang dalam perspektif fikih hanya berstatus ‘dianjurkan bagi orang-orang tertentu’, menjadi sesuatu yang ‘diwajibkan’. Sedangkan posisi poligami, yang dalam perspektif fikih hanya berstatus dibolehkan, juga menjadi sesuatu yang diwajibkan. Dramatisasi ajaran Islam telah menjadi ‘Islam’ itu sendiri sampai kita tidak bisa lagi membedakan mana yang menjadi perintah Tuhan dan mana yang bukan.
Konteks Islam Awal
Penyebutan sunnah Nabi secara berulang-ulang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari obsesi kita akan pernikahan poligami akhir-akhir ini. Stempel sunnah Nabi digunakan untuk menjustifikasi praktik poligami seakan-akan label tersebut dapat menghapuskan berbagai keburukan yang dihasilkan dari praktik ini. Apa yang tidak dipahami, atau mungkin diketahui, oleh para pelaku poligami adalah bahwasanya praktik poligami dalam perspektif Islam hanya bisa dipahami melalui konteks Islam Awal sampai pada Abad Pertengahan dimana tata aturan hukum tentang poligami dibentuk.
Konteks pertama yang penting untuk diketahui adalah adanya analogi kuat antara posisi perempuan dalam pernikahan poligami dan posisi budak perempuan yang berfungsi sebagai simpanan seksual (concubines) di masa Awal dan Pertengahan Islam. Prinsip milk al-yamin (apa yang dimiliki oleh tangan kananmu, yakni prinsip kepemilikan budak di masa Awal dan Pertengahan Islam) dan prinsip milk al-nikah (apa yang dimiliki dari proses perkawinan) selalu dijelaskan secara paralel dalam kitab-kitab klasik fikih Islam. Dalam kitab-kitab tersebut, proses pemberian mahar dalam perkawinan diparalelkan dengan proses pembelian budak, dan proses perceraian dalam pernikahan selalu disandingkan dengan proses pembebasan budak belian. Satu-satunya perbedaan antara kedua prinsip di atas adalah seorang istri tidak bisa diperjual-belikan layaknya seorang budak dan harus dimintai persetujuannya dalam proses pernikahan.
Dalam konteks ini, hubungan pernikahan antara seorang pria dengan beberapa perempuan sekaligus menjadi mungkin dan dapat dipahami karena status seorang perempuan – secara seksual, sosial, dan politik – tak jauh berbeda dengan seorang budak perempuan. Pernikahan bagi laki-laki saat itu adalah legalitas akses seksual terhadap istrinya, dan serupa dengan itu, ketika seorang laki-laki memiliki seorang budak perempuan, maka ia juga memiliki akses seksual terhadap budak perempuan tersebut.
Posisi suami, yang memiliki hak dan juga kewajiban dalam rumah tangga, menjadi lebih suci daripada posisi Tuhan itu sendiri. Sedangkan posisi istri, yang kemanusiaannya diakui sepenuhnya oleh Quran, tak lagi bisa dibedakan dengan posisi budak belian.
Di sisi lain, seorang perempuan merdeka yang bersuami berhak atas akses seksual terhadap suaminya, namun tidak terhadap budak laki-laki yang dimilikinya. Dengan demikian, seperti yang ditulis oleh Kecia Ali dalam karyanya Marriage and Slavery in Early Islam, otoritas kepemilikan laki-laki terhadap perempuan — secara seksual, sosial, dan politik — adalah lebih sempurna daripada kepemilikan perempuan terhadap laki-laki. Seorang perempuan merdeka bisa saja memiliki budak laki-laki secara sosial dan politik, namun ia tidak bisa memiliki budak tersebut secara seksual. Poligami adalah norma dalam konteks ini karena kedirian seksual seorang perempuan (merdeka atau tidak) dapat secara penuh dimiliki oleh laki-laki.
Konteks kedua yang juga penting untuk dipahami adalah kalkulasi sosial-politik yang mengiringi setiap keputusan Muhammad untuk menikahi istri-istrinya. Penting untuk diingat bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin agama, melainkan juga seorang pemimpin politik yang di kala itu sedang berupaya untuk menghapuskan hubungan kesukuan dalam masyarakat Hijaz, dan menggantinya dengan hubungan keagamaan.
Pernikahannya dengan Aisyah merupakan bentuk penghormatannya atas Abu Bakar, sahabatnya dan salah satu tokoh terpenting dalam kerangka sosial-politik Madinah. Umm Salama, Hafsah, dan Sawdah, ketiga istri Muhammad lainnya, adalah janda-janda dari para pejuang Islam Awal dan pernikahan Muhammad dengan mereka adalah bentuk jaminan sosial-politik terhadap keluarga para personel militernya. Pernikahan Muhammad dengan istri lainnya, Umm Habibah, merupakan bentuk konsolidasi politik mengingat ayah Umm Habibah adalah salah satu lawan politik-keagamaan terbesarnya, yakni Abu Sufyan. Zainab juga merupakan salah satu istri Muhammad yang berasal dari klan terhormat di mana keluarganya memberikan dukungan politik yang signifikan bagi kepemimpinan Muhammad.
Dengan demikian, vulgarisasi praktik poligami dalam Islam yang kini sedang menjadi tren di Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan dengan beberapa alasan. Pertama, sakralisasi ‘pernikahan poligami’ merupakan penyalahgunaan klaim yurisprudensi Islam yang menyucikan sesuatu yang tak memiliki nilai kesucian, dan tidak diwajibkan. Kedua, praktik poligami itu sendiri sudah tidak relevan adanya mengingat konstelasi pemahaman kita terhadap hak asasi manusia dan hak-hak perempuan telah mengalami perubahan yang signifikan. Praktik poligami yang berdiri di atas asumsi kepemilikan seksual laki-laki atas perempuan dan dapat dianalogikan dengan praktik perbudakan tidak lagi bisa mendapatkan tempat dalam tatanan sosial-politik saat ini yang berdiri di atas prinsip martabat kemanusiaan. Dan ketiga, pencatutan klaim ‘sunnah Nabi’ sebagai justifikasi praktik poligami masa kini tidak dapat dibenarkan adanya karena klaim tersebut digunakan tanpa menghiraukan aspek sosial-politiknya.
Pada akhirnya, jika ada hal di muka bumi ini yang akan menghancurkan Islam, hal itu bukanlah kelompok beragama lainnya ataupun ‘konspirasi Barat’. Hal yang akan menghancurkan Islam dari dalam adalah vulgarisasi Islam. Dengan kata lain, masyarakat Muslim-lah yang akan menghancurkan diri mereka sendiri.
Lailatul Fitriyah adalah mahasiswi doktoral pada program Agama-agama Dunia dan Gereja Global di Jurusan Teologi, Universitas Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat.