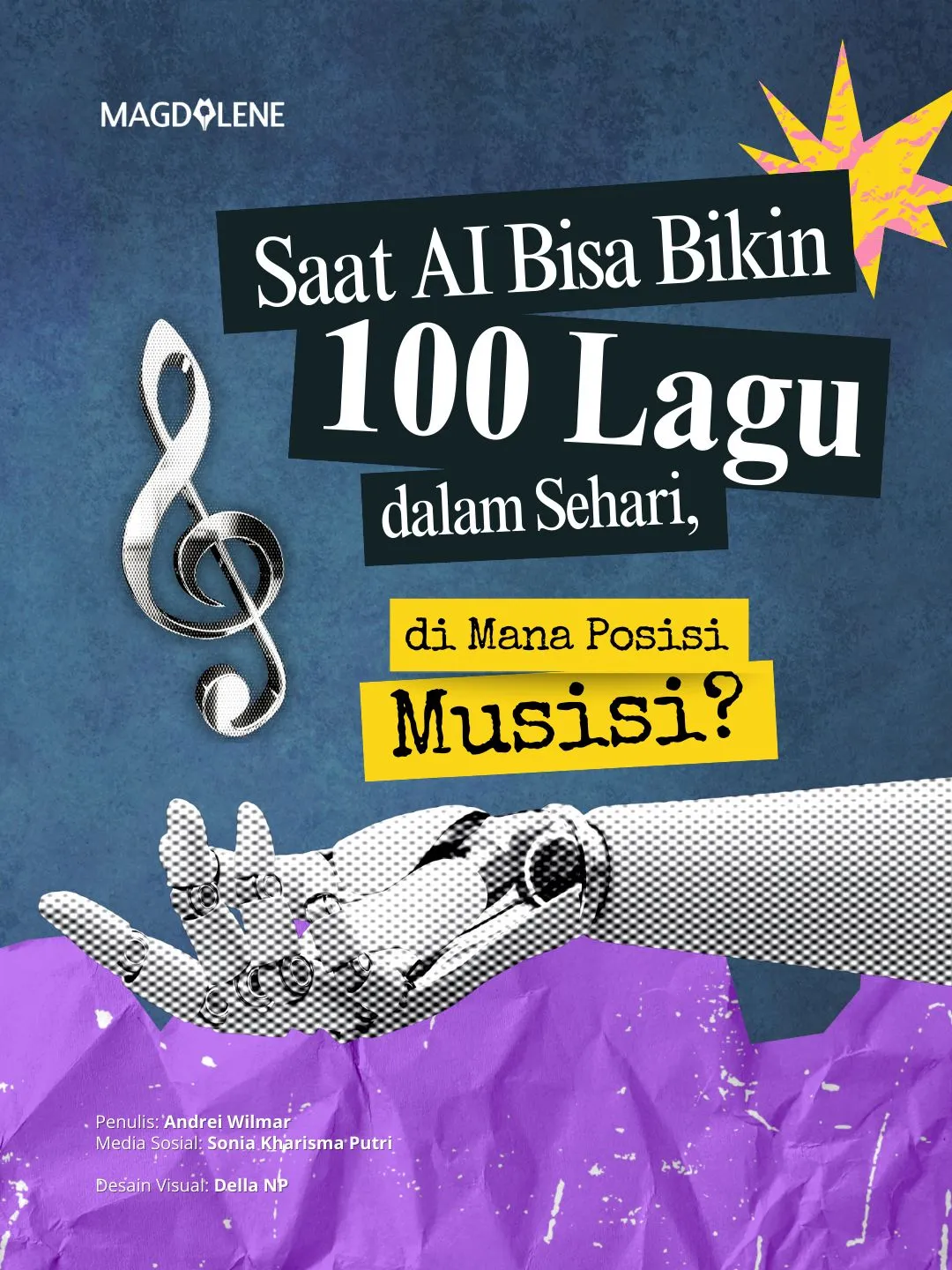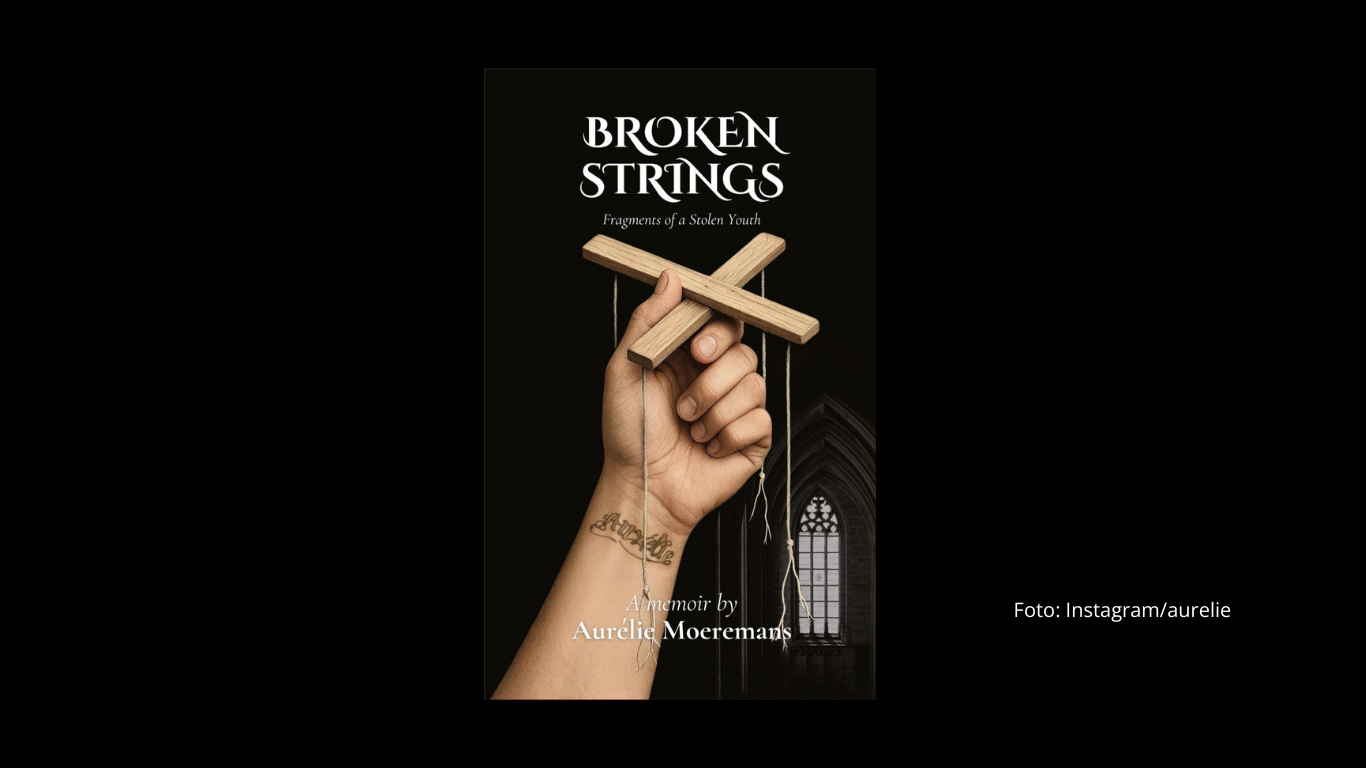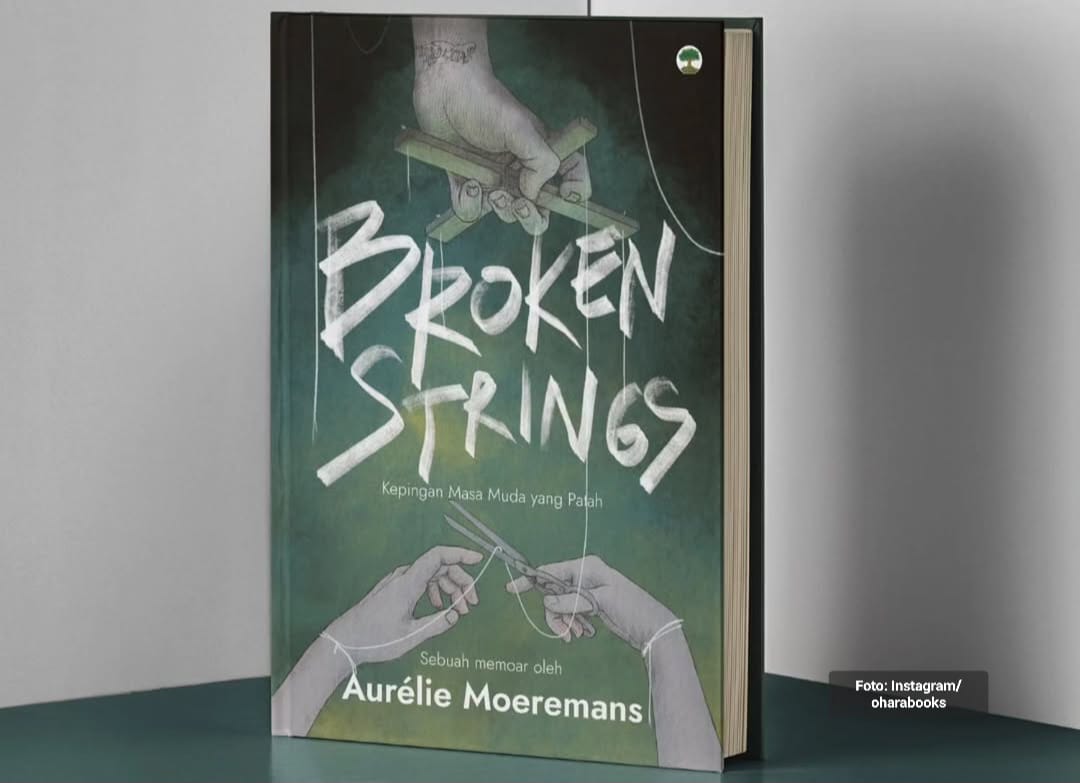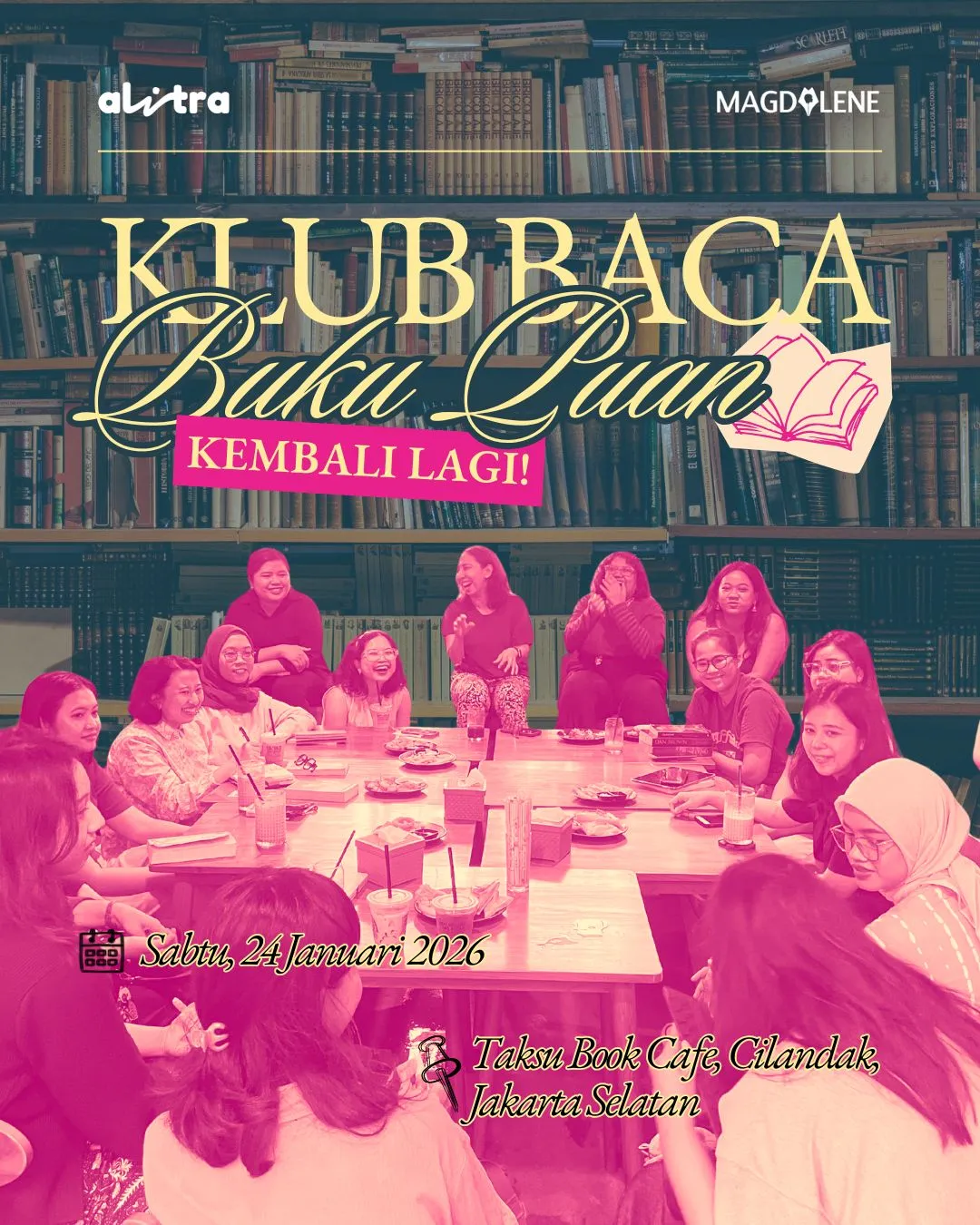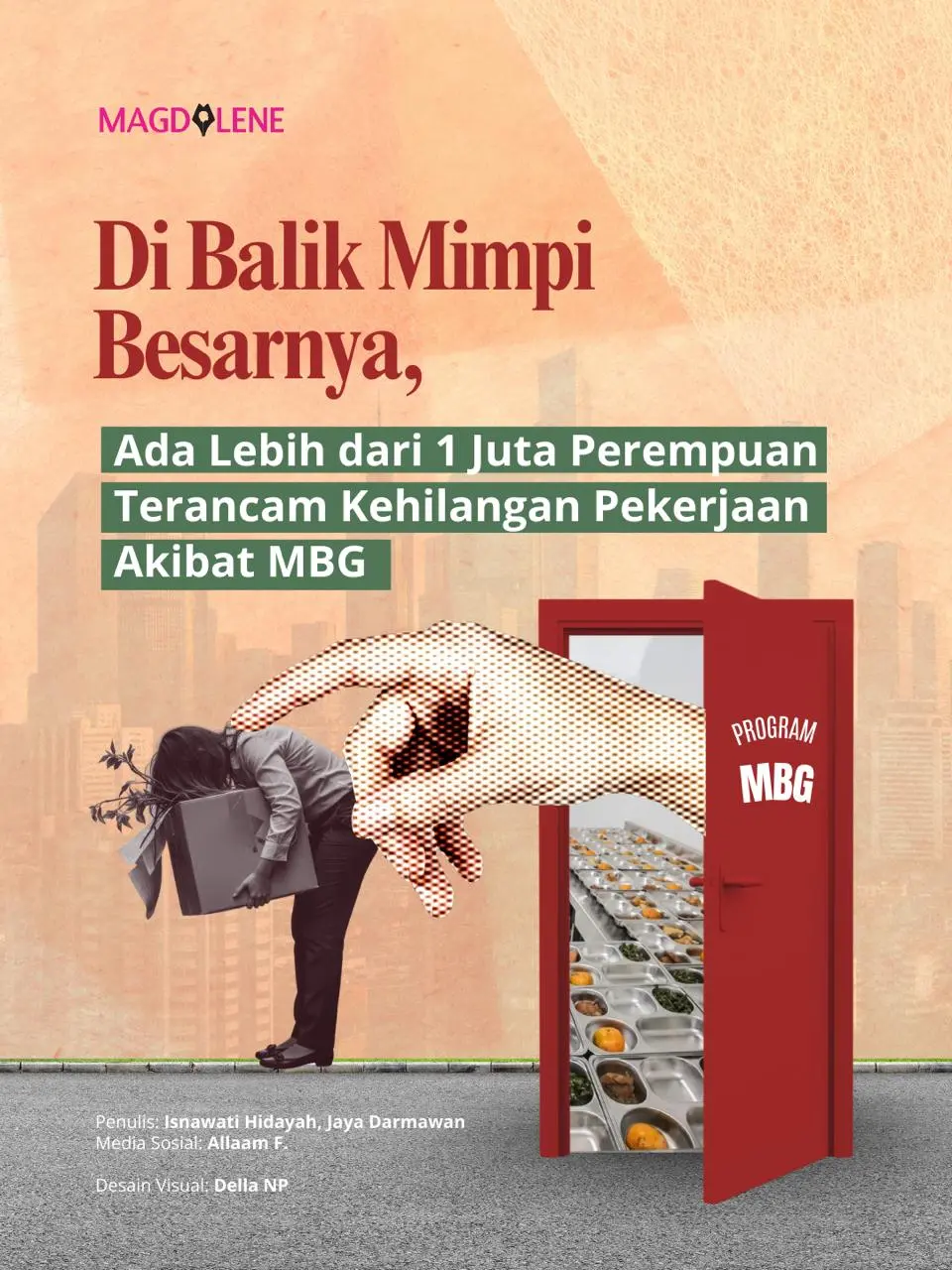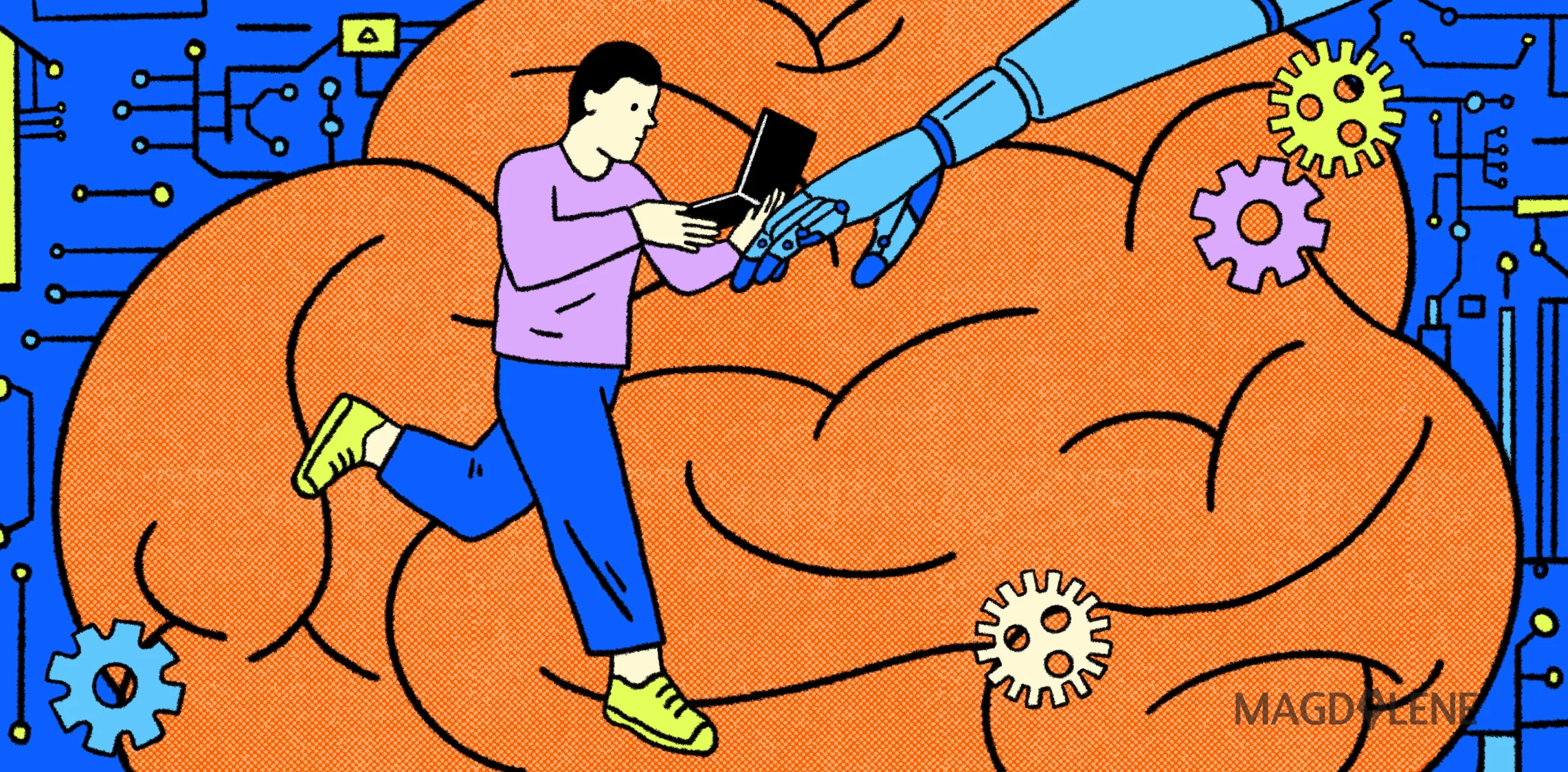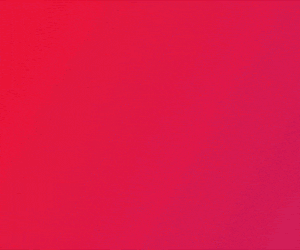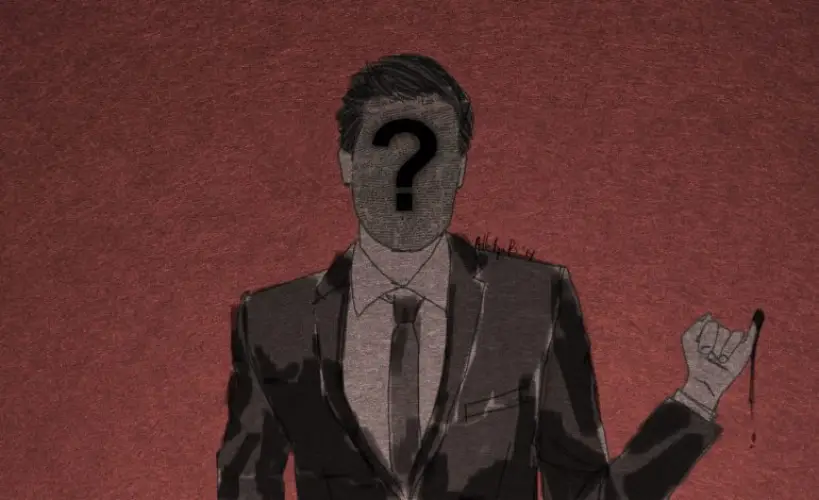Tips Hadapi Lelaki yang Suka ‘Mansplaining’, Berdasarkan Pengalaman Nyata
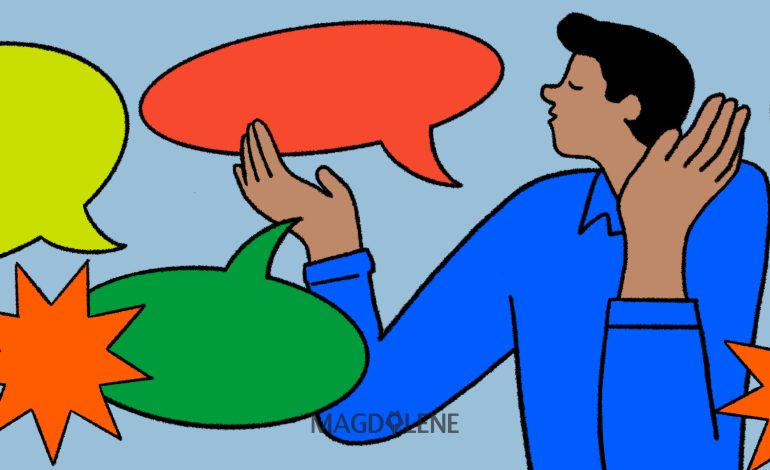
Ayu, 32 sedang latihan angkat beban di sasana (tempat gym), saat laki-laki menghampirinya. “Itu tekniknya salah, yang bener kayak gini,” kata lelaki tersebut.
Itu pertama kalinya Ayu mengalami mansplaining—ketika laki-laki menjelaskan sesuatu pada perempuan tanpa diminta—di tempat gym. Potret gym yang ada di bayangan Ayu langsung jadi kenyataan: Didominasi oleh laki-laki intimidatif, suka mansplaining, dan memonopoli alat-alat angkat beban—karena jumlah perempuan yang rutin memakai alat bisa dihitung dengan jari.
Awalnya, Ayu hanya merespons dengan mengucapkan terima kasih dan berharap tak bertemu laki-laki itu lagi. Namun, di pertemuan berikutnya, ia kembali mendekati. Kemudian flexing soal profesinya sebagai polisi, yang membuatnya terbiasa latihan angkat beban. Bahkan ia menerangkan, kualitas besi barbel dan dumbbell yang ada di gym, enggak sebanding dengan yang laki-laki itu sering gunakan.
“Aku enggak minta dia bragging soal pekerjaan dan pengalaman (nge-gym), tapi dia tetap ngomong,” cerita Ayu.
Dengan melakukan mansplaining, sebenarnya laki-laki tengah merendahkan lawan bicaranya. Baik perempuan, minoritas gender lain, maupun sesama laki-laki yang struktur sosialnya lebih rendah—contohnya kasus Miftah dan tukang es. Pertanyaannya, kenapa laki-laki melakukannya?
Baca Juga: ‘Mansplaining’: Perilaku Seksis yang Hambat Karier Perempuan
Di Balik Laki-laki Mansplaining
Sebagai gender yang dianggap kelas satu oleh budaya patriarki, laki-laki merasa punya kekuasaan di masyarakat dan ingin membuktikan statusnya sebagai yang utama. Hal ini yang disampaikan penulis dan aktivis Rebecca Solnit lewat esainya, Men Explain Things to Me (2014). Solnit menyebutkan, mansplaining dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan dan kepercayaan diri berlebihan karena kedudukan laki-laki dianggap lebih superior.
Anggapan bahwa laki-laki superior kemudian melekat dalam norma, bias, dan peran gender tradisional, yang sering mengesampingkan perempuan dan minoritas gender. Kemudian membentuk pandangan, perempuan enggak cukup kompeten dibandingkan laki-laki.
Koordinator Aliansi Laki-laki Baru (ALB) Wawan Suwandi menjelaskan, pandangan tersebut mulai tertanam dalam diri anak, lewat cara mereka dibesarkan di keluarga. Seperti memperkaya pengetahuan anak laki-laki supaya mereka siap menjadi pemimpin, dan memberikan kesempatan berbicara lebih besar.
Hasilnya, ketika tumbuh dewasa, lelaki terbiasa mengutarakan pendapat meski tak diminta. Bahkan membela pendapatnya dan merendahkan opini orang lain—terutama perempuan yang opininya dianggap enggak tepat.
Normalisasi stereotip itu tak hanya terjadi di keluarga. Di masyarakat luas, perempuan yang banyak bicara dicap cerewet, sedangkan laki-laki dinilai cerdas. Stereotip ini sama halnya dengan membungkam perempuan, dan meminggirkan mereka dari sistem. Misalnya menganggap kontribusi perempuan enggak penting, meragukan opini, dan enggak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan sering kali, mansplaining menjadi salah satu cara untuk membuktikan maskulinitas.
Masalahnya, mansplaining merugikan perempuan dan minoritas gender dengan membuat mereka percaya pada asumsi, bahwa dirinya tak kompeten. Kemudian menghambat mereka dalam mengutarakan ide.
Hal itu dialami “Asta”—bukan nama sebenarnya—yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jakarta. Ide-ide yang disampaikan dalam diskusi sering kali ditolak dan perjalanan kariernya diremehkan, karena Asta seorang minoritas gender.
“Aku jadi males ngasih saran. Soalnya harus membuktikan dulu kalau usulannya bakal berhasil,” tutur Asta
Selain soal pekerjaan, rekan kerja Asta pun pernah bilang, sebagai queer ia enggak perlu terlibat membahas isu lingkungan. Soalnya, persoalan yang dihadapi queer sendiri masih banyak.
“Interaksi sama orang ini memang ngabisin energi banget. Omongannya sampai pernah kebawa mimpi,” tambahnya.
Sedangkan bagi Ayu, mansplaining sempat membuatnya enggak percaya diri saat nge-gym. Terlebih ia enggak menggunakan jasa personal trainer, dan belajar dari video maupun artikel di internet.
“Jadi conscious sama gerakan sendiri karena takut dianggap aneh atau salah,” jelas Ayu.
Baca Juga: ‘Conformity to Masculine Norms’: Alasan Lelaki Berubah Seksis Saat di Tongkrongan
Bagaimana Cara Menghadapi Mansplaining?
Dari pengalamannya, Ayu menyebutkan dua cara yang bisa dilakukan saat menghadapi laki-laki di gym yang suka mansplaining. Pertama, mengucapkan terima kasih atas informasinya dan sampaikan bahwa kamu mengerti apa yang dilakukan—contohnya menggunakan alat-alat di gym. Lalu menegaskan kalau kamu enggak suka dengan penyampaiannya dan tak ingin diganggu. Cara ini bisa menjadi opsi kalau kamu merasa nyaman melakukannya.
Kedua, melapor ke orang yang punya otoritas di suatu tempat, jika perbuatan laki-laki enggak bisa diatasi maupun ditoleransi. Dalam konteks gym, kamu bisa melaporkan ke manajer soal ketidaknyamananmu supaya mereka yang bertindak. Terlebih mereka akan mengutamakan kenyamanan pelanggan. Ketiga, meninggalkan tempat sebagai upaya menghindar.
Sementara Asta menyarankan untuk merespons, dengan mengonfrontasi ucapan mansplain kalau kamu memiliki energi. Atau meminta teman laki-laki yang sadar soal mansplaining untuk memberikan penjelasan, bahwa ucapan itu merendahkan.
Namun, perkara menghadapi mansplaining seharusnya enggak dibebankan pada perempuan. Menurut Jundi, laki-laki bisa belajar membangun empati dengan terlibat dalam aktivitas yang dianggap tanggung jawab perempuan.
Misalnya ikut menyiapkan sarapan sebelum anggota keluarga lainnya bangun tidur, dan terlibat dalam pengasuhan anak. Dengan mengasuh anak—terutama yang belum bisa bicara, laki-laki akan belajar memahami perilaku dan perasaan anak: kenapa ia tantrum, menangis, dan menyebalkan.
Selain itu, bergabung dengan komunitas bisa menjadi opsi untuk belajar mendengarkan orang lain. Dari kegiatan ini, harapannya seseorang akan memahami bahwa setiap manusia memiliki persoalannya masing-masing. Karenanya, ia tidak bisa menjadikan pendapat atau pengalamannya sebagai standar untuk menilai orang lain.
“Empati akan diuji ketika seseorang berhadapan dengan minoritas dan kelompok marjinal,” ungkap Jundi. “Kalau kita punya empati yang baik, sensitivitas kita pun mudah bekerja dan tepat sasaran.”
Sementara, jika laki-laki sudah mengenal atau memahami mansplaining, Jundi menyebutkan untuk tidak bertindak sebagai enabler. Maksudnya, lelaki bisa menunjukkan ketidaksetujuannya atas perbuatan tersebut, dengan tidak reaktif dan mengucapkan apa pun. Bisa juga melakukan pendekatan asertif dengan mengungkapkan alasan mengapa ungkapan mansplaining itu tidak tepat dan bikin enggak nyaman.
Baca Juga: 4 Cara Hadapi ‘Mansplaining’ dan Interupsi dari Rekan Kerja
“Metode itu berguna supaya lawan bicara enggak merasa diserang dan memperburuk situasi,” ucap Jundi. “Tapi kalau kamu punya power atau status sosialnya selevel, bisa menegur langsung saat itu juga.”
Cara tersebut yang dilakukan Habib, 27, videografer asal Jakarta. Sejak mengenal mansplaining di media sosial dan mengulik lebih lanjut, ia bertindak jika ada anggota keluarga yang melakukan mansplain terhadap perempuan.
“Aku berusaha menjelaskan di lain waktu, kenapa laki-laki nggak boleh asal ngasih tahu kalau perempuan nggak minta dijelaskan,” cerita Habib. “Respons keluargaku ya kadang kaget, kadang nerima aja.”
Meski mansplaining kini masih dinormalisasi, kemauan untuk menjelaskan bahwa perbuatan ini merugikan perempuan dan minoritas gender, bisa menjadi langkah awal. Pun menjadi tanggung jawab bersama untuk saling belajar, mengingat mansplaining juga mengakar pada ketidaktahuan.
Artikel ini diproduksi oleh Magdalene.co sebagai bagian dari kampanye #WaveForEquality, yang didukung oleh Investing in Women, inisiatif program Pemerintah Australia.
Series artikel lain bisa dibaca di sini.
Ilustrasi oleh Karina Tungari