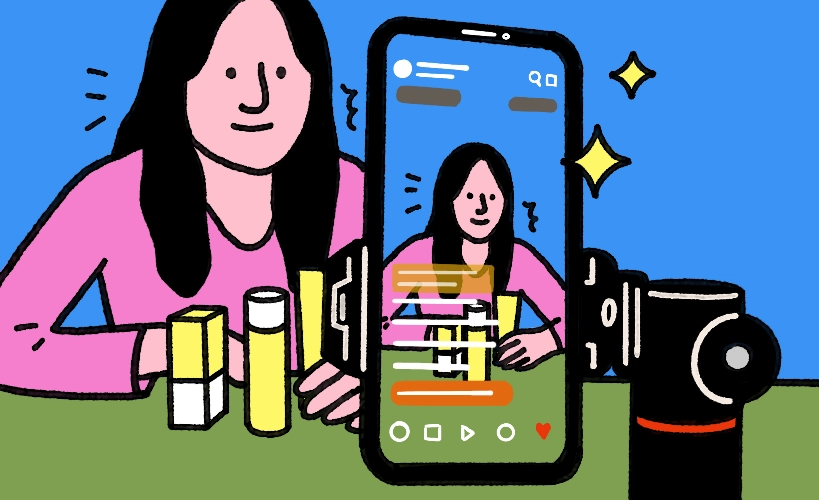Dari Sempak ke Martabat: Catatan Pribadi Relawan Banjir Aceh Tamiang

Minggu lalu, saya mengunjungi salah satu wilayah banjir di Aceh yang sempat ramai di linimasa. Di posko pengungsian, saya menangkap satu kebutuhan yang hampir selalu datang belakangan dalam percakapan bantuan, yaitu pakaian dalam. Ia paling dekat dengan tubuh, paling dekat dengan martabat. Tulisan ini saya tulis bukan sebagai laporan investigasi, melainkan catatan lapangan tentang hal kecil yang kerap terlewat, tetapi menentukan rasa aman penyintas.
Adegan di Posko
“Sempak. Sempak. Siapa yang belum ganti. Ukuran apa.”
Seorang relawan berteriak sambil mengangkat beberapa celana dalam yang baru tiba. Di tengah hiruk pikuk logistik, teriakan itu terdengar sepele. Justru di situlah kerja kemanusiaan yang paling nyata berlangsung.
Dalam potongan video yang sempat beredar, seorang remaja laki laki menjawab pertanyaan relawan dengan polos, “udah seminggu nggak ganti sempak.” Bagi penyintas, pakaian dalam bukan sekadar barang. Ia berkaitan dengan rasa bersih, rasa aman, dan tidak dipermalukan. Kebutuhan paling personal sering kali menjadi yang paling mudah terlewat dalam desain bantuan. Saya belajar, posko bukan hanya ruang logistik. Ia juga ruang martabat. Martabat seharusnya dirancang, bukan penyintas yang dipaksa menyesuaikan diri.
Dalam situasi bencana, pakaian menjadi donasi paling mudah. Ambil dari lemari, masukkan ke kardus, lalu kirim. Niatnya baik. Namun di lapangan, niat baik kerap berubah menjadi beban.
Di Desa Garoga, pakaian menumpuk di tanah, basah, bercampur lumpur. Yang tercecer bukan hanya kain, tetapi juga rasa hormat. Seorang relawan berkata, “banyak orang menyalurkan bantuan pakaian begitu, Bu. Asal dilempar. Makanya banyak yang mubazir. Lalu banyak postingan yang menyalahkan korban.” Penyintas tentu tidak mungkin memakai pakaian yang sudah basah dan berlumpur. Masalahnya bukan korban memilih milih bantuan, melainkan cara kita menyalurkan dan mengelolanya.
Cerita lain datang dari posko di Sibolga. Ada pakaian bagus, tetapi terlalu ketat atau terlalu terbuka. Tidak cocok dipakai ibu-ibu desa yang beraktivitas di ruang komunal. Sebagian akhirnya tidak didistribusikan. Bukan karena relawan sok suci, melainkan memang tidak mungkin dipakai dengan nyaman.
Di titik ini terlihat perbedaan dua logika. Logika yang penting sampai sering berujung pada tumpukan. Sandang menempel langsung ke tubuh. Yang dibutuhkan adalah tepat, layak, dan menjaga martabat, bukan menambah pekerjaan sortir tanpa akhir.
Baca juga: Bencana Sumatera Bukan Panggung Hiburan, Setop jadi ‘Performative Government’
Data Terpilah dan Martabat
Di sinilah gender bekerja secara nyata. Gender bukan slogan, melainkan cara membaca kebutuhan yang tidak netral. Dalam kebijakan pemerintah, pendekatan ini dikenal sebagai Pengarusutamaan Gender, yaitu upaya memastikan layanan publik termasuk respons bencana mencatat dan memenuhi kebutuhan berbeda antara perempuan, laki laki, anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya.
Jika Pengarusutamaan Gender berhenti di pelatihan dan dokumen, yang hilang di lapangan justru hal paling mendasar. Ukuran. Barang sensitif. Rasa aman. Di situasi bencana, gender terlihat ketika daftar kebutuhan berani menyebut pembalut, popok, dan pakaian dalam tanpa rasa malu.
Pengarusutamaan Gender berangkat dari data terpilah. Data yang memisahkan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia menjadi fondasi agar respons tidak meleset. Tanpa data semacam ini, donasi sandang cenderung mengikuti isi lemari kita, bukan kebutuhan tubuh orang lain. Akibatnya, posko menanggung kerja tambahan. Membongkar, memilah, menolak yang tidak layak, sekaligus mengelola rasa malu penyintas.
Pengelolaan sandang yang manusiawi membutuhkan prosedur sederhana. Jalur masuk bantuan jelas. Penyortiran dilakukan di sekretariat atau gudang, bukan di lantai posko. Pakaian diberi label ukuran dan kategori. Barang sensitif dibagikan per individu. Pakaian dalam harus baru. Titik. Di situlah martabat tidak boleh ikut hanyut bersama banjir.
Pengalaman ini saya temui di sekretariat relawan Yayasan Wisma Remaja Indonesia di Medan. Bantuan sandang untuk posko Aceh Tamiang tidak diperlakukan sebagai tumpukan, melainkan sistem. Donasi dibuka, disortir, dilabeli, lalu dikemas agar bisa langsung dipakai. Ukuran ditulis. Kategori dipisah. Barang sensitif disiapkan rapi sesuai kebutuhan.
Di titik itu, teriakan “sempak” bukan candaan. Ia strategi kecil untuk membuka percakapan tentang kebutuhan yang sering dianggap tabu. Hasilnya terasa. Penyintas menerima bantuan yang tepat. Relawan tidak tenggelam oleh lautan niat baik yang salah arah.
Dalam fase pemulihan, beban seharusnya berkurang, bukan bertambah. Pakaian bekas harus mengikuti kebutuhan, bukan isi lemari. Mulailah dari pertanyaan paling dasar. Yang dibutuhkan apa. Jika ragu, berhenti sejenak. Tanyakan. Catat. Lalu belanja sesuai daftar. Bila posko belum siap memberi data, jalur lain tetap tersedia. Donasi dana terarah. Voucher. Pembelian sesuai kebutuhan.
Baca juga: Tahun Gelap, Hari Ibu Tiba: Ketika ‘Berdaya dan Berkarya’ Terasa Jauh
Dan satu hal yang perlu dihentikan. Menyalahkan penyintas. Jika pakaian menumpuk, pertanyaannya bukan mengapa korban tidak bersyukur. Pertanyaannya siapa yang mengatur cara menyalurkan dan membagikannya.
Pada akhirnya, pakaian dalam mengajarkan hal paling sederhana. Martabat manusia sering lahir dari kerja sehari hari. Dari bertanya ukuran. Dari menyortir dengan sabar. Dari cara membagi yang menghormati tubuh orang lain. Dalam bencana, martabat tidak boleh menunggu air surut.