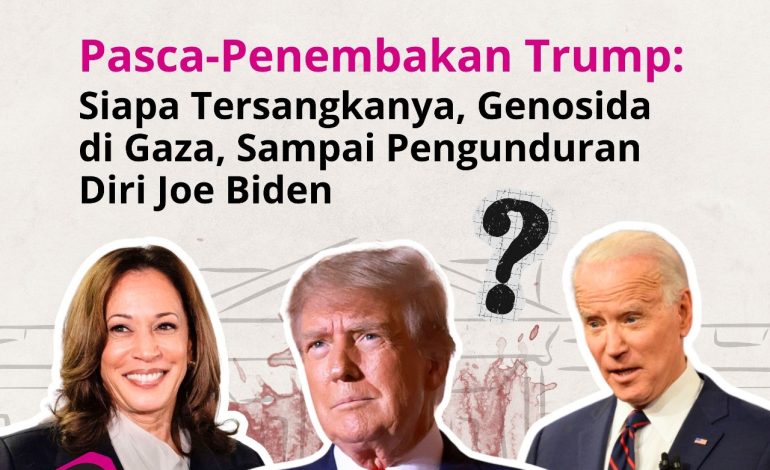Ghosting, Bahasa Gaul, dan Tantangan Penerjemahan

10 Juni 2024 lalu, BBC menerbitkan artikel berjudul “Billie Eilish: ‘I was ghosted. It was insane’. Sebagai pegiat bahasa, saya tertarik untuk mencari terjemahan kata ‘ghosted’ dalam bahasa Indonesia.
Namun, saya tidak bisa menemukan padanan kata yang sesuai, karena dalam konteks ini, ‘ghost’ bukan berarti hantu, dedemit, atau roh seperti terjemahan kamus. ‘Ghosting/ghosted’ dalam konteks tersebut berarti “ketika seorang teman atau calon kekasih tiba-tiba memutuskan semua komunikasi tanpa penjelasan apapun”–menghilang tanpa jejak.
Menariknya, beberapa mesin penerjemah seperti Google Translator dan DeepL juga tidak bisa memberikan padanan kata yang sesuai dalam bahasa Indonesia untuk kata “ghosting”.
Ini menunjukkan fenomena linguistik bahwa beberapa kata memang tidak bisa diterjemahkan (untranslatable). Sebab, bahasa terikat dengan budaya dan pandangan dunia si penutur, sehingga ada beberapa kata dalam satu bahasa yang tidak ada padanannya dalam bahasa lain.
Baca juga: Patah Hati Akibat ‘Ghosting’ Sungguh Melelahkan
Tantangan Penerjemahan
Dunia penerjemahan sering mengalami tantangan ketika beberapa kata dari sumber bahasa (source language) tidak memiliki padanan kata yang sesuai di bahasa sasaran (target language). Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan fenomena ini.
Pertama, Adam Głaz, ahli linguistik dari Universitas Maria Curie-Skłodowska, Polandia, berpendapat bahwa saat ini, dunia penerjemahan mengadopsi konsep ‘linguistic worldview’ yang berbasis pandangan dunia pengguna bahasa. Penerjemahan tidak lagi semudah mencari arti kata di kamus, melainkan sebuah proses transfer yang melibatkan dua pandangan dunia yang berbeda (antara sumber bahasa dan target bahasa). Pandangan ini menganggap bahasa sebagai alat untuk mengonstruksi, menafsirkan, dan mengekspresikan dunia penuturnya.
Bahasa berfungsi sebagai penyaring persepsi penuturnya dan memengaruhi cara suatu kelompok budaya tertentu mengekspresikan pengalaman mereka. Akibatnya, penutur bahasa yang berbeda memiliki cara yang berbeda dalam memandang dunia.
Fred Jandt, pakar komunikasi antarbudaya dari California State University, Amerika Serikat (AS) menjelaskan bahwa komunitas Inuit Eskimo di Kanada mempunyai beragam kata dalam bahasa mereka untuk mendeskripsikan jenis-jenis salju yang berbeda karena pengalaman hidup mereka berhadapan dengan salju sepanjang tahun. Sebut saja, qana (butiran atau kepingan salju); akilukak (salju yang lembut dan mengembang); dan aput (salju yang telah jatuh di atas tanah). Sedangkan negara tropis seperti Indonesia yang tidak mengenal musim dingin bersalju hanya mempunyai satu kata yaitu ‘salju’ untuk mendeskripsikan semua jenis salju tersebut.
Konsep worldview di dunia penerjemahan ini bisa dikaitkan dengan hipotesis linguistic relativity, yang menyebutkan bahwa penutur bahasa yang berbeda memandang dan mengekspresikan dunia di sekitar mereka secara berbeda karena bahasa memengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang.
Kedua, terdapat juga pandangan kontemporer di dunia pengajaran dan pembelajaran bahasa yang melihat bahasa tidak lagi sebatas kosakata, sistem tata bahasa (grammar), atau arti yang tersedia di kamus. Namun, hubungan antara bahasa dan budaya semakin ditekankan. Memahami sebuah bahasa memerlukan pemahaman tentang dunia dan budaya yang tertanam di bahasa tersebut.
Claire Kramsch, ahli linguistik terapan dari UC Berkeley, AS, berpendapat bahwa bahasa mengekspresikan, mewujudkan, dan menyimbolkan/mencerminkan realitas budaya penuturnya. Sementara Patrick Moran, seorang peneliti dan penulis di bidang pengajaran bahasa asing, menuturkan bahwa bahasa tidak hanya melambangkan produk, praktik, perspektif, komunitas, dan orang-orang dalam sebuah budaya, namun bahasa itu sendiri juga merupakan produk dari budaya tersebut.
Nadia Ma’shumah dan Sajarwa, ahli linguistik dari Universitas Gadjah Mada mengulas bahwa untuk istilah-istilah budaya yang tidak bisa diterjemahkan, penerjemah biasanya menerapkan strategi-strategi seperti mempertahankan kata asli untuk menghindari kesalahan penerjemahan (transference; contohnya istilah ‘ayah’ dari bahasa India kontemporer yang berarti pengasuh perempuan yang berasal dari India) atau mengadaptasi kata-kata khusus dari sumber bahasa dengan pengucapan normal di bahasa sasaran (naturalisation; contohnya ‘colonel’ >> kolonel).
Baca juga: ‘Ghosting’ dan ‘Backburner’: Tabiat yang Baru Muncul Pasca-era Dating Apps?
Kamus Saja Tidak Cukup
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa menggunakan arti harfiah dalam kamus saja tidak cukup untuk memahami arti sebuah kata dari bahasa asing. Memahami bahasa terlebih dulu memerlukan pemahaman konteks budaya serta pandangan dunia yang melekat dalam bahasa tersebut.
Ini tidak hanya terjadi dalam bahasa Inggris, seperti dalam contoh ‘ghosted’. Terdapat beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang juga sulit ditemukan padanan katanya dalam bahasa Inggris, seperti:
1. Mudik
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ‘mudik’ sebagai “pergi/berlayar ke udik” atau “pulang ke kampung halaman”. Sedangkan mesin penerjemah online mengartikan ‘mudik’ sebagai ‘going home’, ‘homecoming’, atau ‘exodus’.
Namun, sebagai orang Indonesia, kita paham bahwa mudik bukan hanya sekadar pulang (going home) atau ramai-ramai pulang (exodus). Ada elemen perayaan hari raya serta perasaan rindu seorang perantau terhadap kampung halaman dan keluarga. Emosi yang melekat dalam kata ‘mudik’ ini hilang dalam terjemahan (lost in translation) jika pemahaman akan pandangan dunia atau budaya (worldview) dari kata ini dikesampingkan. Mudik bukan sekadar pulang–terdapat juga rasa memiliki (sense of belonging) dan kerinduan yang mendalam terhadap kampung halaman.
2. Curhat, baper, dan singkatan-singkatan ala anak muda
Beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang tidak ada padanan katanya dalam bahasa Inggris mayoritas merupakan singkatan atau bahasa sehari-hari yang diciptakan oleh anak-anak muda.
Contohnya, ‘curhat’ atau ‘curahan hati’, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi pada orang terdekat”, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ‘to share’ (berbagi) atau ‘to vent’ (mengeluarkan unek-unek).
Padahal, ‘curhat’ bukan sekadar berbagi cerita dan tidak selalu berhubungan dengan rasa kesal atau unek-unek. Ada elemen perasaan mendalam (atas objek yang diceritakan) serta kepercayaan yang diberikan oleh orang yang melakukan curhat terhadap yang dicurhati. Sedangkan, ‘to vent’ dalam bahasa Inggris bisa dilakukan terhadap siapa saja, bahkan orang asing yang baru kita temui di bus.
Baca juga: Bagaimana Tata Ruang Memengaruhi Bahasa Campur-campur Ala Jaksel?
Kata lain yang bisa dijadikan contoh adalah ‘baper’ (bawa perasaan). KBBI mendefinisikan baper sebagai “berlebihan atau terlalu sensitif dalam menanggapi suatu hal”. Sedangkan mesin penerjemah Google mengartikan ‘baper’ sebagai ‘excited’ (bersemangat/sangat senang) dalam bahasa Inggris.
Contoh-contoh di atas menunjukkan adanya makna yang hilang ketika terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain tidak disertai worldview dari bahasa tersebut. Artinya, mempelajari arti sebuah kata dalam bahasa asing saja tidak cukup. Dalam berkomunikasi, memahami orang lain dengan lebih baik memerlukan pemahaman akan bagaimana makna atau arti kata tersebut dikonstruksi. Terutama di dunia global dan kontemporer saat ini, ketika bahasa tidak lagi dilihat sebagai sistem yang statis, melainkan produk budaya yang mengekspresikan pandangan dunia penuturnya.![]()
Billy Nathan Setiawan, PhD Candidate in Applied Linguistics, University of South Australia
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.