Bahagia dan Kejar Mimpi Pasca-Bercerai: Cerita Tiga Perempuan
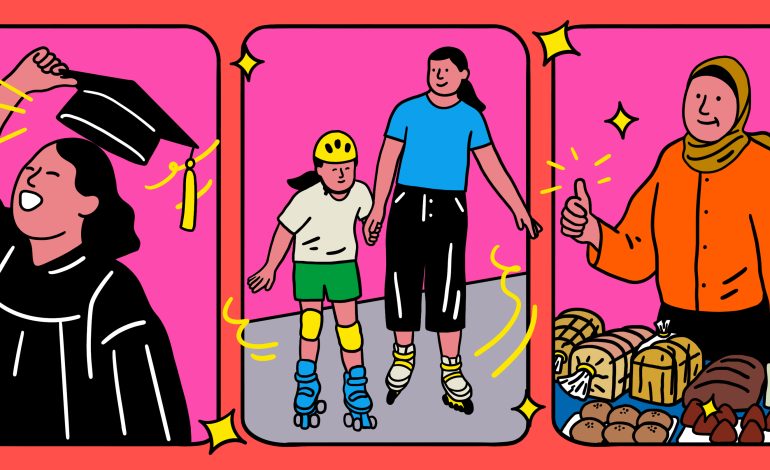
Bagi sebagian perempuan, bangkit dari perceraian bukan hal mudah. Selain menghadapi pahitnya perpisahan, mereka juga rentan didiskriminasi warga. Belum lagi stigma merendahkan yang sering kali membuat perempuan bertambah takut keluar dari penikahan beracunnya. Label bahwa janda senang menggoda lelaki lain, tak bermoral, hingga jadi target objektifikasi seksual misalnya.
Padahal, di balik stigma tersebut, menjadi janda bisa jadi adalah sebuah agensi. Seperti Poppy, 48, konsultan dan ibu satu anak; “A”, 38, karyawan swasta yang juga ibu tunggal; dan “Melia”, 25, guru dan mahasiswa S2. Ketiganya memilih bercerai untuk memprioritaskan kesejahteraan diri.
Meski berasal dari generasi berbeda—X, milenial, dan Z—mereka punya motivasi serupa untuk bangkit. Bahkan mereka menunjukkan berbagai prestasi, sebagai perempuan yang berdaya pasca-bercerai. Berikut kisah lengkap mereka.
Baca Juga: Stigma Janda dalam Pemberitaan di Media
POV Poppy
Tahun 2015, mantan suami memutuskan meninggalkanku dan anak begitu aja. Kami juga enggak tahu dia ke mana. Awalnya perasaanku campur aduk: Khawatir dengan kondisi mantan suamiku, marah karena dia enggak kasih kabar. Terus bingung karena mantan suami enggak pulang-pulang. Padahal waktu dia pergi, kondisi rumah tangga kami membaik, ada banyak konflik yang masih bisa diselesaikan.
Akhirnya mantan suamiku bilang, dia memilih bersama perempuan lain dan sudah enggak mau melanjutkan pernikahan. Padahal di usia pernikahan yang kelima itu, kami sudah bersama lebih dari sepuluh tahun.
Kejadian itu meninggalkan trauma untuk anak kami. Soalnya mantan suamiku pamitnya kerja ke luar kota, tapi enggak pernah pulang. Setelah itu, anakku trauma mendengar kata “kerja”, sampai nelpon aku setiap sore sambil nangis-nangis. Katanya, “Mama kerja ya? Nanti pulang enggak?”
POV “A”
Di tahun pernikahan yang kelima, aku memilih bercerai karena visi dan misi yang enggak sejalan dengan mantan suami. Aku enggak bisa cerita detailnya, yang jelas aku merasa cukup (mempertahankan pernikahan). Daripada saling menyakiti, berantem di depan anak, dan aku nangis terus. Enggak sehat buat kami.
POV Melia
Aku menikah selama empat tahun, lalu memilih cerai karena mantan suami selingkuh beberapa kali. Efeknya fatal. Aku mengalami gangguan jiwa, sampai dua kali dirawat di bangsal psikiatri di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo), Jakarta Pusat.
Pas aku dirawat, mantan suamiku ketemu selingkuhannya. Bahkan, mereka melakukan aktivitas seksual, dan itu mengganggu kewarasanku. Terus pas lagi nangis-nangis, aku bilang ke orang tua kalau pengen cerai. Enggak tahu kenapa, rasanya setengah beban hilang pas ngomong begitu. Walaupun waktu itu belum ada rencana kapan cerainya, tapi ternyata itu yang selama ini kumau.
Cuma ya enggak semudah itu, sempat maju mundur karena saat itu masih sayang sama mantan suami. Tapi di satu sisi aku sadar, itu bukan perasaan sayang, melainkan trauma bonding.
Pertimbangannya ya kesejahteraanku. Aku mau tetap waras dan lanjutin hidup, soalnya dulu pengen bunuh diri setiap ingat mantan suamiku selingkuh. Akhirnya kami resmi bercerai secara agama itu Juni 2024.
POV Poppy
Selama menikah juga aku menyokong hidup dia (mantan suami). Sempat dikejar debt collector karena dia utang sampai ratusan juta, di tiga kartu kredit. Rasanya nggak pengen bayar ya, soalnya bukan utangku. Tapi aku sadar, dengan memberikan nama dan slip gajiku, sebenarnya aku mengizinkan mantan suami untuk berutang.
Setelah paham kalau aku bertanggung jawab untuk itu semua, langkahku jadi lebih ringan. Akhirnya aku minta restrukturisasi kartu kredit satu per satu dan pelan-pelan menyelesaikan masalahnya.
POV “A”
Waktu itu perasaanku campur aduk: Marah, sedih, kecewa, lega, dan emosi naik turun. Sedih karena ternyata mengalami kondisi ini (berpisah dengan pasangan). Lebih ke momennya ya, bukan takut dengan status ibu tunggal—kebetulan orang tuaku juga bercerai. Dulu sempat nyoba rujuk juga, tapi cuma sepihak—aku aja.
Terus mamaku bilang, “Kamu jangan merasa rendah diri, takut, dan bikin malu karena mamamu juga berpisah. Biarin aja (komentar orang lain), daripada kamu kepikiran, stres, sakit, berpengaruh ke aktivitasmu. Mama akan tetap dukung.”
Baca Juga: Pesan Para Janda untuk Perempuan Lajang di Luar Sana
POV Melia
Selain kehilangan orang yang dicintai, sebelum mutusin cerai, aku sempat mikirin konsekuensinya: Omongan orang-orang dan stigma soal janda. Tapi aku nanggepinnya dengan membuktikan kalau aku janda dan berprestasi. Jadi aku bisa balas pandangan rendah dengan itu.
Dulu karierku lumayan gemilang sebenarnya. Tahun 2021 aku lulus kuliah, dapet penghargaan cumlaude. Lanjut bekerja di tempat magangku, karena kinerjaku dinilai bagus. Sejak diselingkuhin, hidupku kacau banget.
Aku resign karena kantorku (letaknya) di lantai atas. Pas mau ngantor, ada pikiran mengganggu untuk loncat. Akhirnya enggak bisa kerja lagi, nganggur, berat badan naik karena depresi, terus enggak bisa beraktivitas apa pun. Kurang lebih dua tahun kondisi kejiwaanku enggak stabil.
POV Poppy
Aku belajar memahami, ada kontribusiku dalam perpecahan rumah tangga ini. Bukan berarti salahku kalau dia selingkuh, tapi ada kontribusiku dalam konflik. Saat itu, aku sibuk memikirkan diri sebagai istri yang terluka karena diselingkuhi, lupa bahwa aku seorang ibu.
Sebenarnya aku baru menggugat cerai pada 2017, dua tahun setelah kami berpisah. Terus ketuk palu (resmi bercerai) Maret 2018. Soalnya dulu aku masih mikir pakai hati. Ibaratnya mantan suamiku yang pergi, aku udah banyak rugi dalam relasi, masa aku juga yang repot menceraikan?
Bahkan sempat mengupayakan rekonsiliasi—dalam arti jangan mikirin relasi antara aku dan mantan suami, tapi dengan anak. Tapi enggak berhasil karena upayanya cuma dari aku. Ini hampir lima tahun (mantan suami) nggak pernah nyamperin atau telepon anaknya. Dibilang berat, sebenarnya enggak juga karena udah terbiasa. Cuma di satu sisi ya ada beratnya, karena apa yang bisa dipukul berdua jadi sendiri.
Pelan-pelan, aku menyeimbangkan antara hati dan logika. Ternyata, I was a single married woman. Soalnya pas menikah, aku yang 90 persen ngurusin keuangan keluarga karena mantan suamiku pekerja lepas. Setelah cerai, perjalanannya justru terasa lebih enteng.
POV “A”
Di masa-masa struggling pasca-bercerai itu, aku mood swing. Pernah ke psikolog tapi enggak rutin. Jadi kalau merasa lagi enggak baik-baik aja, aku me time.
Terus sempat nyobain banyak olahraga—renang, lari, gym, dan jalan kaki. Pernah juga journaling, ikut kursus, belanja, dan makan. Tapi semuanya enggak begitu berpengaruh, enggak ada perubahan signifikan. Kalau ke-trigger sedikit, langsung emosi. Di situ aku sadar, harus menolong diri sendiri dan anak (dari situasi ini).
POV Melia
Dulu aku menggantungkan kepercayaan diriku ke penerimaan mantan suami. Aku (merasa) enggak berharga karena dia selingkuh, berarti aku enggak cukup baik, enggak bisa membahagiakan dia, tapi harus memaafkan. Di satu sisi marah ya, tapi di sisi lain kayak harus menerima lagi. Jadi aku enggak bisa berkembang karena ada di survival mode terus, sampai enggak bisa melakukan apa pun.
Setelah bercerai dan keluar dari survival mode, aku sadar enggak pantas diperlakukan begitu. Walaupun pernah diselingkuhi, bukan berarti aku enggak berharga. Jadi dapet cara pandang yang berbeda banget dan berpengaruh ke semua aspek kehidupanku. Apa pun yang dilakukan mantan suamiku, I’m good enough.
POV Poppy
It was a blessing in disguise. Aku dan anak banyak berkegiatan bareng sebagai proses healing kami. Misalnya staycation, yang jadi tradisi pas libur Lebaran dan Natal. Atau traveling ke luar kota dan luar negeri pas anak libur sekolah.
Kami (Poppy dan anaknya) mulai bangkit dengan bantuan profesional—psikolog dan psikiater. Itu membantu mengurai perasaan kami. Soalnya, aku enggak punya support system. Orang-orang terdekat justru sulit berempati. Makanya mau nanya atau minta tolong pun bingung.
Kalau cerita ke keluarga, malah dimarahin dan dihakimin. “Emang kamu kenapa, kok dia sampai selingkuh?” kata keluarga. Padahal, enggak usah ditanya pun, aku udah nyalahin diri sendiri.
Dan itu momen-momen beratnya. Butuh sekitar dua tahun untuk bisa bangkit secara emosional. Belum lagi dari segi finansial, harus lunasin utang mantan suami karena waktu itu aku masih berstatus istri. Terus mikirin pekerjaan, anak, dan rumah. Makanya aku mendirikan PenTaS (Perempuan Tanpa Stigma), ruang aman berupa komunitas untuk teman-teman perempuan.
POV “A”
Kehadiran keluarga membantuku untuk bangkit setelah bercerai ya. Mereka mendampingi secara emosional, nggak pernah ninggalin aku. Selain itu juga larinya ke ibadah sih. Walaupun ada ketakutan, aku percaya sama Tuhan, pasti bisa menghadapi semuanya.
Oh ya, pas lagi ngejalanin proses perceraian, aku direkomendasikan ikut komunitas Single Mom Indonesia (SMI). Pertamanya mikir, paling kegiatannya arisan dan ngegosip kayak ibu-ibu sosialita. Pas cek Instagramnya, ternyata mereka punya program spesifik dan terarah. Lalu aku registrasi jadi member, terus silent reader aja di grup.
Pas pandemi, beban kerja berkurang, aku memberanikan diri jadi relawan. Setelah ikut rekrutmen, aku diterima untuk pegang public relations SMI. Sekitar sebulan tim SMI melihat performaku, langsung diajak jadi pengurus utama.
Ketika aktif di komunitas, aku merasa bermanfaat karena bisa sharing dan saling mendengarkan pengalaman sesama ibu tunggal. Misalnya ada sesuatu yang triggering pun, aku lebih bisa mengontrol emosi dan bijak menanggapinya.
POV Melia
Aku udah mulai bangkit sebelum resmi bercerai. Saat itu, aku berobat ke psikiater dan ke psikolog—ini gonta-ganti ke beberapa psikolog sampai nemuin yang tepat. Sampai aku bilang ke salah satu psikolog, udah nyoba banyak terapi sama psikolog lain, tapi enggak ngaruh. Akhirnya dia menyarankan terapi brainspotting untuk menyembuhkan trauma.
Itu kan terapi otak ya, kepalaku langsung sakit. Tapi itu tandanya melepas trauma, dan dari situ mendingan banget. Apalagi setelah cerai makin sering terapi untuk mengobati luka.
Jadi aku bisa bangkit karena selama dua tahun itu berusaha banget. Aku enggak berpikir waktu akan menyembuhkan (luka) ya, justru kita yang harus aktif nyari bantuan. Dan enggak harus ke psikolog, cuma buatku ini salah satu cara yang membantu.
Aku juga enggak menafikkan bisa sembuh karena punya support system. Ada keluarga, teman-teman kampus, SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan teman kursus. Alhamdulillah, mereka ada buatku sampai sekarang.
Baca Juga: Dear Janda: Kamu Perempuan Berdaya, Kamu Berhak Bahagia
POV Poppy
Sejak 2017, aku mulai aktif di komunitas. Salah satunya jadi pendamping psikososial Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Lalu aku mendirikan PenTaS tahun 2020, berawal dari banyaknya teman-teman perempuan yang curhat. Aku merasa, cerita para perempuan ini banyak yang mirip. Kebetulan, sebelumnya aku dan partnerku—Mia Amalia—gabung dalam komunitas khusus buat janda. Terus kami mikir, enggak cuma janda yang mengalami stigma, tapi semua perempuan.
Akhirnya, aku dan Mia membangun PenTaS untuk memberikan ruang curhat bagi perempuan, sekaligus meningkatkan kapasitas. Kami saling melengkapi: Aku di bagian edukasi terkait KBG dan pendampingan teman-teman yang mengalami KBG, Mia untuk pengembangan pribadi. Selain itu, PenTaS juga sharing soal well-being. Ini untuk teman-teman belajar meregulasi emosi.
Jalan empat tahun ini, kami melihat teman-teman perempuan (yang tergabung di PenTaS) bersikap kritis. Kalau ada sesuatu yang terjadi, mereka mengurai perasaan sebelum bertindak untuk mengatasi.
Kegiatan lainnya itu kumpul-kumpul, sharing, bikin konten medsos, dan ada Pekan Berdaya untuk para janda. Kami kolaborasi dengan teman-teman perempuan untuk melihat, apa aja yang bikin perempuan berdaya secara finansial. Jadi banyak aktivitasnya.
POV “A”
Di SMI, kami berupaya memberdayakan ibu tunggal—ada yang karena berpisah, suaminya meninggal, atau single mom by choice. Kami kolaborasi dengan psikolog, psikiater, dokter spesialis anak, dokter umum, dan berbagai pakar lain untuk mendukung kebutuhan anggota SMI.
Di situ para member belajar mengenal emosi, co-parenting dengan mantan pasangan, dan cara menghadapi anak pasca perpisahan—ini pun dibedakan berdasarkan usia anak. Pernah juga membahas perencanaan finansial, karena salah satu tantangan terbesar ibu tunggal kan finansial ya.
Nah kalau kolaborasi, kami kasih tahu fasilitatornya terkait perilaku ibu tunggal. Apa yang boleh dan enggak dibicarakan, yang jadi pemicu, dan seperti apa keseharian yang dihadapi.
POV Melia
Setelah bercerai, aku punya kebebasan mengekspresikan emosi dan pendapat. Lalu fokus ke minatku dan lebih mengenal diri sendiri. Tadinya, aku cuma mikirin masalah itu-itu aja, sekarang lebih mempertimbangkan minat dan mengeksplor hal-hal yang kusuka. Soalnya aku tahu, I am good enough.
POV Poppy
Selain mendirikan PenTaS, ada banyak pencapaian yang kuraih setelah bercerai. Yang terbesar sebenarnya mampu membesarkan anak sendirian, menyekolahkan di tempat terbaik versiku, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, dan melihat diriku utuh sebagai orang tua—bukan hanya ibu.
Terus gimana aku bermanfaat bagi banyak orang sebagai pendamping KBG, salah satunya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) karena aku juga penyintas KDRT. Nggak cuma perselingkuhan ya, dulu mantan suamiku nyamain aku dengan binatang karena gemuk. Ditambah posesif juga yang dianggap bentuk cinta.
Sekarang ada korban, penyintas, dan penggerak yang datang ke aku untuk bertanya berbagai hal. Ada juga yang kirim direct message, ngucapin terima kasih karena bisa bercerai. Aku enggak merasa paling berjasa, tapi bisa berdaya bersama. Hal-hal kayak gini yang membuatku terus melanjutkan hidup, dan ada banyak hal yang kupelajari dari membantu orang lain.
Lalu aku juga melanjutkan mimpiku—ingin jadi sarjana hukum kayak almarhum papa. Sekarang kesampaian karena aku punya semangat belajar dan lagi kuliah hukum.
POV “A”
Aku merasa berdaya karena bisa mengeksplor diri sendiri, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Termasuk networking. Di situ aku bisa bikin banyak program bermanfaat untuk para ibu tunggal. Contohnya bedah CV (Curriculum Vitae), latihan percakapan dalam Bahasa Inggris, kerajinan tangan, dan manggang kue.
POV Melia
Di jurnalku, ada banyak kejadian dan pencapaian yang mengubah hidup. Misalnya berani lasik setelah bertahun-tahun pakai kacamata, dapat rezeki umroh, kepilih jadi mentor pendidikan di luar kota. Aku juga kerja sebagai shadow teacher—guru yang membantu anak berkebutuhan khusus—di salah satu sekolah internasional. Bahkan bisa ikut kursus diploma montessori dan Agustus nanti, aku ngelanjutin S2 di bidang sains psikologi pendidikan.
Sama menabung juga sih. Buat orang lain mungkin hal biasa ya, tapi ini pencapaian sangat baik buatku karena punya tabungan berbentuk uang maupun emas.
POV Poppy
Diskriminasi tuh ada banget. Makanya di Instagram, aku bikin segmen khusus judulnya “Janda vs Negara”. Ini ngebahas perbedaan perlakuan di (lingkungan) sosial. Soalnya, pas tahu aku janda, orang melihatku berbeda. Sampai aku memutus hubungan dengan beberapa kelompok orang, yang menurutku enggak bisa melihatku sebagai manusia. Mereka melihatku sebagai ancaman untuk rumah tangga.
Yang menyakitkan lagi, bapaknya anakku kan enggak tahu di mana. Dia enggak pernah menafkahi, nanya kabar, atau kontribusi apa pun ya selain finansial. Tapi pas anakku lulus SD (Sekolah Dasar), nama bapaknya yang ditulis di ijazah.
Karena itu, aku mengupayakan namaku ditulis di ijazah anak dengan bikin petisi, yang diisi lebih dari 16 ribu orang. Yang mendukung bukan ibu tunggal aja, tapi anak-anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Akhirnya Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) menyatakan nama ibu boleh tertulis di ijazah, lewat Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
POV “A”
Alhamdulillah, aku pribadi enggak pernah mengalami diskriminasi. Tapi, teman-teman di komunitas (SMI) banyak yang mengalami. Mereka dianggap calon perebut suami orang, bahkan oleh perempuan sendiri.
Di beberapa perusahaan bahkan enggak memberikan kesempatan ibu tunggal untuk berkarier lebih tinggi. Ada yang didiskriminasi dari tahap wawancara, karena diragukan enggak bisa bagi waktu (antara pekerjaan dan anak).
POV Melia
Dulu aku masih menutup statusku sebagai janda. Soalnya takut banget diomongin tetangga dan saudara—walaupun menurutku mereka ngomongin di belakang. Tapi akhir-akhir ini mulai berani karena udah mengenal diriku. Aku merasa punya kekuatan melawan siapa pun yang mendiskriminasi.
Artikel ini diproduksi oleh Magdalene.co sebagai bagian dari kampanye #WaveForEquality, yang didukung oleh Investing in Women, inisiatif program Pemerintah Australia.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari
Series artikel lain bisa dibaca di sini:
Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian I)
Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian II)
Ketika Bapak Rumah Tangga Bicara Stigma hingga Omongan Tetangga






















