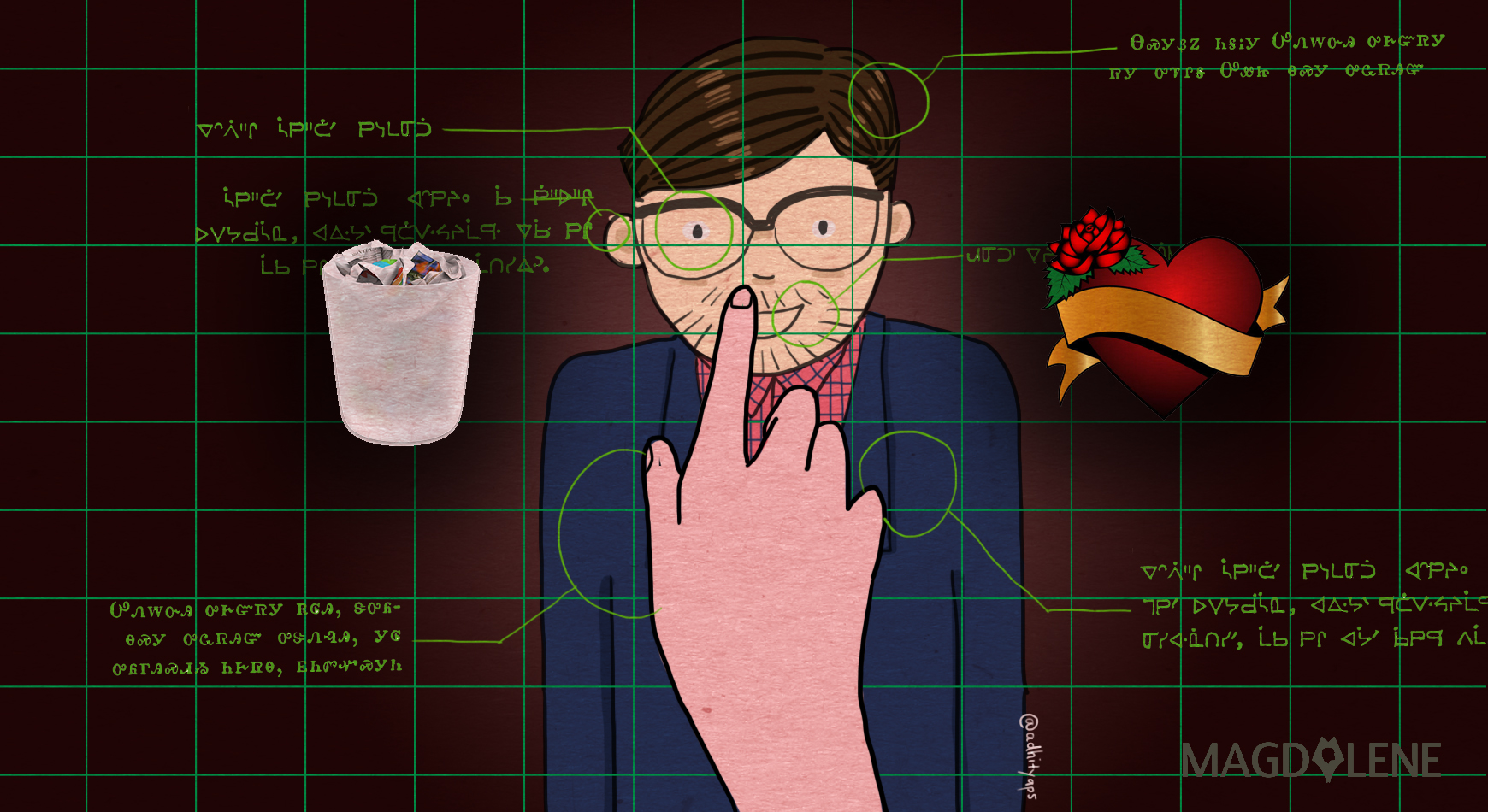Kekerasan dalam Relasi Romantis, Di Mana Jalan Keluar?

Belakangan, Indonesia dihebohkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami selebriti LK oleh suaminya. Keberanian LK untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi memantik kesadaran publik untuk melawan KDRT. Tak heran jika ia panen dukungan dari masyarakat. Namun tak berselang lama, ketika LK mencabut laporan, dukungan publik ikut tercerabut. Mereka berbalik arah mencaci dan menghakimi LK karena merasa di-prank.
Kekecewaan publik ini semakin terlihat lewat munculnya tagar #BoikotLeslar, tepat setelah ia mencabut laporan. Lewat tagar ini, warganet menolak kehadiran pasangan ini kembali lagi ke layar kaca dan jadi bintang tamu di berbagai acara.
Pertanyaannya, kenapa kita harus sibuk mencaci LK? Bukankah keluar dari relasi romantis yang abusif dan KDRT itu tak semudah membalikkan telapak tangan?
Baca Juga: Merebut Tafsir: Yang Tersisa dari Kontroversi Oki Setiana Dewi
Kompleksitas Keadaan Korban KDRT
Reaksi negatif pada LK menjadi penanda bahwa kesadaran publik tentang KDRT masih di level permukaan saja. Dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang menganggap KDRT sebagai kekerasan berbasis gender yang sederhana. Korban bisa dengan mudah mengakhiri relasi abusifnya dengan pasangan, semudah seseorang mengakhiri relasi dengan kata putus atau cerai. Padahal keadaannya tak semudah itu.
Masyarakat harus paham ada kompleksitas dalam kasus KDRT yang membuat para korbannya sulit keluar dari relasi yang abusif. Butuh waktu yang cukup lama dan percobaan berulang kali sampai akhirnya korban memutuskan untuk pergi.
Hal ini bisa dilihat dalam hasil survei DomesticShelters.org yang meneliti 844 responden mantan korban KDRT. Dalam survei itu disebutkan, korban butuh waktu rata-rata sekitar 6,3 kali sebelum mereka benar-benar berpisah dengan pasangan dan keluar dari relasi abusif.
Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Pertama, korban KDRT umumnya mengalami trauma bonding atau ikatan trauma. Mengutip dari laman National Domestic Violence Hotline, ikatan trauma adalah hasil reaksi individu terhadap situasi traumatis, termasuk rasa malu, eksploitasi, dan bahaya.
Secara biologis, ikatan trauma yang kita kembangkan ini berasal dari ketergantungan sejak lahir pada orang lain untuk bertahan hidup. Kelangsungan hidup memang telah jadi dasar keterikatan manusia. Sehingga, ketika kelangsungan hidup terancam, kita secara alami mencari seseorang yang terlihat sebagai pengasuh dalam hidup. Seseorang yang menurut pandangan kita mampu memberikan dukungan, perlindungan, dan perawatan.
Karena itu, ketika sumber dukungan utama seseorang juga adalah pelaku kekerasan, ikatan trauma juga dapat berkembang. Korban punya potensi besar untuk kembali lagi kepada pelaku untuk mendapatkan kenyamanan dan afirmasi ketika mereka terluka, bahkan jika orang lain yang menyebabkannya. Hal ini juga tak lain didasari karena adanya lingkar kekerasan.
Dalam tulisan Lies Marcoes, aktivis perempuan Islam di Magdalene, lingkar kekerasan ini dijelaskan sebagai siklus melingkar yang dialami oleh korban KDRT. Dalam siklus ini, satu kejadian kekerasan dalam rumah tangga biasanya diikuti dengan penyesalan pelaku, lalu suasana psikologisnya masuk ke masa permakluman dan pengampunan dari istri.
Selanjutnya, masa “bulan madu” yang diikuti masa jeda kekerasan. Umumnya ditandai oleh love bombing atau usaha seseorang memberikan perhatian, kekaguman, dan kasih sayang yang berlebihan dengan tujuan memanipulasi hubungan. Di sini, korban merasa mereka dicintai dan dibutuhkan. Mereka jadi yakin pelaku mau berubah. Namun setelah lewat fase ini, pelaku akan menghajar lebih keras lagi. Begitu seterusnya dengan intensitas yang makin kuat dengan siklus waktu yang makin pendek.
Korban KDRT yang mengalami ikatan trauma ini pun akan semakin terpuruk dan susah untuk keluar dari relasi abusif jika mereka telah punya anak. Dalam penelitian Untold Stories of Women Living in Violence: Lived Realities of Why Women Stay: A Case Study of Ngombe and Kanyama Compounds in Lusaka (2019) menemukan, mayoritas responden perempuan memilih bertahan dalam hubungan karena anak-anak. Dalam relasi seperti itu, perempuan lebih mengutamakan kebahagiaan dan keamanan anak-anak terlebih dahulu, ketimbang kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri.
“Saya punya anak dengan dia (pelaku), saya tidak seharusnya pergi.”
Hasil yang sama juga terlihat dalam penelitian pada 2021 terhadap kampanye #WhyIStayed di Twitter. Dalam penelitian yang berjudul Leaving Was a Process, Not an Event”: The Lived Experience of Dating and Domestic Violence in 140 Characters, korban dengan anak-anak memiliki hambatan praktis dan psikologis yang lebih kompleks.
Korban merasa sangat bersalah jika berusaha memisahkan anak-anak dari orang tua dan rumah mereka. Mereka takut anak mereka tumbuh tanpa sosok orang tua yang lengkap dan itu bisa memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Hal ini pun diperparah karena juga dibentuk untuk jadi tak percaya diri oleh pasangannya lewat kekerasan ekonomi. Kemampuan korban menafkahi dan membesarkan anaknya seorang diri, jadi pertanyaan yang sering mendasari keputusan mereka untuk tetap bertahan.
Baca Juga: Beranilah untuk Berpisah
Minimnya Dukungan pada Korban KDRT
Sepanjang 2004-2021, Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, sebanyak 544.452 kasus kekerasan terjadi dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal. Kendati UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah lama disahkan, ternyata masih ada hambatan besar dalam implementasi produk hukum ini, yaitu pencabutan laporan oleh korban.
Kasus LK menandai bagaimana pencabutan laporan oleh korban sudah bukan anomali. Karenanya, kita perlu memahami lebih dalam tentang budaya hukum di Indonesia. Lawrence Meir Friedman dalam bukunya The Legal System A Social Science Perspective (1975) menuliskan, tiap masyarakat memiliki sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan menegakkan hukum. Kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan DPR contohnya. Substansi hukum di sisi lain mengacu pada materi atau substansi aturan hukum (norma), sedangkan budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, opini, cara bekerja, dan berpikir masyarakat tentang hukum.
Dra. Nita Savitri, M.Hum, antropolog dan dosen Universitas Sumatera Utara menulis, UU PKDRT mungkin saja sudah ada, tetapi karena struktur dan budaya hukum kita masih bias gender, korban tak pernah bisa mendapatkan akses yang adil terhadap hak-hak mereka setelah melakukan pelaporan, pun dalam pengusutan kasus.
Dalam kasus LK, kita bisa melihatnya lewat mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana suaminya yang dilakukan melalui restorative justice. Dalam mekanisme ini, tata cara peradilan pidana yang ada berfokus pada proses dialog dan mediasi. Mediasi ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang. Tujuannya dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
Memang restorative justice kerap merupakan cara yang sangat baik untuk menangani kejahatan dan jadi metode yang digunakan dalam sistem peradilan pidana mana pun. Akan tetapi, metode ini tak berlaku pada semua kasus, apalagi dalam kasus KDRT. Banyak akademisi dan feminis memandang restorative justice sama saja dengan penolakan terhadap keadilan yang setara pada korban. Pemakaian metode ini untuk menyelesaikan kasus KDRT adalah indikasi kuat tentang minimnya kesadaran gender para aparat penegak hukum.
Dilansir dari The Guardian, restorative justice pada kasus KDRT tak pernah menempatkan kepentingan korban sebagai hal yang utama. Hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan tidak dijadikan prioritas utama. Mereka dibiarkan berjuang sendiri dalam pusaran trauma tanpa diberikan pendampingan psikologis atau hukum.
Sebaliknya restorative justice hanya menekankan pada “ketertiban umum” dan norma-norma seperti tekanan pada perempuan untuk memperbaiki hubungan mereka jadi porosnya. Pelaku yang dinilai yang jelas-jelas manipulatif seringkali “dimaafkan” dan dihilangkan dalam gambaran besar kekerasan oleh masyarakat, apalagi jika pelakunya dianggap sebagai “orang baik”.
Selain struktur hukum, kasus LK sangat erat kaitannya dengan budaya hukum yang masih buta bahkan bias gender di masyarakat. Buat Friedman budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Ia tercipta lewat kesadaran hukum masyarakatnya, sehingga budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum.
Dalam perspektif gender, budaya hukum inilah yang jadi biang kerok dari minimnya dukungan dan empati masyarakat terhadap korban kekerasan. Hal yang sangat terlihat dari media Indonesia dalam memberitakan kasus LK. Saat memberitakan kasus KDRT LK, media Indonesia banyak menggunakan angle dan headline bias gender. “Terlalu bucin” misalnya jadi diksi yang banyak digunakan media Indonesia dalam menyederhanakan kompleksitas keadaan LS sebagai korban KDRT. Cara yang jelas-jelas ampuh dalam menghakimi korban secara sepihak.
Tak hanya itu, dalam cuitan Kalis Mardiasih, aktivis feminis muslim di Twitter pribadinya ia mengungkapkan, media Indonesia justru memberikan ruang yang sangat besar untuk kuasa hukum pelaku dan orang-orang di sekitar pelaku. Orang-orang ini tampak bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan memojokkan dan menekan korban lewat media.
Karena itu, bisa dibilang percuma saja jika UU PKDRT telah disahkan sejak lama jika struktur dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia tak pernah bisa memihak pada korban. Korban akan terus terjerembab di lubang yang sama seorang diri. Butuh adanya usaha radikal dalam mengubah sistem hukum di Indonesia yang ramah korban dan tentunya ini memakan waktu yang lama.
Baca Juga: Nyaring dan Sunyi KDRT: Suramnya Budaya Kepemilikan dalam Keluarga
Akan tetapi setidaknya, perubahan bisa dimulai dari kita sendiri. Kita setidaknya bisa jadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang suportif yang aman bagi korban. Dilansir dari Center for Prevention of Abuse, setidaknya ada enam hal penting yang bisa kita lakukan secara individual dalam membantu korban KDRT agar mereka tak lagi merasa sendiri:
1. Luangkan waktu untuk mendengarkan dan percaya apa yang mereka katakan.
2. Komunikasikan bahwa kamu peduli dengan keselamatan mereka, bahwa mereka tidak pantas disakiti, dan bahwa pelecehan itu bukan kesalahan mereka.
3. Katakan pada mereka bahwa mereka tidak berlebihan. Seseorang yang telah dilecehkan dan mengalami kekerasan sering merasa kesal, tertekan, bingung, dan takut. Biarkan mereka tahu bahwa ini adalah perasaan yang normal dan perasaan mereka valid.
4. Beri tahu mereka hal-hal baik tentang diri mereka sendiri. Biarkan mereka tahu bahwa kamu pikir mereka cerdas, kuat, dan berani. Hal ini karena kekerasan yang mereka alami sering kali meruntuhkan harga diri mereka dan membuat diri mereka tak berharga.
5. Pastikan kebutuhan mereka dan berikan mereka opsi untuk keluar dari relasi abusif.
6. Apa pun pilihannya, hormati pilihan mereka. Tekankan kamu bagaimana kamu menghargai keputusan mereka dengan terus ada di samping mereka untuk mendengarkan dan berikan bantuan.