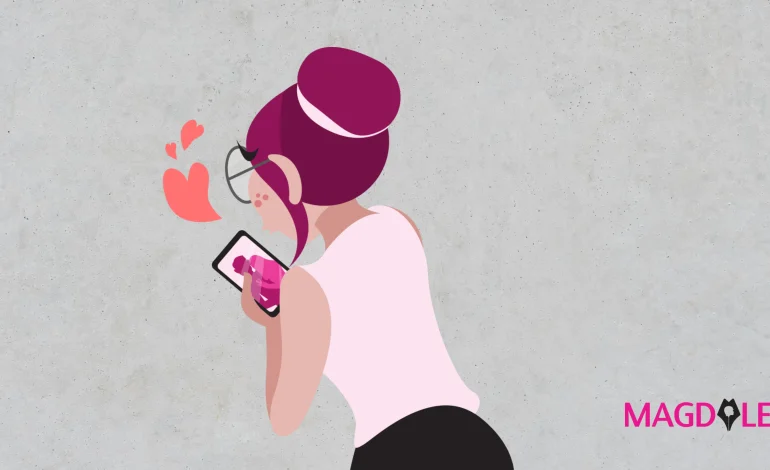Ironi di 40 Hari Kematian Affan: Polisi Bebas, Ratusan Demonstran Masih Ditahan

Herlina, 40, duduk di halaman depan kediamannya di salah satu gang di Jakarta Pusat (7/10), ditemani kakak kandung, Amir, 50. Mereka tampak terdiam sejenak setelah menyiapkan beberapa kebutuhan untuk pengajian malam harinya.
Pengajian tersebut merupakan tahlil 40 hari kematian Affan Kurniawan, ojek online yang tewas dilindas kendaraan rantis Brigade Mobil (Brimob) akhir Agustus silam. Sejak kepergian putra keduanya, Herlina hanya ingin kembali hidup normal.
“Pengen cepet-cepet kembali hidup biasa,” ungkapnya saat ditemui Magdalene.
Di sebelah Herlina, Amir mengamini ucapan tersebut. Datang jauh dari Lampung, kampung halaman Affan, Amir sengaja hadir untuk menuntaskan rangkaian doa bagi keponakannya.
“Saya di sini sampai 40 harian selesai lah ini. Biar sekalian nemenin dia (Herlina) juga. Seenggaknya sampai udah bisa senyum lagi,” jelasnya.

Affan adalah satu dari sepuluh sipil yang meninggal dalam aksi demo 25–31 Agustus 2025. Dilindas rantis Brimob, Affan meninggal tak lama setelah dilarikan ke rumah sakit. Bagi keluarga, tidak banyak yang berubah setelah kepergian Affan. Duka masih menyelimuti rumah mereka.
Baca juga: Kartu Pers Tak Lagi Cukup Melindungi: Intimidasi Jurnalis dalam Aksi Massa
Tidak Ada Polisi yang Mundur atau Ditahan
Sampai saat ini, belum ada satupun personil Brimob yang ditetapkan sebagai tersangka atas pelindasan Affan. CNN Indonesia melaporkan (2/9) hanya satu anggota Brimob yang dipecat tidak hormat, Kompol Kosmas Kaju Gae. Sementara anggota lainnya hanya dijatuhi sanksi demosi atau permintaan maaf lisan, lalu tetap bisa melanjutkan tugas di Brimob.
Tidak hanya pada Affan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat anggota kepolisian banyak melakukan tindakan represif selama demo akhir Agustus berlangsung (28/8). Tindakan ini meliputi serangkaian tindak kekerasan fisik hingga menyebabkan luka pada sebagian tubuh demonstran. Namun, alih-alih mendapat sanksi, demonstran yang mengalami luka justru diangkut paksa menuju Polda Metro Jaya. Setidaknya, sebanyak 370 orang ditangkap secara sewenang-wenang pada 25 Agustus 2025 saja.
Menurut LBH Jakarta, tindakan represif ini melanggar Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 tentang hak atas kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kekerasan terhadap demonstran juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, pelanggaran ini tidak diproses hukum, sementara kriminalisasi justru menimpa ratusan demonstran.
Baca juga: Antara Kritik dan Makar: Saat Negara Gagal Bedakan Pendapat dan Ancaman
Aktivis Masih Jadi Tawanan
Kondisi demokrasi di Indonesia semakin memprihatinkan sebulan pasca-demo akhir Agustus 2025. Penangkapan terhadap ratusan aktivis masih berlangsung, meski gelombang demonstrasi telah mereda. Menurut Andrie Yunus, Deputy Coordinator for External Affairs Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), setidaknya 962 orang telah ditangkap, ditahan, atau ditetapkan sebagai tersangka per awal Oktober 2025. Penangkapan ini tersebar di berbagai wilayah Polda dan menjadi angka tertinggi sejak reformasi 1998, menandakan eskalasi represif yang serius terhadap warga sipil yang bersuara kritis.
“Ini bukan sekedar kesalahan prosedural semata atau pelanggaran, tapi ini juga bentuk nyata prinsip-prinsip hak asasi manusia yang semestinya menjadi hal paling utama justru dikesampingkan,” ujar Andrie. Ia menekankan pola penangkapan ini bukan sekadar kasus individual, melainkan bagian dari praktik sistemik penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian.
Berdasarkan catatan KontraS, metode penangkapan yang diterapkan bervariasi. Ada aktivis yang ditangkap mendadak di rumah mereka tanpa surat perintah, ada yang dikejar di jalan, hingga sebagian lain dipanggil untuk diperiksa kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa keluarga aktivis juga mengalami intimidasi dan ancaman, menimbulkan rasa takut yang meluas di komunitas kritis. Andrie menyebut, “Kami melihat polisi ingin menunjukkan siapapun yang kritis akan diproses hukum. Ini adalah bentuk teror sistemik yang membuat masyarakat takut menyuarakan pendapatnya.”
Andrie juga menekankan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, yang dijamin Pasal 28 dan 28E UUD 1945, serta hak atas perlindungan hukum menurut Undang-Undang HAM, justru diabaikan. Sebaliknya, tindakan represif terus berlangsung tanpa pertanggungjawaban aparat yang melanggar hukum. Dalam beberapa kasus, demonstran yang mengalami luka fisik justru ditangkap dan diproses hukum, sementara aparat yang melakukan kekerasan tetap tidak tersentuh hukum.
Selain itu, KontraS mencatat kelompok yang menjadi target tidak hanya mereka yang turun ke jalan. Mahasiswa, pekerja, dan warga sipil yang menyuarakan kritik melalui media sosial, forum publik, atau tulisan opini juga menjadi sasaran. Ruang kebebasan berekspresi kini semakin sempit. Andrie menyebut, meredanya gelombang demonstrasi bukan tanda demokrasi membaik. “Justru sebaliknya, ini menandai kekerasan dan pembungkaman terhadap kritikus kian sistematis,” katanya.
KontraS juga membandingkan situasi ini dengan periode pasca-reformasi 1998. Menurut organisasi tersebut, jumlah penahanan aktivis yang terjadi saat ini belum pernah terjadi sejak era reformasi, bahkan melebihi angka penangkapan aktivis pada masa-masa politik paling tegang sebelumnya. Kondisi ini menjadi indikator serius praktik demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Andrie menutup dengan menyoroti ironi situasi saat ini. “Ini tentu sangat ironi bagaimana kemudian negara berbanding terbalik mengejar warganya yang kritis, kemudian menetapkan dia sebagai tersangka. Padahal, seharusnya negara menjadi pelindung hak-hak warga, bukan justru menjadi alat intimidasi.” Ia menegaskan tren ini tidak hanya mengancam kebebasan individu, tetapi juga prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi, sehingga masyarakat yang kritis kini menghadapi risiko semakin besar hanya karena menyuarakan pendapatnya.