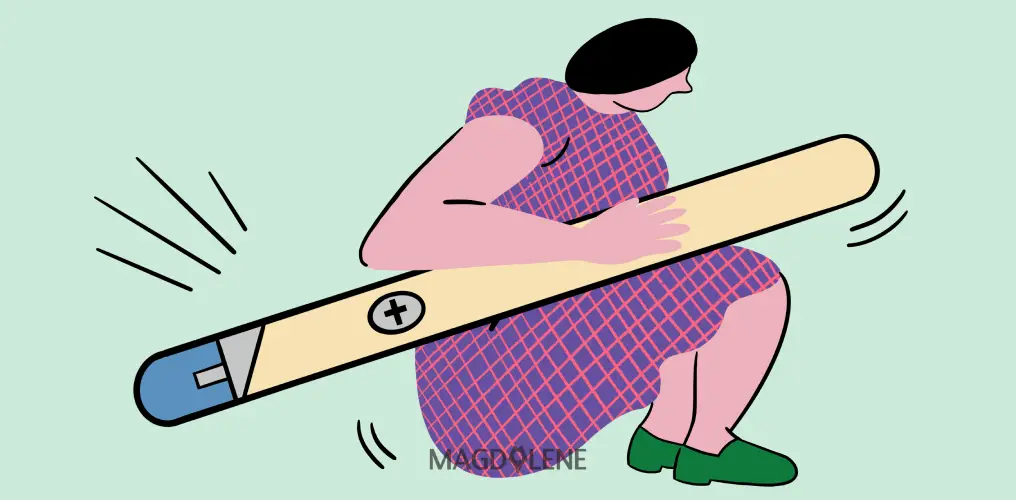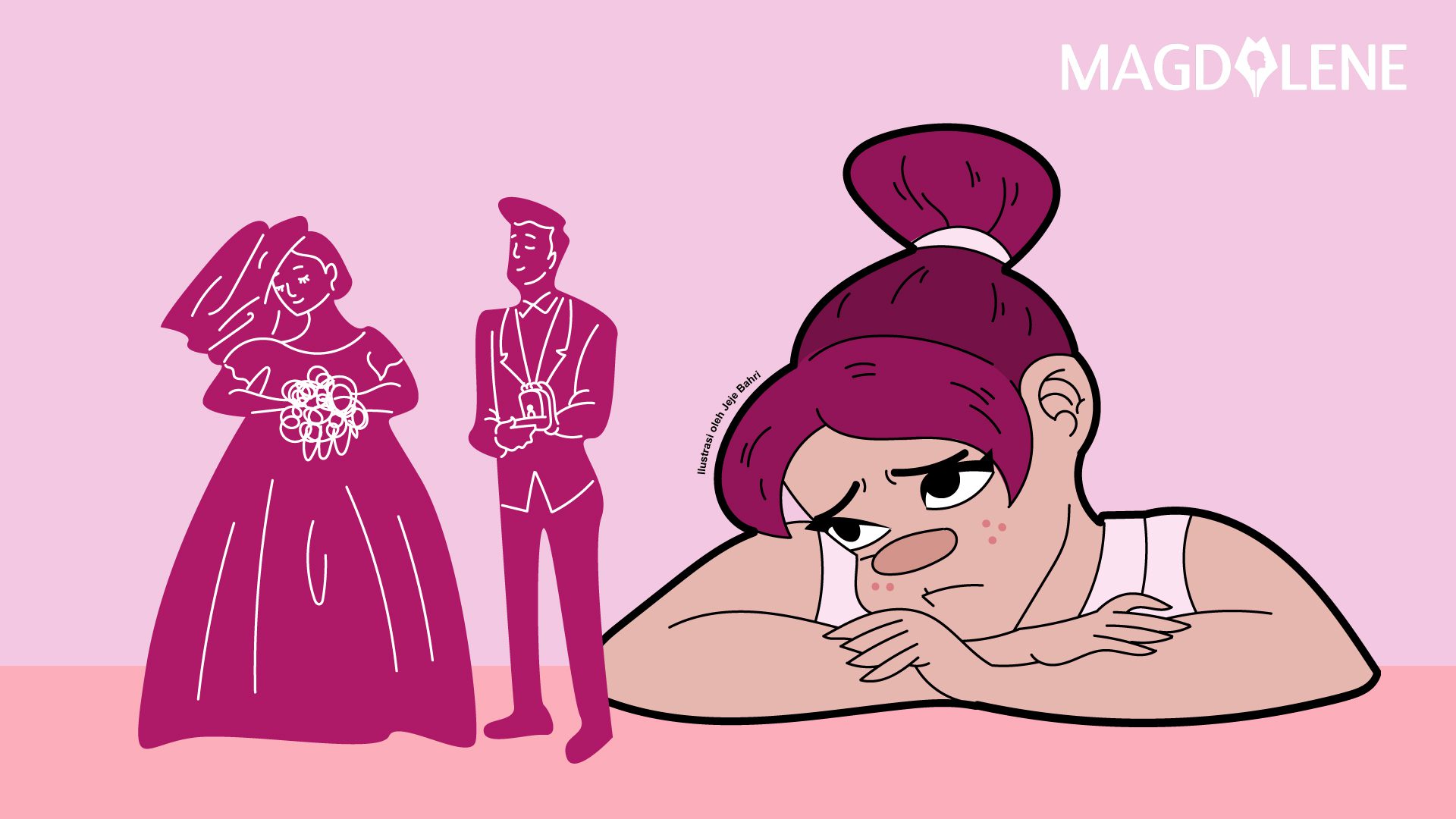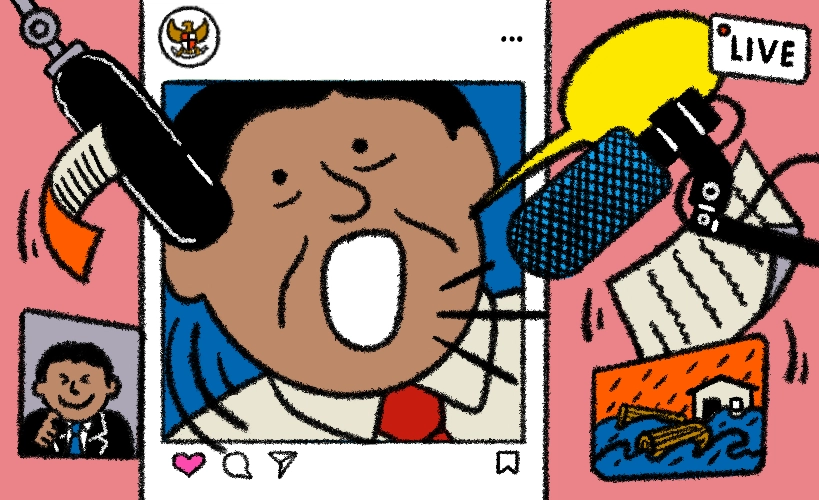Kerja Sama Agama dan Gender Membantu Adaptasi Iklim Warga Pantura

Dimensi agama dan gender seringkali luput dalam perbincangan, penelitian, dan proses penyusunan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Padahal, mengacu pada karakter masyarakat Indonesia, terdapat nilai-nilai keagamaan dan dinamika gender yang berkontribusi, baik positif maupun negatif, dalam upaya individu atau komunitas kala beradaptasi dengan perubahan iklim.
Artikel kami menunjukkan bagaimana dimensi agama dan gender memengaruhi proses adaptasi masyarakat, yakni di wilayah pesisir utara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kawasan ini mengalami perubahan garis pantai yang masif akibat pembabatan hutan mangrove, pembangunan tata kota, dan kenaikan muka air laut, yang membawa dampak multidimensi pada masyarakat, khususnya kelompok perempuan.
Dalam konteks agama, kawasan pantura secara historis lekat dengan syiar agama Islam. Demak, misalnya, adalah lokasi kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Kesultanan Demak. Ada juga Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh salah satu Wali Songo, Sunan Gunungjati.
Dalam konteks dinamika gender, terdapat jejak historis tokoh perempuan seperti Raden Siti Jaenab (Indramayu-Cianjur), Ratu Kalinyamat (Jepara), Kartini (Jepara-Rembang), yang menunjukkan bahwa perempuan eksis dan berpengaruh dalam perjuangan dan pemajuan bangsa.
Bersamaan dengan itu, terdapat juga dinamika gender negatif seperti interpretasi agama bias gender, faktor kultural (stereotipe macak, manak, masak atau bersolek, melahirkan, dan memasak), maupun politik (propaganda ideologi gender), yang menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik. Faktor agama dan dinamika gender ini tidak bisa kita lepaskan saat berupaya memahami masyarakat di pantura.
Baca juga: Perempuan Desa Rendu: ‘Pembangunan Waduk Merampas Hidup Kami’
Pesisir Utara Jawa Barat
Pengalaman perubahan lingkungan dialami komunitas muslim di pesisir utara Jawa Barat, khususnya warga Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi. Sejak awal tahun 2000-an mereka telah kehilangan lebih dari 1000 hektare tanah karena abrasi.
Perubahan lingkungan masif berawal dari pengalihan fungsi lahan mangrove menjadi tambak oleh generasi pertama desa. Hilangnya ekosistem mangrove membuat wilayah pesisir tidak bisa menahan kenaikan muka air laut sehingga menyebabkan abrasi dan erosi.
Menurut warga, para pembangun desa adalah Nahdliyin, pemuda Nahdlatul Ulama (NU) dari Banten yang melarikan diri dari konflik politik pada tahun 1960an. Mereka menetap di Muara Beting—wilayah terluar dari desa yang kini mengalami abrasi ekstrem.
Perubahan lingkungan ini disadari oleh generasi kedua penduduk Desa Pantai Bahagia. Mereka memiliki gagasan progresif untuk menyikapi perubahan lingkungan di sekitarnya dengan menggagas aktivisme lingkungan dengan landasan ajaran Islam. Landasan agama ini mencerminkan afiliasi budaya mereka dengan Nahdliyin, yang notabene merupakan bagian dari NU.
Aktivisme lingkungan tersebut dikenal dengan Alipbata (Aliansi Pemuda Bahagia dan Tangguh) yang memiliki dua tujuan utama. Pertama, beradaptasi dengan melakukan pemulihan mangrove di wilayah yang terdampak. Kedua, sebagai upaya menebus dosa orang tua mereka yang telah membabat hutan mangrove.
Selain dimensi agama, dimensi gender juga menjadi landasan dalam proses adaptasi iklim di Desa Pantai Bahagia. Desa ini memiliki aktivitas Kebaya (Kelompok Bahagia dan Berkarya), bagian dari aktivisme Alipbata, teketapi terdiri dari ibu-ibu rumah tangga. Mereka mengolah hasil bakau menjadi makanan dan minuman.
Kebaya terbentuk sebagai upaya perempuan mencari penghasilan tambahan dengan menjual produk mangrove. Kini, keberadaannya telah diakui sebagai UMKM. Kebaya telah mengembangkan beragam produk dari olahan hasil bakau seperti sirup dan batik.
Selain aktivitas Kebaya, perempuan di Desa Pantai Bahagia juga terlibat dalam praktik keagamaan kolektif, yaitu pengajian. Aktivitas pengajian rutin mingguan menjadi sarana penting untuk berkomunikasi dan berbagi informasi antarwarga di tengah keterbatasan jaringan internet.
Selain itu, pengajian turut menjadi ruang untuk menumbuhkan rasa keterhubungan dan solidaritas antar warga–baik yang masih bertahan di desa maupun yang terpaksa berpindah karena abrasi.
Baca juga: Masyarakat Dairi Menolak Tambang: Kami Berjuang Sampai Mati
Pesisir Utara Jawa Tengah
Dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh warga Desa Bedono dan Timbulsloko di pesisir Demak, Jawa Tengah. Dua desa pesisir ini mengalami abrasi sejak tahun 1990an saat banjir rob mulai menenggelamkan sawah dan akses jalan.
Warga desa kemudian melakukan berbagai model adaptasi seperti meninggikan makam, menanam mangrove, dan membangun jembatan. Bentuk adaptasi tersebut tidak bisa dipisahkan dari dimensi agama dan gender yang saling beririsan.
Di Demak, terdapat figur penyebar Islam yang lekat dengan adaptasi masyarakat pesisir, yaitu Kyai Mudzakir. Makam sang Kiai yang terletak di Dusun Tambaksari, Desa Bedono, kini menjadi destinasi Ziarah yang dikenal dengan makam terapung.
Upaya meninggikan makam oleh keluarga Kyai Mudzakir dan warga sekitar, membawa berkah tersendiri pada warga. Banyak peziarah yang mengunjungi makam keramat tersebut.
Fenomena ini menjadi penguat bahwa agama dapat berkontribusi secara tidak langsung pada proses adaptasi iklim, melalui hadirnya wisata ziarah yang membantu penghidupan warga desa.
Perempuan Demak juga melakukan upaya adaptasi iklim, salah satunya karena motivasi keagamaan. Misalnya adalah aksi Mak Jah di Desa Bedono. Ia memilih bertahan dan menanam bakau di dusunnya yang telah tenggelam, yakni Dukuh Rejosari Senik. Tujuannya untuk menjaga berkah Kiai Mudzakir dan desanya.
Upaya Mak Jah membuahkan hasil yang tidak main-main. Dukuh Rejosari Senik diresmikan sebagai cagar alam yang berfungsi menahan laju abrasi di Desa Bedono.
Kemudian, di Desa Timbulsloko terdapat kelompok perempuan yang terhubung dengan jejaring advokasi gerakan Puspita Bahari. Para perempuan ini mengumpulkan uang sumbangan setiap kali melakukan pertemuan kelompok dan iuran pengajian. Uang tersebut digunakan untuk membangun jembatan dan membuka akses jalan di desa.
Para perempuan juga berinisiatif merawat makam leluhur dan meninggikan masjid di desanya yang mayoritas dilakukan secara swadaya. Mereka menunjukkan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari (everyday resistance) seperti menggunakan pembalut kain dan menanam, meski tidak ada lagi tanah di rumah sekeliling mereka.
Baca juga: Transisi Energi yang Berkeadilan: Mengapa Perempuan Harus Terlibat?
Perempuan dan Perlawanan Sehari-hari
Terdapat fakta menarik bahwa penyebaran nilai-nilai agama dan lingkungan kepada kalangan perempuan justru terjadi di luar forum keagamaan formal seperti pengajian.
Di Desa Pantai Bahagia, obrolan mengenai agama dan keberlanjutan lingkungan terjadi di sela-sela proses pembuatan produk oleh Kebaya. Di Desa Bedono, perbincangan mengenai lingkungan ditemukan saat para sukarelawan dan peziarah mengunjungi Mak Jah di Bedono.
Di Desa Timbulsloko, percakapan mengenai krisis iklim di kalangan perempuan justru dipicu karena kegelisahan mereka yang tidak bisa lagi beribadah di musala sekitar rumah dan melakukan aktivitas sosial karena banjir rob. Mereka berbincang ketika belanja, mengantar anak sekolah, dan saat pertemuan kelompok.
Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang agama dan adaptasi di kalangan perempuan ternyata justru kuat dan dapat ditemukan dalam proses keseharian.
Sebaliknya, forum keagamaan formal belum menjawab kebutuhan warga untuk beradaptasi perubahan iklim. Misalnya, forum-forum pengajian—baik di Desa Pantai Bahagia, Bedono, dan Timbulsloko—belum memasukan persoalan krisis iklim atau perubahan lingkungan sebagai pembahasan.
Selain itu, dalam forum sosial keagamaan, perempuan kerap ditempatkan pada peran-peran domestik, seperti menyediakan makanan dan minuman selama kegiatan.
Mengacu pada fakta tersebut, diseminasi tentang perubahan lingkungan dan persoalan iklim di kalangan perempuan mengambil pola yang lebih cair dan informal. Ketika forum sosial-keagamaan tidak memberikan ruang untuk diskusi, perempuan menemukan cara yang lebih hangat dan seringkali lebih kuat, yaitu dalam obrolan sehari-hari.
Pada akhirnya, isu agama dan gender dalam krisis iklim perlu dilihat secara politis dan tidak bisa ditinggalkan dalam konteks kebijakan iklim di Indonesia.
Indonesia sedang merumuskan dokumen aksi iklim yang terbaru. Momen ini sepatutnya menjadi kesempatan kita untuk memasukkan isu agama dan gender dalam upaya meredam dan bertahan di tengah krisis iklim.
Aliyuna Pratisti, Dosen/Lektor, Universitas Padjadjaran dan Andi Misbahul Pratiwi, PhD Candidate, School of Geography, University of Leeds
This article was first published on The Conversation, a global media resource that provides cutting edge ideas and people who know what they are talking about.