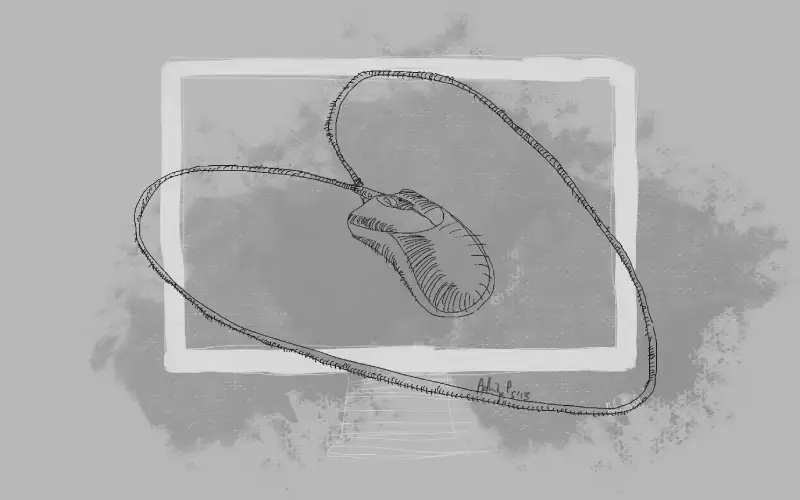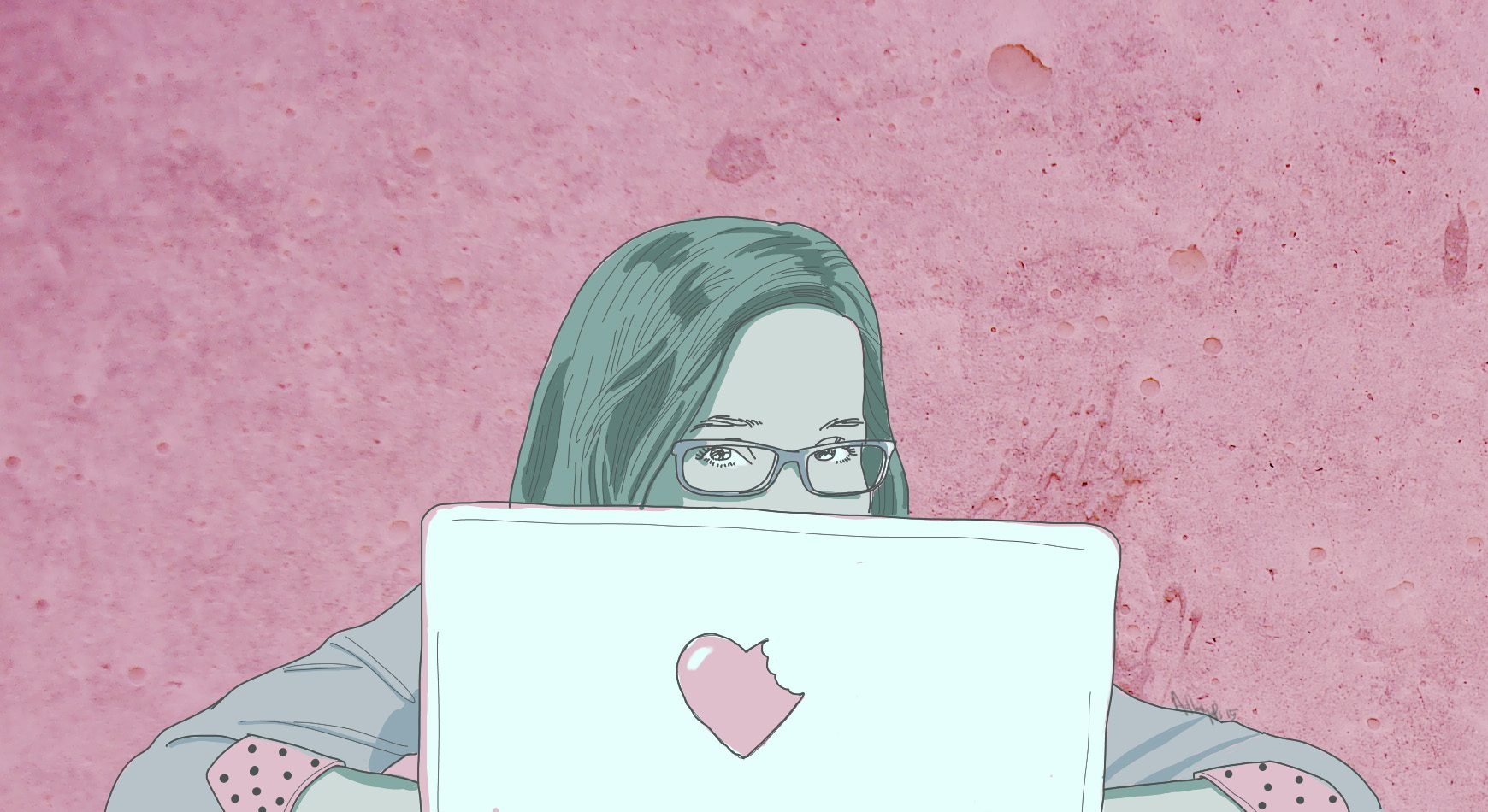Perbedaan Anak dan Orang Tua yang Sering Jadi Petaka

Bisa dibilang dulu saat masih kecil hingga duduk di SMA, aku adalah contoh sempurna dari anak perempuan dari keluarga Jawa. Manut dan nerimo. Semua anjuran dan arahan orang tua aku ikuti tanpa kecuali, termasuk salah satunya adalah cara beragama.
Tak pernah satu kali pun aku membantah. Aku dulu percaya membantah atau bahkan punya pandangan berbeda dengan orang tua itu salah. Maka jadilah aku anak kebanggaan Mama dan Papa yang tak pernah buat ulah.
Fase menjadi anak “baik-baik” kemudian berakhir ketika aku masuk kuliah. Aku yang dari Sekolah Dasar (SD) hingga SMA belajar di sekolah Islam mulai terpapar dengan berbagai mata kuliah yang mengharuskanku untuk berpikir kritis. Hal yang tak pernah aku lakukan selama belasan tahun karena cuma bisa menelan semua yang guru dan orang tua ajarkan.
Masih segar dalam memori, untuk pertama kalinya aku berdebat dengan Mama soal jilbab. Aku yang waktu itu sudah capek terus dimintai memakai jilbab panjang sampai menutupi perut, lengkap dengan kaos kaki mencoba memberikannya pemahaman tentang batasan aurat.
Aku bilang tafsir ulama tentang ini ternyata beragam. Tidak ada yang kesepakatan antar-ulama tentang batasan aurat. Mama tidak terima dengan argumenku, dia bahkan sempat menangis karena tahu anaknya mulai berubah. Mama sepertinya curhat sama Papa soal ini, yang bikin aku akhirnya diceramahi panjang lebar soal kewajiban seorang Muslimah.
Baca Juga: ‘Emotional Caretaker’: Lindungi Perasaan Ortu, Dipaksa Dewasa Sebelum Waktunya
Konflik dengan orang tua semakin melebar saat Eyang Papi meninggal. Eyang Mami yang hendak mengadakan tahlilan tujuh dan empat puluh harian Eyang Papi, justru diomeli Papa. Papa bilang tahlilan itu bidah. Papa pun menolak hadir di tiap tahlilan Eyang Papi dan mengajak Mama juga.
Aku yang memandang tak ada yang salah dengan tahlilan melihat sikap Papa itu egois. Aku bilang tidak sepatutnya Papa bertindak demikian apalagi Eyang Mami sedang dalam masa berduka. Papa sebagai anak seharusnya ada di sisi ibunya untuk menguatkan. Ternyata tindakanku ini jadi langkah fatal. Aku disebut sebagai orang Islam liberal yang beragama seenak hatinya dan tidak mau mengamalkan perintah Nabi dengan menyeluruh.
Mulai detik itu, aku merasa hubunganku dengan Papa jadi renggang. Perbedaan pandangan dan nilai yang aku pegang sekarang buat interaksiku dengan Papa jadi terbatas. Baik aku dan papa seperti berusaha kuat untuk tidak dalam ruangan yang sama berdua karena rasanya luar biasa canggung dan tidak nyaman. Aku juga jadi malas untuk sekadar mengungkapkan pendapat di depannya, karena aku tahu pasti dia pasti akan berusaha menyanggahnya sekuat tenaga.
Konflik ‘Abadi’ Antara Anak Dewasa dan Orang Tua
Gesekan antara anak dewasa dengan orang tua karena perbedaan pandangan dan nilai ternyata tidak hanya dialami oleh aku sendiri. “Lia”, pekerja media berusia 24 tahun juga mengalaminya. Lia bercerita ketika kecil ia cukup akrab dengan ibu dan interaksinya dengan sang ayah juga tidak canggung.
Semua berubah ketika ia mulai punya pandangan dan nilai berbeda dengan kedua orang tuanya. Lia seperti banyak anak dewasa lain mulai belajar banyak hal di luar lingkar kecil keluarganya. Ia jadi banyak membaca, mencari informasi di internet, dan mengobrol dengan teman-temannya untuk memperluas wawasan dan perspektif. Sayang kekayaan wawasan dan perubahan pandangan serta nilai yang kini ia pegang justru membuat hubungan Lia dengan orang tuanya renggang.
“Aku merasa ortuku enggak woke dengan situasi yang terjadi, jadi kita enggak ada titik temu. Pernah beberapa kali ngobrol, aku jadinya sadar distance-nya makin gede. Value kita emang udah beda aja sih, ini kelihatan dari cara kita memandang situasi yang aku lihat di bapakku misalnya masih suka body shaming dan lontarin homophobic slurs. Makanya di rumah aku merasa enggak nyaman,” curhat Lia.
Lia pun melanjutkan perbedaan pandangan atau nilai yang ia miliki dengan orang tuanya serasa tak ada ujung dan titik penyelesaian. Ini karena sedari kecil ia diajarkan untuk patuh, tidak diberikan ruang untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat. Hal ini berdampak pada respons Lia yang tiap kali punya waktu bicara dengan orang tua, terutama sang ayah, selalu berakhir tertekan dan menangis.
Selain Lia, ada juga “Mutia” (29) dan “Cemi” (27). Mutia yang kini tinggal sendiri di kosan di Jakarta Barat mengatakan hubungannya dengan orang tua bisa dibilang sudah diambang “kehancuran” karena penolakan Lia untuk menikah dan punya anak.
Mutia bercerita sebenarnya ia sudah memutuskan tidak akan menikah dan punya anak dari usia 25 tahun. Ia merasa tanggung jawab jadi orang tua jaman sekarang begitu besar. Dia merasa masih punya luka batin yang belum sembuh. Mutia takut kalau dia sendiri belum bisa pulih, dan justru akan mentransfer trauma ke anaknya. Selain itu, dia juga paham makin ke sini dunia makin jadi ruang hidup yang berantakan, ia pasti harus jadi orang tua super untuk bisa melebihi orang tuanya dulu.
“Gue harus lebih siap mental dan finansial dibandingkan bokap nyokap gue dulu. Padahal permasalahan gue sama diri gue sendiri aja belum kelar, pekerjaan gue yang seorang freelancer juga enggak menjamin secara finansial. Belum lagi kan dunia udah ancur gini. Ngeliat banyak kasus kekerasan, climate change depan mata, gue jadi mikir gimana ya gue nanti ya, besarin anak gue di tengah chaos kayak gini,” curhat Mutia.
Mutia sudah beberapa kali melakukan negosiasi pandangan dengan orang tuanya. Sayang, orang tuanya sudah terlalu keras untuk bisa memahami. Dengan dalih perempuan memang sudah kodratnya jadi ibu dan organ reproduksi mereka normalnya hanya bisa sanggup melahirkan di usia tertentu, kedua orang tua Mutia terus memaksanya untuk segera mencari jodoh.
Konflik antara anak dewasa dan orang tua ternyata memang lumrah terjadi. Karen Fingerman, profesor Pengembangan Manusia & Ilmu Keluarga di Universitas Texas dalam penelitiannya (2003) pernah mengembangkan developmental schism hypothesis atau hipotesis perpecahan perkembangan.
Teori ini menggarisbawahi konflik anak dan orang tua lumrah terjadi dan ini dikarenakan kedua belah pihak punya kebutuhan perkembangan masing-masing menurut generasi, gender, dan usia. Penolakan pandangan jadi hal biasa, apalagi kalau menurut Anna Surti, psikolog anak dan keluarga yang diwawancarai Magdalene, orang tua yang berusia 40 hingga 60-an tahun atau yang ia sebut middle adulthood punya kekhususan perkembangan.
Menurutnya, pada usia ini manusia cenderung punya sikap matang terhadap hidup mereka dibandingkan dengan manusia berusia 20-an. Artinya, semua pandangan, nilai-nilai, dan sikap mereka akan cenderung lebih kaku atau tidak bisa diganggu gugat.
“Ini karena berdasarkan pengalaman dia (orang tua), pemahaman atau pandangan yang mereka miliki bikin dia berhasil dalam hidup. Pengharapan bahwa anaknya juga harus ‘berhasil’ akhirnya diekspresikan dengan nilai-nilai atau sikap yang dia pegang berdasarkan pengalaman dia,” kata Anna.
Anna kemudian menambahkan “Di usia 20-an anak-anak cenderung lebih open-minded dari orang tua. Keterbukaan ini susah dipahami orang tua yang pernah punya pengalaman keterbukaan itu justru membingungkan atau bahkan membuat dia ke arah yang keliru di usianya dia dulu.”
Baca Juga: Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, Orang Tua Perlu Kontrol Diri
Ina Luthfie, konselor kesehatan mental dan psikoterapis bersertifikat juga menambahkan sebenarnya sangat wajar jika anak dewasa punya perbedaan pandangan dan nilai dengan orang tua mereka. Menurutnya ini justru jadi pertanda anak bertumbuh seiring dengan perkembangan pikiran, emosi dan terutama untuk proses dia mencari self-identity. Dalam proses ini tentu aja kadang sudah tidak bisa diarahkan orang tua, karena anak sudah tahu yang betul dan salah menurut mereka sendiri dia.
“Justru ortu harusnya menyadari dan memandang anak-anaknya sebagai sesama dewasa sekarang. Walau statusnya anak, anak dewasa ini kan sudah punya pemikirannya sendiri. Sayangnya, sebagian ortu tidak bisa menerima (fakta) ini. Mereka mau anaknya selalu mengikuti pandangan mereka dengan dalih that’s what best for the kids,” jelasnya.
Menyalahkan Pihak Luar atas Perbedaan Pandangan Anak
Dalam konflik antara anak dewasa dan orang tua, gesekan karena perbedaan pandangan atau nilai memang suatu hal yang biasa. Tetapi dari pengalamanku dan orang yang aku wawancarai, orang tua sering kali menyalahkan pihak luar atas perubahan yang terjadi pada anaknya. Ini seakan menandakan orang tua enggan merangkul fakta bahwa sebagai manusia sudah sewajarnya anak mereka tumbuh dan belajar.
Dalam kasusku, pihak yang disalahkan adalah universitas serta jurusan (humaniora dan ilmu sosial), tempatku menempuh pendidikan S1 dan S2. Dalam perbedaan pandangan, Mama misalnya selalu menyalahkan dirinya yang telah memberikanku kebebasan untuk memilih universitas dan jurusan yang justru bikin aku terpapar ilmu-ilmu filsafat dan pemikiran modern.
Aku dinilai jadi terlalu kritis. Punya lingkungan akademis yang terlalu “liberal” dan teman-teman feminis kebablasan. Mama jadi menyesal telah menyekolahkanku tinggi-tinggi kalau ujungnya aku justru jadi Muslim yang “tidak taat”.
Aku tidak sendiri. Orang tua Cemi yang cukup konservatif juga menyalahkan pihak luar, yaitu lingkungan tinggal dan kekasih Cemi. Padahal menurut Cemi, perubahan pandangan ini hadir lewat pergumulan panjang soal agamanya sendiri.
“Pokoknya sikap aku yang beda itu dianggapnya karena tinggal di Jakarta dan dipengaruhi pacar. Padahal, aku juga punya pandangan sendiri. Aku belajar dan baca banyak buku. Apalagi ya konflik di Timur Tengah dan gimana they treat women itu juga jadi titik di mana aku mulai mempertanyakan agama dengan kritis. Ya, tapi mereka kan enggak melihat itu,” jelas Cemi.
Baca Juga: Kenapa Orang Tua Zaman Sekarang Cenderung Kasih Nama ‘Ribet’ untuk Anak?
Perubahan ini pun direspons oleh ayah Cemi dengan memberikannya air doa. Air yang sengaja didoakan agar dia kembali jalan yang benar karena dianggap sudah kurang ibadah, istikharah, dan ngaji. Dalam kasus Mutia, responnya lebih ekstrem lagi. Dia hampir dibawa ke salah satu orang pintar untuk diruqyah. Orang tua Mutia yakin sekali pembangkangan Mutia muncul karena dia ketempelan jin.
Beruntung dia berhasil kabur ketika itu. Walau usahanya berakhir, Mutia lebih diomeli lagi dan membuat orang tuanya semakin keras bahkan sampai menyuruh memutus relasi dengan beberapa teman yang dianggap telah “mencemari” pikiran anak mereka.
Kecenderungan orang tua menyalahkan faktor luar atas perubahan anak dewasa mereka ternyata bisa dijelaskan. Anna mengatakan pengalaman orang tua membesarkan dan melihat berkembangan anaknya membuat orang tua kesulitan menerima perubahan. Mereka merasa telah menurunkan pandangan dan nilai-nilai baik pada anaknya, sehingga ketika anak punya perbedaan mereka akan kesulitan memahami apalagi menerima.
“Makanya mereka merasa perlu ada yang disalahkan atau bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Yang cukup sering disalahkan ya hal-hal eksternal karena ini hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol,” jelas Anna.
Kecenderungan ini pun menurut Anna semakin sering dilakukan orang tua. Menyalahkan sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol lebih mudah dan lebih masuk akal dibandingkan berefleksi pada diri sendiri. Atau bahkan bertanggung jawab atas sesuatu yang mungkin saja keliru mereka lakukan selama membesarkan anak-anak mereka.
Ketika orang tua menerima pandangan anak dewasa mereka dan justru menyalahkan pihak eksternal akan perubahan itu, banyak anak-anak dewasa yang akhirnya memutuskan untuk mengambil jarak. Lia, Cemi, dan Mutia adalah buktinya. Penolakan orang tua atas perubahan pandangan dan nilai Cemi dan Mutia, membuat mereka jadi jarang pulang ke rumah. Sedangkan Lia menjaga jarak dengan memutuskan pindah kos, dibandingkan harus tiap hari serumah dengan orang tuanya.
Anna menyayangkan renggangnya hubungan antara anak dan orang tua ini. Oleh karena itu, Anna pun mengatakan komunikasi bisa jadi kunci untuk menjembatani ketegangan hubungan antara anak dewasa dan orang tua ini.
“Mungkin bukan berbeda tapi mereka (orang tua) belum paham. Maka cara mengomunikasikan dengan cara atau angle yang berbeda diperlukan. Misalnya alih-alih kita menjelaskan sendiri, kita bisa minta orang yang lebih ahli atau orang yang lebih mereka percaya untuk memahami pandangan kita. Perbedaan komunikator itu bisa lho membuat orang tua jadi lebih bisa menerima,” pungkas Anna.
Selanjutnya menurut Anna, anak juga bisa mengganti cara berkomunikasi mereka. Jika sekiranya anak tidak pernah bisa terlibat dalam perbincangan mendalam dengan orang tua, ini mungkin saatnya anak mengajak orang tuanya deep talk. Dengan deep talk, orang tua jadi bisa punya ruang juga untuk bertanya lebih dalam dan ini akan jadi cara untuk membuka pikiran mereka.
Selain Anna, Ina juga punya pesan khusus pada orang tua. Untuk menjembatani konflik ini, tidak hanya anak saja yang harus bertindak. Ia secara spesifik mendorong orang tua untuk bisa lebih terbuka pada anak. Memberikan mereka ruang untuk menjelaskan alasan perubahan pandangan atau nilai yang kini mereka anut tanpa penghakiman
“Orang tua harus mulai lihat sisi anak. Kenapa sih anak punya pandangan tersebut. Dikomunikasikan dan diskusikan. Dan lagi-lagi menyadari anak sudah tumbuh dewasa jadi sudah sewajarnya menghargai keputusannya juga,” kata Ina.
Tak kalah penting, jika memang pada akhirnya perbedaan ini tidak bisa disepakati bersama Anna menawarkan pilihan lain yang sebenarnya bisa dilakukan kedua belah pihak. Pilihan ini adalah agree to disagree. Dalam banyak konflik keluarga, baik anak dan orang tua berusaha kuat untuk mengubah pandangan satu sama lain. Padahal menurut Anna pandangan atau nilai itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan kepada individu mana pun.
“Dengan sepakat untuk tidak sepakat, maka keduanya itu akan menganggap bahwa ya itu memang dia dan tiap orang punya pandangannya masing-masing. Ada penghargaan di situ dan itu meminimalisir gesekan atau konflik yang lebih besar,” tutup Anna.