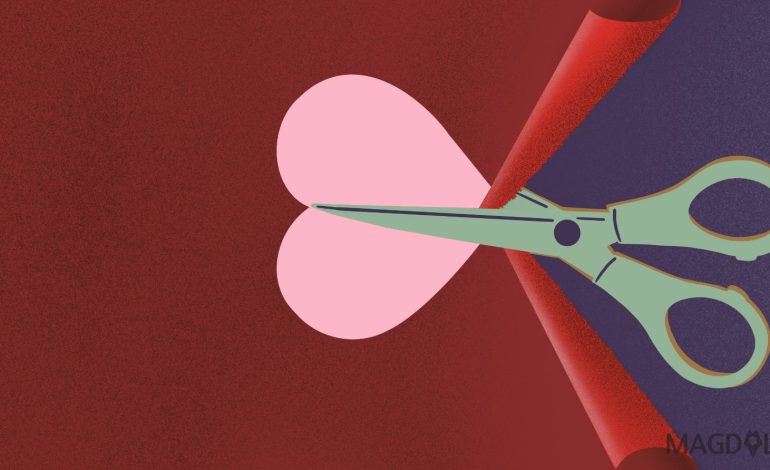Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian II)
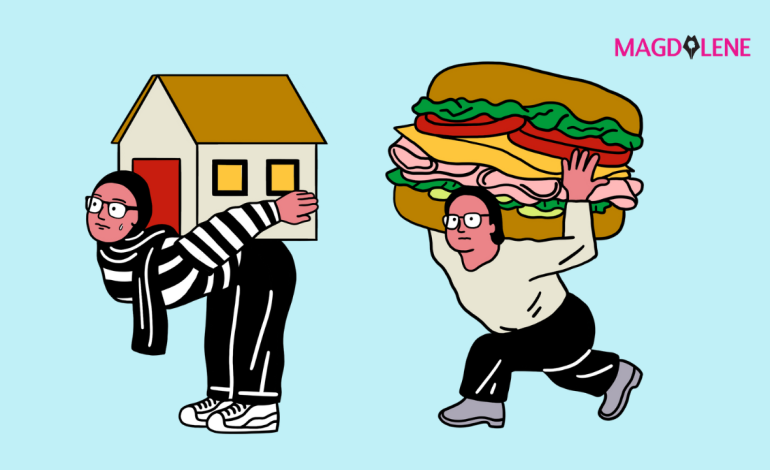
Kami mengikuti empat perempuan Milenial Jabodetabek dengan latar belakang berbeda. Ada yang generasi sandwich, tulang punggung keluarga, lajang tanpa anak, dan menikah tapi childfree. Ketika dunia mulai beralih membahas kebutuhan Generasi Z dan Alfa, masalah hidup Milenial ternyata belum selesai. Andini, Nandira, Eka, dan Caca tentu saja tidak merepresentasikan seluruh Milenial.
________
Generasi Milenial Memilih Childfree dan Tak Menikah
Selain Eka, Caca, 36 dari PurpleCode Collective, juga mengalami kekhawatiran finansial. Sebelum menikah pada 2022 lalu, ia sudah memutuskan untuk tidak memiliki anak alias childfree. Beruntungnya suami Caca juga tak keberatan dengan keputusan ini. Caca bilang, salah satu alasan tak mau punya anak adalah ekonomi yang belum stabil.
Ia boleh saja bukan generasi sandwich, tetapi Caca tetap menyisihkan Rp1 juta per bulan untuk ibunya. Ia juga masih menyesuaikan kebutuhan hidup berumah tangga. Selain mengirim ke ibu, gaji Caca habis untuk kebutuhan sehari-hari.
Sebagai pengidap diabetes sejak usia 26, makanan harian Caca harus dikelola ketat. Ia mengganti nasi dengan beras porang yang satu kilo sekitar Rp130 ribu. Selain itu, ia lebih banyak mengonsumsi protein dan buah-buahan, yang harganya bisa mahal sekali.
“Kalau dibandingkan dulu (sebelum diet khusus) yang sebulan Rp500 ribu tuh cukup. Sekarang segitu buat seminggu aja,” kata Caca.
Baca juga: Solusi Rumah Murah bagi Milenial Saat Harga Tanah Melangit
Selain makanan, pengeluaran Caca habis untuk makan dua kucing, rumah kontrakan senilai Rp20 juta per tahun, iuran BPJS, cicilan laptop, dan asuransi kematian. Caca sadar, punya anak bisa jadi mahal sekali hari ini.
Hal serupa diungkapkan Nandira. Sampai saat ini, ia masih berencana tidak mau menikah dan punya anak. Beban sebagai pencari nafkah utama sudah cukup menguras energinya. Nandira tidak bisa membayangkan jika seperempat gaji bulanannya sekarang, harus dibagi lagi dengan kebutuhan keluarga baru.

“Kayaknya aku juga sadar, sebagai perempuan ada banyak yang dikorbankan ketika menikah dan punya anak. Sedangkan aku masih punya mimpi yang mau diraih,” kata Nandira, yang punya mimpi ingin lanjut studi doktoral.
Alasan ekonomi bukan satu-satunya alasan Caca dan Nandira memutuskan childfree. Kebetulan keduanya bekerja di isu sosial, membuat mereka cukup melek dengan permasalahan struktural di negara ini.
Caca misalnya, sadar bahwa kita didesain untuk menjadi miskin terus-menerus.
“Enggak kepikiran kita harus banting tulang kayak apa. Aku ngerasa enggak akan mampu punya tanah atau rumah di Jakarta, mau kerja berpuluh-puluh tahun sekali pun,” kata Caca. Buatnya, punya rumah sendiri, apalagi di Jakarta, sudah seperti mimpi di siang bolong. Bukan pada tempatnya.
Selain soal rumah, Caca juga mempertimbangkan biaya pendidikan yang makin mahal. Saat datang ke Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Universitas Indonesia, Depok pada 25 Juni lalu, ia mendengar biaya kuliah salah seorang mahasiswa. Katanya, per semester mencapai Rp15 juta rupiah. Alhasil, Caca membandingkan dengan biaya kuliahnya dulu yang berkisar Rp1,3 juta per semester.
“Enggak tahu nih, sepuluh atau 17 tahun lagi akan berapa (biaya kuliah) kita. Belum lagi ada isu soal student loan. Lagi-lagi kita ngomongin kapitalisme dan segala macam privatisasi pendidikan yang udah lama terjadi. Disusul Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang memang arahnya akan makin mahal, bukan malah makin murah,” jelasnya.
Ia juga khawatir biaya pendidikan akan makin tinggi jika anaknya punya kebutuhan khusus—secara fisik atau mental. Pasalnya, sistem pendidikan Indonesia masih belum ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Nandira punya kekhawatiran serupa. Bekerja di isu sosial—salah satunya perlindungan anak, ia paham ada kesenjangan di isu pendidikan. Aksesnya makin mahal dan makin diprivatisasi.
Caca dan Nandira juga punya climate depression. Mereka melihat permasalahan iklim akan memengaruhi kemampuan mereka membesarkan anak. Caca sendiri, yang banyak bekerja di isu lingkungan, merasa pemerintah tak banyak menjalan peran mereka di berbagai masalah: hunian rumah buat milenial, biaya pendidikan mahal, sampai krisis iklim.
Kekhawatiran-kekhawatiran itu seolah dikonfirmasi pernyataan kontroversial Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. Pada 27 Juni kemarin, ia bilang BKKBN punya menargetkan perempuan rata-rata melahirkan satu anak perempuan untuk memastikan regenerasi terus berjalan. Setelah pernyataannya ini viral, Hasto kembali menyita perhatian masyarakat lantaran menyalahkan orang-orang childfree bikin struktur demografi Indonesia tidak seimbang.
“Fokusnya tuh gimana kita mengatasi masalah lingkungan dan kemiskinan, bukan mengontrol rahim ataupun seksualitas kita (perempuan),” protes Caca.
Buatnya, omongan Hasto adalah bukti negara cuma sibuk mengatur tubuh dan seksualitas perempuan. Kacamata yang memang sudah lama dipakai, dan belum dalam waktu dekat akan dilepas. Tubuh perempuan cuma dilihat sebagai “pabrik anak”.
Baca juga: Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian I)
Dicap Sakit Jiwa, Saat Jaminan Sosial Tak Memadai
Selain dicap tidak pintar mengurus keuangan, milenial juga dicap lemah mental. Sebelum Gen Z dikenal vokal soal hak-hak kesehatan mental mereka, terutama di tempat kerja, milenial adalah generasi pertama yang membawa isu itu ke permukaan. Namun,
“Sekarang itu bukan soal trauma-trauma personal kita yang bikin kita sakit mental, tapi juga gara-gara negara makin brengsek. Kemiskinan, enggak bisa punya rumah gitu itu kan sesuatu yang struktural. Jadi walaupun trigger-nya bisa macam-macam, sekarang pemicunya bisa karena negara,” katanya.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat lebih dari 19 juta penduduk Indonesia usia lebih dari 15 tahun memiliki gangguan mental emosional. Selain itu, sebanyak lebih dari 12 juta penduduk dengan rentang usia sama diketahui mengalami depresi.
Nandira termasuk salah satunya. Ia rutin ke psikolog. Bisa sekali atau dua kali sebulan. Pengeluaran ini sebetulnya berat buat Nandira, karena ia harus merogoh kocek antara Rp400 ribu sampai Rp500 ribu. Faktor utama yang selama ini ia rasakan datang dari bebannya sebagai tulang punggung keluarga.
“Memang jadi pencari nafkah utama ini yang paling berat, sampai memenuhi pikiran dan bikin stres. Apalagi pas sadar gajiku cuma seperempat gaji bulanan,” kata Nandira.
Efeknya, ia sering kesulitan tidur hingga harus menelan suplemen agar dapat tidur berkualitas.
Dari sesi konseling bersama psikolog, Nandira mulai belajar untuk mengelola stres. Salah satunya mengubah pola pikir bahwa gaji yang diterima tiap bulan hanya seperempat total gaji seluruhnya. Namun, sesi rutin ini tidak selamanya terjamin. Saat ada kebutuhan mendesak, mau enggak mau Nandira harus merelakan sesi konselingnya.
“Aku beli sepatu terakhir dua tahun lalu. Terus kemarin ngeliat, sepatuku udah bolong. Akhirnya mikir, kayaknya nggak usah ke psikolog dulu nggak apa-apa. Jadinya memang harus ngatur keuangan untuk beli sepatu yang diperluin,” curhat Nandira.
Nandira terhitung yang beruntung bisa mengakses layanan kesehatan. Tidak semua milenial—terutama mereka yang generasi sandwich—bisa mengakses layanan kesehatan mumpuni. Riskesdas 2018 juga menyoroti akses layanan kesehatan mental yang juga bermasalah. Hanya 9 persen dari mereka yang terdiagnosis depresi yang menerima pengobatan rutin.
Per Oktober 2022, seperti dilansir dari rilis Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi, hanya 50 persen dari 10.321 unit puskesmas yang punya pelayanan kesehatan jiwa.
Tak jauh beda dari Nandira, Eka stres karena pekerjaan. Belakangan, kantornya melakukan efisiensi manajemen, dan pekerja diberikan dua pilihan: Resign atau bersedia beban kerjanya ditambah. Eka memilih yang kedua lantaran lingkungan kerjanya suportif dengan peran sebagai ibu tunggal.
Konsekuensinya, Eka lembur di kantor atau melanjutkan pekerjaan di rumah setelah anaknya tidur. Bahkan sesekali mencuri waktu kerja di akhir pekan, saat quality time dengan anak. Untuk mengatasi stres, ia hangout dan hiking dengan teman-teman. Atau main game di ponsel.

Realitas yang dihadapi milenial—terlebih yang merupakan generasi sandwich, nyatanya tak cuma berdampak pada kesehatan mental, tetapi masa depan negara.
Baca juga: Beda Gen Z dan Milenial Hadapi Tekanan Kerja di ‘Start-up’, Siapa Lebih Tangguh?
Situasi buruk ini, sebetulnya tergambar dari pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia yang terlihat bagus, tapi sebetulnya mengkhawatirkan. Dalam kolom terbarunya di Kompas, ekonom dan mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, menyebut ada penurunan daya beli kelompok menengah bawah selama enam bulan terakhir. Dalam bacaannya, ada persentase kelas menengah yang juga terus menurun sejak 2019.
“Sejak tahun 2019, sebagian dari kelas menengah “turun kelas” menjadi AMC (aspiring middle class—calon kelas menengah) dan AMC turun menjadi kelompok rentan,” tulisnya.
Sejak 2019, persentase kelas menengah turun menjadi 21 persen. Sebaliknya kelompok AMC meningkat menjadi 48 persen. Kecenderungan ini terus terjadi. Tahun 2023, kelas menengah turun menjadi 17 persen (2023); AMC naik menjadi 49 persen (2023); kelompok rentan meningkat menjadi 23 persen.
Hitung-hitungan itu muncul dari data garis kemiskinan 2024 yang adalah Rp550 ribu. Dengan hitungan itu, mereka dengan pengeluaran Rp1,9 juta sampai Rp9,3 juta adalah yang dihitung sebagai kelas menengah. Menurut Basri, bukan cuma kelompok miskin yang perlu perlindungan sosial.
“Instrumen perlindungan sosial dan lapangan kerja kelas menengah memang perlu dipikirkan. Mereka tak tergolong miskin, tapi guncangan ekonomi dapat mengantar mereka pada kemiskinan,” kata Basri.
Para generasi sandwich juga bisa terbantu jika jaminan sosial untuk lansia diperbaiki. Sayangnya menurut Deshinta Vibriyanti, peneliti isu lansia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pemerintah Indonesia sampai saat ini masih belum memperlihatkan keseriusannya terhadap lansia.
Indonesia sebetulnya punya sejarah pernah memiliki Komnas Lansia, yang fokus pada kesejahteraan para lansia, dibentuk pada 2004. Setelah berkiprah selama 16 tahun, komisi ini resmi dibubarkan Presiden Joko Widodo lewat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2020.
Baca juga: Generasi Z: Rumah Tak Terbeli Bukan karena Kebanyakan ‘Ngopi’
Sebelum ada Komnas Lansia, besarnya jumlah penduduk lansia di Indonesia telah diantisipasi sejak zaman Orde Lama melalui bantuan penghidupan orang jompo. Namun, menjamin kesejahteraan lansia tidak dapat dilakukan dalam satu dua cara saja. Tak cukup dengan bantuan uang tunai, tapi juga bantuan psikologis dan kesehatan yang perlu dipenuhi agar mereka lebih sejahtera.
“Kurang ‘seksinya’ topik lansia di kalangan pemangku kebijakan menjadi tantangan tersendiri. Wafatnya Komnas Lansia menjadi salah satu buktinya,” ungkap Marya Yenita Sitohang, peneliti isu lansia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional RI.
Nandira yang bekerja sebagai peneliti, sepakat bahwa tiadanya jaminan sosial universal adalah masalah besar di Indonesia. Padahal, jaminan sosial itu memungkinkan siapa saja—lajang atau mereka yang punya pendapatan dobel di rumah tangga (double income household).
“Benefit lansia itu harusnya dimulai dari sekarang. Kita udah ‘nabung’ dari uang pajak, sampai punya jaminan hari tua yang universal untuk semua orang, bukan cuma angkatan kerja,” kata Nandira. Menurutnya, itu akan meringankan generasi sandwich sepertinya.
Caca juga ingin mengkritisi UU Cipta Kerja dan rencana iuran Tapera. Dua instrumen hukum ini yang dimaksud Caca sebagai bukti nyata gagal fokusnya pemerintah menjalankan kerja mereka. Faktanya, setelah UU Cipta Kerja muncul, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Banyak usaha-usaha rintisan (startup) me-lay-off para pekerjanya.
“Aku justru berharap, konsep kesejahteraan itu betulan berlaku,” kata Caca.
“Rumitnya perlindungan sosial untuk kelas menengah ini bukan cuma soal dukungan keuangan, melainkan juga soal kualitas,” ungkap Basri. “Kelas menengah akan menuntut birokrasi yang baik, kualitas jasa publik yang baik, kualitas pendidikan yang baik, kualitas kesehatan yang lebih baik, juga keadilan dan demokrasi. No viral no justice. Dan itu punya dampak ekonomi politik,” tambah Basri.
Artikel ini diproduksi oleh Magdalene.co sebagai bagian dari kampanye #WaveForEquality, yang didukung oleh Investing in Women, inisiatif program Pemerintah Australia.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari
Series artikel lain bisa dibaca di sini:
Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian I)
Bahagia dan Kejar Mimpi Pasca-Bercerai: Cerita Tiga Perempuan
Ketika Bapak Rumah Tangga Bicara Stigma hingga Omongan Tetangga