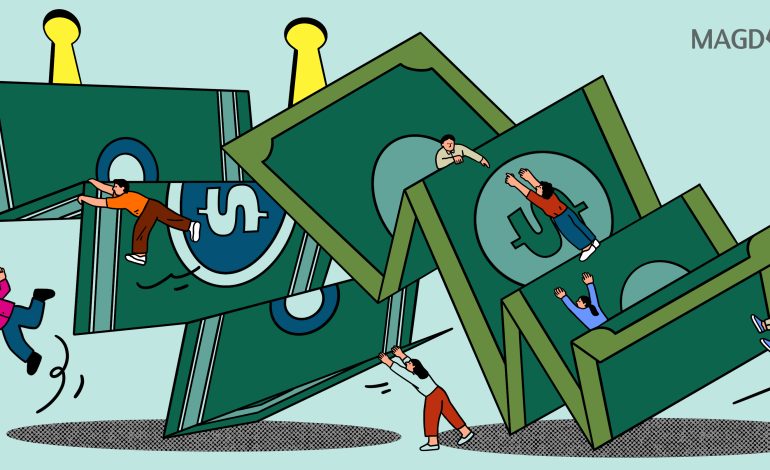Rumah untuk Milenial: Bahkan Kerja Selamanya pun Masih Tak Terbeli (Bagian 1)

Tahun ini Indira genap berusia 30 tahun, tapi mimpi punya rumah sendiri masih jauh panggang dari api. Tak seperti teman-teman dekatnya yang bisa beli rumah dengan skema Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Indira harus pintar-pintar mengatur gaji agar bisa menghidupi keluarga: Ibu, kakek, adik laki-lakinya.
Sebenarnya gaji Indira relatif besar untuk ukuran pekerja Jakarta, yakni Rp19 juta per bulan. Namun nasibnya sebagai generasi sandwich sekaligus pencari nafkah utama, membuat transferan gaji itu sekadar numpang lewat. Segala kebutuhan keluarga, seperti bahan makanan, listrik, gaji Pekerja Rumah Tangga (PRT), hingga uang saku adik laki-lakinya, semua ditanggung Indira. Ini belum termasuk kebutuhan pribadi Indira. Di luar kebutuhan pokok keluarga, ia harus merogoh kocek sekitar Rp2 juta untuk transportasi ke kantor, asuransi sebesar Rp1,3 juta, konseling psikiater Rp2 juta.
“Sebulan itu udah habis Rp7 juta buat kebutuhan sehari-hari. Itu pun masih di luar aku ngasih uang jajan adikku. Ya, tiap bulan sisa buat diri aku sendiri Rp3 juta yang benar-benar bersih,” curhat Indira pada Magdalene.
Baca Juga: ‘Saya dan Keadilan’: Ubah Paradigma Lingkungan yang Berpusat pada Manusia
Pengeluaran inilah yang bikin Indira terpaksa tetap tinggal di rumah orang tua. Katanya, sisa gaji itu tak mungkin bisa menutupi uang sewa kos atau apartemen di dekat tempat kerja, apalagi bayar cicilan rumah. Terlebih, harga rumah di Jakarta bahkan kota-kota penyangga macam Depok, Bogor, Tangerang semakin tak masuk akal dengan bunga mencapai 8 persen.
“Beli rumah di Jakarta udah enggak mungkin sih dan harga-harga rumah yang pinggiran aja udah enggak makes sense. Dengan harga segitu, kamu harus bisa commit bayar KPR yang menurutku terlalu tinggi untuk 10 sampai 25 tahun ke depan. Sementara, aku enggak punya financial security sampai puluhan tahun,” jelas Indira.
Kondisi serupa dialami Caca dari Purplecode Collective. Di usianya yang menjelang 40, Caca juga tidak bisa memiliki rumah sendiri. Sejak 2013, dari masih melajang hingga menikah, ia harus mengontrak di tempat yang sama di daerah Jakarta Selatan.
Sejujurnya Caca ingin punya rumah sendiri di Jakarta, tempat kelahirannya. Sayang, semakin hari Caca melihat rumah-rumah yang dijual di sini sudah tak mungkin lagi terbeli dengan gajinya yang Rp11 juta.
Setiap bulannya, Caca mesti membeli bahan makanan diet diabetes khusus, makan untuk dua kucing, rumah kontrakan senilai Rp20 juta per tahun, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), cicilan laptop, dan asuransi kematian. Alokasi pengeluaran ini kian berat karena penghasilan suami yang mengembangkan karier di bidang penerjemahan belum memadai. Alhasil mimpi untuk beli rumah dia kesampingkan dulu.
“Rumah di Jakarta udah enggak affordable sama sekali. Enggak kepikiran harus banting tulang kayak gimana lagi. Aku merasa udah enggak ada jalan lah gitu (beli rumah di Jakarta). Padahal aku lahir dan tumbuh di Jakarta. Sedih ya,” tuturnya.
Baca Juga: Energi Terbarukan Muncul di Desa, Pemerintah Harus Dukung
Harga Rumah yang Selangit
Indira dan Caca bukan satu-satunya generasi milenial kelahiran 1981-1996 yang sulit punya rumah hari ini. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih ada 10,51 juta rumah tangga di Indonesia yang belum punya rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,39 juta rumah tangga merupakan generasi milenial. Sisanya 4,30 juta rumah tangga generasi X, generasi pre-boomer sebanyak 201.371 rumah tangga, dan generasi Z sebanyak 97.903.
Ini selaras dengan temuan Desy Delvina dan Njo Anastasia dalam “Pertimbangan Generasi Milenial pada Kepemilikan Rumah Dan Kendala Finansial” (2021) di Jurnal Manajemen Aset dan Penilaian. Keduanya mengungkapkan, sebanyak 77 persen generasi milenial sulit beli rumah karena kendala finansial. Harga rumah tiap tahunnya juga terus naik, tapi tidak sebanding dengan kenaikan gaji dan besarnya harga kebutuhan bulanan.
Temuan mereka bukan isapan jempol. Berdasarkan Indeks Harga Properti Residensial Bank Indonesia (IHPR BI) sepuluh tahun terakhir, harga rumah kecil di Jabodebek-Banten rata-rata meningkat 6,47 persen per tahun. Sementara, kenaikan harga rumah sedang (tipe 36-tipe 70) 4,45 persen per tahun dan rumah besar (lebih dari tipe 70) 2,72 persen per tahun.
Di Jakarta sendiri, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selama sepuluh tahun terakhir, dari 2014 ke 2024 cuma sebesar Rp2.626.381. Sementara, jika mengacu pada data Rumah123 pada Agustus 2024, harga rumah di Jakarta dengan ukuran luas tanah 36 meter persegi paling murah sudah dibanderol dengan harga Rp330 juta dengan paling mahal Rp1,35 miliar. Harga rumah Rp330 juta pun kondisinya di pinggiran Jakarta, di dalam gang sempit, dan cuma bisa diakses kendaraan motor.
Ketimpangan antara harga rumah dan gaji para pekerja ini tentu mengkhawatirkan. Karena dalam konsep price income ratio (PIR), harga rumah baru bisa dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari tiga kali penghasilan rumah tangga dalam setahun, atau berskor 3. Sebaliknya, menurut perhitungan Bank Dunia (2019), nilai PIR Jakarta sudah mencapai 10,3.
Ini berarti harga rumah di Jakarta rata-rata nilainya lebih dari 10 kali lipat penghasilan per tahun rata-rata rumah tangga di Jakarta. Padahal nilai PIR New York hanya 5,7, sementara Singapura dan Tokyo/Yokohama masing-masing 4,8. Tidak mengherankan kemudian Jakarta menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 menjadi provinsi terendah dengan persentase kepemilikan rumah sendiri sebesar 56,6 persen.
Jika rumah-rumah di Jakarta saja sudah sulit dijangkau, di daerah perkotaan lain pun sebenarnya tak jauh beda. Harian Kompas Februari lalu menganalisis data jual-beli rumah di Rumah123.com dengan data upah minimum kota (UMK) di 12 kota di Jawa dan luar Jawa. Hasilnya, rumah tangga dengan sumber penghasilan total senilai UMK, tetap tidak mampu membeli rumah di wilayah tempat mereka bekerja.
Untuk data UMK 2024 sendiri kisarannya antara Rp2,3 juta (Kota Surakarta) dan Rp5,3 juta (Kota Bekasi). Dengan menggunakan konsep PI ditemukan, harga rumah yang bisa dijangkau berada pada kisaran Rp81,7 juta hingga Rp192,4 juta. Sebaliknya pasaran harga rumah di 12 kota tersebut sudah tidak ada lagi yang kurang dari Rp200 juta. Bahkan harga tengah rumah dengan ukuran bangunan kurang dari atau hingga 60 meter persegi paling murah di Kota Surakarta berkisar Rp400 juta.
Ketidaksesuaian antara harga rumah dan gaji UMK memperlihatkan, Indonesia mengalami kelebihan penawaran rumah (oversupply housing). Di saat bersamaan, mereka kekurangan penawaran rumah dengan harga terjangkau (undersupply affordable housing). Selain itu, menurut Yusuf Kurniawan, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), harga lahan di perkotaan terutama di Jakarta juga mahal, dan otomatis membuat harga rumah tapak ikut mahal.
“Ada mismatch antara supply and demand. Selama keduanya match, harga itu bisa terjangkau. Lahan juga mahal karena use case-nya bermacam-macam terutama di perkotaan. Ada yang bisa dibangun untuk rumah, kantor, toko, mal. Jadi satu plot tanah di kota banyak yang menginginkan, sehingga otomatis harganya naik. Simpelnya seperti itu,” terang Yusuf.
Mahalnya lahan di wilayah perkotaan dijelaskan lebih lanjut oleh oleh Roni Septian dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Lepas dari teori ekonomi terkait permintaan dan penawaran, Roni bilang, mahalnya lahan di perkotaan bersifat struktural karena ada monopoli penguasaan lahan oleh sejumlah konglomerat bisnis dan badan usaha skala besar.
Baca juga: Problem Perempuan Penjaga Hutan: Akses Minim hingga Kesenjangan Upah
Menurut data KPA pada 2022, di Jabodetabek saja terdapat 63.000 ha tanah yang dikuasai hanya 25 perusahaan. Mereka di antaranya ada PT Sentul City TBK, Agung Podomoro Land, PT Ciputra Development Tbk, dan MNC Group.
“Karena dimonopoli (segelintir pebisnis), jadinya mereka yang mengatur standar harga. Enggak ada yang bisa mengintervensi. Kawan-kawan buruh dan masyarakat yang berpenghasilan rendah jadi enggak bisa masuk ke sistem pasar, mau beli tanah enggak mungkin. Sekalinya dapat ya tanah sisa di pinggiran kayak Bogor, Bekasi pun ujung kayak Cikarang, Karawang,” jelasnya.
Harga yang semakin melambung tinggi dengan daya beli masyarakat yang rendah akhirnya bikin Indonesia masuk dalam lingkaran krisis kebutuhan kepemilikan rumah (backlog). Backlog merupakan indikator dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengukur kesenjangan (gap) antara kebutuhan dan pasokan rumah. Berdasarkan data Susenas terbaru pada 2023 yang dirilis oleh BPS, Indonesia rata-rata mengalami backlog kepemilikan rumah yang sangat tinggi sebesar 13,56 persen atau sebanyak 9.905.820 rumah tangga.
Artikel ini diproduksi oleh Magdalene.co sebagai bagian dari kampanye #WaveForEquality, yang didukung oleh Investing in Women, inisiatif program Pemerintah Australia.
Series artikel lain bisa dibaca di sini:
Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian I)
Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian II)
Bahagia dan Kejar Mimpi Pasca-Bercerai: Cerita Tiga Perempuan
Di Balik Milenial ‘Childfree’: Ada Masalah Struktural Ekonomi yang Jarang Dibahas
Ketika Bapak Rumah Tangga Bicara Stigma hingga Omongan Tetangga
Ilustrasi oleh Karina Tungari