Rumah untuk Milenial: Bahkan Kerja Selamanya pun Masih Tak Terbeli (Bagian 2)
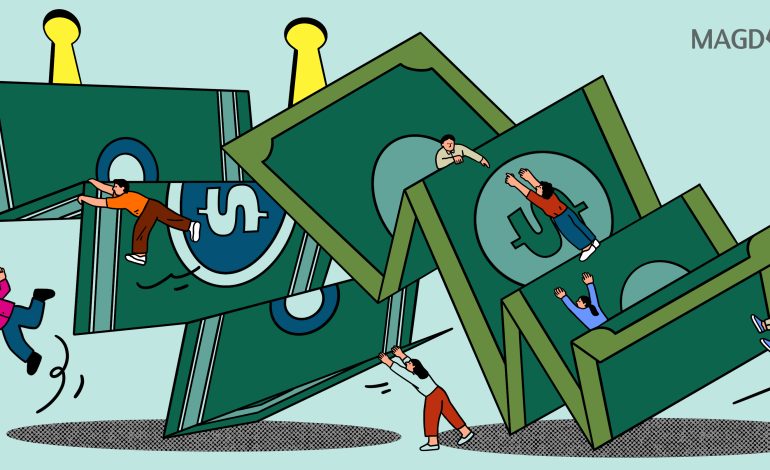
Rumah Subsidi Tak Layak Huni
Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) berusaha menyiasati backlog dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menawarkan KPR bersubsidi. KPR bersubsidi itu difokuskan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa membeli rumah.
Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, MBR mengacu pada masyarakat dengan penghasilan maksimal senilai Rp7 juta untuk yang belum kawin dan maksimal senilai Rp8 juta untuk yang sudah kawin
Karena ditujukan khusus untuk MBR, maka KPR bersubsidi pun ditawarkan dengan suku bunga KPR stabil 5 persen per tahun sepanjang masa pinjaman. Mereka pun cuma perlu membayar uang muka 1 persen dari harga rumah. Walau harganya terjangkau, Kementerian PUPR menjamin rumah-rumah ini layak huni.
Sepintas, kebijakan itu bak angin segar untuk kita generasi milenial. Namun pada kenyataannya, janji layak huni itu sekadar janji. Lintang, 31, yang memilih mengambil KPR bersubsidi sejak 2018 adalah salah satu “korban” kecewa usai membeli rumah bersubsidi. Sebagai pekerja bergaji pas-pasan tapi mengidamkan punya rumah tapak sendiri, Lintang enggak menyia-nyiakan kesempatan saat ditawari KPR bersubsidi oleh teman ayahnya.
Baca Juga: ‘Saya dan Keadilan’: Ubah Paradigma Lingkungan yang Berpusat pada Manusia
Ia lantas mempersiapkan segala persyaratan termasuk surat keterangan kerja sebagai karyawan tetap di kantornya. Lalu Lintang mengambil rumah harga Rp150 juta di Cikarang, Jawa Barat. Dengan masa cicilan atau tenor sepuluh tahun, ia membayar cicilan KPR Rp1,5 juta per bulan dan uang muka sebesar Rp20 juta. Nahas, ada harga yang harus dibayar untuk rumah murah meriah ini.
Lintang bercerita, kawasan rumahnya selalu rawan banjir. Hujan deras satu jam saja, daerah sekitar rumahnya akan langsung tergenang air dan baru bisa surut berjam-jam kemudian. Selain itu, sumber airnya juga berbau menyengat seperti bau selokan. Sampai-sampai ia harus gosok gigi dengan air mineral. Dengan kondisi seperti ini, Lintang bersama tetangga-tetangganya memutuskan merogoh kocek lagi untuk patungan menaikkan jalan dan mengebor sumur serta mengelola sumber air mereka sendiri.
“Ninggiin jalan satu gang itu kami habis patungan per keluarga Rp3,5 juta, itu bisa dicicil. Terus karena air jelek banget akhirnya ada inisiatif bikin bor, semacam bikin PAM sendiri. Itu patungan lagi Rp2,5 juta dan per bulannya untuk pengelolaan bayar Rp40 ribu,” jelas Lintang.
Biaya tak terduga yang harus dikeluarkan Lintang bukan cuma satu-satunya masalah yang harus dia hadapi selama pindah ke rumah KPR bersubsidi itu. Lintang yang masih bekerja di daerah Jakarta Selatan kesulitan melakukan mobilisasi dari Cikarang. Satu-satunya moda transportasi umum yang tersedia cuma Kereta Rel Listrik (KRL).
Stasiun kereta Cikarang dari rumahnya cukup dekat, berjarak 5,7 km saja tapi karena Cikarang termasuk daerah peri-urban (pinggiran kota), armada kereta yang diterjunkan cenderung sedikit. Ia pernah sampai menunggu satu jam dari Stasiun Sudirman hanya untuk berganti kereta. Jika ditotal perjalanannya dari kantor ke rumah begitu pun sebaliknya mencapai lima jam tiap hari.
Untuk mengakali panjangnya waktu perjalanan, Lintang dan suami lalu memutuskan untuk membeli mobil. Namun ternyata punya mobil bukan juga jadi solusi. Setelah dihitung-hitung, waktu yang ia habiskan di jalan tidak begitu banyak berubah. Ia dan suaminya bahkan harus menambah pengeluaran lagi untuk mengisi bensin dan servis mobil.
“Ngisi Rp400 ribu itu cuma tiga kali bolak-balik karena jaraknya udah hampir 100 km. Terus karena jarak kilometer-nya cepet naik jadi lebih berasa diservis mobil kayak ganti oli,” jelasnya.
Karena sudah tidak sanggup harus bolak-balik Cikarang-Jakarta, Lintang dan suaminya pun memutuskan untuk mengontrak di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Walaupun harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp5 juta per bulan, setidaknya ia mengaku kondisi fisik dan mentalnya jadi lebih baik.
Keputusan Lintang dan suami untuk mengontrak dan menetap di rumah Cikarang hanya pada akhir pekan seminggu atau dua minggu sekali, memperlihatkan fenomena baru yang terjadi belakangan soal tingkat kekosongan rumah bersubsidi. Mengutip Kompas.com, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto bilang, walau minat masyarakat tinggi, tapi banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi kosong tidak dihuni.
Dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2024 yang telah diserap habis sebanyak 166.000 unit, tingkat kekosongannya bahkan tembus 60 sampai 80 persen. Buat Yusuf yang meneliti di bidang perkotaan, transportasi, dan pembangunan, tingginya tingkat kekosongan rumah bersubsidi adalah kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tanpa pertimbangan aksesibilitas. Pun, pemerintah luput mempertimbangkan persoalan job-residence spatial mismatch.
Yusuf menjelaskan, frasa itu merujuk pada situasi di mana masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah cenderung memilih tinggal di area yang relatif terhubung dengan pusat perkotaan. Ketiadaan atau minimnya kesempatan kerja yang memberikan kompensasi upah yang sepadan atau lebih baik di daerah suburban jadi alasannya.
“Jadi ketika rumah tapak asal dibangun aja, enggak memperimbangan lokasi yang dekat dengan pusat perekonomian dan transportasi, ya menurut saya jadi wajar aja rumah-rumah murah bersubsidi juga jadi kosong,” tambah Yusuf.
Baca Juga: Energi Terbarukan Muncul di Desa, Pemerintah Harus Dukung
Tapera Bukan Solusi, Lalu Apa?
Selain dengan menawarkan rumah bersubsidi, untuk mengatasi krisis hunian, pemerintahan belakangan menetapkan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sebelumnya Tapera digagasi dan disepakati pertama kali oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di era pemerintahan SBY pada 2012.
Pembahasan RUU itu beberapa kali diperpanjang, dan baru secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. Program Tapera sedianya dihadirkan untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan dukungan fasilitas finansial agar dapat memiliki rumah sendiri.
Namun baru disahkan beberapa hari, Tapera langsung menuai kontra dari masyarakat. Lintang misalnya menyatakan, besaran iuran Tapera yang diwajibkan oleh pemerintah terlalu besar buat dirinya dan buat dia yang sudah punya rumah, jelas program ini tidak memberikan manfaat langsung.
“Potongannya itu 3 persen menurutku besar banget. Untuk aku yang keluarga double income tanpa anak aja itu besar. Apalagi yang sudah berkeluarga dan hanya one income. Apalagi potongan Tapera itu menurutku enggak bisa dinikmati secara langsung seperti BPJS Ketenagakerjaan yang bisa langsung dicairkan, atau BPJS Kesehatan kalau kita berobat ya,” jelas Lintang.
Kekhawatiran Lintang cukup beralasan. Mengacu pada PP tersebut, iuran wajib Tapera dikenakan sebesar 2,5 persen dari pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja, sedangkan untuk pekerja mandiri atau freelancer, harus menanggung penuh potongan 3 persen. Peserta yang memenuhi syarat Program Tapera nantinya memperoleh manfaat melalui tiga skema pembiayaan rumah, yakni Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Sedangkan buat mereka yang sudah punya rumah atau tidak punya niat beli rumah, peserta masih dapat mencairkan hasil tabungan yang telah dikumpulkan setelah kepesertaan berakhir (maksimal 30 tahun).
Permasalahannya pencairan hasil tabungan ini pun belum mekanisme yang jelas. Ditambah lagi, ada berbagai kasus hukum yang membelit Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (ASABRI), Jiwasraya, dan Taspen (2018-2024) telah mencederai kepercayaan publik terhadap kredibilitas pengelolaan dana yang dihimpun oleh perusahaan milik pemerintah.
Dengan carut marutnya Program Tapera beserta permasalahan lain terkait rumah subsidi, Yusuf menuturkan, sudah waktunya pemerintah memikirkan ulang kebijakan hunian layak buat masyarakat Indonesia. Dalam hemat Yusuf, selama ini pemerintah masih terjebak dalam pemaknaan sempit hunian yang menyasar hanya pada rumah tapak.
“Padahal kalau kita berbicara hunian, definisinya lebih luas. Bisa milik sendiri seperti rumah tapak, tapi juga sewa atau berbentuk rumah susun yang tipe bentuknya seperti apartemen midrise lima lantai. Unitnya hanya beberapa dan aksesnya juga dipertimbangkan. Saya yakin demand-nya ada di situ,” kata Yusuf.
Pemaknaan lebih luas dari hunian kata Yusuf bisa juga berarti pada penyediaan social housing atau perumahan sosial yang fokus menyediakan hunian bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu mengakses perumahan di pasar swasta. Mengutip kembali pada laporan spesial LPEM FEB UI, alokasi perumahan sosial ini dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan kemampuan bayar layaknya di pasar swasta.
Perumahan sosial dapat disediakan oleh pemerintah sendiri contohya perumahan publik atau rusun maupun lembaga non-profit seperti perumahan komunitas. Lagi-lagi perumahan sosial ini juga harus mempertimbangkan aksesibilitas di mana harus dibangun dekat pusat perekonomian masyarakat dan diperlukan akses konektivitas (transportasi umum dan jalan tol).
Baca juga: Problem Perempuan Penjaga Hutan: Akses Minim hingga Kesenjangan Upah
Namun sebelum berbagai solusi ini program dijalankan, menurut Roni ada satu hal paling krusial yang harus terlebih dahulu dilakukan. Pemerintah perlu menindak tegas monopoli atas lahan alih-alih memberi karpet merah pada pengusaha tanah dan properti. Kita bisa melihat contohnya lewat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu, solusi harga rumah mahal tidak bisa semata-mata diatasi dengan kebijakan teknis. Harus ada transformasi berkelanjutan dalam sisi hukum untuk mengatasinya.
Pertama, untuk mencegah monopoli tanah atas tanah maka harus ada pengaturan pembatasan tanah yang diperinci dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA).
“Perlu ada penguatan agar UU PPA bisa efektif dengan perkembangan zaman. Harus dirinci batas maksimum dan minimum monopoli agar tidak ada lagi nih celah untuk menyiasati hukum,” kata Roni,
Kedua, pemerintah perlu menetapkan standarisasi harga tanah agar para konglomerasi bisnis tidak jadi tuan tanah yang bisa semaunya menetapkan harga di pasar. Sehingga perlu ada evaluasi mendalam terkait harga-harga tanah di pasar property sendiri. Terakhir standarisasi ini kata Rono lalu bisa diperkuat dengan tindakan afirmatif dari pemerintah bagi masyarakat miskin perkotaan.
“Jadi harus ada tanah-tanah yang dialokasikan khusus untuk mereka. Jangan semuanya dijual. Intinya pemerintah harus memikirkan gimana caranya ada sistem yang bisa membuat masyarakat bisa nyicil punya tanpa tapi bukan dengan harga tanah sekarang. Jadi intinya harus mengevaluasi, memperbaiki, dan endistribuukan. Baru dari situ kebijakan teknis bisa dilakukan,” tutup Roni.
Artikel ini diproduksi oleh Magdalene.co sebagai bagian dari kampanye #WaveForEquality, yang didukung oleh Investing in Women, inisiatif program Pemerintah Australia.
Series artikel lain bisa dibaca di sini:
Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian I)
Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian II)
Bahagia dan Kejar Mimpi Pasca-Bercerai: Cerita Tiga Perempuan
Di Balik Milenial ‘Childfree’: Ada Masalah Struktural Ekonomi yang Jarang Dibahas
Ketika Bapak Rumah Tangga Bicara Stigma hingga Omongan Tetangga
Rumah untuk Milenial: Bahkan Kerja Selamanya pun Masih Tak Terbeli (Bagian 1)
Ilustrasi oleh Karina Tungari






















