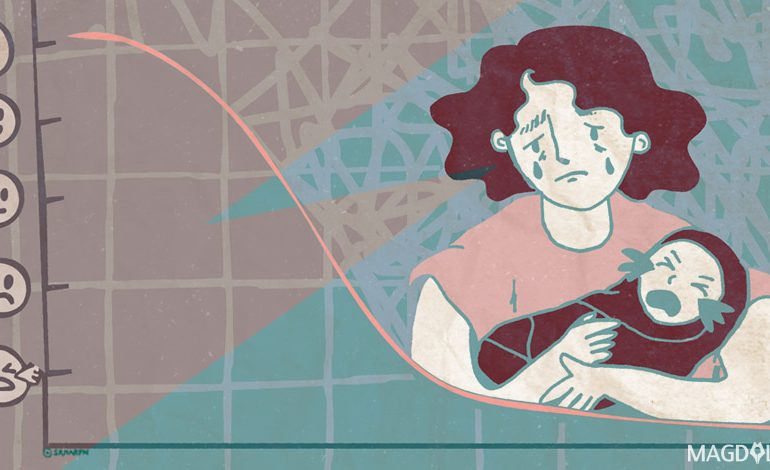Lewat Buku Muslimah Reformis, Musdah Mulia Tekankan Penafsiran Feminis-Humanis

Peradaban manusia muncul dari tulisan, bukan secara verbal. Alasan itulah yang membuat cendekiawan Islam Musdah Mulia menyanggupi keinginan penerbit Dian Rakyat yang meminta mengumpulkan pemikiran-pemikirannya.
Maka terbitlah Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi, yang bertujuan menjadikan agama sebagai institusi pemberi solusi bagi persoalan-persoalan kemanusiaan.
“Agama seharusnya membantu manusia mengenali hakikat dirinya. Semakin kita beragama, seharusnya kita menjadi semakin manusiawi,” ujar Musdah Mulia dalam diskusi buku yang diadakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Suara Kita, dan Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini di Jakarta, 16 November lalu.
Ia menambahkan, ajaran agama yang mengedepankan prinsip-prinsip konservatif, intoleran, dan radikal pada akhirnya akan membangun sebuah belenggu yang menghambat tumbuhnya peradaban manusia.
“Beberapa penelitian terbaru mengungkapkan bahwa di negara-negara religius, kemajuan sains dan teknologinya pasti terhambat. What is the problem? Kenapa agama tidak bisa bersanding dengan sains dan teknologi yang mengedepankan pikiran kritis dan analisis filosofis?” ujarnya.
Buku setebal 772 halaman ini sangat komprehensif, mengupas berbagai isu dari mulai pendidikan dan keluarga berencana, hingga demokrasi dan keadilan gender. Pada intinya Musdah ingin mendorong para muslimah berjihad menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi esensi ajaran Islam, dan berdialog mengenai persoalan-persoalan kemanusiaan.
Penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu hal yang dibahas dalam buku ini. Musdah mengatakan prinsip dasar HAM sebetulnya selaras dengan konsep keesaan Tuhan atau tauhid dalam Islam.
“Ketika mendengar kata HAM, masih banyak umat Islam yang berkata, ‘Ini kan nilai-nilai asing dan barat”. Banyak di antara kita yang mengaku Islam tetapi tidak mengerti konsep tauhid,” ujarnya.
“Kalau Anda mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, berarti yang lainnya adalah makhluk. Dalam posisi sebagai makhluk, kita semua setara. Konsep Tauhid dalam Islam membawa kepada prinsip kesetaraan manusia. Dan konsep kesetaraan manusia ini yang menjadi landasan utama dari penyusunan prinsip-prinsip HAM,” tambahnya.
Baca juga: Kelompok Pengajian ‘Salam’ Kaji Islam dari Perspektif Kemanusiaan
Ia juga menyoroti “pengerasan” dalam praktik beragama, yang biasanya menyasar perempuan, seperti yang terjadi dengan praktik syariat di Aceh.
“Upaya mensyariatkan Aceh dimulai dari perempuan, dan ujung-ujungnya adalah urusan jilbab. Saya pernah tanya para penerap syariat Islam di Aceh dengan mengatakan, ‘Kenapa ketika Anda ingin menegakkan syariat Islam di Aceh, Anda tidak mulai dengan menata pendidikan yang berkualitas terutama bagi kaum yang tidak mampu?’,” ujar Musdah.
“Mereka menjawab, ‘Pendidikan bukanlah wilayah kami’. Saya merespons, ‘Ayat pertama dalam Alquran adalah ‘yang artinya “bacalah’. Bukanlah itu adalah isyarat bahwa hal yang pertama-tama perlu diperbaiki adalah pendidikan?” ujarnya.
Kebenaran tunggal dalam beragama
Salah satu isu yang terus menjadi pergulatan dan perdebatan bagi perempuan muslim adalah jilbab, seperti yang dialami penulis Dewi Nova.
“Sampai saat ini saya masih dikirimi pesan melalui WhatsApp dan didoakan seluruh keluarga supaya berjilbab. Dan ini pelik sekali. Peliknya adalah karena saat ini tekanannya bertambah. Kalau dulu, hanya ada tekanan teologis, tetapi sekarang juga ada tekanan budaya. Misalnya, kalau saya enggak pakai jilbab, tiba-tiba ada orang yang menganggap saya Katolik atau Kristen,” ujarnya dalam diskusi buku tersebut.
Dewi menambahkan, ada sekelompok orang yang berusaha mendefinisikan budaya sesuai dengan penafsirannya sendiri.
“Budaya adalah sebuah hasil kesepakatan yang tidak melibatkan banyak orang. Akhirnya, kebudayaan selalu dibangun oleh orang yang punya kuasa. Keterbatasan pemikiran seperti itu berisiko menimbulkan pembatasan terhadap kelompok orang yang dianggap menyimpang dari apa yang saat ini dianggap sebagai budaya,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, ada keinginan para pengusung kebenaran tunggal untuk memengaruhi berbagai regulasi.
“Mereka menginfiltrasikan interpretasi agama, dalam hal ini Islam, pada hukum nasional seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-Undang Kesehatan, dan sekarang mereka mau memasukkan konsep ketahanan keluarga ke dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” ujarnya.
“Beberapa tahun terakhir, untuk mengegolkan kepentingan yang monolitik itu, selain menggunakan argumen tafsiran agama, mereka juga selalu menggunakan argumen moral publik, yang mengacu kepada budaya,” katanya.
Baca juga: Saat Semua Orang Merasa Jadi Tuhan: Wawancara dengan Musdah Mulia
Menurut Dewi, lewat buku Ensiklopedia Muslimah Reformis, Musdah menawarkan penafsiran feminis-humanis. Pertama, mengidentifikasi teks-teks perempuan dalam Islam untuk menanggapi teks-teks populer yang misoginis. Kedua, mengkaji teks-teks Alquran dan hadis secara umum untuk membentuk perspektif teologis yang dapat mengkritisi nilai-nilai patriarkal. Ketiga, mengkaji teks tentang perempuan untuk belajar dari sejarah mengenai kapasitas perempuan kuno dan modern yang hidup di dalam kebudayaan patriarki.
Penanggap lain dalam diskusi buku tersebut adalah Suarbudaya Rahadian, pendeta Gereja Komunitas Anugerah, yang mengatakan bahwa menafsir agama secara logis saja tidak cukup.
“Kita perlu sumber lain, yaitu pengalaman berteologi umat. Yang saya lihat di bukunya Bu Musdah ini adalah, bahwa dalam menafsir, beliau tidak hanya menarik dalil-dalil dari kitab suci dan ajaran-ajaran klasik Islam, tetapi juga realitas sejarah dan sosial politik,” ujarnya.
Di gerejanya, Suarbudaya sedang menggeluti dan membentuk teologi konstruktif, yakni menghayati ketuhanan dan tafsir kitab suci tidak hanya secara gramatikal dan sejarah, melainkan juga dari pengalaman seseorang.
“Mereka yang beragama saat ini bukanlah orang-orang yang hidup di abad ke-7. Yang beragama adalah saya, yang hidup di abad ke-21. Kalau sesuatu menjadi relevan di abad ke-7, apakah masih relevan, di abad ke-21?,” ujarnya.
“Misalnya, pada abad ke-7, ada ide tentang perbudakan. Di Alkitab, tidak ada satu pun ayat yang melarang perbudakan. Namun, saat ini, tidak ada orang Kristen, yang paling fundamentalis sekalipun, yang membeli budak.”