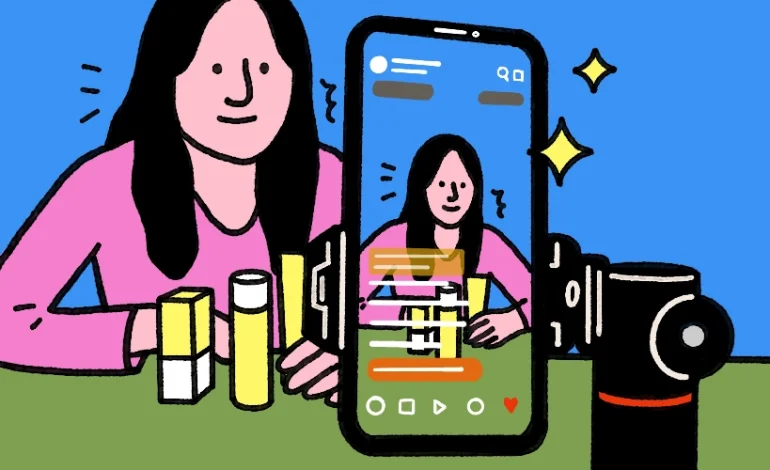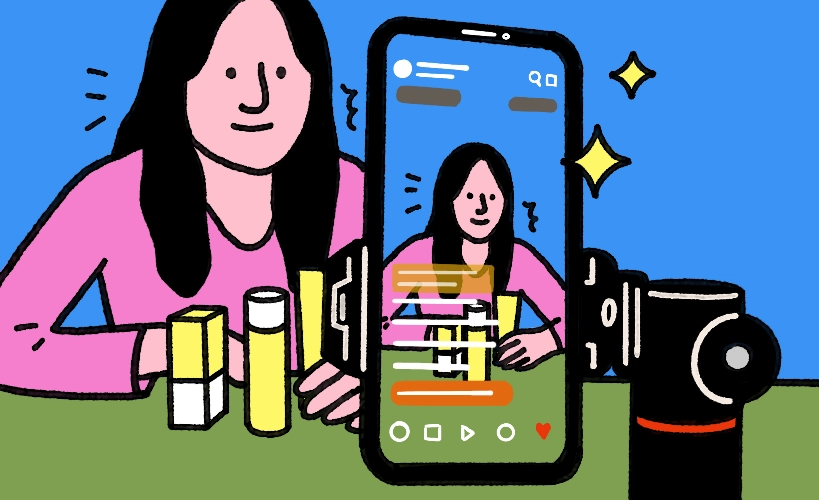Dilarang Marah-marah di Negeri Sendiri: yang Saya Pelajari dari Vonis Laras

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengeluarkan Laras Faizati dari tahanan. Ia boleh pulang. Kalimat “boleh pulang” terdengar seperti tebusan yang lunak. Padahal inti vonisnya tetap ngegas: Laras resmi bersalah, dan pidana pengawasan menjadi pagar yang setiap saat bisa menutup kembali pintu kebebasan.
Laras dijatuhi pidana kurungan enam bulan, tapi pidana itu tidak perlu dijalani sepanjang ia tidak melakukan tindak pidana lain selama masa pidana pengawasan satu tahun. Di atas kertas, pidana pengawasan sering dianggap lebih manusiawi dibanding penjara jangka pendek. Namun dalam perkara kebebasan berekspresi, mengganti penjara dengan pengawasan tidak menyentuh inti masalah. Negara tetap memilih memidanakan kemarahan warga.
Baca juga: Skenario yang Mungkin Usai Vonis Janggal Laras Faizati
Marahnya Manusiawi tapi Kenapa Dipidanakan
Vonis bersalah terhadap Laras bukan hanya kabar buruk bagi dirinya. Ini alarm bagi siapa pun yang masih percaya ruang kritik relatif aman. Laras adalah perempuan kelas menengah, berpendidikan, dengan akses pendampingan hukum dan sorotan publik. Justru karena itu, vonis ini mengirim pesan yang lebih menakutkan. Jika yang terlihat saja bisa dipidana, maka yang tidak terlihat akan jauh lebih mudah dibuat tak terdengar.
Di titik ini, demokrasi tidak runtuh dengan ledakan. Ia menyusut pelan-pelan. Kemarahan tidak dibaca sebagai sinyal publik atas ketidakadilan, melainkan sebagai gangguan yang harus ditertibkan. Wajah negara memberi pesan dingin: Bukan carilah kebenaran, melainkan jangan bersuara terlalu keras. Ketika hukum dipakai untuk mendisiplinkan emosi, yang dipersempit bukan hanya ruang kritik, tetapi juga rasa aman warga untuk mengatakan bahwa ada yang salah.
Bagi perempuan, konsekuensinya berlapis. Perempuan sejak lama hidup dalam standar ganda. Mereka diminta peduli, menjaga suasana, juga tetap tenang. Bahkan ketika kemarahan lahir dari ketidakadilan yang nyata, ia cepat diberi label berlebihan dan mudah diseret menjadi perkara.
Efeknya tentu serius sekali. Ia menggerus keberanian untuk mengawal kasus kekerasan berbasis gender, melemahkan kontrol sosial, dan membuat ruang publik kehilangan suara yang paling dibutuhkan untuk mendorong perubahan.
Maka tagihan kepada negara seharusnya jelas. Jangan pidanakan kemarahan yang manusiawi. Jangan jadikan pengadilan alat untuk merapikan warga. Yang patut diuji bukan ekspresi marah, melainkan kegagalan akuntabilitas yang membuat nyawa bisa hilang, lalu kritik justru diproses.
Baca juga: Hasil Putusan Laras Faizati: Bersalah dengan Pidana Pengawasan di Luar Penjara
Jurang Kelas dalam Kebebasan Bersuara
Kebebasan bersuara tidak pernah benar-benar setara. Modal sosial menentukan banyak hal: siapa yang cepat mendapat pendampingan hukum, siapa yang bisa mengakses jaringan solidaritas, siapa yang kisahnya dianggap layak diberitakan. Laras berada di posisi yang relatif lebih kuat. Ada pendampingan dan sorotan yang membuat proses hukumnya sulit disembunyikan.
Namun bagi perempuan di akar rumput, marah sering berarti risiko berlapis. Kriminalisasi, stigma, kehilangan nafkah, dan keluarga yang ikut menanggung beban ketika satu orang diproses hukum. Dalam kondisi seperti itu, hak berpendapat mudah berubah menjadi privilese, hanya tersedia bagi mereka yang cukup kuat menanggung ongkosnya.
Vonis bersalah terhadap Laras menjadi berbahaya bukan hanya bagi aktivis, tetapi bagi warga biasa. Ia mengirim sinyal bahwa jika yang terlihat saja tetap diputus bersalah, warga tanpa jaringan perlindungan akan lebih mudah hilang tanpa jejak. Kita tidak akan pernah tahu berapa banyak suara yang lenyap sebelum sempat menjadi isu publik.
Saya memandang kritik sebagai tagihan publik. Tagihan atas kerja negara yang dibiayai pajak dan mandat konstitusi. Ketika warga marah, yang seharusnya hadir adalah mekanisme akuntabilitas, bukan refleks pemidanaan. Publik berhak tahu ukuran yang dipakai pengadilan untuk membedakan ungkapan marah dari hasutan yang benar-benar memenuhi unsur pidana. Tanpa standar yang transparan, yang lahir bukan ketertiban, melainkan ketakutan sosial.
Baca juga: Perburuan Senyap di Ruang Digital Pasca-Aksi Agustus
Selama pasal-pasal lentur tetap tersedia, benteng terakhir ada di pengadilan. Di situlah ekspresi warga seharusnya ditakar dengan kehati-hatian, bukan dipukul rata sebagai ancaman. Dalam perkara kebebasan berekspresi, kehati-hatian adalah kewajiban.
Seandainya Laras adalah perempuan akar rumput, mungkin kisah ini tidak pernah kita baca. Ia bisa ditahan lebih lama, diproses tanpa sorotan, lalu hilang tanpa jejak. Vonis Laras memperlihatkan dua hal sekaligus: negara masih canggung menghadapi kritik, dan jurang kelas membuat ketidakadilan itu semakin dalam. Jika ruang marah dipersempit oleh pidana, demokrasi kita tidak hanya kehilangan kebisingannya. Ia kehilangan keberaniannya.