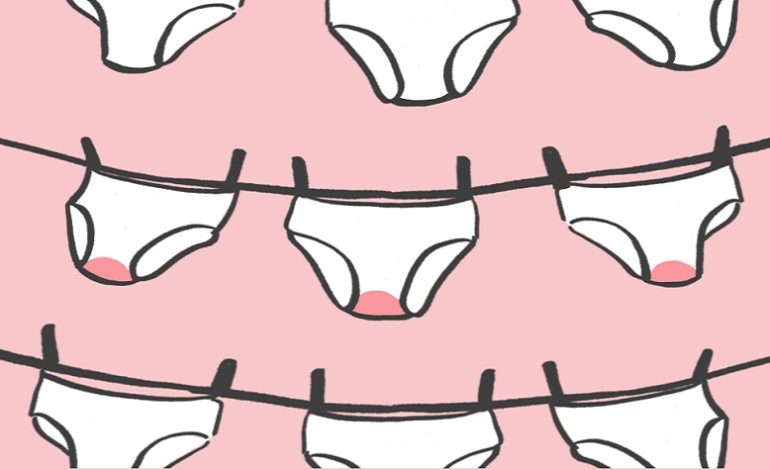Pendidikan Perempuan untuk Siapa?

Saya menyadari tulisan ini sedikit reaktif. Tulisan ini saya buat untuk menanggapi sebuah percakapan di warung dan unggahan di media sosial yang menurut saya telah mempromosikan pendidikan perempuan dengan cara yang salah. Keduanya sama-sama mendeskripsikan pendidikan bagi perempuan sebagai penunjang kebahagiaan suami.
Awalnya saya berpikir, apa saya terlalu berlebihan? Baru dua kali bertemu konten serupa sudah marah-marah. Meskipun begitu, akhirnya saya putuskan untuk tetap menuliskannya. Saya harap bila ada di luar sana promosi pendidikan dengan cara seperti ini, kita bisa sama-sama menanggapinya dengan baik.
Dari percakapan dan tulisan yang saya temui itu, saya menyimpulkan setidaknya ada dua mekanisme yang mendasari hubungan pendidikan perempuan dengan kebahagiaan suami, yaitu:
- Yang dimoderasi kemampuan mengurus anak, dan
- Yang dimoderasi kemampuan lain untuk membahagiakan suami
Logikanya seperti ini. Pada mekanisme pertama, perempuan yang berpendidikan lebih mampu untuk mengurus anak. Anak yang terurus, membuat suami lebih bahagia.
Lantas apakah mengurus anak adalah hal yang salah?
Tentu saja tidak. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab orangtua dalam memenuhi hak anaknya. Yang menjadi masalah adalah, percakapan yang tak sengaja saya dengar itu menyiratkan pesan bahwa mengurus anak sebenarnya hanya sebuah means to an end bagi kebahagiaan suami, dan bukan usaha pemenuhan hak anak itu sendiri.
“Harus bisa ngurus anak dong, biar suami seneng,” kira-kira begitu ucapannya.
Pada mekanisme kedua, perempuan yang berpendidikan lebih mampu membahagiakan suami. Entah dengan cara apa saya tidak tahu, karena tidak dituliskan secara jelas dalam unggahan tersebut. Mungkin, perempuan yang berpendidikan lebih mampu mengurus keuangan, memperhatikan kesehatan suami, dan menyelesaikan konflik-konflik rumah tangga. Sehingga lagi-lagi, suami jadi lebih bahagia karena semua kebutuhannya terpenuhi. Ya pokoknya intinya: suami, suami, suami.
Saya tidak bermaksud melarang siapa pun untuk membahagiakan suaminya. Membahagiakan suami tentu sah-sah saja. Sama halnya dengan suami membahagiakan istri, atau siapa pun membahagiakan siapa pun. Dalam berbagai kasus, membuat orang lain bahagia bisa memberikan efek bahagia bagi yang melakukannya. Hanya saja ketika hal tersebut dijadikan tujuan akhir dari pendidikan perempuan, atau lebih parah lagi, tujuan akhir dari eksistensimu, di situlah saya merasa terganggu.
Fungsi pendidikan direduksi menjadi sekedar perangkat untuk membahagiakan suami. Kemudian perempuan digambarkan seolah-olah keberadaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Selanjutnya, lagi-lagi lelaki dijadikan pusat dunia. Apa pun yang perempuan lakukan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan laki-laki. Bahkan kemampuan yang didapatkan perempuan dari pendidikan, adalah untuk suami.
Memang benar pemikiran Simone de Beauvior. Perempuan tidak memiliki eksistensi dalam dan untuk dirinya sendiri. Bayangkan saja, pendidikan yang seharusnya mampu meningkatkan martabat perempuan, hanya dimaknai sebagai penunjang kebahagiaan orang. Dalam narasi seperti ini, perempuan dan pendidikan mungkin seperti komputer yang sistem operasinya dimutakhirkan. Tujuan pemutakhiran tentunya bukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan komputer, melainkan untuk membuatnya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks ̶ seperti membahagiakan suami misalnya.
Benar, kita harus terus memperjuangkan hak perempuan untuk mendapat pendidikan. Lebih dari itu, kita harus memperjuangkan hak siapa pun untuk memperoleh pendidikan. Akan tetapi jika alasan di balik pendidikan kita adalah suami, apa itu bisa disebut kemajuan? Saya sih melihat promosi seperti ini justru kontraproduktif, karena secara halus mempertegas peran domestik perempuan sekaligus memperkuat gagasan bahwa perempuan ada untuk keperluan orang lain. Bahkan, cara-cara seperti ini bisa jadi lebih berbahaya karena dikemas dalam bahasa yang manis dan terasa memiliki niat yang baik.
Perempuan masih sering mendapat tanggapan sinis mengenai pendidikannya. Kemudian datanglah promosi ini, yang berusaha melegitimasi pendidikan bagi perempuan dengan cara menyenangkan si tuan. Berusaha menghibur para perempuan dengan alasan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak salah, karena itu dilakukan untuk suaminya.
Oleh orang-orang ini, sesuatu yang dahulu tidak diperkenankan bagi perempuan, kini dipromosikan sebagai hal yang wajib. Wajib untuk dimiliki karena dengan begitu, perempuan lebih mampu memenuhi kebutuhan-Nya.
Bukan, bukan Tuhan. Tapi suami.
Astrid F. Marjuan adalah mahasiswi sok tahu yang suka ngomel. Belum punya personal brand; masih terus mengeksplorasi siapa dirinya. Ini twitternya: @astridfauzia.