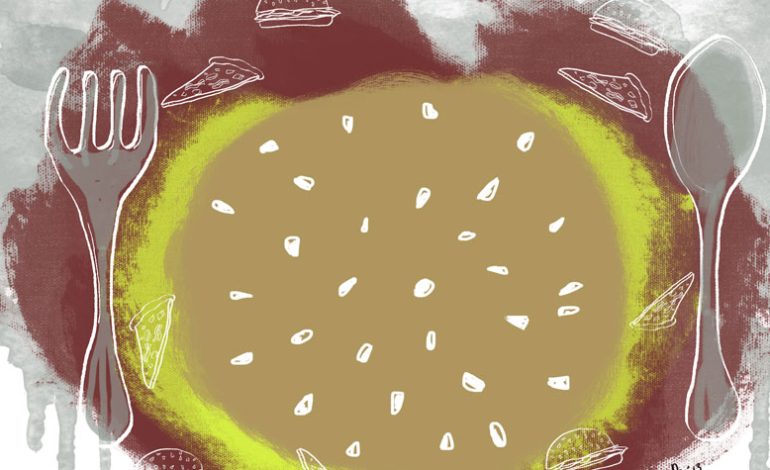‘Perempuan Tanah Jahanam’: Kemiskinan sebagai Sumber Horor

Maya (Tara Basro) dan Dini (Marissa Anita) adalah dua sahabat yang mesti bertarung hidup di ibu kota. Keduanya bekerja sebagai petugas karcis tol. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, mereka berharap memperbaiki nasib mereka dengan berganti mata pencaharian menjadi penjual baju.
“Parah lah di negara kayak gini semua mau diganti mesin. Makin banyak tuh pengangguran,” kata Maya membicarakan tentang fungsi kerjanya yang dapat dengan mudah digantikan oleh mesin e-toll.
Perempuan Tanah Jahanam (2019) karya Joko Anwar telah menggambarkan latar belakang ekonomi kedua karakter dari adegan pembuka film. Latar belakang ini pula yang menjadi motivasi bagi kedua karakter untuk pergi ke suatu daerah terpencil untuk mengklaim sebuah harta warisan—meski mereka tidak tahu menahu situasi macam apa yang akan mereka hadapi.
Menjadi penjaga karcis tol tidak memberikan cukup pendapatan bagi mereka. Berwirausaha menjadi penjual baju juga tidak lebih baik. Maya dan Dini tidak begitu saja pergi meninggalkan zona nyaman mereka. Mereka bukan sekadar iseng, ingin membuat dokumenter, merekam pengalaman mereka, atau sekadar berlibur ke sebuah desa terpencil. Kebutuhan mereka lebih mendesak dari itu.
Lantas, apakah pergi ke sebuah desa terpencil dan menjual rumah peninggalan orang tua Maya akan menyelesaikan semuanya? Nyatanya, tidak semudah itu.
Perjuangan kelas pekerja
Sebagai kelas pekerja, pikiran-pikiran Maya dan Dini tak akan jauh-jauh dari uang. Maya khawatir dengan Dini yang menghabiskan tabungannya untuk modal dagangan mereka. Dini mengeluhkan konsep kuburan yang memakan tempat—ketika sebenarnya tanah tersebut bisa dipakai untuk membangun hunian bagi orang-orang yang masih hidup. Sempat tercetus bagaimana mereka menimbang kelebihan dan kekurangan menjadi pekerja seks, atau Dini yang selalu mengomentari luas rumah peninggalan orang tua Maya serta potensi jumlah uang yang bisa didapatkan dengan menjualnya.
Melihat karakter film yang memiliki kekhawatiran finansial menjadi menyenangkan. Sebab, ketika pikiran kebanyakan orang tak jauh dari gaji yang tak kunjung turun, cicilan yang tak kunjung beres, hingga tabungan yang nilainya tak bertambah-tambah, tak banyak film horor—bahkan film Indonesia pada umumnya—yang mencoba mengupas hal tersebut.
Kebanyakan para karakter film di Indonesia telah dikaruniai pekerjaan yang mengasyikkan, mudah bepergian ke luar negeri, dan rumah yang besar. Namun penonton tidak diberi tahu dari mana semua itu berasal, atau bagaimana mereka bisa semapan itu. Raina dalam Magic Hour (2015), misalnya, bisa tinggal di rumah besar di pusat kota, walaupun ia hanya bekerja sebagai pengantar bunga.
Menyenangkan melihat kelas pekerja bukan hanya menjadi pajangan dalam film, tetapi juga menjadi implikasi bagaimana cerita bergulir.
Ada pula film horor semacam Bayi Gaib: Bayi Tumbal Bayi Mati (2018), yang karakter utamanya, Farah (Rianti Cartwright) dan Rafa (Ashraf Sinclair), bisa dengan mudah membeli dan pindah ke rumah lain ketika menyadari mereka selalu diganggu di rumah sebelumnya. Film-film ini seolah-olah membuat status kaya sebagai hal yang default—terlepas dari fakta bahwa persentase orang kaya di Indonesia hanya sebesar 0,04 persen pada 2017, dan semakin parahnya kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Dalam Perempuan Tanah Jahanam, yang terjadi justru sebaliknya: Maya dan Dini diganggu karena mereka menginginkan rumah dan penghidupan yang layak.
Sebagaimana film-film Joko Anwar lain seperti A Copy of My Mind (2015) atau Gundala (2019), status ekonomi bukan hanya jadi pajangan, tetapi akan berimplikasi pada bagaimana cerita bergulir. Dalam A Copy of My Mind, Sari (Tara Basro) yang bekerja di salon murah dan Alek (Chicco Jerikho) yang membuat subtitle untuk DVD bajakan berakhir menjadi korban dari penyelewengan kekuasaan. Dalam Gundala, Sancaka (Abimana Aryasatya) dan keluarganya menjadi korban dari kesewenang-wenangan negara.
Sementara itu dalam Perempuan Tanah Jahanam, faktor kemiskinan adalah gerbang bagi film ini menceritakan kisahnya. Kemiskinan jadi alasan bagi Maya dan Dini untuk pergi ke desa terpencil. Kemiskinan, sebagai salah satu sumber penderitaan Maya dan Dini, juga jadi alasan mengapa film ini seolah menyatakan bahwa melahirkan anak ke dunia adalah suatu kesalahan besar.
Perempuan Tanah Jahanam memperlihatkan penderitaan setiap anak yang dilahirkan ke dunia. Maya, sebagai contoh, tak pernah hidup sejahtera sejak orang tuanya tak ada. Begitu pula Dini yang mengeluh bahwa punya orang tua tak membuat hidupnya lebih baik. Ada pun bayi dan anak-anak lain berakhir menjadi korban kekerasan.
Maka, menurut Perempuan Tanah Jahanam, horor itu datang dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Maya pun bukan diincar oleh hantu, tetapi oleh orang-orang desa yang menganggap keluarganya telah membawa kutukan. Sementara hantu dalam film ini sendiri tidak melakukan apa-apa yang membahayakan nyawa Maya dan Dini.
Baca juga: ‘Pengabdi Setan’: Simbol Kekerasan terhadap Perempuan
Jump scare jadi pedang bermata dua
Sayangnya, dengan fokus horor yang telah beralih dari hantu, Perempuan Tanah Jahanam masih mengandalkan teknik jump scare untuk menakuti penonton. Bahkan beberapa jump scare ada untuk memperlihatkan ancaman palsu, seperti adegan ketika Dini datang tiba-tiba mengagetkan Maya.
Memang, jump scare yang lebih banyak diasosiasikan dengan manusia ini hendak menunjukkan sumber ancaman sesungguhnya: manusia itu sendiri. Namun beberapa kemunculan hantu yang tidak berbahaya masih diiringi dengan jump scare, membuat motif cerita untuk membuat hantu itu tidak menyeramkan jadi tidak konsisten.
Perempuan Tanah Jahanam pada dasarnya punya pendekatan cerita yang serupa dengan The Witch (2015). Dalam film horor ini, praktik sihir bukanlah ancaman utama bagi Thomasin (Anya Taylor-Joy), karakter utamanya. Horor itu datang pula dari keluarganya: orang tuanya yang selalu menyalahkannya, serta agamanya yang membuatnya selalu merasa bersalah dan pantas untuk masuk neraka.
Namun, The Witch tidak banyak memanfaatkan jump scare untuk menciptakan suasana horor. Horor itu justru datang dari adegan yang berjalan lambat dan atmosfer film yang selalu suram dan penuh curiga. Lebih dari itu, yang membuat The Witch berkali-kali lebih menyeramkan adalah kedalaman dan relevansi cerita itu sendiri: penganutan agama yang jadi pedang bermata dua, keluarga yang toksik, hingga represi terhadap perempuan.
Maka, jika dibandingkan dengan film horor psikologi lain, fokus Perempuan Tanah Jahanam terlihat masih agak terbelah: antara menakuti penonton dengan kengerian cerita dan menakuti penonton dengan kekagetan.
Di atas kelemahan itu, Perempuan Tanah Jahanam adalah film horor yang dekat dengan masyarakat. Karakter-karakter yang berasal dari kelas pekerja dan motivasi mereka yang berlandaskan kekhawatiran finansial jadi bahan cerita yang menarik dan relevan. Menurut film ini, yang horor adalah hidup di dunia itu sendiri.
Foto oleh Rapi Films.