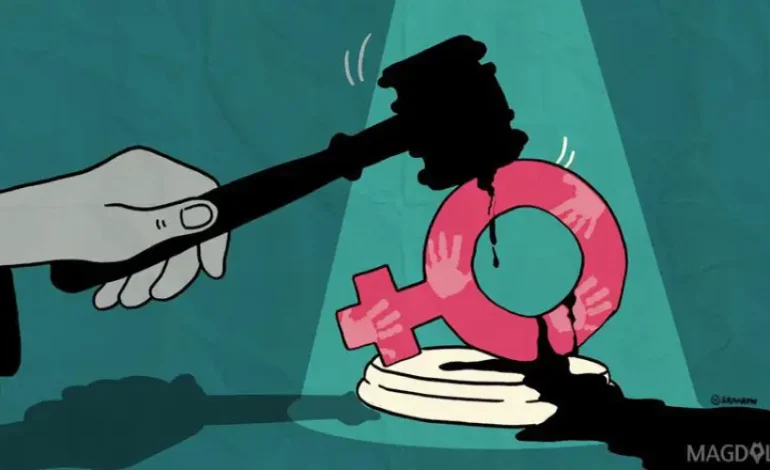Perempuan Transmigran Hadapi Beban Berlipat, Hak Dasar Belum Terpenuhi

Kendari, Sulawesi Tenggara. Heni Herlina, 29, masih bisa menertawakan situasi sulit yang dihadapinya selama tiga tahun terakhir menjadi perempuan transmigran di Desa Roda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sekitar satu jam perjalanan dari ibukota provinsi Kendari.
“Di tahun-tahun awal itu paling susah mbak, listrik belum ada, air juga belum ada, kalau mau ambil air harus jalan sekitar 2 kilometer dari rumah. Itu pun bareng-bareng dengan ibu lainnya berangkat pagi-pagi sekali,” ujar perempuan asal Tasikmalaya itu di rumahnya di Desa Roda, Desember tahun lalu, sambil menggendong anak perempuannya yang berusia dua tahun.
Pekerjaan sebagai guru honorer yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga membuat Heni akhirnya memutuskan untuk ikut dengan ibunya menjadi transmigran ke Konawe Selatan pada 2016. Berharap nasibnya menjadi lebih baik, yang didapat malah justru kebuntuan.
 Bersama dengan 118 kepala keluarga lainnya, Heni tinggal di daerah penempatan transmigrasi di Unit Penempatan Transmigrasi (UPT) Roda. Akses ke desa transmigran ini terbatas, dengan jalanan yang menanjak dan terjal berbatu, di samping jurang tanpa ada pembatas jalan.
Bersama dengan 118 kepala keluarga lainnya, Heni tinggal di daerah penempatan transmigrasi di Unit Penempatan Transmigrasi (UPT) Roda. Akses ke desa transmigran ini terbatas, dengan jalanan yang menanjak dan terjal berbatu, di samping jurang tanpa ada pembatas jalan.
Tidak terpenuhinya hak dasar atas air bersih ini berdampak banyak pada kehidupan sehari-hari. Akses yang jauh dari sumber air membuat mereka sulit untuk mencari nafkah dalam bidang pertanian. Belum lagi, dua bidang lahan dan pekarangan yang menjadi modal utama mereka, berkonflik dengan perusahaan swasta, dan belum terdistribusi dengan baik.
Akibatnya, para suami harus bekerja di luar desa, sehingga yang perempuan menanggung semua beban rumah tangga sendiri, termasuk memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga yang lain.
Ruth Indiah Rahayu, peneliti kajian gender dari Lembaga Penelitian Inkrispena, menemukan pola ketimpangan gender di lokasi-lokasi transmigrasi di mana perempuanlah yang banyak terkena dampak dari konflik dalam transmigrasi. Berbasis di Jakarta, Inkrispena merupakan lembaga penelitian yang berfokus pada bagaimana masyarakat bertahan dalam krisis dan mencari model ekonomi alternatif untuk bertahan dari sistem ekonomi yang kapitalistik.
“Dampaknya ya macam-macam, ketika terjadi sengketa tanah dengan perusahaan kelapa sawit misalnya, perempuan jadi dijauhkan oleh sumber pangan. Belum lagi karena adanya perkebunan sawit, air menjadi keruh. Ini sangat menghambat proses pengadaan pangan di rumah tangga,” ujar Ruth dalam wawancara baru-baru ini.
Ruth mengatakan bahwa para transmigran membutuhkan waktu setidaknya 15 tahun untuk membangun kehidupan yang mapan dengan mengerjakan lahan pertanian di lokasi penempatan. Namun, ketika mereka sudah berhasil mengelola lahan-lahan pertanian mereka, perusahaan-perusahaan, seperti usaha perkebunan sawit, malah merebut lahan mereka, ujarnya.
“Tidak ada perlindungan tanah maupun kehidupan dari pemerintah terhadap transmigran. Jangankan membangun infrastruktur, melindungi dari industrialisasi ekstraksi saja tidak. Yang terjadi malah pemerintah membiarkan dan memberikan izin pada perusahaan-perusahaan untuk mengambil tanah-tanah para transmigran,” jelasnya.
Akibatnya, beban berlipat pun diemban oleh perempuan karena sumber pangan dijauhkan dan lahan pertanian tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Beban ini tidak hanya berhubungan dengan waktu saja, namun tenaga yang diperlukan.
Fasilitas umum belum terbangun
Masalah air dan lahan bukan hanya satu-satunya masalah yang dihadapi oleh para transmigran di Kabupaten Konawe Selatan. Fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, juga sangat minim. Heni, yang juga merupakan kader posyandu, mengatakan distribusi obat-obatan dan praktisi kesehatan minim untuk posyandu mereka.
Akibatnya, masalah kesehatan ibu dan bayi pun mulai bermunculan terkait masalah gizi dan akses imunisasi.
“Di sini juga belum ada bidan, padahal rumah dinasnya sudah ada fasilitasnya juga lengkap. Tetapi kendalanya, akses ke daerah ini sangat sulit, jadi mungkin bidan-bidan berpikir dua kali untuk tinggal di sini,” ujar Heni.

Para ibu hamil di daerahnya hanya diberikan obat penambah darah agar si ibu tetap sehat, ujar Heni. Ketika akan melahirkan, para perempuan kesulitan untuk pergi ke rumah sakit akibat jalanan yang rusak. Hal ini dialami sendiri oleh Heni.
“Ambulansnya tidak bisa naik ke desa, karena jalannya terjal. Akhirnya dibantu oleh warga, bidannya bisa sampai ke rumah saya, lalu setengah jam kemudian baru saya melahirkan dibantu oleh ibu saya juga,” tuturnya.
Selain fasilitas kesehatan masih minim, tidak ada sekolah di desa itu sehingga anak-anak harus menumpang di gudang serba guna desa untuk proses belajar mengajar dengan pengajar orang tua.
“Pelajaran saat ini ya kurang sekali. Yang kami ingat saja yang kami ajarkan ke anak-anak. Kalau berkenan kirimlah guru pembimbing, untuk membimbing kami. Karena kami juga kekurangan tenaga pendidik jadi kami sangat tertinggal dari daerah lain dalam hal pendidikan,” ujar Heni.
Mulyani, tetangga sesama transmigran di UPT Roda, mengatakan ia khawatir dengan nasib pendidikan anak-anaknya yang seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik.
“Pendidikan di sini kacau sekali, ketinggalan pokoknya. Setiap hari cuma menulis-menulis saja. Pendidikan itu kan penting untuk masa depan anak. Anak-anak harus lebih dari kita, pintar dari kita, kalau di sini pendidikan saja begini, payah nanti,” ujar Mulyani, 30 tahun.
Baca juga bagaimana golput mengesampingkan kerja keras gerakan politik perempuan.