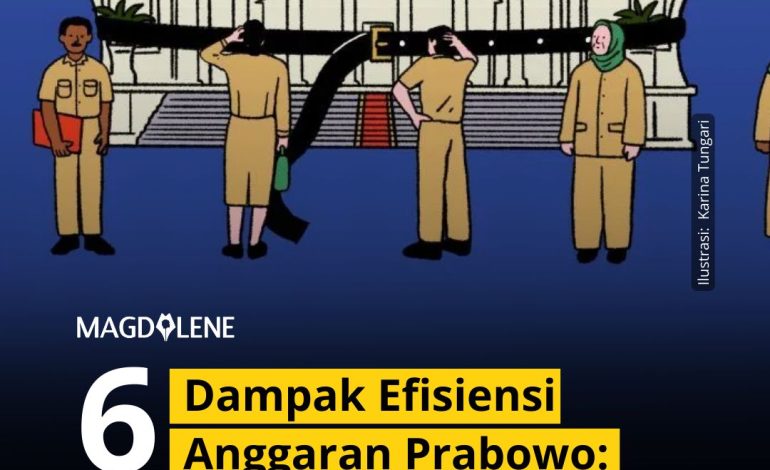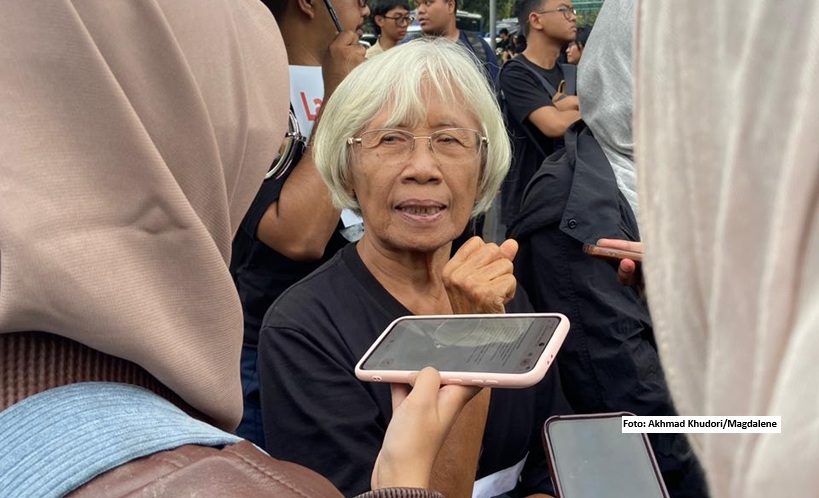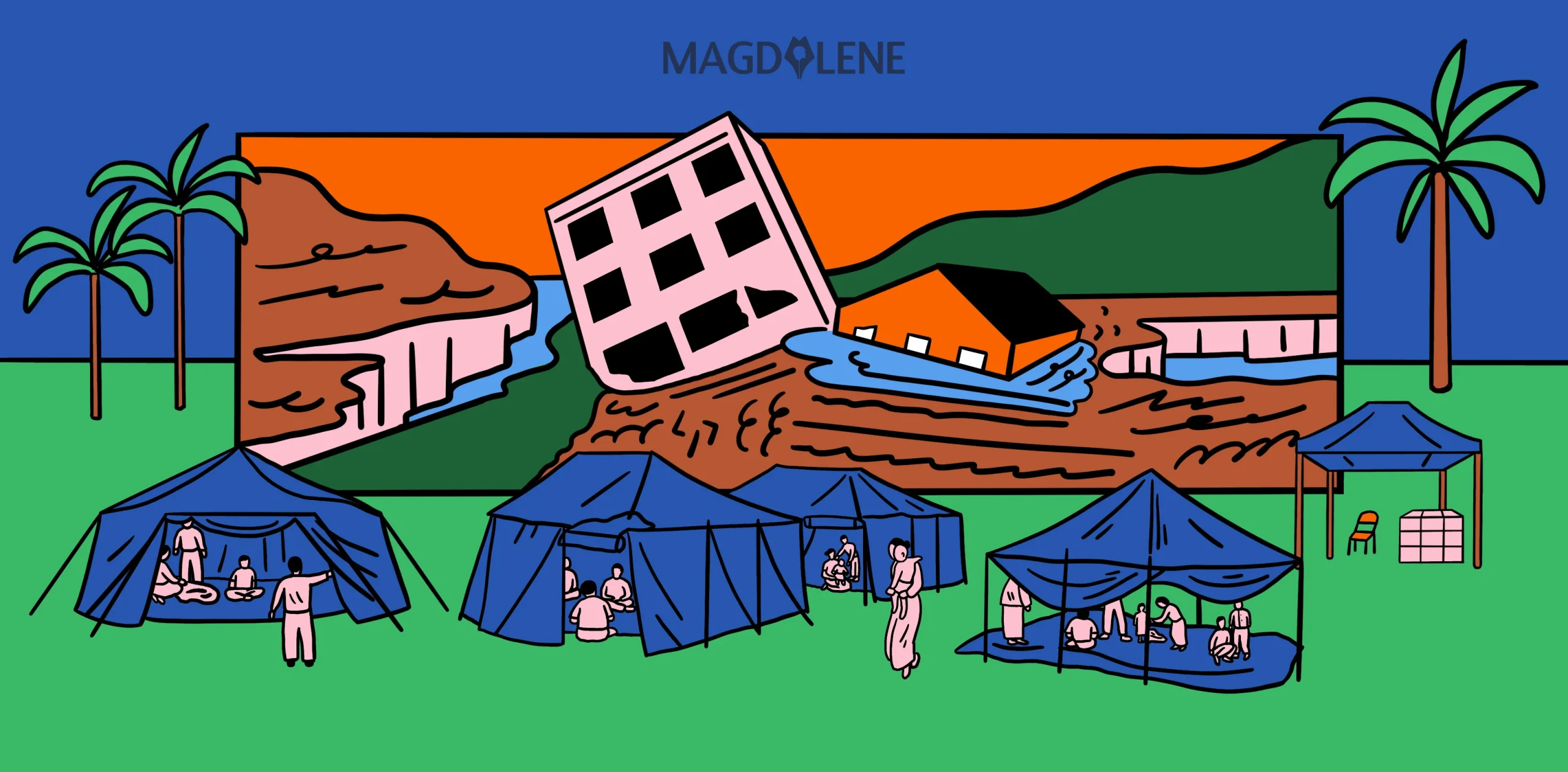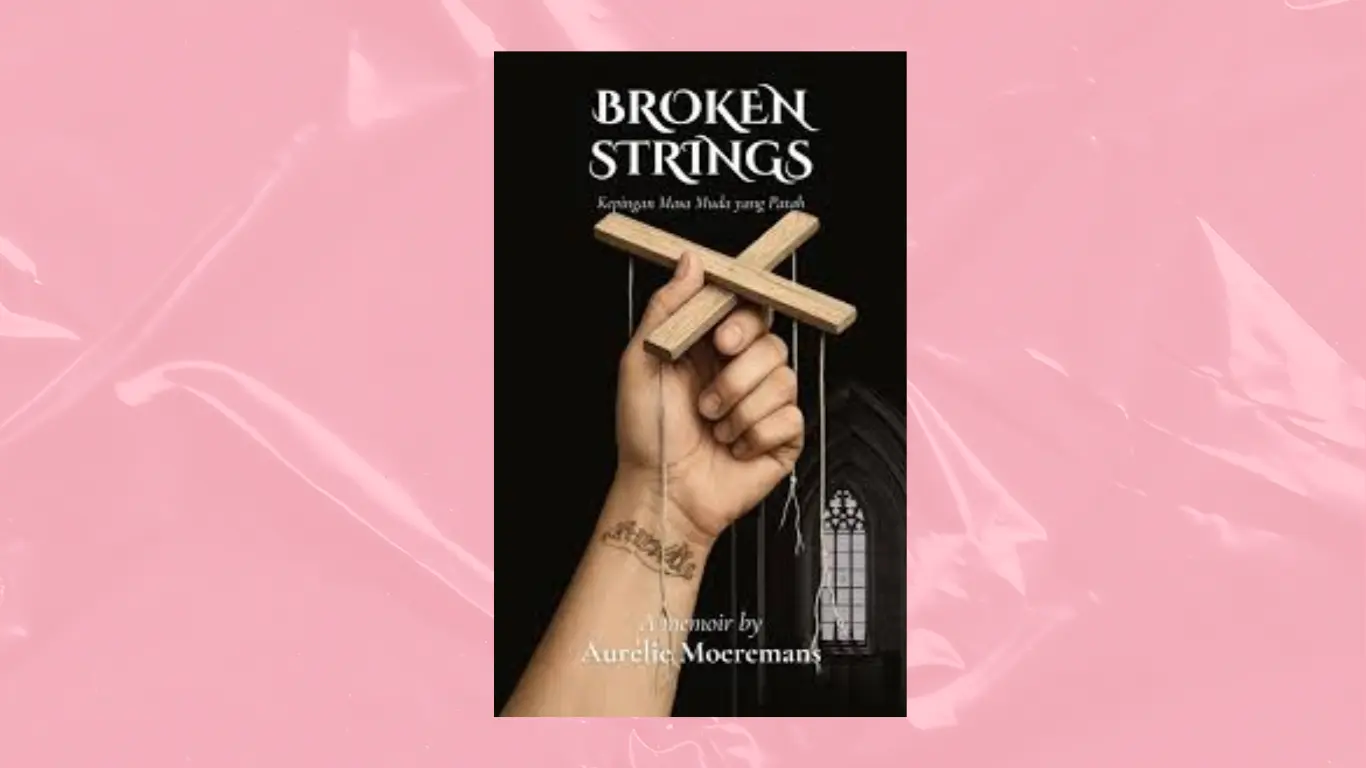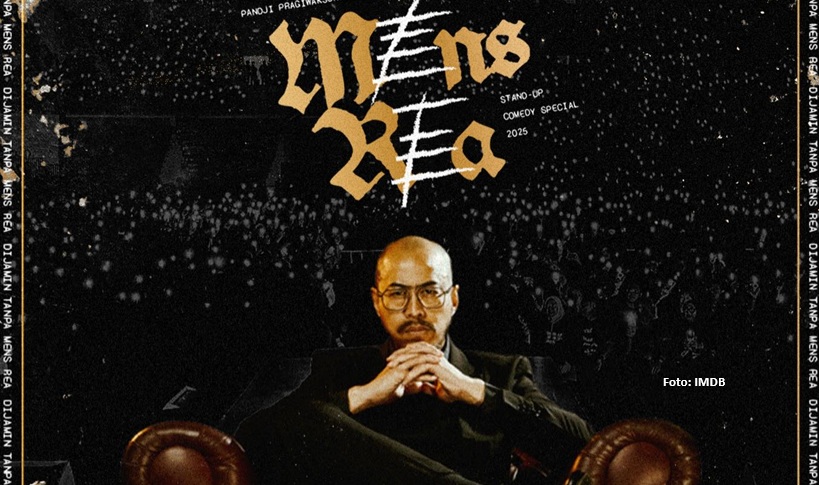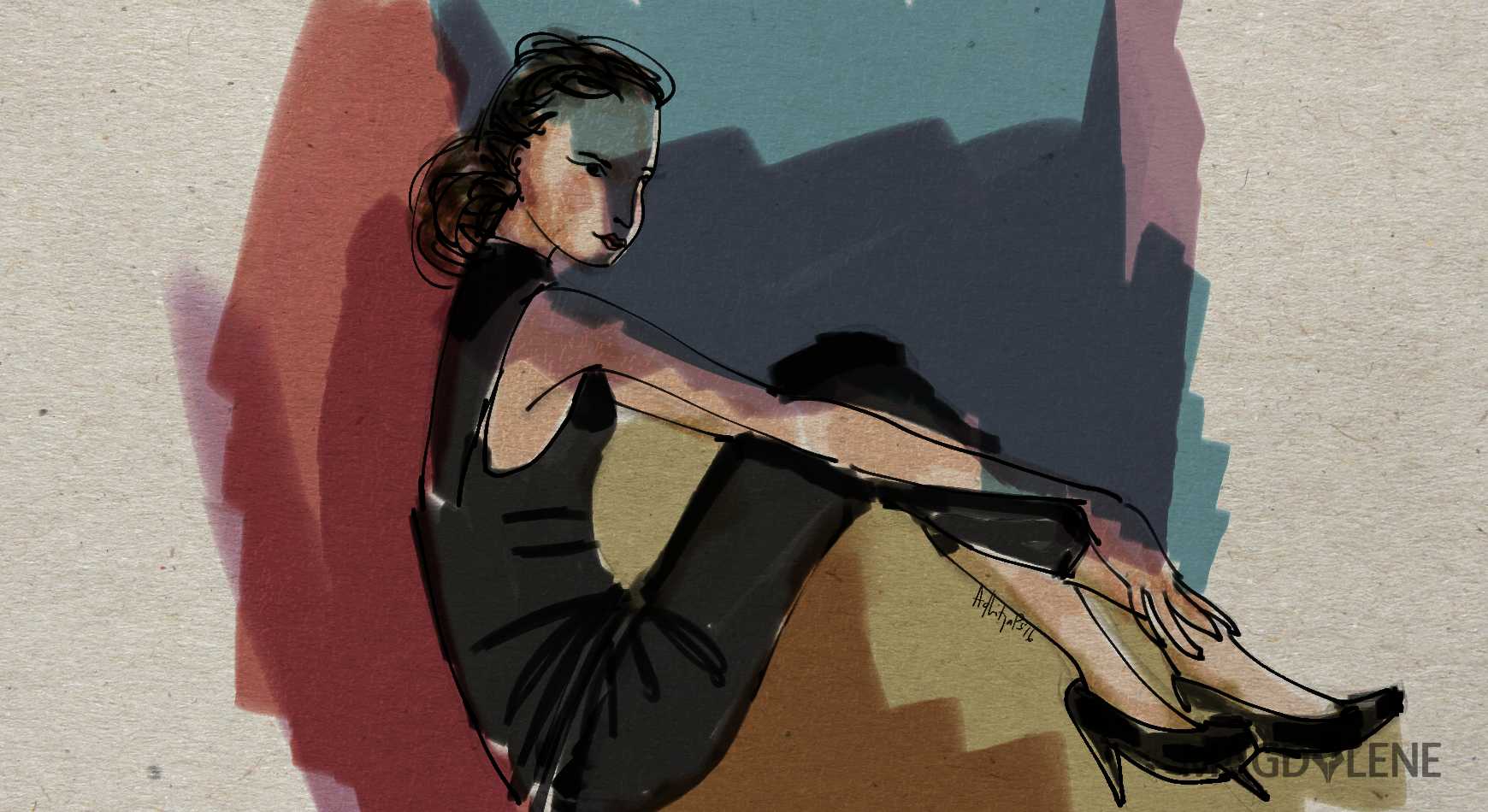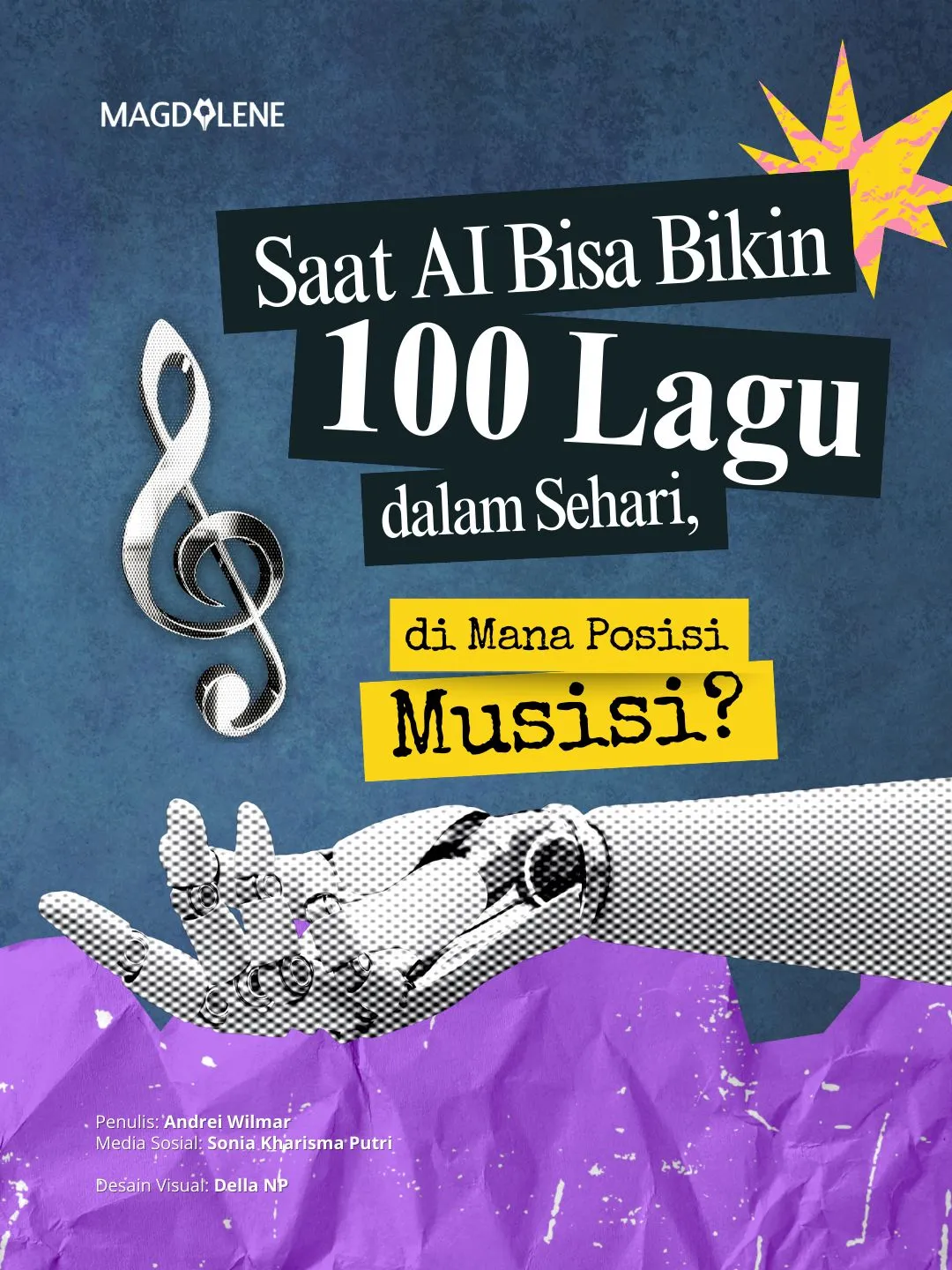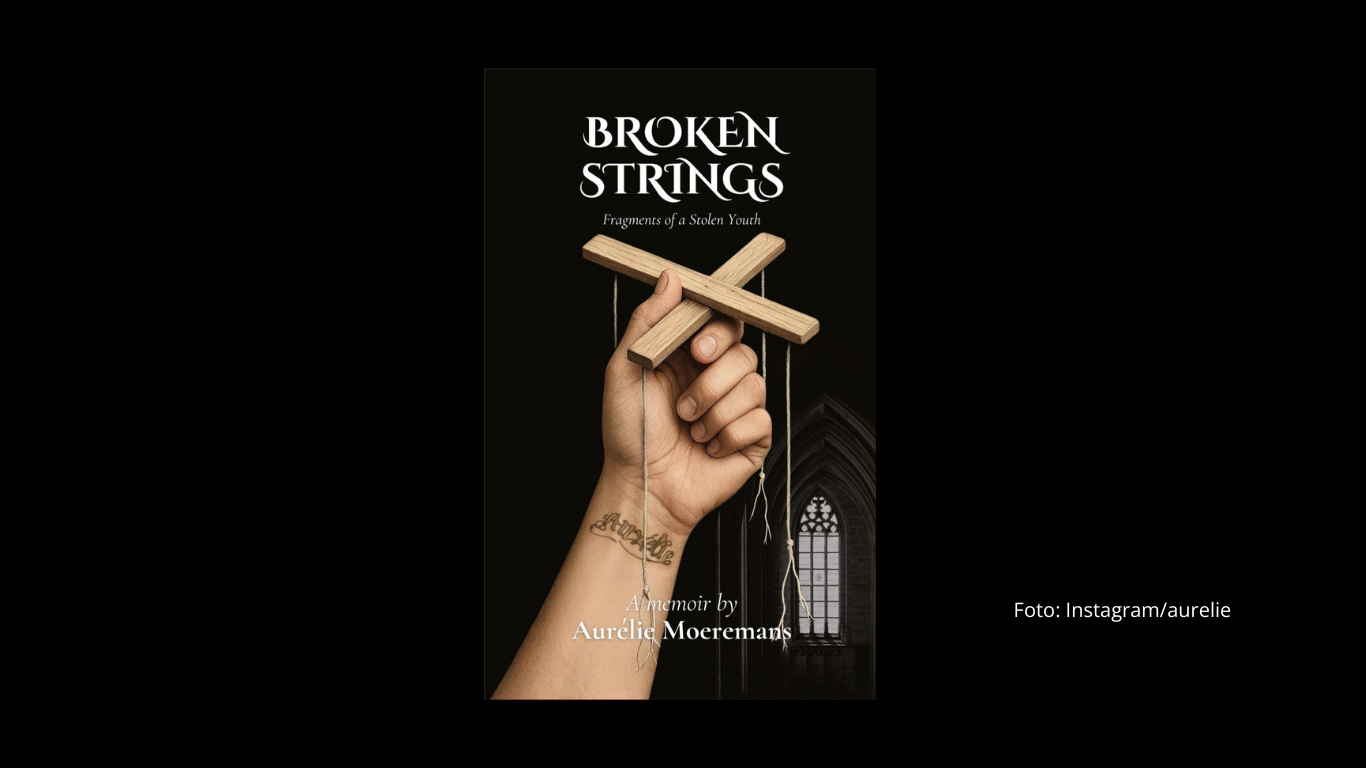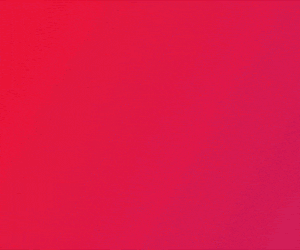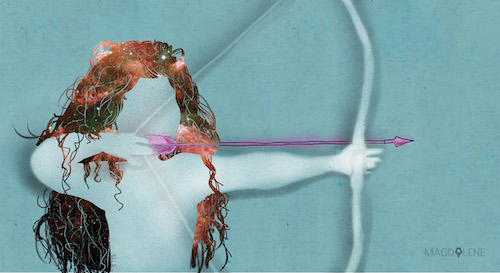Perkawinan Kopi dan Maskulinitas: Dari Simbol Jantan Hingga Citra Intelektual

Dalam satu dekade terakhir, kopi di Indonesia menempati posisi yang prominen di tengah kultur kehidupan masyarakat sehari-hari. Saking pesat pertumbuhannya, keberadaan skena kopi hampir sulit diabaikan, bahkan untuk non peminum kopi sekalipun.
Coffee shop alias kedai kopi menjamur di setiap sudut kota, dari kedai kecil di gang sempit hingga cafe berkonsep minimalis di pusat bisnis. Kopi tidak lagi sekadar minuman untuk menghilangkan kantuk, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup, identitas, dan bahkan simbol status sosial.
Di Indonesia sendiri, kedai kopi sudah ada sejak tahun 1878, sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Sejarah itu tercatat dalam tesis Melati Sosrowidjojo yang dikutip Kompas. Kedai kopi itu milik laki-laki etnis Cina bernama Liauw Tek Soen. Berlokasi di Molenvliet Oost Batavia yang sekarang menjadi Jl. Hayam Wuruk, Jakarta. Banyaknya orang Belanda yang tinggal di Batavia jadi salah satu kemungkinan faktor munculnya kedai kopi tersebut, lengkap dengan budaya nongkrongnya.
Budaya nongkrong itu, nyatanya hadir untuk laki-laki dan dunia maskulinnya. Sejak dulu, kedai kopi sudah mengalienasi perempuan, dan jadi ruang dominasi “laki-laki”. Fakta ini tak terlalu berbeda dalam konteks hari ini. Meski siapa saja bisa masuk kedai kopi dan ikut tren candu pada kafein, potret keakraban kopi dan laki-laki masih lengket.
Menariknya, dalam perjalanan ini, kopi juga mengalami pergeseran makna, terutama dalam hubungannya dengan maskulinitas. Jika dulu kopi dikaitkan dengan pria pekerja keras yang minum kopi hitam pekat di warung sederhana, kini kopi menjadi bagian dari citra pria modern yang intelektual, estetik, dan berbudaya.
Film dan budaya populer juga membantu kopi jadi simbol maskulinitas yang lebih intelektual.
Baca juga: Menelusuri Sejarah Kedai Kopi: Kenapa Dulu Perempuan Tidak Nongkrong di Kedai Kopi?
Dari Pekerja Keras Hingga Cowok Estetik: Evolusi Makna Kopi
Dulu, kopi sering diasosiasikan dengan dunia kerja keras. Utamanya dalam sinetron dan sitkom Indonesia tahun 2000-an, kopi kerap dimunculkan sebagai bagian dari kehidupan buruh, petani, atau pria yang bekerja siang dan malam. Kopi hitam tanpa gula dalam gelas kaca menjadi simbol ketahanan, kedisiplinan, dan kesederhanaan.
Namun, sekitar tahun 2010-an, makna kopi mulai berubah. Dengan munculnya third-wave coffee dan tren kopi specialty, kopi tidak lagi hanya tentang fungsi, tetapi juga pengalaman. Pria yang dulu hanya butuh kopi untuk tetap terjaga kini mulai peduli pada asal biji kopi, metode seduh, hingga teknik latte art. Kopi tidak lagi hanya dinikmati, tetapi juga dipahami.
Perubahan ini terilustrasikan secara gamblang dalam Filosofi Kopi (2015) dan sekuelnya Filosofi Kopi 2 (2017), yang mengangkat kopi sebagai simbol intelektualitas dan idealisme. Karakter Ben (Chicco Jerikho) dan Jody (Rio Dewanto) mewakili dua sisi maskulinitas: Yang satu penuh gairah dan filosofi, sementara yang lain lebih pragmatis dan perhitungan.
Melalui film ini, kopi menjadi lebih dari sekadar minuman—ia menjadi ekspresi diri, perwujudan karakter, dan bagian dari perjalanan hidup seorang pria.
Coffee Shop dan Pria Urban Intelektual
Fenomena menjamurnya coffee shop di Indonesia bukan hanya tentang meningkatnya konsumsi kopi, tetapi juga perubahan cara pria membangun identitas mereka. Kedai kopi kini menjadi ruang sosial, tempat pria bisa bekerja, berdiskusi, atau sekadar menghabiskan waktu dengan buku di tangan.
Di era media sosial, coffee shop bukan lagi hanya tempat nongkrong, tetapi juga menjadi bagian dari estetika gaya hidup. Pose dengan secangkir kopi, sudut meja kayu yang minimalis, atau candid shot saat mengetik di laptop—semua turut membentuk citra pria modern yang produktif, kreatif, dan memiliki selera. Terlebih saat work from cafe sudah jadi sesuatu yang umum, kopi perlahan-lahan menyatu dengan hustle culture.
Tren ini juga tercermin dalam berbagai film dan serial Indonesia. Dalam Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan (2019), karakter pria yang digambarkan cerdas dan berwawasan luas sering kali memiliki hubungan erat dengan kopi. Begitu juga di berbagai web series dan iklan, yang menggambarkan pria sukses dan mandiri selalu memulai harinya dengan secangkir kopi.
Baca juga: Harga Kopi Melambung Tinggi tapi Tidak dengan Gajiku
Kritik terhadap Kopi Sebagai Simbol Maskulinitas
Namun, apakah kopi sebagai simbol maskulinitas hanya sekadar fenomena budaya, atau ada dampak lain yang lebih dalam?
1. Kopi sebagai Eksklusivitas Maskulin
Sejarah kedai kopi yang didominasi laki-laki masih terus berlanjut, bahkan dalam representasi modernnya. Filosofi Kopi, misalnya, mengangkat kopi sebagai simbol pemuda berjiwa bebas, tetapi tetap dalam bingkai maskulinitas. Jarang ada film atau media populer yang menampilkan perempuan dalam narasi utama dunia perkopian, kecuali sebagai pemanis cerita atau pelengkap latar.
2. Bias Kelas dalam Budaya Kopi
Preferensi kopi sering kali menjadi alat untuk menilai seseorang. Peminum kopi instan dianggap kurang sophisticated dibanding mereka yang memesan single origin atau cold brew. Hal ini menunjukkan bagaimana kopi telah menjadi simbol bias kelas. Bukankah agak ironis jika kopi—yang dulu menjadi bagian dari kehidupan buruh—kini menjadi penanda status bagi kalangan menengah ke atas?
Baca Juga: Dengan Kuas dan Kopi, Aji Yahuti Gambarkan Perjuangan Perempuan
3. Persilangan Kopi dan Gender
Menariknya, kopi juga mengalami proses pemberian gender. Jika kopi hitam atau espresso sering dikaitkan dengan maskulinitas, minuman seperti matcha latte atau frappuccino justru lebih sering dianggap sebagai pilihan ‘The Nuruls’—slang yang datang dari kritik orang-orang queer untuk perempuan Islam yang queerfobik—dan/atau pria dengan ekspresi gender selain heteroseksual. Tidak jarang, pria yang memesan minuman non-kopi mendapat label tertentu—mulai dari “kurang jantan” hingga stereotip homofobik yang mengaitkan matcha latte dengan laki-laki gay.
Dalam artikel GQ, pada 2019 lalu, penulis Alim Kheraj menjabarkan investigasi panjang mengapa es kopi (iced coffee) diidentikkan dengan pria gay.
“Minuman seperti es vanila latte atau favoritnya Britney Spears, Frappuccino, hampir tidak dianggap kopi; Lebih seperti minuman manis, mirip makanan penutup (dessert),” tulis Kheraj. Minuman kopi campuran seperti matcha latte atau frappucino sering kali dianggap lebih feminin ketimbang kopi hitam. Pandangan biner patriarki ini meluas di tiap aspek masyarakat.
“Jadi, masuk akal jika es kopi, yang kandungan kafeinnya lebih hambar dibanding kopi hitam akan jadi antitesis dari kekuatan dan kejantanan kopi “normal”, yang dianggap milik heteroseksual,” tulis Kheraj.
Di era modern ini, kopi bukan lagi sekadar kebutuhan harian, tetapi juga bagian dari citra diri. Ia bisa menjadi simbol maskulinitas klasik yang kuat dan pahit, atau maskulinitas intelektual yang lebih estetis dan mendalam.
Namun, semakin kopi diperlakukan sebagai simbol eksklusif bagi pria atau kelas sosial tertentu, semakin ia mengalienasi kelompok lain. Jika kopi terus dikonstruksi sebagai bagian dari performativitas maskulinitas, lalu di mana posisi perempuan, queer, atau mereka yang sekadar ingin menikmati kopi tanpa embel-embel simbol sosial?
Dari Filosofi Kopi hingga tren es kopi susu di Instagram, kopi telah berkembang menjadi lebih dari sekadar minuman. Ia adalah ekspresi identitas, alat pembentukan citra diri, tetapi juga ruang yang masih menyimpan bias gender dan kelas.