Kenapa Poligami Pejabat Publik Patut Digugat
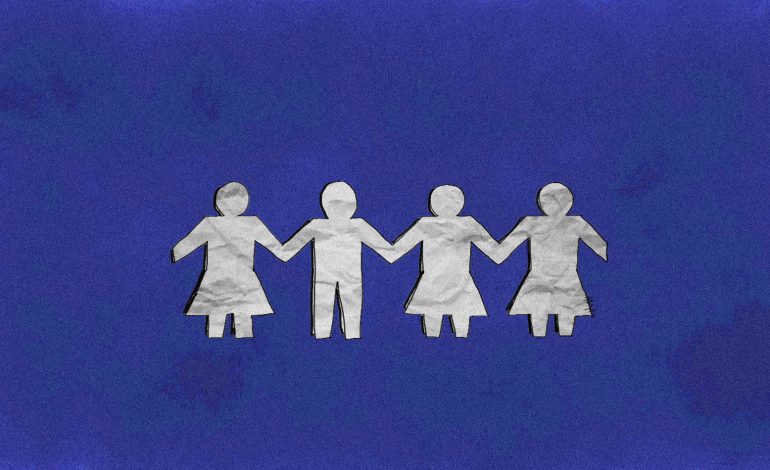
Setelah pelantikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 1 Oktober, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan kelakuan Lora Fadil, salah satu anggota DPR terpilih, yang memamerkan ketiga istrinya di acara resmi pelantikan.
Tidak sedikit perempuan yang menghujat kelakuan politikus Partai NasDem tersebut. Ia dianggap tidak menghargai perjuangan perempuan Indonesia, yang sudah seabad lebih mengumandangkan perjuangan menentang poligami. Terhitung sejak Kartini hingga sekarang ini.
Tetapi tidak sedikit juga yang membela Lora. Dari barisan konservatif hingga beberapa bekas aktivis progresif. Salah satu argumentasi yang mereka dengungkan: poligami adalah urusan privat.
Lantas, karena ini urusan privat kita tidak boleh menggugat?
Sekadar berpendapat, poligami bukan sekedar pamer atau tidak. Di sini ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu tentang bagaimana mewujudkan kesetaraan gender di republik ini, termasuk di dalamnya kesetaraan dalam perkawinan. Bukankah cita-cita berbangsa dan bernegara ini adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur?
Dalam konteks itulah, ada tiga alasan kenapa praktik poligami yang dilakukan Lora Fadil patut dipersoalkan oleh siapa pun yang menghendaki kesetaraan dan keadilan sosial di negara ini.
Pertama, sudah semenjak munculnya ide kesetaraan gender, yang mekar bersama dengan nasionalisme, poligami sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan penindasan oleh kaum perempuan.
Kartini yang memulai. Ia menyaksikan dari dekat, pada ibu kandung dan adiknya, betapa poligami menghadirkan perlakuan tidak adil dan menyengsarakan perempuan.
Tahun 1910-an, ketika organisasi perempuan mulai berkecambah, penolakan terhadap poligami makin menggema. Organisasi perempuan nasionalis-sekuler menganggap poligami sebagai bentuk ketidakadilan dalam perkawinan.
Pada Kongres Perempuan pertama pada 1928, penolakan terhadap poligami menggema sangat keras. Saat itu, semua organisasi perempuan nasionalis-sekuler mengkritik poligami dan perkawinan anak.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, perjuangan gerakan perempuan mengarah pada usaha memperjuangkan undang-undang perkawinan yang demokratis. UU tersebut diharapkan bisa menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, menghapus perkawinan paksa, dan melarang poligami.
Akhirnya, sejak 1960, Rancangan UU Perkawinan mulai bergulir. Namun, prosesnya sangat alot, terutama terkait larangan poligami. Baru pada 2 Januari 1974 Indonesia punya UU perkawinan, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974. Meski tidak melarang penuh, tetapi UU ini membatasi poligami dengan syarat-syarat yang cukup ketat.
Baca juga: Melihat ‘Qanun Poligami’ dan Aturan Terkait Lainnya Lebih Dekat
Bahkan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat, pada 2017 lalu, sudah menyatakan bahwa poligami bukan tradisi Islam, melainkan warisan zaman jahiliyyah pra-Islam, yang bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Jadi, dalam rentang waktu yang panjang, poligami sudah ditentang oleh banyak perempuan. Lewat tulisan, perdebatan kongres, aksi demonstrasi, hingga perjuangan politik lewat wakil-wakil perempuan di parlemen, bahkan dianggap salah oleh ulama perempuan. Apakah masih pantas menganggap ini sebagai urusan privat?
Kedua, perkawinan poligami tidaklah terbentuk dengan sendirinya (alamiah), melainkan terkonstruksi secara sosial oleh faktor ekonomi-politik.
Filsuf Jerman Friedrich Engels dalam The Origin of the Family, Private Property and the State, 1884, menyatakan, pernah dalam perkembangan umat manusia, belum dikenal bentuk perkawinan dan keluarga seperti sekarang. Pada masa-masa awal, ujarnya,
yang berlaku adalah perkawinan kelompok (hubungan seksual tak terbatas dalam sebuah kelompok), yang menjadi dasar terbentuknya keluarga primitif: keluarga pertalian-darah. Itu terjadi di “zaman kebuasan”.
Pada perkembangan selanjutnya, hubungan seksual itu pelan-pelan dibatasi. Seperti larangan inses atau hubungan seksual sedarah (ibu dengan anak laki-lakinya dan antara saudara sekandung), hingga selanjutnya larangan pernikahan dengan sepupu.
Setelah perkawinan kelompok itu punah, lahirlah bentuk keluarga punaluan. Sebuah kelompok saudara perempuan (sekandung atau sepupu) membentuk keluarga bersama laki-laki yang bukan saudara-sepupu mereka. Begitu juga sebaliknya. Karena ibu yang melahirkan, merawat dan melindungi anaknya hingga mandiri, maka peran sentral ibu dalam keluarga diakui. Ibu juga yang menjadi penunjuk garis keturunan.
Setelah bentuk keluarga punaluan runtuh, lahirkan bentuk-bentuk keluarga berpasangan. Mulai muncul pasangan tetap untuk jangka waktu tertentu, lama atau singkat. Awalnya, di masa perkawinan kelompok dan punaluan, seorang suami selalu memiliki istri utama di antara istri-istri lainnya. Begitu juga sebaliknya, seorang istri memiliki suami utama di antara suami-suami yang lain. Pada perkembangannya, ini menjadi perkawinan satu laki-laki dan perempuan yang menetap dan berjangka lama. Inilah dasar lahirnya keluarga monogami seperti sekarang.
Baca juga: Diskresi Pemerintah untuk Batasi Poligami
Semua perkembangan bentuk perkawinan dan keluarga itu tidak lepas dari cara manusia mengorganisasikan produksi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Dalam konteks itu, seperti dijelaskan Engels, seiring dengan munculnya pemilikan pribadi (yang umumnya di tangan laki-laki), muncul juga bentuk keluarga patriarkal. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki muncul sebagai inti dalam keluarga, penentu dalam ruang produksi, dan penguasa dalam ruang sosial/publik. Ini bersamaan dengan penyingkiran perempuan dari ruang produksi, lalu dipaksa hanya mengurus rumah tangga (domestikasi).
Dalam keluarga patriarkal, laki-laki memiliki satu atau beberapa istri (baik sah maupun pergundikan), untuk mewariskan kekayaannya pada anak-anaknya. Kekayaan terbesar jatuh pada anak laki-lakinya.
Yang menarik, seperti ditegaskan Engels, meski keluarga patriarkal mengarah pada monogami, hal itu hanya berlaku pada perempuan/istri. Sementara laki-laki, sebagai penguasa sosial dan pemilik kekayaan, tetap boleh memiliki banyak istri (poligini).
Karena itu, dalam konteks masyarakat patriarkal, poligini sebetulnya juga bentuk penegasan kekuasaan atau superioritas laki-laki. Persis seperti yang dikatakan filsuf Simone de Beauvoir, penulis buku The Second Sex: “Karena seorang istri menjadi hak milik layaknya seorang budak, seekor hewan penghela, atau sebuah benda bergerak, adalah wajar jika seorang laki-laki memiliki istri sebanyak yang ia suka.”
Jadi, tuan-tuan pengikut patriarki, memilih beristri banyak (poligini) itu bukan melulu ekspresi pilihan pribadi yang sifatnya bebas, yang tak boleh dicampuri oleh siapa pun. Tetapi dia juga terkait dengan kehendak untuk menegakkan sekaligus merawat sebuah sistim sosial yang menegaskan superioritas laki-laki sebagai gender kelas satu alias paling terhormat di dalam masyarakat. Sistim sosial ini disebut patriarki.
Ketiga, sebetulnya kalau merujuk ke UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, hukum Indonesia menganut asas perkawinan monogami. Lihat Pasal 3 Ayat 1: “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”
Memang,UU ini masih memberi celah bagi poligami, tetapi dipersempit sekali ruangnya dengan syarat-syarat yang sangat ketat.
Sementara itu, Lora Fadil akan menjadi salah satu dari 575 anggota DPR periode 2019-2024, yang tugasnya antara lain menyusun dan menetapkan UU. Bagaimana ia menjadi contoh pembuat UU yang baik, sementara dirinya mengangkangi UU yang mengurus soal perkawinan.






















