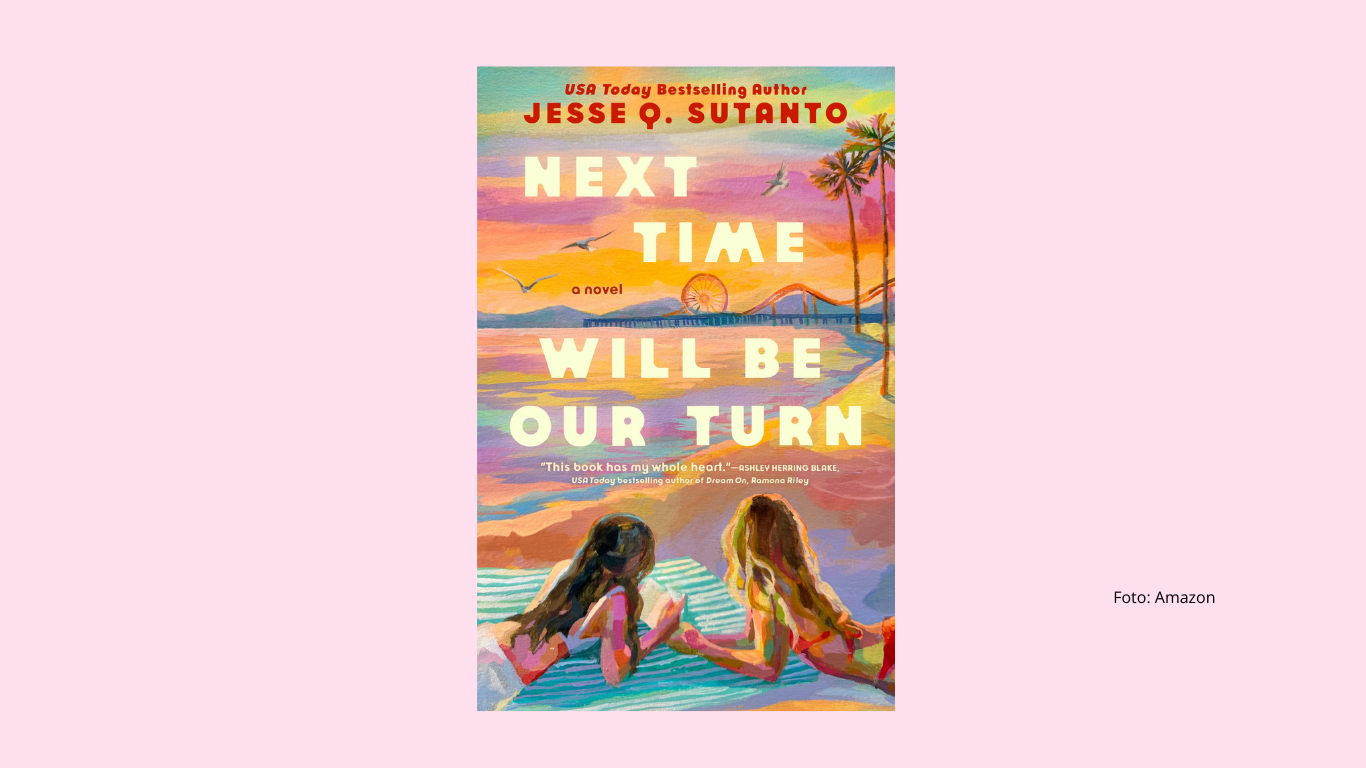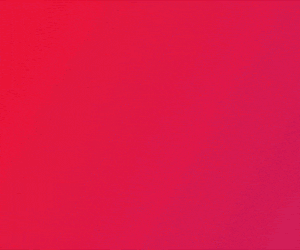Review ‘Autobiography’: Potret Militerisme di Era Kini danRepresentasi Homoerotik yang Homofobik

Peringatan: Artikel ini mengandung spoiler
“Duduk, minum kopinya.”
Suasana mencekam mulai terasa, begitu Purnawinata (Arswendy Beningswara)—mantan jenderal yang nyaleg sebagai bupati—meminta Rakib (Kevin Ardilova) menuruti perintahnya. Kalimat itu diucapkan Purna karena Rakib menyuguhkan minuman, tanpa mengetahui preferensinya. Akibatnya, pemuda itu harus meminum kopi bikinannya sendiri.
Adegan yang muncul di menit-menit pertama tersebut telah mewakilkan tagline “seram tanpa setan”, yang diusung Autobiography (2022). Dalam film panjang pertamanya, penulis, produser, sekaligus sutradara Makbul Mubarak, mengisahkan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Membuat adegan pembuka tersebut mewakilkan inti sari cerita.
Secara garis besar, Autobiography memang berangkat dari rantai kekuasaan militerisme, yang mengakar sejak pemerintahan Orde Baru (Orba). Film ini menceritakan tentang Rakib, pemuda yang meneruskan pengabdian kakek dan ayahnya untuk keluarga Purna. Selama proses kampanye, ia bertugas menjadi kaki tangan Purna, yang memperlakukan Rakib seperti anak sendiri.
Bak seorang diktator, karakteristik Purna dipotret sebagai sosok intimidatif, manipulatif, dan simbol atas pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Alhasil mengingatkan penonton dengan rezim Orba. Bahkan menimbulkan perasaan was-was selama menonton, sambil menebak langkah apa yang akan dilakukan Purna, jika mendapati sipil menghalangi prosesnya menjadi bupati.
Sebenarnya penonton akan familier dengan tindakan represif dan arbitrer seorang penguasa. Seperti strategi tertutup yang dilangsungkan Purna, untuk melakukan kekerasan terhadap Agus (Yusuf Mahardika), warga yang tidak berpihak kepadanya. Sampai kematian Agus, tak satu pun orang tahu—selain Rakib—bahwa Purna adalah dalangnya. Seorang warga malah menduga, kematian Agus berkaitan dengan sengketa lahan kopi milik ibunya, dan meminta Purna menelusuri tragedi yang menimpa pemuda itu.
Kejadian tersebut mengingatkan penonton dengan Gerakan 30 September (G30S). Peristiwa itu menyebabkan penculikan, penangkapan, dan eksekusi terhadap sipil, yang dianggap berhubungan dengan kelompok komunis. Meskipun pemerintah Indonesia menuding rakyat yang marah terhadap komunis sebagai pelaku di balik kekerasan tersebut, aktor penggeraknya tak lain tak bukan, adalah negara dan aparat militer.
Cara Purna menggerakan pemerintahan pada dasarnya tidak dapat sepenuhnya, disebut “perpanjangan tangan” Orba yang masih eksis di era ini. Mengingat Purna adalah purnawirawan, membuat militerisme begitu melekat pada kepribadiannya.
Di samping itu, Autobiography menggarisbawahi aspek lain yang melekat dengan Orba, yakni bapakisme.
Dominasi Bapakisme dan Paternalisme
Di rezim Orba, bapakisme menjadi gaya kepemimpinan Soeharto. Ideologi ini mencerminkan patriarki maupun paternalisme, lewat peran “bapak” sebagai kepala keluarga, yang memimpin, menafkahi, dan melindungi keluarganya. Atas dasar itulah Soeharto menggambarkan masyarakat sebagai anak, yang harus menghormati dan mematuhinya sebagai bapak.
Dalam Autobiography, Purna bukan hanya menunjukkan kekuasaannya dalam mengontrol pemerintahan, melainkan atas individu seperti Rakib. Walaupun Purna menganggap Rakib seperti anaknya, ia tetap menekankan bahwa Rakib harus tunduk terhadapnya—mencerminkan relasi bapakisme.
Karena itu, ketika Rakib berusaha melarikan diri, Purna mengerahkan pasukannya untuk “menjemput” pemuda tersebut. Setibanya Rakib di rumah, layaknya seorang bapak, Purna mengungkapkan kekhawatirannya akan kehidupan Rakib di luar sana. Bahkan, Purna “mengingatkan” bangunan tempat mereka menetap adalah rumah bagi Rakib.
Kemudian, relasi bapakisme juga digambarkan dalam diri Rakib, yang mengagungkan Purna. Di matanya, Purna adalah sosok bijaksana dan panutan. Terlihat ketika Rakib memercayai, dan meniru kata-kata Purna. Yaitu permintaan maaf bisa jadi hadiah.
Kekaguman Rakib kian terpancar, ketika ia dibiarkan mencicipi kekuasaan. Melihat kemurkaan Purna akibat spanduk kampanyenya yang dirusak, Rakib berinisiatif mencari tahu pelakunya. Ia memiliki kebanggaan tersendiri, ketika berhasil membawa pelaku ke hadapan Purna. Seolah berhasil menyelesaikan misi besar yang berarti, bagi sosok yang disegani—sekalipun akhirnya bertentangan dengan kehendaknya.
Kendati perbuatannya berisiko besar, keselamatan Rakib tetap terjamin. Itu merupakan buah bagi Rakib, yang mematuhi perintah Purna. Misalnya untuk menyembunyikan perilaku kejinya dari sorotan warga, maupun tidak meninggalkan pekerjaannya.
Tentu Rakib tidak lagi menikmati kekuasaannya, begitu tahu, sebagai sipil ia tidak berdaya. Tidak ada kekuatan untuk melawan penguasa seperti Purna, yang bisa melakukan berbagai cara demi mewujudkan keinginannya. Satu-satunya yang seharusnya dilakukan adalah, “menikmati” pemerintahan itu demi mengutamakan nyawa.
Seperti diucapkan ayah Rakib terhadapnya, “Dinikmati aja, yang penting sehat dan selamat.”
Homoerotik yang Homofobik
Selain kelamnya kepemimpinan militerisme dan relasi bapakisme, Autobiography turut menampilkan adegan homoerotik–ketertarikan seksual antara karakter berjenis kelamin yang sama. Ini ditampilkan lewat karakter yang melakukan perilaku homoseksual.
Salah satunya ketika Rakib dan Agus sedang dalam perjalanan menuju kediaman Purna. Dengan alasan harus fokus menyetir, Rakib meminta Agus mengambilkan kerikil di pedal remnya. Kemudian, Rakib tersenyum–menyiratkan kemenangan dalam diri, ketika Agus menunduk menghadap ke selangkangannya. Setelah itu Rakib menyentuh bahu Agus, meyakinkannya agar tidak takut terhadap Purna.
Namun, adegan tersebut ditampilkan begitu saja, tanpa mengidentifikasi karakter Rakib sebagai homoseksual. Dengan menggambarkan relasi antara laki-laki di luar batas ekspektasi gender, mungkin Makbul ingin menampilkan Autobiography sebagai film progresif.
Sayangnya, aspek progresif yang diharapkan bertolak belakang dengan scene homoerotik lain yang juga muncul. Yakni ketika Purna mengajarkan Rakib menggunakan senapan, maupun saat sang jenderal memaksa memandikan Rakib. Kedua aksi tersebut justru meninggalkan ketakutan, serta ketidaknyamanan dalam raut wajah Rakib.
Penggambaran perilaku homoseksual antara Purna dan Rakib mengingatkan saya, dengan penelitian yang dilakukan penulis Patrick Schuckman. Dalam riset berjudul Masculinity, the Male Spectator and the Homoerotic Gaze (1998), Schuckman melihat hasrat homoseksual dalam adegan homoerotik sering kali disangkal. Yaitu sebagai hukuman, tindakan mendominasi, atau penindasan.
Hal itu kemudian menjelaskan, dibandingkan perilaku homoseksual, penonton lebih menganggap adegan Rakib dimandikan Purna sebagai ganjaran dari upayanya meninggalkan rumah—sekaligus menunjukkan otoritas Purna atas tubuh Rakib. Begitu pula ketika Rakib belajar menggunakan senapan. Seolah kengerian itu muncul dari figur Purna yang otoritatif dan mendominasi.
Di sisi lain, kedua adegan Purna dan Rakib sekaligus mencerminkan homofobia. Perilaku tersebut tersampaikan lewat ekspresi Rakib yang tidak nyaman, meninggalkan kesan bahwa homoseksual itu menyeramkan dan perlu ditakuti. Seketika Rakib lupa atas perilaku homoseksualnya, yang dilakukan terhadap Agus.
Permasalahannya belum selesai di situ. Autobiography juga tidak menjelaskan makna scene homoerotiknya lebih lanjut, yang melanggengkan homohisteria.
Homohisteria mendeskripsikan ketakutan dianggap homoseksual, karena perilakunya dinilai atipikal gender. Kondisi itu kemudian menuntut laki-laki untuk menyesuaikan diri dengan norma gender, demi membuktikan maskulinitasnya.
Autobiography memperlihatkannya lewat karakter Purna. Selain tidak mengidentifikasi Purna sebagai homoseksual, perempuan berperan sebagai objek afirmasi heteroseksualitas—yang adalah tameng dari homohisteria.
Tepatnya ketika istri Purna menghubungi via video call, yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Purna seorang heteroseksual. Kendati demikian, wajah istri Purna tidak begitu ditampilkan. Hal itu menggarisbawahi, peran sang istri bersifat sekunder dan tidak memiliki identitas.
Adegan itulah yang menerangkan, mengapa Autobiography tidak bermasalah dengan isu gender. Film ini tidak mengakui homoseksualitas, dan berlindung lewat penyalahgunaan karakter perempuan.
Soal penyalahgunaan karakter perempuan, sebenarnya tidak hanya disampaikan oleh Autobiography. Point Break (1991) melakukan hal serupa pada karakter Tyler (Lori Petty). Ia adalah mantan pacar Bodhi (Patrick Swayze), yang berpacaran dengan Johnny Utah (Keanu Reeves).
Namun, adegan homoerotik antara Utah dan Bodhi mengimplikasikan perubahan relasi yang tidak pasti, entah sebagai musuh, teman, atau pacar. Yang jelas, peran Tyler lama-lama terpinggirkan. Ia hanya menjadi bayangan di balik hasrat Utah dan Bodhi terhadap satu sama lain.
Selain merugikan perempuan, homohisteria justru membahayakan homoseksual yang semakin rentan dan termarginalkan di masyarakat. Keberadaan mereka tidak begitu diinginkan, sebagaimana masyarakat secara naluri menerima heteroseksual.
Kondisi tersebut juga membuat laki-laki mengkhawatirkan persepsi masyarakat akan menilai mereka gay, hanya karena tidak sesuai dengan stereotip gender. Kesalahpahaman ini mendorong laki-laki gay menyesuaikan perilakunya dengan norma gender, untuk membebaskan diri dari tudingan masyarakat tentang seksualitasnya.
Alhasil, saya jadi mempertanyakan slogan “seram tanpa setan” dalam film ini. Apakah penggunaannya sekaligus untuk melanggengkan persepsi terhadap homoseksual?