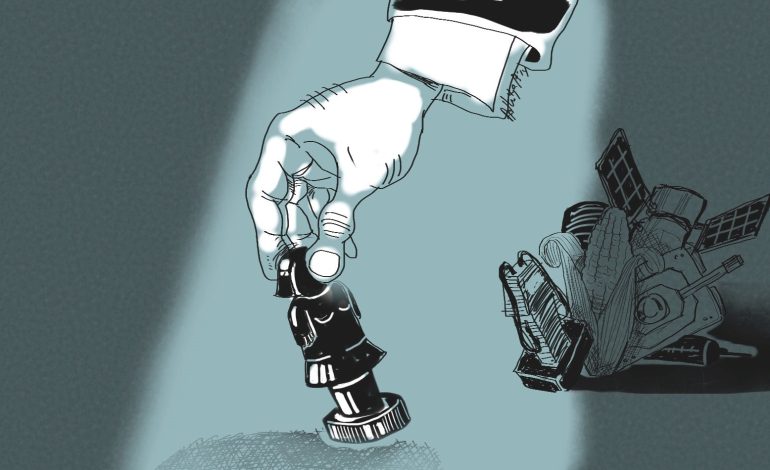“The Normal Heart”, LGBT dan Pemilu

Saya sedang menonton The Normal Heart dua hari yang lalu ketika pernyataan berikut menyentuh saya, “Mengapa mereka membiarkan kita mati?”
Pertanyaan itu menggarisbawahi rasa frustrasi kelompok gay karena mengalami diskriminasi.
Drama televisi tersebut, disutradarai oleh Ryan Murphy dan didasarkan pada pertunjukan teater Larry Kramer dengan judul sama, menggambarkan pasang surut (sebagian besar surut) yang dihadapi komunitas gay di New York pada puncak krisis HIV-AIDS pada awal 1980an.
Saat itu, penyakit sistem kekebalan tubuh manusia tersebut bahkan belum diidentifikasi sebagai AIDS, namun lebih dikenal sebagai “kanker gay.” Orang-orang gay di Amerika Serikat sebetulnya telah sangat didiskriminasi bahkan sebelum epidemi tersebut, namun penyebaran HIV/AIDS semakin meningkatkan homofobia dan stiga terhadap homoseksualitas.
Para pemain, Mark Ruffalo, Matt Bomer yang sangat seksi dan Julia Roberts, menampilkan akting yang kuat.

Karakter Ruffalo, Ned Weeks, adalah aktivis gay yang vokal dan keras kepala, dengan gaya kampanye konfrontasional yang seringkali bertubrukan dengan kekasihnya Felix Turner (Bomer), dan kolega-koleganya.
Roberts bermain sebagai Dr. Emma Brookner, seorang dokter berkemauan keras yang merawat banyak orang dengan AIDS – sebagian besar pria gay – bahkan ketika sebagian besar rumah sakit pada saat itu menolak melakukannya.
Murphy berhasil menggambarkan perjuangan para protagnis dalam upaya menjadikan AIDS sebuah isu prioritas di tengah persepsi arus utama negatif yang menyebutnya penyakit gay pada saat itu.
Sekarang ini, pemerintah AS jelas telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan perawatan publik untuk orang-orang dengan HIV/AIDS dan dalam menghapus diskriminasi melawan mereka. Pada Januari 2010, misalnya, AS menghapus status HIV sebagai salah satu faktor untuk dipertimbangkan dalam memberikan visa perjalanan.
Bagaimana dengan Indonesia? Meski telah ada perbaikan dalam hal perawatan medis dengan, misalnya, program cakupan rawatan kesehatan yang menyertakan orang-orang dengan HIV/AIDS (ODHA), diskriminasi masih meluas.
Hal ini dapat dilihat dari perilaku dan pernyataan publik para pemimpin politik. Tahun lalu, angota legislatif Wirianingsih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan bahwa pasien-pasien AIDS seharusnya diberi sangsi bukannya diberi obat-obatan gratis.
Tahun lalu, pada periode Oktober-Desember saja, sedikitnya ada 8.624 pasien baru yang didiagnosa dengan HIV.
Diskriminasi bukan saja terjadi atas ODHA, tetapi juga terhadap mereka yang mengalami kesulitan karena ‘berbeda’.
Diterbitkan pada 17 Juni, sebuah laporan gabungan PBB yang berjudul “Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report”, menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh para lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia, dari seorang transgender yang ditolak bekerja di sebuah salon kecantikan karena “terlihat seperti perempuan” sampai seorang mahasiswi yang terbuka dengan homoseksualitasnya yang dipermalukan oleh dosennya di depan kelas karena tampak “feminin.”
Menjelang pemilihan presiden 9 Juli, tidak diragukan lagi masih banyak warga Indonesia yang mendapat pelecehan karena termasuk kelompok LGBT. Meski suara mereka berarti untuk membuat pemimpin berkuasa, mereka masih memiliki representasi nol di kantor publik.
Dua tahun lalu, aktivis hak asasi manusia sekaligus aktivis gay terkemuka, Dede Oetomo, disoraki oleh para anggota parlemen – yang barangkali mendapatkan kursinya berkat suara dari kelompok LGBT juga sebetulnya – saat proses seleksi anggota komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena statusnya sebagai pria gay yang terbuka.
Tidak ada satu pun dari kedua kandidat presiden, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, yang menyoroti pentingnya perawatan HIV/AIDS dalam kampanye mereka; apalagi bagaimana menghapus jenis diskriminasi melawan orang-orang LGBT. Sayang sekali mereka tidak menyoroti isu tersebut, padahal ada kabar bahwa salah satu kandidat memiliki anak yang homoseksual.
Sebenarnya ada setitik momen penuh harap dari saya sebagai pria gay, ketika mantan jenderal militer Prabowo mengakui putranya sebagai perancang busana dalam debat calon presiden yang ditayangkan televisi. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Namun, negara ini perlu lebih dari sekedar momen mengharukan, yang beberapa pihak mengecamnya sebagai aksi politik semata.
Saya sangat, sangat ingin menjadi optimistis dengan harapan-harapan saya bahwa lebih banyak anak muda Indonesia akan memberikan dukungan mereka terhadap hak-hak LGBT di waktu yang akan datang, tidak hanya di media sosial, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Namun mengingat banyak individu terkemuka termasuk politisi yang menutupi status homoseksualnya (meski saya tidak menyalahkan mereka), jalan kita masih panjang.
Sementara itu, seperti pertanyaan yang dilontarkan dalam The Normal Heart, apakah kita akan dibiarkan mati? Saya sudah muak dengan hanya bertahan, terus terang saja. Kali ini, saya ingin tumbuh berkembang.
Tentang Amahl S. Azwar
Amahl adalah seorang penulis yang terbuka dengan status gaynya dan tinggal di Bandung, Jawa Barat. Noveletnya, ‘Husbro’, akan ditampilkan dalam ‘LGBTIQ’- Love-Gifted-Bravery-Trust-Imagination-Quest’, buku berisi serangkaian novella yang merupakan kolaborasi dengan penulis-penulis lain, termasuk Hendri Yulius.