UU Cipta Kerja Tak Ciptakan Lapangan Kerja, Perkuat Oligarki
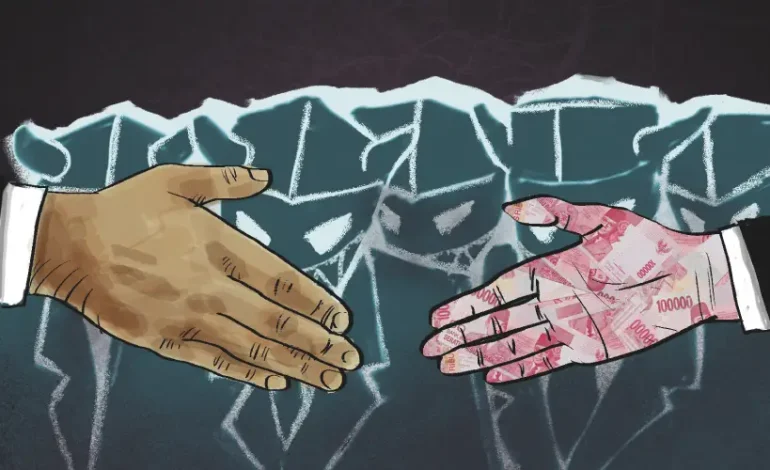
Pandemi COVID-19 dan demonstrasi tak menyurutkan langkah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkankan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Meski sempat berjanji untuk menunda, pemerintah justru mengebut penyusunan aturan kontroversial ini, bahkan saat DPR sedang reses.
Proses politik yang problematik dan tidak transparan tentu mengundang pertanyaan. Gelombang penolakan terus muncul menyusul pengesahan UU Cipta Kerja yang memukul mundur hak pekerja. Pemerintah berdalih bahwa UU Cipta Kerja diperlukan untuk memulihkan perekonomian. Asumsinya, pelonggaran aturan kerja akan menarik investor masuk, yang kemudian mendorong pembukaan lapangan kerja.
Celakanya, RUU Cipta Kerja tidak akan berdampak banyak untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang terjadi justru regulasi ini akan memperkuat oligarki atau politik mempertahankan kekayaan lewat lobi-lobi dan korupsi.
Hanya menguntungkan kalangan atas
Pemerintah mengklaim desain kebijakan ini memudahkan investasi. Namun, revisi ratusan aturan dalam Omnibus Law tidak akan mendatangkan kemudahan, tetapi justru ketidakpastian di tengah resesi . UU Cipta Kerja juga solusi salah sasaran karena tidak menyentuh akar masalah utama yang menghambat bisnis di Indonesia, yaitu korupsi.
Pemerintah berargumen bahwa investasi adalah kunci dalam menciptakan lapangan kerja. Sayangnya, data realisasi investasi mengindikasikan bahwa akar masalah pengangguran di Indonesia bukan karena kurang suntikan modal. Analisis ekonom Faisal Basri pun menyebutkan bahwa performa investasi di Indonesia cukup baik, terbukti dari investasi yang terus naik, tetapi serapan tenaga kerja justru turun.
Untuk menjawab mengapa investasi di Indonesia tidak berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan perbaikan nasib pekerja, yang perlu dipertanyakan bukan bagaimana menarik investasi, tetapi ke mana modal mengalir.
Baca juga: Magdalene Primer: Setelah UU Cipta Kerja Disahkan
Data terbaru Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengonfirmasi bahwa sektor manufaktur yang pernah menjadi andalan kini digantikan oleh sektor jasa atau sektor tersier yang makin mendominasi. Sektor jasa yang paling banyak menyerap modal adalah konstruksi, transportasi, telekomunikasi, dan jasa keuangan/perbankan.
Aliran modal di Indonesia punya dampak berbeda dalam dua arah: Merugikan ke bawah dan menguntungkan ke atas. Bagi pekerja kelas menengah ke bawah, tren ini cenderung merugikan.
Pertama, sektor jasa merupakan industri padat modal, bukan padat karya – artinya minim penyerapan tenaga kerja.
Kedua, kualitas relasi kerja di sektor jasa –terutama bagi pekerja yang minim keahlian dan daya tawar pasar— juga cenderung buruk mengingat sektor ini sarat dengan penggunaan outsourcing, penggunaan tenaga kontrak tanpa batas, dan pemecatan sewaktu-waktu. Perlindungan hak pekerja juga minim, salah satunya karena gerakan serikat pekerja dalam sektor ini tidak sekuat di sektor manufaktur.
Salah satu contohnya adalah Gojek dan Grab. Perusahaan aplikasi disorot sebagai primadona dalam menggenjot investasi di Indonesia serta diklaim sebagai solusi membuka lapangan kerja.
Klaim demikian mengabaikan fakta bahwa bisnis ini mengaburkan relasi kerja antara pengemudi dan perusahaan. Akibatnya, pekerja tidak punya perlindungan hukum. Kontrak dapat diputus sewaktu-waktu, pemasukan tidak pasti karena tarif dan kebijakan perusahaan terus berubah, serta tidak ada kesempatan untuk upskilling atau peningkatan keahlian.
Akhirnya, investasi yang terus naik tidak berdampak bagi perbaikan lapangan kerja baik secara kuantitas maupun kualitas di Indonesia. Apalagi jika kita bandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, rata-rata pendapatan riil bulanan yang diterima pekerja di Indonesia masih paling rendah. Sebaliknya, yang paling diuntungkan dari kenaikan investasi di Indonesia adalah aktor kelas atas, terutama konglomerat dan politikus yang telah mendominasi tatanan kelas sosial-ekonomi di Indonesia.
Aliran modal di Indonesia merugikan ke bawah dan menguntungkan ke atas. Bagi pekerja kelas menengah ke bawah, tren ini cenderung merugikan.
Dana investasi paling banyak mengalir ke proyek konstruksi infrastruktur dan bangunan, serta sektor listrik, gas, air, telekomunikasi, transportasi, dan keuangan.
Di luar sektor jasa, investasi di Indonesia juga mengalami kenaikan di sektor komoditas perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Investasi di bidang kehutanan bahkan mengalami peningkatan lebih dari 15 kali lipat dalam lima tahun (2014-2019).
Bisnis dalam sektor-sektor tersebut identik dengan perilaku memburu rente (rent-seeking). Alih-alih mengandalkan penciptaan nilai tambah baru (capital-generating) melalui produksi dan penggunaan tenaga kerja, bisnis pemburu rente mengejar keuntungan dengan cara utama melakukan produksi serta memanipulasi penyaluran sumber daya ekonomi lewat transaksi politik dengan penguasa, misalnya kongkalikong tender, perizinan, atau konsesi lahan. Akibatnya, oligarki makin menguat.
Indikasi suburnya oligarki terlihat dari harta kekayaan lima puluh konglomerat terkaya di Indonesia yang justru meroket saat ekonomi negara melambat. Sebagian besar pundi-pundi mereka berasal dari bisnis pemburuan rente dan koalisi dengan politisi.
Pertalian kepentingan antara pejabat dan konglomerat juga makin erat karena hampir separuh anggota DPR periode 2019-2024 adalah pengusaha, pemegang saham, komisaris, hingga direksi di lebih dari seribu perusahaan yang mendominasi aliran investasi di Indonesia.
Kebijakan yang mendatangkan petaka
Kondisi ini bukan berarti investasi di sektor jasa selalu buruk. Tidak dimungkiri, aliran modal memang diperlukan untuk pembangunan. Yang menimbulkan bahaya adalah pertumbuhan aliran modal yang dilandasi pelemahan kelas pekerja dan penguatan oligarki.
Berbagai kajian dan diskusi publik telah menjabarkan poin-poin Omnibus Law yang berdampak buruk bagi pekerja. Namun, penciptaan Lembaga Pengelola investasi (LPI) yang diatur dalam UU Cipta Kerja belum banyak disoroti.
Baca juga: Ahli: UU Cipta Kerja Tak Jamin Investasi, Rusak Lingkungan Hidup
Lembaga baru ini digadang akan memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengontrol aliran dana investasi. Akuntabilitas dan audit lembaga ini tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi oleh kantor akuntan publik.
Dewan pengawas dan pimpinan lembaga ini akan diisi oleh pejabat, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dipilih oleh presiden.
Hadirnya lembaga seperti ini patut dikhawatirkan karena justru mengendurkan kontrol terhadap politik oligarki yang melandasi alokasi dana investasi, apalagi jika LPI ini menjadi sumber “dana non-budgeter” yang rawan korupsi dan minim transparansi.
Disahkannya UU Cipta Kerja makin melengkapi berbagai revisi aturan yang sebelumnya telah dilakukan untuk melemahkan rakyat dan menguatkan oligarki.
Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU KPK tahun lalu, disusul dengan revisi UU Minerba awal tahun ini yang memperkuat jejaring oligarki tambang.
Omnibus Law kluster lingkungan makin memudahkan eksploitasi dan penguasaan lahan. Alih-alih memperbaiki ekonomi, Omnibus Law justru memperparah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dengan cara mengonsolidasikan kekuatan oligarki.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.






















