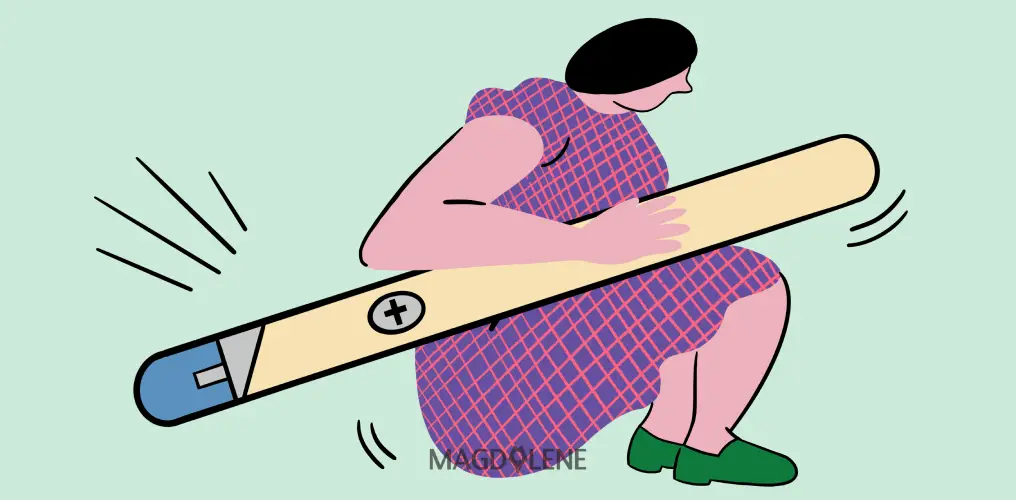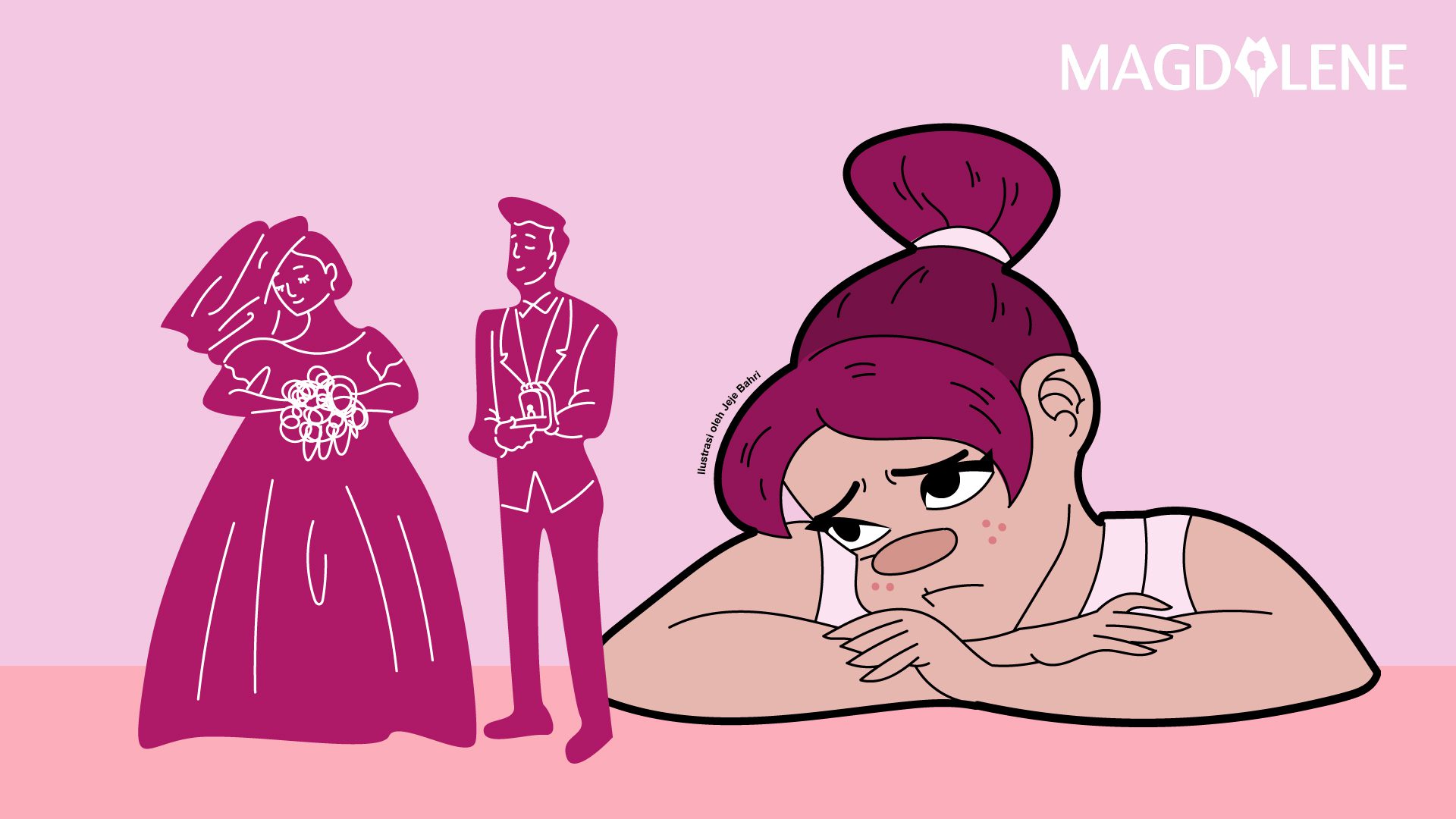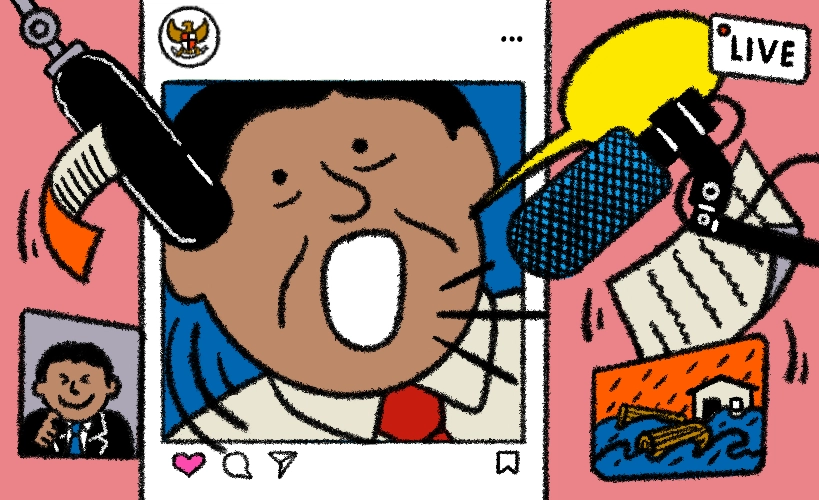Kalau Mau Bahas Misdinar Korban Kekerasan Seksual, Harus Bahas Gereja Juga

Walaupun saya ini bagian dari Katolik NaPas, alias yang muncul di gereja ikut menuh-menuhin tempat misa hanya saat Natal dan Paskah, sedikit banyak saya mengikuti perkembangan Gereja Katolik zaman now.
Kelihatannya perkara kekerasan seksual yang menimpa anak-anak yang menjadi misdinar atau putra putri altar di Gereja Herkulanus, Depok, Jawa Barat tidak begitu menjadi perhatian banyak media mainstream. Saya hanya menemukan beberapa artikel terkait kejahatan seksual tersebut, termasuk salah satunya di laman media yang dikelola oleh komunitas Gereja Katolik.
Sebenarnya berita ini tidak hanya menyedihkan tapi juga menyakitkan, karena kejahatan yang terjadi dengan rentang waktu yang tak pendek kok baru ketahuan. Apalagi ada beberapa saksi yang menyebutkan bahwa sebenarnya kasus ini sudah pernah diungkap oleh salah satu korban, beberapa tahun lalu, tapi kemudian senyap saja. Diselesaikan secara “kekeluargaan”, katanya, dan gereja pun menutup rapat-rapat kasus ini.
Saya paham, amat sangat paham bahwa banyak yang masih menjaga citra gereja sebagai tempat suci umat Kristiani beribadah. Tempat ibadah yang seharusnya tidak mungkin menjadi tempat terjadinya kejahatan seksual. Itulah mengapa tak banyak yang membahas kasus ini—tepa selira, kata orang Jawa.
Padahal penyangkalan semacam ini jelas salah, bukan preseden baik bagi kehidupan gereja yang sehat. Dan pengungkapan kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan gereja ini tujuannya jelas, bukan untuk menjelek-jelekkan gereja, tapi untuk duduk bersama, mencari solusi agar kejadian-kejadian seperti ini tak lagi terulang di masa depan.
Rumah aman bagi keluarga?
Dalam surat yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus pada 2 Febuari 2015, beliau menyebutkan bahwa gereja adalah rumah aman bagi keluarga-keluarga. Gereja akan memegang komitmen untuk menempuh segala upaya baik demi melindungi anak-anak dan anggota keluarga mereka yang rentan.
Hal ini sebagai bagian dari reformasi tubuh gereja Katolik secara keseluruhan dengan gerakan konkret yang disebut Ecclesia simper reformanda, atau gereja harus selalu memperbaiki diri. Agar citra gereja sebagai menara gading yang tak tersentuh tak lagi ada. Karena sejatinya fungsi gereja adalah menjadi pelayan umat, bukan sebaliknya.
Surat tentang gereja sebagai rumah aman bagi keluarga-keluarga itu terbit bukan tanpa alasan. Sejak tahun 1950an, gereja Katolik sebenarnya sudah menghadapi skandal kejahatan seksual. Skandal-skandal yang terjadi baru menjadi konsumsi media di dekade 1980an, itu pun terkonsentrasi pada kejadian yang terjadi di beberapa negara saja. Hingga memasuki tahun 2000, skandal kejahatan seksual yang terjadi tak lagi tabu dibahas, berbagai kejahatan seksual yang terjadi mulai diungkap oleh publik.
Baca juga: Menjadi Seorang Katolik Indonesia Setelah Pengungkapan Skandal Seks Gereja di AS
Tapi tetap saja kasus-kasus yang ada hanya menjadi konsumsi kalangan terbatas. Pun berakhir menjadi sekadar gosip saja, ketimbang wacana terbuka yang intens untuk dijadikan pelajaran bersama. Atau gereja cenderung diam dan menutupi kasus yang ada, melakukan pembiaran. Biasanya gereja hanya akan memindahtugaskan pelaku kejahatan di daerah lain dengan tujuan agar si pelaku melakukan menyadari kesalahannya dan melakukan pertobatan.
Tapi sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Di tempat tugas yang baru mereka bukannya bertobat, tapi justru mengulangi kejahatan yang sama dengan korban baru. Kalau sudah begini, kan, repot, hanya menambah panjang daftar korban.
Itulah mengapa pada Desember 2013, Vatikan membentuk satu komisi baru, yaitu Komisi Kepausan bagi Perlindungan Anak dan Orang Dewasa Rentan sebagai wadah penanganan bagi para korban kejahatan seksual yang dilakukan kaum klerus (mereka yang menerima janji imamat, dalam kalangan Katolik dikenal juga dengan julukan kaum berjubah). Komisi ini bertugas merangkul serta menyembuhkan korban atas trauma yang mereka alami.
Lalu di tahun 2014, Paus Fransiskus secara khusus mengadakan pertemuan dengan para korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh sebagian kaum klerus (biarawan). Itulah latar belakang terbitnya surat Paus Fransiskus yang menyebutkan bahwa seharusnya gereja adalah rumah aman bagi keluarga-keluarga.
Di Indonesia sendiri hal tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Kerja Sama Bina Lanjut Iman-iman Indonesia (BKBLII). Komisi ini mendampingi para korban kejahatan seksual yang terdiri dari seminaris (frater), suster, dan orang awam. Sementara ini sudah ada 56 korban tercatat dalam data mereka.
Dengan catatan tambahan, ada 33 pelaku yang berasal dari kaum klerus yang berada di rentang usia 28-52 tahun. Dan ada 23 pelaku di luar kaum klerus, atau disebut juga sebagai kelompok nonreligius (salah satunya seperti pembina misdinar di Gereja Herkulanus, Depok) yang melakukan kejahatan seksual saat berusia 15-65 tahun. Sedihnya lagi, kasus-kasus kejahatan yang mereka lakukan, baru terungkap setelah lebih dari satu dekade terlewati.
Terbayang kondisi para korban kejahatan seksual di Gereja Herkulanus yang saat ini sedang diusut. Pelaku sudah melakukan kejahatan tersebut selama rentang waktu 20 tahun. Jika 20 tahun lalu ada korban yang berusia 9 tahun, lalu baru saat ini kasus ini diangkat dan diusut, berarti korban saat ini sudah berusia 29 tahun, dan baru mendapat konseling setelah 20 tahun terlewati.
Apa enggak terlambat banget? Padahal trauma akibat kasus kejahatan seksual adalah salah satu trauma yang tak bisa sembuh seumur hidup.
Kasus-kasus seperti ini benar-benar harus menjadi pembelajaran publik agar mereka mau bersuara jika mengalami ketidakadilan. Bukan hanya diam saja, enggan mengungkapkan karena takut dianggap menjelek-jelekkan citra gereja. Dan pendiaman serta pembiaran hanya akan berujung pada cluster baru dengan deretan korban yang terus bertambah.
Baca juga: Menemukan Kedamaian dalam Layanan Ibadah Daring
Gereja tanpa umat, kiamat
Gereja jelas harus memperbaiki diri juga, menanggapi hal ini sebagai cambuk, sebagai pengingat bahwa memang selama ini ada yang rusak dalam hierarki gereja. Bukan terus menutup-nutupi dan menutup mata terhadap kejahatan kaum klerus hanya demi menjaga citra gereja agar terlihat baik, suci tanpa noda.
Alasannya sederhana sih, gereja tanpa umat, apa artinya? Agama tanpa pengikut, apa fungsinya? Kalau gereja tak mau memperbaiki diri, mengimplementasikan Ecclesia simper reformanda, maka kehancuran gereja hanya tinggal menunggu waktu saja. Toh akhir-akhir ini jumlah ateis di kalangan kaum muda di seluruh dunia tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Kenapa?
Karena kaum muda saat ini sudah mulai muak dengan yang namanya agama. Mengingat beberapa tahun terakhir ini perang atas nama agama menghancurkan banyak kehidupan di atas bumi. Dan mereka sudah mulai muak dengan tingkah laku kaum tua yang mabuk agama, menganggap agama adalah segalanya, melupakan citra sebagai manusia yang seharusnya mengasihi sesama.
Gereja jelas harus memperbaiki diri, menanggapi kasus kekerasan seksual sebagai cambuk dan pengingat bahwa memang selama ini ada yang rusak dalam hierarki gereja.
Dalam kasus kejahatan seksual, sebetulnya ada kemiripan. Ada relasi kuasa antara yang tua dan yang muda, tak hanya relasi kuasa antara imam dan umat. Kesombongan para kaum tua yang memakai relasi kuasa mereka dengan semena-mena jelas tak bisa dibiarkan terus menerus.
Apalagi gereja dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk merusak kehidupan masyarakat. Belum lagi, jika gereja benar-benar memperhatikan Injil, pasti paham betul bagaimana Yesus menempatkan anak-anak (yang paling banyak menjadi korban kejahatan seksual kaum klerus dan nonreligius) dalam pangkuan-Nya.
Perkara keselamatan anak-anak ini disinggung beberapa kali dalam Injil. Bahkan di Injil Matius (18:6) disebutkan dengan terang, “Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut.”
Anak-anak adalah kepolosan, kemurnian, dan sesuatu yang murni semacam itu, tak seharusnya menjadi korban nafsu sesat orang-orang yang memanfaatkan jubah mereka dan mengingkari janji imamat. Apalagi orang-orang yang mengabdikan diri sebagai bagian dari gereja, berkeluarga, tapi tetap merusak kehidupan seorang anak. Tanpa mau bercermin, seandainya anak-anaknya yang menjadi korban kejahatan yang sama, bagaimana perasaannya?
Inilah pentingnya kenapa kasus kejahatan seksual di tempat ibadah harus diusut dan dibuka secara terang benderang. Bukan malah ditutupi dan dianggap tidak ada dengan alasan tabu, tak sopan, tak patut. Karena kejahatan yang paling keji adalah kejahatan yang dilakukan di tempat ibadah, di mana doa-doa dan kidung pengharapan dilagukan dengan penuh ketulusan.