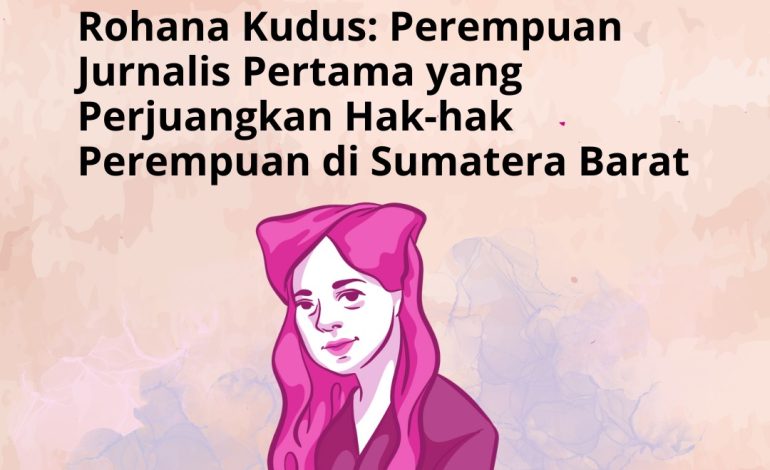Suatu Hari di Toko Barang Antik

Aku melewati warung kopi tempat kita pertama kali bertemu. Tahukah kau? Tak ada lagi kopi dijajakan, tapi cuma kumpulan barang antik yang dipenuhi debu. Meja dan kursi yang dulunya jadi tempat kita berbincang, telah disulap jadi jam tua dari kayu jati cokelat.
Orang bilang, barang antik adalah makhluk paling malang. Mereka dibuang setelah disayang. Tapi setelah disimpan di toko barang antik, setidaknya mereka punya rumah baru, bukan? Toko barang antik memberi kesempatan pada kenangan kita agar tak tercecer di jalan.
Aku tersenyum, mengingat sajak terakhir yang kau buat untukku di warung kopi itu.
Masing-masing tak punya cukup imajinasi untuk menerka bagaimana kabar kekasihnya..
Masing-masing juga tak pernah punya nyali untuk sekadar bertanya, bagaimana keadaannya?
Tak juga bisa dimengerti, bagaimana mungkin impian bisa memisahkan dua orang yang pernah begitu jatuh cinta?
Bagaimana mereka dipisahkan oleh satu alasan tak nyata, oleh jalan yang beda?
Kisahku ini memang usang.
Walau kini si perempuan ada di tempat bermatahari,
Dan mungkin si laki-laki ada di tempat yang kini sedang berbulan,
Dada mereka dirasuki rasa lega.
“Kami tetap di bawah langit yang sama… “
Tak perlu sama-sama tahu jalan pulang,
Mereka masih bisa menertawakan kehidupan.
Baca juga: Membunuh Kekasih
Kau menulis sajak tersebut dengan di atas selembar kartu pos. Pada bagian belakang kartu pos, terdapat lukisan indah Sungai Seine. Sejak itu aku tahu, kau berhasil meneruskan cita-citamu ke sana.
Aku berbahagia untukmu. Sungguh. Walaupun membaca sajakmu membuatku sesak.
Aku menyesal tak bisa membalas sajakmu hingga kini. Aku merasa tak pernah cukup berani menghadapi kemungkinan akan jatuh cinta lagi.
Aku melangkah ke sisi lain di toko barang antik. Ada banyak piringan hitam hingga piano yang entah masih bisa berfungsi atau tidak. Sang pemilik toko menghampiri, bertanya apakah aku sedang mencari sesuatu.
Aku tersenyum malu karena sudah memasuki tokonya bukan untuk membeli sesuatu. Aku masuk ke sana hanya untuk mengenang seseorang.
Setelah pamit pada si pemilik toko, aku beranjak ke arah pintu keluar. Tapi tiba-tiba sesuatu menghentikan langkahku. Aku sungguh tak percaya dengan apa yang kulihat.
Dari jendela yang buram karena guyuran hujan, aku melihat sosokmu. Kau berdiri di luar sana sambil memegang payung dan memandangiku. Sejak kapan kau berdiri di sana?
Sudah terlanjur beradu tatap, tak mungkin aku menghindarimu. Kini kita malah berada di salah satu meja di teras toko barang antik itu. Kau masih sama, meminum cokelat hangat kesukaanmu.
“Aku tak menyangka bisa bertemu kau lagi,” kataku memecah situasi hening. Agak canggung.
“Kau sengaja ke sini untuk beli barang antik?” tanyamu. Aku diam sejenak karena ragu.
Aku menggeleng pelan, terlalu takut berkata jujur.
“Tidak sengaja lewat, dari toko sebelah untuk beli susu anak,” kataku sembari menunjukkan kantong plastik yang sejak tadi kubawa.
Setelah mendengar jawabanku, kau diam. Aku tak berani memandang wajahmu saat itu. Aku merasa begitu nahas terjebak di situasi seperti ini.
“Bagaimana Paris?” Aku tak mau kita terus diam, jadi kulontarkan lagi pertanyaan basa-basi.
“Indah.”
Baca juga: (Bukan) Rumah untuk Semua (1)
Aku mengangguk sembari berpikir keras, harus apakah aku setelah ini? Aku merindukanmu, tapi dengan keadaan seperti ini? Rasanya aku ingin berlari menjauh.
“Kau sudah menikah?”
Aku tak langsung menjawab. Kini aku memandang lurus matamu yang juga tengah memandangku. Tatapanmu begitu datar, sehingga aku tak bisa menerka apa isi kepalamu. Apakah kabar ini akan membuatmu terluka atau justru membuatmu bahagia?
“Perempuan tak punya cukup kesempatan untuk belajar sepertimu, bukan?” kini aku merasa bodoh dengan jawaban seperti itu.
Aku tahu ini serupa tuduhan yang mungkin akan membuatmu marah. Padahal aku tahu, kau membuat upaya cukup keras untuk bisa belajar di Paris. Aku tahu, kau membuat banyak pengorbanan untuk bisa menggapai cita-cita di kota yang kau sebut indah tadi. Ya, termasuk mengorbankanku.
Tapi…tidak. Bukan kau yang seharusnya marah. Itu aku. Aku tak punya kesempatan sepertimu karena aku adalah perempuan. Aku perempuan kampung yang terlahir tidak punya tempat untuk beranjak dan berkembang. Orang-orang menggariskanku menjadi istri yang patuh, mengasuh anak, dan mulia jika melayani keluarganya sepenuh hati. Aku terlahir sebagai manusia yang tidak punya banyak pilihan sepertimu. Aku tak diberi ruang untuk punya cita-cita besar sejauh dirimu.
Itu sebabnya kau bisa seperti sekarang ini sedang langkahku terhenti di pelaminan. Itu sebabnya kau meninggalkanku. Itu sebabnya aku adalah ibu rumah tangga, sedang kau adalah orang yang semakin terpelajar, bukan?
Kau kini menunduk sehingga aku tidak bisa melihat jelas air mukamu. Kau diam lagi dan aku ingin menangis. Aku ikut menunduk, melihat bajuku yang kusut. Baru kusadar, rambutku pun diikat dengan sembrono. Ya, aku adalah perempuan seperti ini sekarang, Jodi.
Baca juga: Parasit di Inang Muda
Aku paham. Kita harus mengakhiri pertemuan ini.
“Aku harus pergi, kau tetap di sini?” kataku setelah menghela napas panjang.
Kau mengangguk dan tersenyum kecil. Aku mulai beranjak melangkah jauh.
“Rima…” aku berhenti melangkah dan menoleh ke arahmu. Aku sedikit terkejut kini kau ada di hadapanku. Kau menggapai rambutku dan mulai mengikatnya ulang.
“Kau perempuan… dan kau selalu hebat,” ujarmu seraya menuntaskan perkara rambutku. Aku memandangi semburat senyum yang ada di wajahmu. Usai itu, kau mengambil payungmu dan meninggalkanku.
Ya. Aku perempuan yang tak punya banyak pilihan, bahkan hanya untuk mengejarmu agar bisa kembali kupeluk.