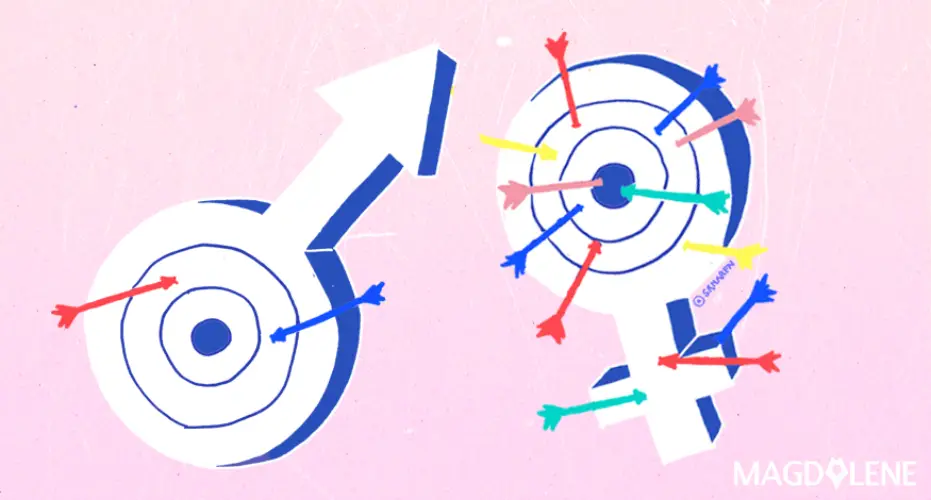(Bukan) Rumah untuk Semua (2)

(2)
Shinjuku dingin sekali malam itu. Suhu udara sekitar satu dua derajat. Ribuan manusia kedinginan mondar-mandir di bawah papan-papan neon dan lampu-lampu jalanan Tokyo yang memantul di atas trotoar yang cukup dilalui dua buah mobil dengan nyaman. Mereka berjalan baik dalam kelompok maupun sendiri-sendiri. Dibungkus mantel-mantel tebal berpotongan tajam, yang dilengkapi oleh sarung tangan dan sepatu-sepatu lars, manusia-manusia itu cekikikan dan tertawa-tawa, mengobrol dan menggoda satu sama lain; berbeda sekali dengan reputasi orang Jepang yang terlanjur beredar: muka serius dan selalu membungkuk dalam-dalam setiap satu menit. Di sini mereka tampak rileks, nongkrong dengan teman-teman sejawatnya selepas pulang kerja. Ini pertengahan Desember. Libur akhir tahun sudah sebentar lagi, dan Shinjuku mulai juga dipenuhi orang-orang Eropa, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan pelancong lainnya.
Seorang perempuan Indonesia berjalan membelah keramaian. Perawakannya tinggi, kulitnya hitam manis, rambut hitamnya terpangkas sependek telinga, pipinya dipoles merah muda dan bibirnya merah. Mantel kuning kunyitnya tergantung lurus menjuntai dari bahunya yang tegap. Tangannya tidak terbungkus apa-apa, sehingga sesekali dia harus mendekatkan tangannya ke depan mulut untuk dihembuskan napas hangat sembari dia berjalan. Perempuan itu berbelok ke kanan, ke gang yang mengecil sebelum bercabang menjadi dua. Di antara jalanan bercabang itu, di seberang penginapan murah City Lonestar, adalah sebuah bangunan pendek, di mukanya melambai-lambai bendera pelangi sepanjang rentangan tangan penuh yang ditancapkan di atas sebuah pintu kayu. Di bagian atas terbaca sebuah papan: “Bar Gold Finger”. Perempuan itu melangkahkan sepatu lars cokelatnya, mendorong pintu kayu hingga menganga ke dalam dan melangkah masuk.
Bar lesbian paling terkenal seantero negeri matahari terbit itu masih lumayan sepi. Putri sengaja datang di waktu itu. Dia cuma ingin minum sedikit dan menertawakan orang-orang yang menyanyi-nyanyi buruk dengan perangkat karaoke yang ada di situ. Dia berencana pulang setelah menghabiskan satu atau satu setengah jam. Maklum, hari itu masih Kamis. Dia masih harus kerja satu hari lagi sebelum bisa bangun siang dan menonton drama Korea seharian. Namun, sepuluh menit setelah Putri mendapatkan minumnya, dia hampir menumpahkan gelasnya dari konter bar setelah seorang perempuan Cina-Indonesia yang menggigil kedinginan melangkah masuk.
Sofia.
Mereka berdua cuma bisa sama-sama terpana. Pintu kayu terbanting menutup dan penjaga bar yang melihat adegan reuni dadakan itu menjulurkan leher untuk mengamati lebih dekat apa yang bakal terjadi. Memang mereka berdua terlihat paling mencolok di bar kecil itu – Putri yang jelas-jelas sawo matang sudah pasti bukan orang Jepang, sementara Sofia yang salah tingkah, kedinginan, dan membawa-bawa ransel besar, sudah pasti turis, meski matanya sipit.
“Ya ampun!” jerit Putri akhirnya, sambil melangkah maju dan memeluk gadis itu, yang sebetulnya masih membeku karena kedinginan dan terkejut. Sofia masih mematung ketika Putri menarik bangku di sebelah bangkunya dan menuntun dia ke situ. Ia duduk sambil memandang wajah Putri lekat-lekat.
“Astaga, Putri, kamu bikin pangling.”
Memang betul. Putri yang dulu berdiri agak kikuk karena dia lebih tinggi dari rata-rata manusia Indonesia kini berdiri tegak penuh percaya diri. Rambutnya kini demikian pendek, sangat kontras dengan rambut panjangnya yang dulu hampir mencapai pinggang. Matanya bersinar-sinar. Dari dulu Putri sudah cantik. Sekarang, bukan hanya dia sadar akan hal itu, namun juga dia sangat nyaman dengan gaya dirinya, tak peduli apakah dia sedang memakai baju gembel rumahan maupun sedang berdandan rapi.
“Kamu tinggal di sini? Memang aku sempat dengar kamu pergi belajar ke sini.” Sofia akhirnya menurunkan ransel dari pundaknya dan memesan minuman. Tubuhnya mulai menghangat dan ia sudah pulih dari rasa kaget. Sofia masih terlihat hampir sama dengan ketika dia SMA: rambut hitam tipisnya masih diikat ke belakang, hanya sedikit lebih pendek. Kini, dia tampak nyaman dengan jaket tebal sepinggang, celana jins biru muda, dan sepatu lars hitam.

“Ya, aku tinggal di sini. Aku bekerja sebagai programmer di perusahaan artificial intelligence. Puji Tuhan, tahun lalu aku diangkat jadi kepala tim infrastruktur mereka,” kata Putri. Dia bicara selayaknya orang yang memiliki karier memuaskan dan pencapaian-pencapaian yang mereka inginkan – kebanggaan yang tidak dibuat-buat namun tidak ada kesan angkuh. Putri selalu menghitung berkat-berkat dan keberuntungan dan kebaikan yang diterimanya, dan tidak pernah merasa hidupnya adalah murni hasil kerjanya seorang diri. Karena itu dia bercerita tentang dirinya dengan tulus.
Sofia mengangguk. Dia tidak terlalu terkejut, karena Putri memang dari dulu pintar. Anak itu tidak akan menemukan kesulitan di mana saja. “Bagaimana denganmu? Sampai kapan di Tokyo?”
“Aku hanya berlibur di sini satu minggu. Hari Sabtu aku pulang ke Jakarta.”
“Di Jakarta sibuk apa?”
“Aku membantu Mama menangani salah satu anak usahanya yang mau bangkrut. Tidak menyenangkan sama sekali. Aku memang suka bisnis, tapi jika kerjaku cuma membereskan kekacauan yang dibuat pegawainya, atau memegangi kepala usaha-usaha yang toh akan modar, itu sangat menyedihkan,” kata Sofia. Dia bukan orang yang suka mengeluh, sebetulnya. Tapi memang begitu kenyataannya. Putri meringis penuh simpati. Minuman tiba di hadapan mereka berdua.
“Bagaimana dengan Papamu? Mungkin bekerja dengannya lebih menyenangkan,” kata Putri, mencoba menawarkan perspektif. Seingatnya, Sofia dan bapaknya sangat dekat. Tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi.
“Aku dan Papa tidak bisa seperti dulu, Put. Ingat waktu dia marah besar dan menelepon ibumu untuk memberi tahu dia bahwa kita pacaran? Itu sebetulnya dia lakukan setelah menaruh ekstasi dan ganja di laci tempat tidurku, menelepon polisi untuk menggeledah kamarku dan menangkapku. Aku menghabiskan sepuluh hari di kurungan kantor polisi, dan dibebaskan setelah aku diperkosa sipir untuk ‘dikembalikan ke jalan yang benar’. Sejak itu, aku tinggal bersama Mama dan tidak lagi dengan Papa. Aku tidak pernah ke Amerika. Aku belajar bisnis dengan Mama.”
Putri menutup mulutnya dengan telapak tangan, tidak menyangka nasib Sofia setragis itu. Sofia buru-buru menenangkan. “Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa menceritakan kejadian ini semua, bahkan ke orang asing sekalipun. Ketika masih trauma aku dibantu oleh komunitas orang yang pernah menjadi korban kekerasan, dan kini setelah sembuh aku pun membantu orang-orang lain. Aku telah menceritakan pengalaman burukku ke banyak orang. Tadinya ke satu, dua, dan tiga orang, lama-lama di mimbar di hadapan ratusan peserta. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah berdamai dengan itu semua dan justru menemukan kekuatan untuk dibagi ke perempuan-perempuan yang pernah diperkosa,” Sofia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan. “Aku juga sudah memaafkan Papa.”
Pada momen itu, Putri pula dibikin pangling. Sofia dulu begitu tak acuh. Namun dari deritanya gadis itu bangkit, dan membantu yang lain bangkit juga. Perempuan itu lebih kuat daripada rupanya: gadis Cina berperawakan kecil yang sejak lahir dimanja uang. Sofia telah mengenal kepahitan dari uang dan kuasa, dan meski sekarang masih memiliki keduanya, gadis itu memahami maknanya lebih baik daripada kebanyakan orang.
Sofia telah mendirikan lembaga-lembaga yang bekerja untuk perempuan dan anak. Dia mengajak orang-orang desa untuk mendirikan sekolah-sekolah dan klinik-klinik murah yang memutarkan keuntungan cukup untuk biaya operasional berkelanjutan. Dia menaruh uang di perusahaan-perusahaan rintisan yang digawangi perempuan-perempuan lebih brilian dari dirinya, dan mendorong mereka secara bisnis. Dia mendirikan yayasan-yayasan pendidikan dan perlindungan hukum. Dia telah membantu banyak istri yang ditinggal mati suaminya, anak-anak yang putus sekolah, laki-laki dan perempuan yang dipecat sepihak dari pabrik tempat mereka bekerja, dan banyak orang lain yang bahkan tidak pernah ditemuinya langsung. Investasinya di bisnis-bisnis kecil perempuan-perempuan itu selalu berbuah keuntungan, namun Sofia tidak pernah masuk majalah bisnis karena itu. Mamanya akan selalu lebih terkenal, lebih kaya, dan lebih sukses. Namun Sofia tidak pernah cemburu.
Sofia menyeruput minumannya. Dia telah selesai bercerita.
Dengan lembut, Putri menaruh tangannya di atas tangan Sofia dan berkata,” Aku bangga sekali bisa punya teman seperti kamu, Sofia.” Sofia tersenyum.
“Aku pun,” katanya. Putri kemudian berkata dalam hati bahwa dia akan menelepon ibunya akhir pekan itu. Pertama kali dalam sepuluh tahun. Kedua perempuan muda itu lalu minum dan mengobrol lagi tertawa-tawa seperti waktu mereka pertama kali pergi menonton bioskop. Ketika makan bersama di Sarinah. Malam semakin jauh.
Sofia dan Putri ikut bernyanyi-nyanyi jelek lagu-lagu Amerika tahun 90an. Kedua mantan kekasih itu telah menjadi manusia-manusia yang mereka inginkan. Tidak peduli bagaimana orang melihat mereka pertama-tama sebagai lesbian, sebagai jalang penyuka sesama perempuan, pada akhirnya mereka adalah manusia.
Di luar bar itu, udara yang menggantung jauh di atas bendera pelangi besar itu mendingin dan membeku, menggumpal menjadi awan, menggantung berat sebelum pecah menjadi salju yang demikian halus sehingga ia tidak kelihatan pada awalnya. Angin menghempas butiran-butiran itu ke seluruh kota Tokyo – ke depan pintu-pintu tempat makan ramen yang tertutup, ke taman-taman kota, ke jendela gedung-gedung di Roppongi Hills, ke halaman gereja-gereja tempat orang-orang Methodist, Katolik dan Lutheran memanjatkan lagu-lagu pujian dan mengenakan pakaian terbaik mereka di hari Minggu, ke atas kubah-kubah masjid di mana populasi Muslim Jepang salat subuh, zuhur, asar, magrib dan isya dengan menadahkan tangan mereka ke langit sebelum menyentuh tanah dengan dahi mereka dan mengucap nama Allah dengan khidmat. Salju turun ke atas lengkung atap kuil-kuil kuno Shinto yang setia menyambut jutaan peziarah setiap tahun, mendengarkan doa-doa yang disampaikan baik oleh mulut, hati, maupun air mata. Salju turun menghampiri rumah orang-orang tua dan pasangan-pasangan muda, orang-orang kaya dan orang-orang miskin, mendarat di jendela orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya, di pekarangan Kaisar Jepang maupun pendatang. Salju turun dan berembus di kota Tokyo, yang menaungi segala rupa manusia itu.
Baca bagian pertama dari cerpen ini di sini.
Ilustrasi oleh Adhitya Pattisahusiwa