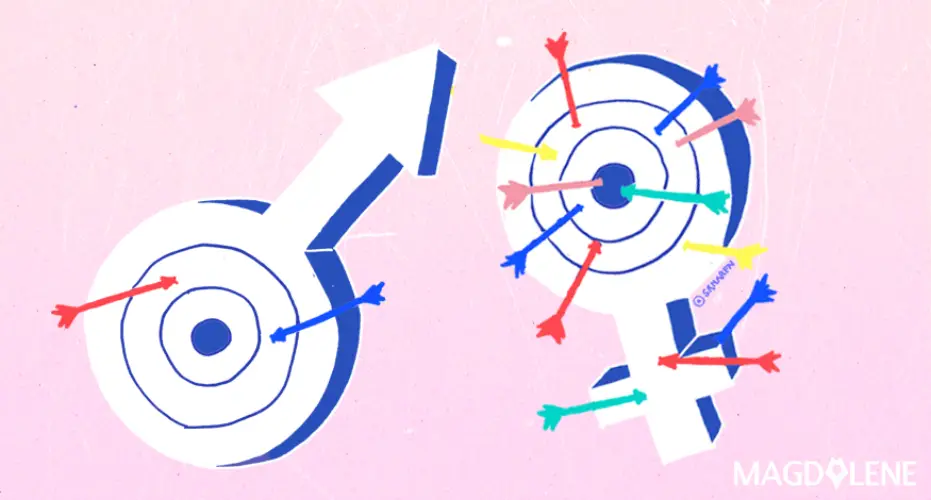Nak, Benarkah Hidup Berjalan Seperti Bajingan?

“Aluna mengeluh burnt-out. Bukan karena tugas sekolah, tapi feminisme. Tentu dia enggak ngaku. Apalagi ke aku, ibunya yang konvensional itu. Aluna sangat defensif tentang kegiatan-kegiatan perlawanannya padaku. Padahal aku tidak pernah melarang. Harusnya dia sadar, aku mengizinkan berarti aku mendukung kemelekan dia. Tapi bukan berarti aku selalu setuju dengan cara berpikirnya yang sangat dipengaruhi teman-temannya dan media sosial.” (hal. 4)
Pertanyaan pertama saya ajukan untuk Aluna: Kenapa memilih menjadi feminis, jika bisa menjadi biasa saja? Feminis mungkin sekali membuat repot diri sendiri, sebab seperti isme-isme lainnya, menjadi pengikut feminisme berarti siap memiliki musuh. Musuh utama tentu saja ideologi utama yang dilawannya: Patriarki. Musuh selanjutnya adalah orang terdekat. Ini pasti. Dalam kisah Aluna, musuh bagi feminismenya adalah mama—yang konvensional itu.
Sejak permulaan cerita, keresahan sudah hadir pada diri mama Aluna. Lewat narasi orang pertama, sebenarnya mama Aluna sudah memberi tahu pembaca betapa konvensionalnya ia sebagai seorang—bolehlah kita asumsikan—baby boomer. Seorang ibu baby boomer yang selalu ingin membawa seisi rumah tiap kali bepergian, yang kemudian berusaha praktis, simpel, dan seperti tuntutan masa kini, menjadi lebih minimalis.
Sementara itu, Aluna bagi mamanya adalah anak masa kini yang punya keperluan mobilitas tingkat tinggi sehingga segalanya mesti dibuat lebih praktis. Apalagi Aluna adalah aktivis. Dalam hati, pembaca pasti senang membayangkan bagaimana penampilan Aluna; Outfit-nya, gaya rambutnya, totebag dan buku panduan aksi di perayaan Women’s March, kosakata apa yang sering ia lontarkan, serta hashtag untuk setiap perjuangannya di media sosial.
Baca juga: ‘Sisterhood’ dan Hal-hal yang Tak Selesai
Persaingan Antar-Perempuan Paling Tabah
Kita pasti sering mendengar kelakar “anak perempuan cenderung lebih dekat dengan ayahnya dan kerap mencemburui ibu karena merebut ayah dari dirinya”. Kita kerap melihat konten ini di media sosial diikuti komentar paling populer: “Tahu enggak kenapa? Karena cinta pertama perempuan adalah ayahnya”, sambil menganggap lucu perseteruan imut anak perempuan itu dengan ibunya.
Namun, pernahkah kita mengira relasi tersebut adalah satu bentuk fenomena psikologis paling kuno yang disadur dari konsep perkembangan psikoseksual Oedipus Complex milik Sigmund Freud.
Oedipus Complex pada dasarnya adalah teori yang dibangun Freud atas pengamatannya terhadap anak laki-laki, yakni masa phallic; ketika pada usia 3-4 tahun, anak laki-laki akan mengembangkan ketertarikan pada ibu. Freud sebenarnya tidak pernah membuat teori sandingan atas perkembangan psikoseksual anak perempuan, seperti yang para penganut psikoanalisis sebut dengan Electra Complex. Yang jelas, anak perempuan juga mengalami masa phallic, saat mereka mengembangkan ketertarikan pada ayah dan mulai mencoba melepaskan diri dari ibu.
Yang kita lihat di media sosial mungkin hanyalah visualisasi anak perempuan yang mencoba menarik perhatian ayah karena logika simplisitas “cinta pertama” yang kita ciptakan itu. Hal kompleks yang sebenarnya tidak tampak adalah anak perempuan itu sedang melakukan pemberontakan feminitas terhadap ibunya; merebut perhatian ayah sembari merebut identitas keperempuanan yang ia tiru dari ibu. Sebab, anak perempuan dan ibu sama-sama seorang perempuan.
Ester Lianawati dalam “Akhir Penjantanan Dunia” menyebut fenomena tersebut sebagai “persaingan pertama anak perempuan terhadap ibu sekaligus upaya emansipasi pertama anak perempuan dari ibu”. Ia menilai, persaingan perempuan paling kuno ialah persaingan antara ibu dan anak perempuannya. Saya kira banyak orang akan menolak gagasan tersebut. Sebab, menurut Ester persaingan ibu dan anak perempuannya tidak pernah dibicarakan lantaran tidak memenuhi penggambaran klasik tentang ibu.
Dalam cerpen yang sedang kita bicarakan ini, Cyntha Hariadi, dengan hati-hati sekaligus liar dan berbahaya, menggambarkan sosok ibu dalam diri mama Aluna sebagai ibu rumah tangga, yang jauh dari sifat egois dan toksik yang kita bayangkan ada dalam sinetron televisi. Mama Aluna lebih sering mengambil jalan berlogika ketimbang jalan defensif penuh duri dalam menghadapi anak perempuannya.
“Bergabunglah dia dalam Gerakan Perempuan Merdeka Tanpa Anak. Aku tak punya hak melarangnya tidak punya anak–Koko yang mendamba punya cucu, bukan aku. Yang aku khawatirkan adalah keselamatannya. Apalagi dia pakai kaos yang bertuliskan gerakan itu ke mana-mana. Sendirian. Malam-malam.” (hal. 6)
“…Aku tak melarang ia ikut gerakan tersebut, tapi dia marah ketika aku menyarankan jangan pakai kaos itu. ‘Mama, perempuan bebas pakai baju apa saja!’ Aku tak tahan pada kenaifannya. ‘Kalau memang itu pilihanu, apa mesti kamu mengumumkan pada semua orang? Itu urusan pribadi. Kamu juga harus menghormati orang yang memilih anak…’’” (hal. 7)
Itu adalah contoh paragraf yang menunjukkan upaya komunikasi antara si paling feminis (Aluna) dan yang didakwa konvensional (mamanya). Mama Aluna mungkin adalah gambaran ibu paling jinak yang kita lihat, dengan cobaan anak perempuan feminis. Sebenarnya, jika kita cermati, kita dapat melihat suatu cara pemikiran feminisme pada ucapan mama Aluna—sesuatu yang hampir musykil dilakukan “ibu rumah tangga sejati”.
Di sisi lain, saya melihat adanya bentuk represi; suatu mekanisme pertahanan diri untuk meredam keinginan dan hasrat diri. Mimpi yang dialami mama Aluna saya kira adalah manifestasi dari kekesalan, kekecewaan, dan ketidaksiapan yang sebenarnya timbul dalam relasi dengan anak perempuannya. Dalam mimpi itu Aluna bahkan menjelma perempuan horor dengan sikap yang sebenarnya mamanya inginkan: Menjadi anak kecil dan ingin tidur di sampingnya. Dalam realitas, Aluna akhirnya sakit. Seperti yang diam-diam sang mama inginkan, Aluna kembali menjadi anak kecil–anak kecil yang tidak mengenal feminisme.
Jangan-jangan—kita sah juga untuk berprasangka—inilah yang disebut Anna Dufourmantelle, filsuf & psikoanalis Perancis, sebagai kebuasan maternal/ibu. Selain muncul dalam gambaran ibu tiri jahat, kebuasan maternal ternyata dapat tampil dalam bentuk yang halus dan tidak langsung. Mama Aluna, contohnya.
Ibu—mama Aluna—ingin selalu menjaga anak perempuannya dari norma-norma di luar yang dianut kehangatan rahimnya. Rahim ini, kata ibu, planet paling subur yang tidak akan membuatmu kelaparan sepanjang hidupmu. Padahal ibu pun kelaparan. Sangat. Mungkin untuk itulah Planet Aluna dibutuhkan. Selain sebagai petunjuk seperti apa gambaran dunia feminisme anaknya, mama Aluna jadi punya kesempatan berlibur dari mengurusi rumah dan suami.
Tetap saja, karena ini adalah represi, mama Aluna ingin sekali bertanya kepada Aluna untuk setiap pemberontakan yang ia lakukan: Nak, benarkah hidup berjalan seperti bajingan?
Baca juga: Menjadi Feminis yang Tak Sempurna
Menjadi Feminis vs Perempuan
Teringat satu fakta bahwa Simone de Beauvoir menulis The Second Sex jauh sebelum ia mendeklarasikan diri sebagai feminis, membuat saya yakin seseorang memang tidak terlahir feminis. Persis seperti kutipan termashyur Beauvoir: “One is not born, but rather becomes, a woman.” (Seseorang tidak terlahir, melainkan menjadi, perempuan), feminis juga begitu. Bedanya, sementara menjadi perempuan (gender) dibentuk oleh struktur sosial dan karenanya membentuk ketidaksadaran kolektif masif atas nilai-nilai patriarkis, menjadi feminis dibentuk oleh (dan memang membutuhkan) kesadaran utuh.
Pembaca tidak pernah tahu mengapa Aluna memilih feminisme dan menjadi SJW. Pembaca hanya melihat dan percaya situasi seperti apa yang mungkin terjadi jika mereka seorang feminis dan ibu mereka tidak. Mau tidak mau kita mesti mengakui cerpen ini begitu realis dan faktual.
Pada pertemuan di Post Bookshop itu, Cyntha Hariadi mengatakannya di hadapan kami. Pada mulanya ia berniat menulis esai, tapi yang tercipta akhirnya para tokoh dan plot fiksi ini. Tidak jadi soal, menurut saya. Bukankah fiksi kerap kali lebih kencang mengabarkan kebenaran? Bisa saya katakan, sedikit banyak Cyntha membeberkan pandangan personalnya dalam cerpen ini—tentang feminisme, tentang menjadi ibu dari seorang anak perempuan. Berkali-kali Cyntha berujar, “Sebab saya seorang ibu, dan saya punya seorang anak perempuan remaja.”
Alih-alih sebuah cerita yang berpihak sebelah pada posisi dan peran seorang ibu dan ibu rumah tangga (Cyntha bisa saja melakukan ini karena ia adalah seorang ibu), cerpen ini tampil apa adanya. Perseteruan ibu dan anak perempuan antara Aluna dan mamanya adalah gambaran perseteruan menjadi feminis versus menjadi perempuan.
Aluna mungkin masih terlalu muda untuk memahami, tidak semua perempuan yang memperjuangkan pemberdayaan perempuan mau disebut feminis. Ada banyak perempuan semacam itu di Bumi ini. Jika mama Aluna mampu mengutarakan pendapatnya seperti dialog-dialog dalam cerpen ini, saya ingin memujinya sebab itulah sesungguhnya sikap kerendahan hati dan kebijakan yang dibutuhkan oleh setiap orang muda yang menyebut dirinya feminis.
Dalam kepala Aluna, hidup berjalan sebegitu bajingan—hidup setiap perempuan di muka Bumi tepatnya, termasuk hidup mamanya. Dalam benak mamanya, yang bajingan adalah yang mengancam keselamatan anak perempuannya, termasuk setiap hal yang mengancam runtuhnya kelekatan yang telah susah payah ia bangun sejak dalam rahimnya.