Ulasan ‘Lessons in Chemistry’, Benarkah Perempuan Kini Sudah Setara?
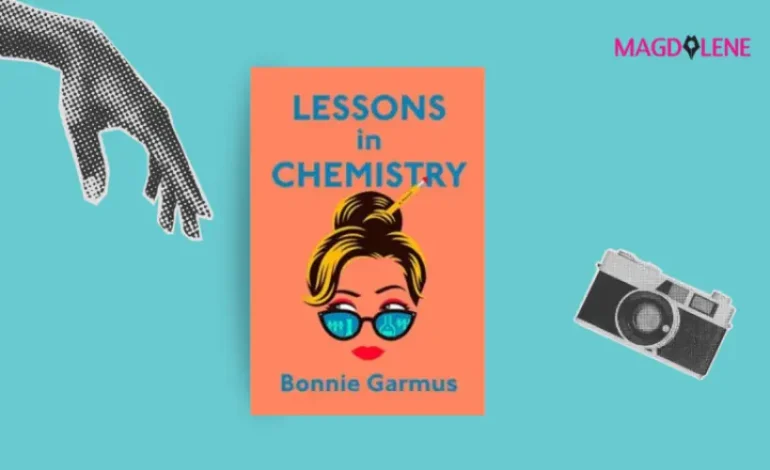
“Anak-anak, siapkan meja. Ibumu butuh waktu untuk dirinya sendiri.”
Perintah ini selalu diungkapkan oleh Elizabeth Zott, bintang acara memasak 1960-an di setiap akhir acara TV Supper at Six. Dalam acara tersebut, dapur diubah jadi laboratorium. Ia memakai jubah putih yang biasa digunakan para ilmuwan. Garam adalah natrium klorida, cuka adalah asam asetat, dan memasak adalah eksperimenn ilmuwan untuk menguji pengetahuan mereka.
Para pemirsa setia Zott adalah ibu rumah tangga. Mereka datang langsung ke studio atau sekadar duduk di depan TV, lengkap dengan buku catatan dan pensil. Mereka siap mencatat apa pun yang Zott katakan ke layar. Di sinilah suara dan kehadiran mereka dihargai.
Sebelum jadi bintang acara memasak, Zott adalah ahli kimia jenius dan inovatif. Dia satu-satunya perempuan di Hastings Research Institute, lembaga penelitian bioetika di New York, Amerika Serikat. Sayang, karena suatu kejadian tak terduga, dia dipaksa keluar dan merelakan mimpi.
Potongan cerita Zott ini adalah bagian dari novel debut Bonnie Garmus berjudul Lessons In Chemistry. Diterbitkan pada 2022 dan ditulis saat ia sudah berusia 65 tahun, Lessons in Chemistry adalah sajian penuh satir yang menempatkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender perempuan era 1950-an dan 1960-an dalam kacamata mikroskopik. Ini membuat para pembaca jadi bisa berefleksi dan bertanya pada diri sendiri tentang hal paling sederhana.
Apakah perempuan saat ini sudah setara dan mendapatkan semua hak dasarnya?
Baca Juga: ‘Invisible Women’: Data Laki-laki yang Utama, Perempuan Nanti Saja
Perempuan Masih Belum Setara
Membaca Lessons in Chemistry terutama buat pembaca perempuan mungkin akan lebih banyak menyisakan amarah, kesal, juga sedih. Novel ini boleh saja merupakan karya fiksi, tetapi pengalaman Zott sebagai perempuan di masyarakat patriarki, juga dirasakan banyak perempuan lintas generasi. Bahkan tiap kisah dan momen hidup Zott relate dengan perempuan yang hidup terpaut enam dekade darinya. Bahwa kekerasan akan selalu jadi momok buat para puan.
World Health Organization (WHO) dalam liris persnya pada 2021 menyatakan, sepanjang hidup, 1 dari 3 atau sekitar 736 juta perempuan, pasti pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangan dekat atau orang yang bukan pasangannya. Jumlah ini kata WHO yang sebagian besar tidak berubah selama satu dekade terakhir.
Kekerasan seksual ini dalam banyak hal merugikan perempuan. Dalam temuan SurveyUSA pada 2017 misalnya menyebut, sebanyak 41 persen dari 605 responden perempuan keluar dari pekerjaannya setelah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di kantor. Hal yang sama juga ditemukan studi Association of Women for Action and Research (Aware) Singapore yang terbit pada 2021.
Dalam penelitian yang dilakukan selama 2019 – 2021, Aware menemukan, 22 dari 39 perempuan berhenti dari pekerjaannya setelah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Sementara satu dari empat responden berpindah jalur karier.
Zott yang hidup enam dekade sebelum rilis pers WHO dan kedua temuan studi ini, nyatanya juga mengalami hal sama. Saat itu ia tengah mengejar kandidat PhD dalam bidang Kimia. Zott senang ketika proposalnya diterima, sebab selangkah lagi bisa mewujudkan mimpi masa kecilnya. Sayang, saat mimpinya sebentar lagi bakal terwujud ,profesor pembimbingnya justru melakukan kekerasan seksual terhadapnya.
Sebagai pembelaan diri, Zott yang kala itu tengah diperkosa menancapkan ujung runcing pensilnya ke perut profesor. Pasca-kejadian itu, ia dipanggil pihak universitas dan dipaksa untuk meminta maaf dan mengungkapkan penyesalan verbal atas tindakan melukai sang pelaku.
Tak sampai situ saja, pihak universitas bahkan membatalkan kadidat PhD Zott dan mengancam akan mengeluarkannya kalau tak mau minta maaf dan menyesali perbuatannya. Zott marah atas perlakuan tak adil dari universitas. Ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan terpaksa merelakan gelar PhDnya.
“Aku menyesal. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak membawa lebih banyak pensil.” – Elizabeth Zott
Ini bukan terakhir kalinya Zott mengalami kekerasaan seksual. Saat sudah bekerja di Hasting Research Institute, ia sempat mengalami kekerasan seksual dari atasannya. Kekerasan seksual ini parahnya juga ditambah dengan kekerasan berbasis gender lainnya, yaitu pemutusan kerja paksa karena kehamilan tidak direncanakan (KTD).
Seperti yang dikatakan Garmus dalam wawancara eksklusifnya bersama Scroll.in, ia menggambarkan Zott sebagai seseorang yang terus menerus menentang gagasan “normal” tentang menjadi perempuan. Ia menolak untuk didikte oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan tidak menikah dan memiliki anak. Ia lebih memilih menjalani hubungan romansa di luar ikatan pernikahan dengan kekasihnya, Calvin Evans.
Karena itu, ketika ia mengalami KTD dengan kekasihnya, ia secara sepihak dikeluarkan dari Hasting. Dalih Dr. Donatti (atasannya) kala itu Zott sudah melanggar aturan tak tertulis perusahaan dan masyarakat. Ia dicap sebagai perempuan amoral karena hamil di luar pernikahan dan sampai saat itu masih gamang apakah ingin mempertahankan kehamilannya atau tidak.
“Kamu tahu betul perempuan tidak bisa terus bekerja saat hamil. Tapi kamu—kamu bukan hanya sedang mengandung, kamu juga tidak menikah. Itu memalukan.”
Zott tentu bingung dengan dalih pemecatan dari Dr. Donatti. Kehamilannya tidak ada sangkut pautnya dengan kinerjanya sebagai ilmuwan, tapi kenapa pemecatannya justru didasari alasan tak masuk akal ini. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Apakah laki-laki yang menghamili perempuan juga mendapatkan perlakuan yang sama?
Jawabannya bisa ditebak. Laki-laki tak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Zott. Alasannya sederhana, karena yang hamil bukan laki-laki dan perempuan jadi seharusnya perempuan yang bisa lebih menjaga “kesuciannya”.
Nasib Zott bisa dibilang miris. Perempuan bisa begitu saja dipecat karena suatu hal dil uar kuasanya, lebih penting lagi dipecat karena proses alamiah dalam tubuhnya. Ironinya, diskriminasi gender yang dialami Zott masih dialami banyak perempuan di abad 20 ini.
Menurut laporan terbaru Women, Business and the Law 2021, 38 dari 190 negara masih melakukan pemecatan sepihak kepada perempuan yang hamil karena tidak dijamin oleh undang-undang. Penelitian menunjukkan, sebagian besar perempuan diberhentikan pada tahap awal kehamilan, bahkan sebelum mengambil cuti hamil.
Selain pemecatan, stigma pada perempuan yang mengalami KTD juga masih subur hingga sekarang. Di Indonesia misalnya perempuan yang mengalami KTD masih dianggap sebagai aib atau perempuan nakal yang tidak bisa menjaga diri. Realitas ini salah satunya terefleksi dalam penelitian yang diterbitkan Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia pada 2018.
Dengan menggunakan data profil kesehatan, penelitian ini secara spesifik menemukan di Kabupaten Pati, kasus KTD pada remaja sebanyak 43 persen berdampak langsung pada pernikahan di usia dini. Angka ini kemungkinan lebih tinggi jika mengacu data nasional. Peneliti pun menduga, tingginya pernikahan dini untuk remaja KTD terjadi karena masih adanya stigma sosial yang melekat pada perempuan. Menikah pun dijadikan jalan keluar untuk menutup “aib”.
Baca Juga: “Bagaimana Cara Mengatakan ‘Tidak’?” Tampilkan Perempuan di Lingkaran Kekerasan
Efek Matilda dan Pentingnya Sisterhood
Garmus dalam wawancaranya bersama The Sydney Morning Herald mengatakan, mendapatkan diskriminasi gender di dunia kerja. Ia pernah bekerja di biro iklan sebagai satu-satunya perempuan yang menghadiri pertemuan lapangan untuk kampanye teknologi besar.
Dalam presentasi ide kampanye, wakil presiden di ruangan itu tanpa malu mengambil ide Garmus, mengklaim sebagai miliknya. Garmus tentu saja kesal, masalahnya ia sendiri baru saja mempresentasikan ide itu dengan PowerPoint yang bahkan masih terpampang jelas di belakangnya.
“Dia melihatnya (PowerPoint Garmus) dan menyatakan semuanya, ide-ide itu sebagai miliknya. Dia mendapat pujian penuh atas kampanye itu. Tidak ada yang mengatakan apa pun. Tidak ada yang membela saya. Tidak ada yang melakukan apa pun.”
Pengalaman Garmus nyatanya bukan hal yang langka. Perempuan selama ratusan tahun lamanya telah mengalami diskriminasi gender ini yang dikenal dengan istilah Matilda effect atau efek Matilda. Dikutip dari penelitian The Matthew Matilda Effect in Science (1993) dijelaskan efek Matilda adalah bias yang mengarah pada diskriminasi gender di mana perempuan tidak diakui pencapaiannya sebalikya pencapain diakui atau diatribusikan kepada rekan laki-lakinya.
Fenomena ini pertama kali dijelaskan oleh aktivis hak pilih dan abolisionis Matilda Joslyn Gage dalam esainya Woman as Inventor (1870). Efek Matilda ini sudah mendarah daging dalam sejarah peradaban dunia. Dalam dunia komputer misalnya, kita lebih mengenal nama Charles Babbage yang didapuk sebagai bapak komputer. Padahal pada kenyataannya pada pertengahan tahun 1800-an, Ada Lovelace telah menulis instruksi untuk program komputer pertama.
Dalam bidang Matematika, kita lebih mengenal nama Pythagoras. Padahal dalam penemuan terbesar Pythagoras ada perempuan filsuf bidang Matematika yang karyanya selalu dikaitkan bahkan diklaim sebagai milik suaminya sendiri, Pythagoras.
Efek Matilda yang dialami Garmus dan banyak perempuan di dunia selama ratusan tahun ini berusaha diangkat dalam pengalaman diskriminasi gender yang dialami Zott. Efek Matilda dialami Zott ketika Dr. Donatti mencuri penelitian yang sudah dilakukan Zott selama berbulan-bulan dan menerbitkanya atas namanya sendiri. Zott sayangnya tidak bisa berbuat apa-apa walau sudah sekuat tenaga mengkonfrontasi atasannya itu.
Dunia ternyata lebih percaya kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Mau sepintar apapun Zott, ia tak akan pernah diakui. Ucapan dari seorang laki-laki apalagi jika ia berada dalam posisi yang lebih tinggi lebih punya kedudukan kuat dari kebenaran itu sendiri.
Dunia yang tidak pernah berpihak pada Zott juga diperparah dengan banyaknya para perempuan dalam hidupnya yang tak mau bersolidaritas dengannya. Sejak ia masih jadi pelajar hingga bekerja, banyak perempuan di dalam hidupnya justru ingin membuatnya jatuh. Frask, kepala sekretaris Hasting salah satunya.
Frask digambarkan Garmus sebagai perempuan yang menginternalisasi seksisme. Ia menyebarkan gosip tentang Zott agar semua orang membencinya. Ia mendorong prasangka bias gendernya pada Zott karena sebagai perempuan Zott pasti menggunakan rayuan dan tubuhnya untuk mendapatkan posisi di Hasting. Ia juga mempraktikan kuasanya terhadap Zott dengan memaksanya menandatangani surat pengunduran diri ketika Dr. Donatti secara sepihak memecat Zott karena alasan KTD.
Membaca kelakukan Frask kepada Zott mungkin bikin pembaca geram. Sayang pada kenyataannya, perempuan seperti Frask banyak jumlahnya. Inilah mengapa gerakan kesetaraan dan keadilan gender terasa jalan ditempat alias menemukan jalan buntu.
Laki-laki akan terus berada di posisi yang menguntungkan sedangkan perempuan akan terus terjebak dalam posisi ketertindasannya. Padahal menurut Bell Hooks dalam tulisannya Sisterhood: Political Solidarity between Women (1986) adalah ideologi supremasi laki-laki yang mendorong perempuan untuk percaya bahwa perempuan adalah musuh ‘alami’ sehingga solidaritas tidak boleh ada di antara perempuan. Perempuan tidak bisa, tidak seharusnya, dan tidak terikat satu sama lain karena akan menghambat pencapaian bahkan mengurangi nilai dirinya.
Di kalangan perempuan, nilai-nilai supremasi laki-laki diekspresikan melalui perilaku curiga, defensif, dan kompetitif. Seksismelah yang menyebabkan perempuan merasa terancam satu sama lain tanpa sebab. Seksisme mengajarkan perempuan untuk membenci perempuan, dan secara sadar dan tidak sadar kita melakukan kebencian ini dalam kontak sehari-hari satu sama lain.
Baca Juga: ‘As Long As Lemon Trees Grow’: Trauma dan Perlawanan dalam Konflik Suriah
Seperti Frask, perempuan kata Hooks menghabiskan berjam-jam waktunya setiap hari untuk melecehkan perempuan lain secara verbal, biasanya melalui gosip. Sinetron televisi dan drama terus-menerus menggambarkan hubungan perempuan-ke-perempuan yang bercirikan agresi, penghinaan, dan persaingan. Ini yang membuat gerakan feminisme jalan ditempat.
Oleh karena itu menurut Hooks, satu hal penting yang harus dilakukan kesetaraan dan keadilan gender bisa diraih adalah dengan bersolidaritas. Dengan bersolidaritas atau yang dikenal dengan sisterhood, perempuan bisa mengakhiri ketertindasan seraya berbagai pengalaman dan kecakapan mereka masing-masing.
Solidaritas ini tidak melulu harus dilandasi oleh kesamaan pengalaman sebagai korban. Perempuan juga tidak memerlukan sentimen anti-laki-laki untuk bersolidaritas. Begitu banyak kekayaan pengalaman, budaya, ide, dan keahlian perempuan yang bisa dibagikan satu sama lain.
Perempuan bisa menjadi saudara yang dipersatukan oleh kepentingan dan kepercayaan yang sama, bersatu dalam menghargai keberagaman, bersatu dalam perjuangan mengakhiri penindasan seksis, bersatu dalam solidaritas politik
Dengannya, perempuan tidak hanya akan mengakhiri kertindasan berbasis gender saja tetapi juga ketertindasan lain seperti rasial dan memperkaya diri. Hal ini karena dengan bersolidaritas, perempuan akhirnya mampu mengenali apa musuh mereka sebenarnya dan bisa dengan kuasa penuh melawan sekaligus menjaga satu sama lain.






















