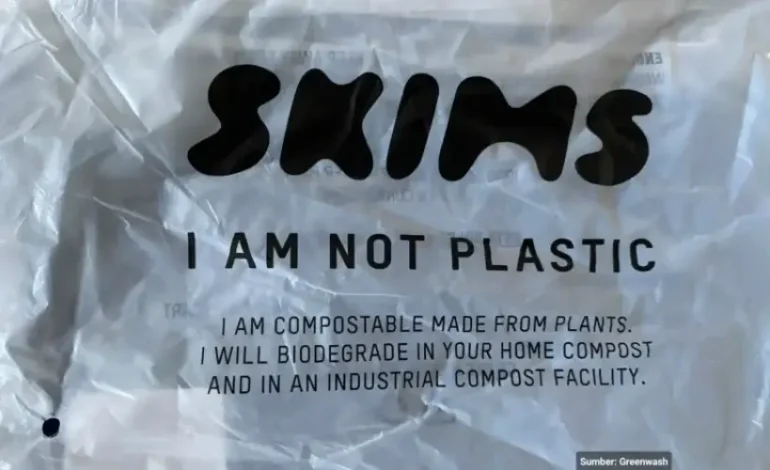25 Tahun Komnas Perempuan Nyalakan Api Perjuangan: Mimpi hingga Hambatan

Komisi Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah putri sulung Reformasi. Lahir dari desakan publik agar negara bertanggung jawab pada Tragedi Mei 1998, sejak itu Komnas Perempuan menjadi Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM). Kerja mereka di antaranya pendidikan publik, pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, kajian, pemberian rekomendasi, dan kolaborasi. Tujuannya, yakni mendorong perubahan kebijakan demi menekan angka kekerasan perempuan.
Kini Komnas Perempuan genap berusia seperempat abad. Momentum itu dirayakan dengan acara puncak perayaan 25 Tahun Komnas Perempuan yang bertajuk “Satu Suara, Wujudkan Cita-Cita: Perempuan Indonesia Aman, Sentosa, Berdaulat” yang digelar di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, (15/11).
Dalam sambutannya, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani bilang, perjalanan 25 tahun Komnas Perempuan bukan sekadar tentang lembaga ini saja. Namun, tentang semua pihak yang berjuang untuk menghadirkan kehidupan bebas dari kekerasan. Sebab, kata dia, kerja-kerja Komnas Perempuan tak bisa dilakukan sendirian. Ada dukungan publik, termasuk gerakan perempuan.
“Pertama, kami memastikan suara korban dan penyintas menjadi pelita dalam menapaki perjalanan perjuangan yang panjang dan kerap sunyi. Kedua, Komnas Perempuan terus mengupayakan ruang untuk partisipasi substantif dari komunitas penyintas, pendamping korban, dan perempuan pembela HAM untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kerja Komnas Perempuan,” ujar Andi pada Magdalene.
Perjalanan Komnas Perempuan sendiri tak melulu berjalan mulus. Bak bekerja di atas bara, jika meminjam istilah jurnalis perempuan Maria Hartiningsih yang melukiskan sifat kerja Komnas Perempuan. Melalui wawancara eksklusif bersama Magdalene, Andy Yentriyani berbagi kisah lengkap dan suka duka Komnas Perempuan dalam memaknai kerja serta tantangan LNHAM sejauh ini. Berikut kutipan obrolan tersebut.
Magdalene: Komnas Perempuan telah hadir selama 25 tahun. Buat Komnas Perempuan, apa refleksi penting dalam mengadvokasi isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?
Tentunya refleksi 25 tahun Komnas Perempuan dimulai dari membincangkan bahwa semua capaian tak lepas dari orang-orang yang menjaga semangat independensi dan gerakan yang menjadi fondasi kerja-kerja kami.
Komnas Perempuan dijaga oleh banyak orang, gerakan perempuan, sipil, bahkan lembaga lain yang sama-sama berkomitmen mewujudkan kehidupan bebas dari kekerasan. Apa yang harus dilakukan ke depan inilah yang perlu diperhatikan karena setiap zaman punya tantangannya sendiri.
Ke depannya pasti banyak ketidakpastian, banyak situasi yang dirasa musykil. Hanya dengan memastikan kita menggunakan modalitas tadi, independensi, menjaga ruh kepemimpinan bersama, kreativitas dan agilitas, mawas pada situasi, mencari strategi-strategi baru, serta membuat peluang baru untuk perubahan, itu yang paling utama.
PR kita banyak banget. Kita punya UU TPKS tapi implementasinya harus dikawal bareng-bareng, termasuk memastikan infrastrukturnya ada di setiap tempat. Kita harus bisa memberikan layanan ke pulau-pulau yang tak terhubung dengan infrastruktur, sehingga pelayanan itu enggak hanya bisa dijangkau di Pulau Jawa atau di perkotaan saja.
Kedua, memastikan tempat yang aman bagi perempuan ada di setiap tempat. Di dalam rumahnya, tempat dia bersekolah, dan tempat mengartikulasikan diri. Tanpa itu, perempuan tidak bisa bisa menikmati kesetaraan karena dibatasi dengan berbagai ancaman.
Ketiga, kita butuh pola kebijakan yang memungkinkan pembangunan itu bermakna bagi perempuan. Tidak mencabut akar atau sumber penghidupan dan jati dirinya. Mereka juga bisa turut secara aktif merencanakan, menentukan, melaksanakan, mengawasi pembangunan itu sendiri dalam pola yang berkelanjutan. Karena kalau tidak, situasi konflik ini akan berulang. Perempuan akan terus jadi korban.
Terakhir, proses kita dalam bernegara dan berbangsa ini kan mensyaratkan kebhinekaan karena perempuan beragam, datang dari latar belakang luar biasa. Kalau ngomongin perempuan Islam misalnya, kita membayangkan seakan mereka homogen padahal tidak.
Bagaimana kita menciptakan kemungkinan untuk semua perempuan merasakan yang sama, kesempatan untuk menikmati sebagai warga hak-hak konstitusionalnya itu yang juga menjadi PR. Karena kita lihat politik identitas sendiri masih berlangsung. Dalam situasi seperti itu isu moralitas suka dimunculkan. Kalau soal isu moralitas perempuan yang akan selalu dikejar dan bikin satu kebijakan dengan pondasinya pada satu norma moralitas mayoritas yang sebetulnya dipaksakan pada kebhinekaan Indonesia yang ada. Kita perlu jaga sama-sama
Tak lupa, memastikan institusi yang bekerja untuk kepentingan kemajuan hak perempuan itu memiliki kapasitas yang memungkinkan mereka bekerja dengan baik. Tidak hanya Komnas Perempuan tapi salah satunya Komnas Perempuan.
Baca juga: Mpu Uteun: Kelompok Perempuan Pelindung Hutan Aceh yang Melawan Patriarki
Magdalene: Tak lengkap ngomongin refleksi tanpa menyinggung alotnya pembahasan UU TPKS. Sebagai lembaga nasional independen yang giat mendorong UU ini disahkan sampai digolkan, pembelajaran penting apa yang didapat dari Komnas Perempuan?
Ini kerja lintas generasi ya. Orang bilang 2015 udah bikin naskah akademik, tapi dari proses ini dimulai bahkan sebelum era Reformasi, semangat kita sudah ada. Kita ingat kasus Marsinah, dan berpikir kok bisa ya ada orang meninggal dengan kondisi serupa itu (jadi korban kekerasan). Kita juga berefleksi dari tragedi seksual Mei 98 di mana cerita cerita-cerita kekerasan perempuan di wilayah konflik lainnya dibuka. Sejak itu pelan-pelan kita bikin CATAHU (Catatan Tahunan). Kita punya data, orang tidak bisa bilang ini orang cuma satu dua saja, tapi data mengatakan kasus ini banyak. Jadi meskipun ada hoaks dan siar kebencian soal UU TPKS, mereka tidak bisa mematahkan data karena kita tumbuh secara organik tapi juga sistematis untuk menunjukkan bahwa ini permasalahan serius yang dihadapi perempuan Indonesia.
Mereka bilang ini (UU TPKS) pemikiran Barat, seks bebas. Enggak. Ini real. Berapa banyak perempuan yang diperkosa setiap tahunnya, berapa banyak yang harus mengalami pelecehan seksual yang tidak ada payung hukumnya kita bisa sampaikan itu. Buat mereka ini tidak ada, tapi kita ada buktinya kalau ada yang melapor. Satu saja (laporan) itu pun menjadi sesuatu yang penting.
Magdalene: Dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan Komnas Perempuan Senin lalu (12/10), Komisioner Theresia Iswarini menyinggung hak pemulihan korban kekerasan korban yang masih stagnan. Apa yang membuat hak pemulihan mandek?
Sebetulnya kami sudah membuat rekomendasi kebijakan, salah satunya memastikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian itu jadi direktorat. Karena begitu jadi direktorat, maka dia punya kekuatan yang lebih full misalnya jumlah awak yang lebih baik, tentunya ini pasti berbarengan dengan jumlah anggaran yang baik. Kalau anggarannya baik, maka dia bisa mengadakan pelatihan yang lebih sering, memastikan berbagai layanan yang sampai sekarang ini tidak terpegang. Bagaimana bisa membuat perlindungan sementara yang cepat kalau tidak ada orang yang melakukannya atau tidak ada fasilitasnya.
Dengan UU TPKS sekarang juga diharapkan yang akan mendampingi dan menguatkan memberikan ruang ketika berbicara. Korban paling banyak perempuan dan anak. Mereka butuh orang yang memahaminya. Kita sebagai perempuan yang besar di lingkungan patriarki itu sulit sekali bercerita kepada kawan laki-laki tentang urusan seksual yang dialami kita. Apakah otomatis dengan polwan bisa ditindak? Tidak juga, tergantung bagaimana pendekatan yang diambil tapi itu bisa dilatih dengan pendidikan dan pola pengawasan yang mengedepankan kualitas penerimaan laporan, kualitas bagaimana berinteraksi dengan pelapor dan korban bisa lebih baik.
Ada kebutuhan yang bersifat substantif, struktur hukumnya tapi juga budayanya. Karena kan selama ini kepolisian memperlakukan kekerasan perempuan bersifat personal saja, dan kalau bisa jangan ribut-ribut. Kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan saja. Makanya itu jadi penting tagline peringatan 25 tahun komnas perempuan. Aman, sentosa, dan berdaulat.
Yang pertama kita buat ruang aman buat perempuan di manapun dia berada. Bagaimana sekolah bisa aman. Bagaimana transportasi bisa aman, tempat kerja jadi aman dan jangan bayangkan rumah pasti aman karena banyak kan kalau kita lihat datanya rumah juga tidak aman bagi perempuan. Jadi bagaimana kita menciptakan itu jadi di manapun dia berada perempuan merasa aman.
Kalau dia mengalami tindakan kekerasan juga dia dipastikan tau dan bisa mengakses layanan yang memungkinkan dia mendapatkan keadilan dan pemulihan yang sifatnya multiaspek. Hanya dengan bantuan multi aspek maka seseorang bisa merasa sentosa.
Sentosa bukan soal ekonomi tapi ini kesejahteraan lahir dan batin, ukurannya lebih rumit. Nah dia mensyaratkan kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri seperti korban pemerkosaan dia harus bisa menentukan apa yang dia inginkan tapi kan sekarang lebih banyak korban ditentukan nasibnya oleh keluarganya oleh komunitasnya. Tapi juga dengan memberikan pemulihan multiaspek perempuan ini bisa menjadi penyintas, penyintas itu adalah orang yang mampu mengambil keputusan dengan mengenali konsekuensi konsekuensi yang ada.

Magdalene: Dalam pidato sambutan, mbak Andy sempat menyampaikan bagaimana Komnas Perempuan sama seperti perempuan pembela HAM lainnya juga mendapatkan intimidasi dan ancaman selama mengadvokasi isu kekerasan terhadap perempuan. Intimidasi dan ancaman seperti apa sih mbak?
Kalau kita lihat pas advokasi UU TPKS tuh langsung tuh mengatakan “Pasti ini perempuan yang kebarat-baratan, perempuan yang benci keluarga, perempuan benci agama”. Banyak labelnya. Untuk banyak perempuan pembela HAM termasuk Komnas Perempuan itu (ucapan dan klaim) tidak hanya sekedar menyakitkan, tapi juga membuat kami takut. Karena kami tahu bahwa serangan bertubi-tubi di ruang digital memungkinkan persekusi terjadi ke ruang nyata. Begitu pula sebaliknya dari ruang maya ke ruang nyata, enggak ada jedanya.
Atau ketika advokasi kasus, ada suatu peristiwa saya ingat menyemangati teman-teman di Komnas Perempuan karena ada satu perempuan mengambil nyawanya. Dia merasa tidak mendapatkan pertolongan padahal kita sudah jadwalkan dia untuk konseling. Saat hal itu terjadi, semua orang marah tanpa peduli bahwa kami orangnya sedikit, tapi jumlah kasusnya banyak dan kami sendiri juga sudah menjadwalkan konseling tapi sayangnya sebelum konseling sudah kejadian. Itu kan ucapannya “Udah enggak digaji, tapi enggak kerja”. Tanpa dimarahi pun kami merasa bersalah ya dan itu bertingkat dari Komnas Perempuan sampai ke teman-teman rujukan.
Intimidasi bisa datang dari seperti itu. Buat pendamping korban itu membuat mental jadi sangat terpuruk. Intimidasi jangan dibayangkan hanya terror tapi juga tidak memahami situasi yang dihadapi pendamping dan secondary trauma yang mereka alami. Banyak teman-teman Komnas Perempuan itu enggak ada stop-nya. Satu korban belum selesai, korban lain sudah datang. Jadi itu situasi yang dihadapi.
Apalagi ada teman-teman yang dituntut secara hukum. Komnas Perempuan pernah juga mengalami hal ini karena dianggap melakukan tindakan yang meresahkan publik sedangkan kami, Komnas Perempuan Berpikir bahwa setiap korban harus didengarkan.
Baca juga: Isu Lingkungan Jadi Napas Kerja Chitra Subyakto
Magdalene: Dengan intimidasi dan ancaman yang diterima Komnas Perempuan, apakah pemerintah sendiri sudah menaruh perhatian pada perlindungan hukum perempuan pembela HAM?
Kalau ditanya, concern-nya masih parsial dan kadang-kadang kita sulit mengenali bagaimana membangun komitmen holistik. Ada juga permasalahan diksi, kalau di Indonesia kan kesannya pemerintah itu eksekutif saja. Sementara kalau dalam Bahasa Inggris goverment itu berarti ada pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan itu harus bekerja bersama membangun sistem agar penegakan payung hukum bisa terlaksana.
Saya sering ditanya pemerintah punya concern tidak? Pemerintah yang mana? Dalam isu yang mana? Ini yang menurut saya ini perlu cara gerak berbeda. Durasi 25 tahun adalah waktu yang cukup untuk berefleksi tentang kenapa dengan segenap energi yang kita punya butuh 3 abad kalau menurut penuturan Karlina Leksono Supelli (dalam pidato dia sebelumnya di Ulang Tahun Komnas Perempuan), kita baru bisa mencapai kesetaraan yang betul-betul substantif. Lantas, bagaimana kita mempercepat itu?
Magdalene: Komnas Perempuan tidak bisa dilepaskan dari gerakan perempuan. Sebagai LNHAM yang lahir dan tumbuh dari dan bersama gerakan perempuan, bagaimana Komnas Perempuan memandang gerakan perempuan di Indonesia kini?
Dia (gerakan perempuan) adalah gerakan yang paling dinamis mungkin ya. Karena sejak kelahirannya, gerakan perempuan lahir dengan spektrum yang luas, bukan cuma di Indonesia. Mulai dari ada yang percaya dengan struktur sampai enggak percaya dengan struktur.
Yang percaya bilang kita harus advokasi kebijakan. Yang enggak percaya bilang enggak mungkin dismantle sebuah struktur menggunakan alat dari the master tools. Karena master akan memastikan alatnya tidak akan lebih canggih dari kapasitasnya menciptakan inovasi baru yang mampu memperkuat alat. Jadi menurut saya yang paling membanggakan dari gerakan perempuan di Indonesia adalah meski spektrumnya luas, ruang ngobrol itu masih ada walau kita berbeda pendapat.
Magdalene: Dulu di zaman Orde Baru, salah satu tantangan besar gerakan perempuan adalah adanya ibuisme negara. Sementara, sekarang banyak narasi yang berseliweran bahwa (gerakan) perempuan yang satu “menjatuhkan” (kanibalisme) dengan gerakan perempuan lain, sehingga jadi mandek. Menurut Mbak sebenarnya tantangan yang paling signifikan dari gerakan perempuan di Indonesia itu apa, sih?
Mungkin kita juga terlalu delusional saat berpandangan perempuan itu cakar-cakaran dengan sesama perempuan, karena sebenarnya kan bisa terjadi juga di lelaki. Kenapa kita tidak menyampaikan itu? Karena kita merekatkan kuasa dengan laki-laki, sehingga ketika ada pertarungan antarlaki-laki itu dianggap wajar-wajar saja. Sementara, jika terjadi di perempuan, kita terperangah heran. Semua karena dari kecil kita dididik dengan cara yang patriarkis.
Contoh konkretnya seperti kereta listrik (KRL) dan gerbang perempuan. Banyak yang mengeluhkan lebih sulit masuk ke gerbong perempuan dibandingkan campuran, karena perempuan sikut-sikutan. Tapi coba bayangkan struktur apa yang membuat perempuannya tetap dalam kompetensi yang sama seperti itu?
Semua perempuan capek kerja dan dia harus bangun pagi ngurusin keluarganya. Privilese untuk bisa duduk di KRL itu mungkin satu-satunya waktu untuk dia berhenti sejenak menikmati waktunya. Sementara lelaki cuma harus mandi dan berangkat kerja, perempuan harus masak, ngurusin suaminya, segala macam dilakukan sama dia. Masuk ke KRL itu mungkin peristiwa ke-30 yang harus dia lakukan dari pagi.
Baca juga: Santi Warastuti dan Legalisasi Ganja Medis: Saya Takkan Berhenti
Magdelene: Lalu berkaca dari situ, agenda paling mendesak untuk bareng-bareng kita dorong guna memajukan hak perempuan di Indonesia apa ya, Mbak?
Ini pertanyaan berat banget ya. Kita memerlukan cara kerja baru untuk mengatasi ketimpangan yang sifatnya lebih struktural, ada di semua tempat, dan menyebabkan penindasan tetap langgeng. Maka menurutku agenda paling utamanya adalah pendidikan kritis. Karena tanpa itu kita enggak tahu apa yang menindas kita.
Meskipun ada pendidikan merdeka tapi kan butuh fasilitator, artinya mendidik anak untuk merdeka, gurunya harus merdeka dulu. Kalau gurunya enggak punya cara kritis, bagaimana bisa memerdekakan orang lain. Itu kenapa di Indonesia menjadi sangat sulit untuk seorang mempertanyakan sesuatu. Padahal curiosity, rasa ingin tahu dan menelaah secara kritis adalah titik awal untuk mencari tahu sebab akibat dan titik awal menemukan solusi.
Magdalene: Komnas Perempuan sejak 2001 telah merilis CATAHU. Semangat awal CATAHU sendiri adalah untuk memperlihatkan pada publik bahwa kekerasan pada perempuan itu memang ada dan benar terjadi. Terlepas dari itu, bagaimana kita seharusnya memaknai CATAHU?
CATAHU itu punya muatan yang beragam, orang kadang melihat cuma jumlahnya saja. Ke depan saya berharap kita menceritakan keberhasilan dan hambatan penanganan kasus.
Magdalene: Tren kekerasan apa yang signifikan muncul di CATAHU selama 25 tahun dan prediksi ke depan?
Kita perlu pahami, kehadiran payung hukum memungkinkan orang melaporkan lebih banyak. Itu kenapa sampai sekarang setelah UU PKDRT disahkah, paling banyak kasus yang dilaporkan adalah kasus KDRT. Orang sudah paham KDRT tidak boleh dilakukan. Jadi ekspektasi kita adalah dengan ada UU TPKS, angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan akan banyak. Karena dulu orang tidak tahu ini pelecehan seksual sekarang dia tahu.
Kedua, digitalisasi menghantui perempuan. Tidak hanya untuk urusan kekerasan seksual di ruang maya tetapi juga sebentar lagi digitalisasi akan menghabisi ruang-ruang kerja perempuan yang membuat mereka masuk dalam sektor yang paling gampang dieksploitasi. Pada titik ini kita belum tahu solusinya, karena sumber daya manusia (SDM) kita sendiri juga terlalu rendah: Pendidikan kurang dari 9 tahun atau intelektualitas sarjana yang setara anak SMP. Jadi kami khawatir nantinya akan ada dampak domino dari digitalisasi pada perempuan.
Lalu dampak lingkungan, banyak tempat hilang karena banjir rob karena kita tidak berhasil menemukan strategi pembangunan yang betul-betul berkelanjutan. Energi terbarukan itu penting tapi bagaimana cara menciptakan energi ini tanpa mengorbankan sumber penghidupan dan jati diri perempuan itu justru lebih penting.
Misalnya ada geothermal sebagai alternatif sumber energi, tapi berdiri di atas tanah ulayat yang dikelola perempuan, itu yang tidak boleh. Belum lagi perempuan juga diposisikan sebagai pihak yang dibebankan dan menginternalisasi peran sosialnya.
Jadi itu sekiranya tiga tren itu yang saya lihat di CATAHU dan kemungkinan akan meningkat di kemudian hari.