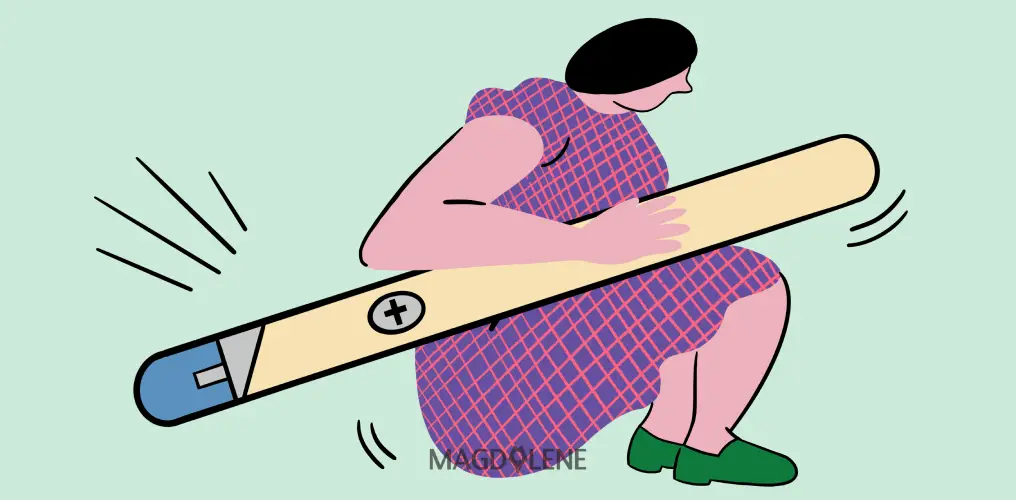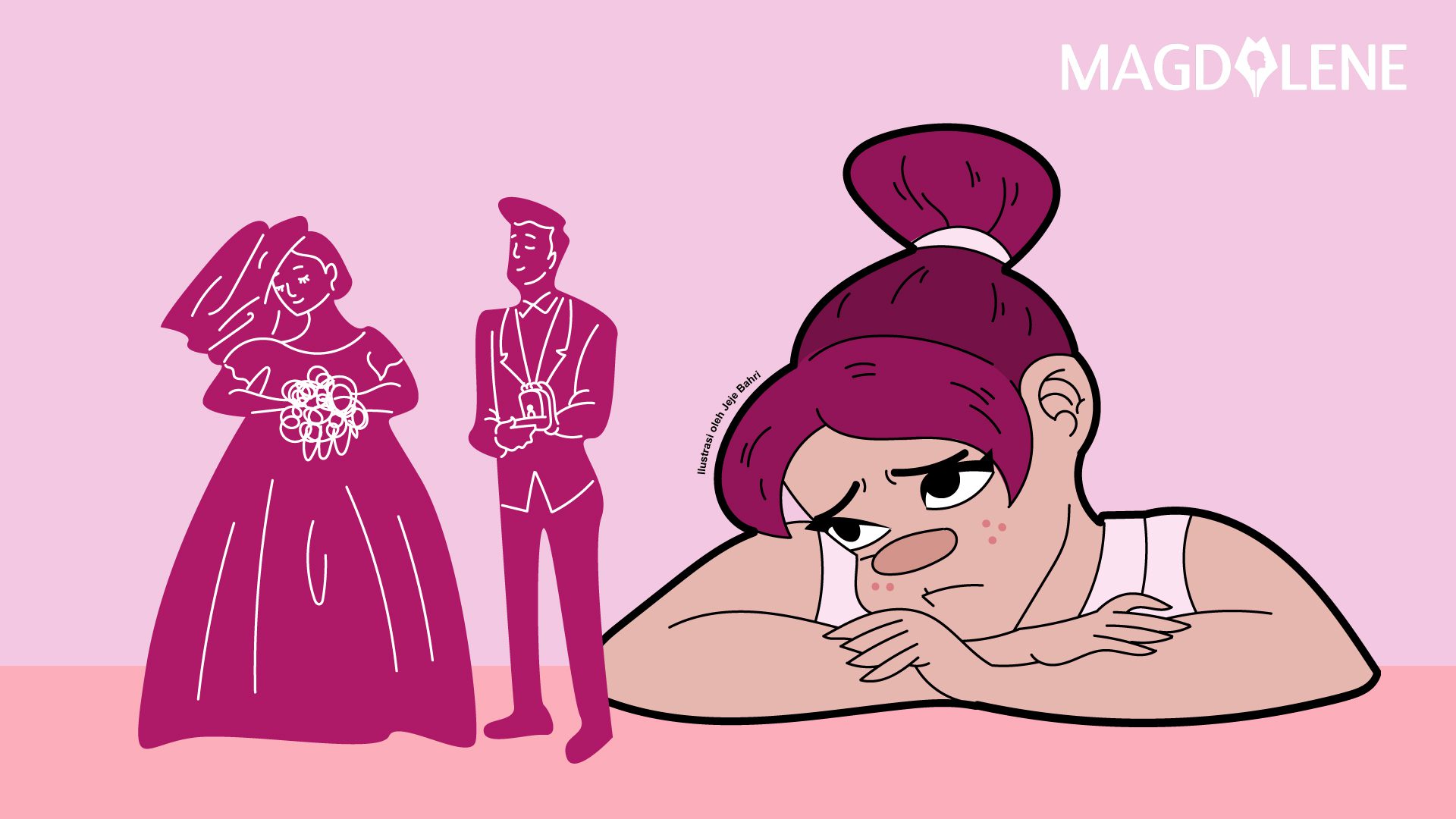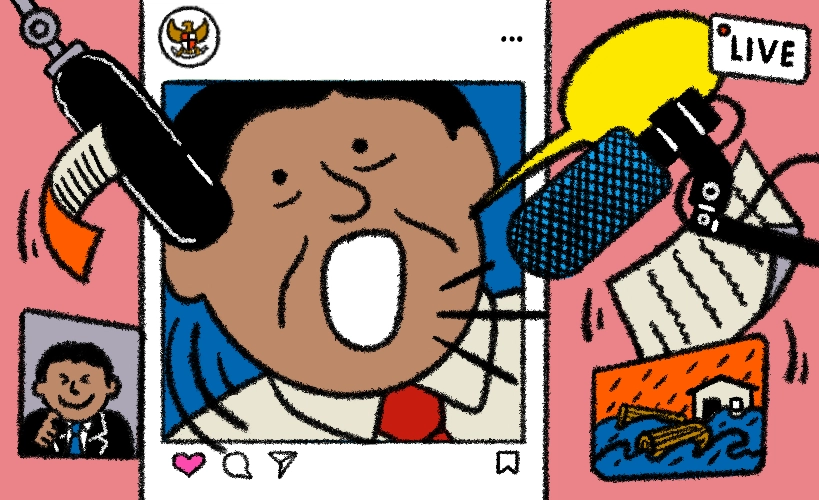Review ‘Monster’: Bukan yang Terbaik dari Kore-eda

Buat saya, Hirokazu Kore-eda adalah pencerita ulung. Nobody Knows (2004) adalah film pertamanya yang bikin saya selalu penasaran dan mulai mengikuti karya-karya lain Kore-eda.
Dari daftar tukang cerita ulung yang pintar menangkap luka dan cerita-cerita menyakitkan, nama Kore-eda selalu masuk paling atas. Ia salah satu yang paling berempati. Film-filmnya banyak bercerita tentang kisah-kisah mereka yang tak diinginkan.
Ada cerita Akira, anak terlantar dalam Nobody Knows (2004); atau Kohichi dan Ryunosuke, dua kakak-adik yang terpisah karena perceraian orang tua mereka dalam I Wish (2011); atau yang paling teranyar di ingatan, kisah “keluarga palsu” dalam Shoplifters (2018) yang terdiri dari orang-orang miskin dengan label kriminal.
Film terakhirnya Broker (2022) juga menangkap nuansa orang-orang yang tak diinginkan itu lewat lima karakter utamanya. Mereka yang tak diinginkan ibunya, tak diinginkan orang tua, tak diinginkan anaknya, tak diinginkan pasangan, tak diinginkan negara.
Selalu ada simpati besar buat karakter-karakter-yang-tak-diinginkan dalam film-film Kore-eda. Termasuk dalam Monster, film terbarunya yang bercerita tentang dua anak lelaki yang harus menghadapi kejamnya dunia cuma karena mereka punya perasaan mendalam pada masing-masing.

Plotnya, secara teknis, dibagi Kore-eda menjadi tiga bagian yang diceritakan lewat tiga perspektif berbeda. Pertama, ibu (Sakura Ando) yang khawatir melihat perubahan ganjil tingkah laku anaknya, Minato Mugino (Soya Kurokawa). Semua yang bolong dalam perspektif sang ibu lalu diisi oleh bagian kedua yang diceritakan lewat perspektif gurunya (Eita Nagayama), terutama hal-hal yang dilewati Minato di sekolah.
Lalu, sebagai pelengkap, sepertiga terakhir film diceritakan langsung lewat sudut pandang Minato.
Dengan cara ini, Kore-eda ingin menyentil kita—penonton sekaligus masyarakat—untuk bisa melihat sebuah cerita dengan sudut pandang yang lengkap, terutama ketika membicarakan hal yang dihadapi protagonis utama kita, Minato. Di saat bersamaan, Kore-eda juga ingin mengingatkan bahwa kita—penonton dan masyarakat—akan selalu punya blind spot (titik buta) saat melihat suatu cerita atau peristiwa.
Cara ini ternyata berhasil bikin kita bersimpati pada Minato, seorang bocah sekolah dasar yang tiba-tiba galau setengah mati karena sadar punya rasa pada kawan sekelasnya, Yori (Hinata Hiiragi). Masalahnya, Yori adalah anak laki-laki yang sering di-bully dikelas karena dianggap kemayu dan feminin.
Sebagai bocah, keresahan Minato muncul karena dia sadar bahwa perasaannya pada Yori tidak diterima di masyarakat, atau norma di lingkungannya tumbuh. Hal itu bikin Minato tak leluasa bicara jujur pada ibunya sendiri, bahkan berbohong, atau memfitnah gurunya hanya demi melindungi diri sendiri dan Yori.
Banyak orang lalu bersimpati pada Minato dan Yori setelah menonton Monster. Lalu menyebut monster sebenarnya dalam film itu adalah kita semua yang tega dan begitu keras pada anak-anak seperti mereka.
Pada level itu, saya pikir Kore-eda berhasil membawa Monster sebagai film queer yang diceritakan oleh heteroseksual untuk para heteroseksual. Kacamata yang dipakai dalam sepanjang cerita jelas-jelas adalah: heteronormativitas. Fungsinya jelas: satu, untuk bikin protagonis utama mudah diberi simpati, lalu penonton bisa melihat sendiri bagaimana kejam bengisnya heteronormativitas itu sendiri.
Baca juga: Review ‘Broker’: Menguliti Label-label Manusia ala Kore-eda
Debat tentang Ending yang Diperlukan
Saat bilang Monster adalah film yang diceritakan oleh heteroseksual untuk para heteroseksual, saya tidak sedang menebak-nebak orientasi seksual Kore-eda. Saya cuma sedang membandingkan Monster dengan film-film yang bercerita tentang hidup orang queer. Terutama yang dibikin oleh orang queer sendiri.
Keberpihakan Kore-eda untuk bersimpati pada Minato dan Yori adalah statement yang jelas: Ia berpihak pada mereka. Namun, ending film yang dibikin terbuka dan multitafsir jadi kontroversi.
Spoiler alert.
Monster ditutup dengan adegan longsor yang menimpa Minato dan Yori. Di saat Ibunya dan sang Guru menggali-gali tempat yang mereka duga berisi Minato dan Yori, di sisi lain, kedua anak itu justru keluar dan berlari ke tempat lebih terang.
Adegan penutup tersebut lalu jadi pertanyaan besar: Apakah dua bocah itu mati?

Baca juga: Menjadi Positif: Serial Komik tentang Pria Gay Indonesia dengan HIV
Pertanyaan ini jadi penting karena ujung tragis di film queer sudah lama jadi perdebatan. Terutama yang mengeksploitasi identitas queer lewat hetero-gaze. Mereka sudah lama dipertanyakan. Ada masanya, film-film queer yang diproduksi fokus pada cerita-cerita sengsara hidup sebagai queer, misalnya mati karena HIV, mati karena amuk massa, diusir keluarga, atau ditinggal mati pasangan. Film-film ini lalu dikritisi karena bikin representasi cerita-cerita queer selalu depresif dan menyedihkan. Padahal, hidup tak selalu begitu.
Di beberapa interview, Kore-eda langsung menjawab bahwa Minato dan Yori tidak mati.
Dalam naskah aslinya, adegan terakhir adalah pertemuan Ibu dan Sang Guru dengan Minato dan Yori. Mereka dipanggil, lalu dua bocah menoleh, melihat ke belakang dan menatap langsung kamera—menembus tembok keempat. Adegan itu lalu dibuang Kore-eda, dan dengan sengaja memilih adegan yang lebih multitafsir.
Buat saya, adegan yang dibuang Kore-eda harusnya adalah ending yang jauh lebih baik. Ending yang dibiarkan di bioskop, seberapa besar pun upaya Kore-eda menjelaskan lalu mempertahankan argumennya untuk menyimpan ending itu, ternyata tetap tak bisa membendung dugaan multitafsir para penonton. Sehingga, Monster tetap hadir sebagai film queer yang dibuat untuk orang-orang dengan kacamata heteronormatif.
Diskusi yang ia bawa tidak terlalu progresif dibandingkan film-film queer yang sudah ada hari ini. Kesuksesan Monster jadi percakapan di media sosial dan fakta bahwa ia bisa ditayangkan di bioskop Indonesia adalah bukti dua hal: satu, kesuksesan Kore-eda sebagai pencerita ulung; dua, film ini masih meletakkan isu queer sebagai pertanyaan eksistensial buat kaum heteroseksual, belum mampu membayangkan hidup orang queer yang lebih kompleks. Alih-alih diskursus tentang masa depan yang lebih baik.