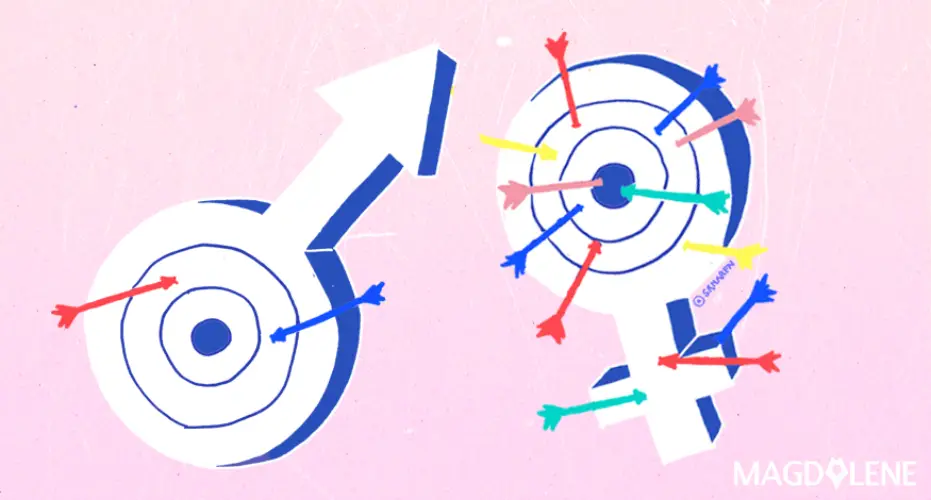‘Demi Hindari Zina’: Gus Zizan dan Sesat Pikir Perkawinan Anak
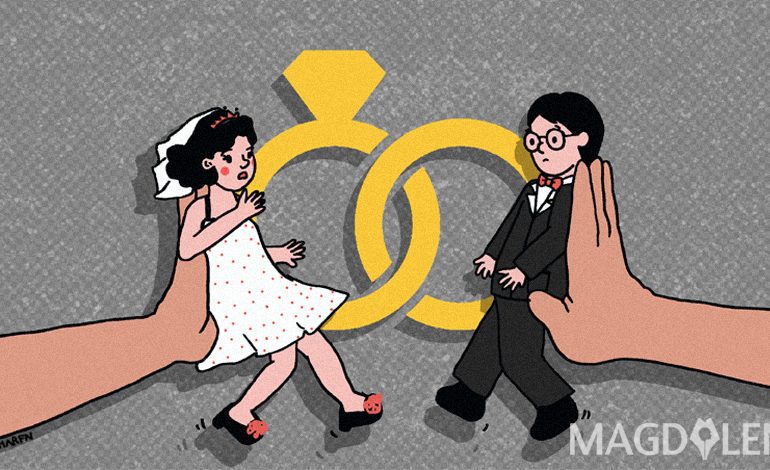
Pekan lalu, pasangan TikTokers—Gus Zizan, 21 dan S, 17 dikritik netizen karena melangsungkan perkawinan anak. Dari unggahan ibu S di Instagram story, pernikahan ini bertujuan untuk menyempurnakan setengah agama—yang sering didefinisikan dengan mengendalikan nafsu dan menghindari zina.
Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan, seseorang yang menikah berarti telah menyempurnakan setengah agama. Separuh sisanya tinggal bertakwa kepada Allah. Masalahnya, hadis tersebut kerap diartikan secara literal. Padahal, Kiai Faqih pernah bilang di Mubadalah, menyempurnakan agama yang dimaksud adalah komitmen menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, supaya terdapat nilai-nilai kebaikan dalam pernikahan.
Posisi pernikahan sendiri enggak bisa disejajarkan dengan salat, puasa, maupun zakat. Lagi pula, ajaran Islam enggak mewajibkan pernikahan—itu bergantung pada kemampuan dan tujuan seseorang menikah.
Problemnya bukan cuma itu. Ibu S justru menormalisasi perkawinan anak lewat Instagram story. Ia menegaskan, pernikahan S dan Zizan berlandaskan agama dan sudah direstui keluarga. Kemudian ia mencontohkan beberapa tokoh zaman dulu yang menikah di usia anak: Siti Aisyah yang belum genap 10 tahun, Cut Nyak Dien berusia 12 tahun, dan Siti Oetari yang menikah dengan Sukarno di saat umur 16 tahun.
Padahal, praktik pernikahan itu perlu dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang karena kondisi sosiologis yang berbeda. Salah satunya pada abad ke-6, saat Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad. Pernikahan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan perempuan, sekaligus memberikan haknya sebagai manusia. Sebab, waktu itu anak perempuan mengalami perbudakan seks.
Kita kerap tak melihat lebih dalam bahwa di balik dalih pernikahan untuk menyempurnakan agama, ada dampak berlapis perkawinan anak.
Baca Juga: Kisah Resi Mencegah Perkawinan Anak di Kampungnya
Pemikiran Keliru Soal Perkawinan Anak
Ada berbagai dampak perkawinan anak: Mengganggu kesehatan fisik, mental, dan reproduksi, mendorong kemiskinan dan upah rendah, memutus pendidikan, hingga berisiko terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Beberapa hal itu menjadi sinyalemen pernikahan bukanlah solusi tepat untuk mencegah zina, yang kerap dijadikan pembenaran ketika pasangan heteroseksual berpacaran. Sebab, setiap orang bisa mengendalikan diri dan punya pilihan untuk tidak berhubungan seks—yang disebut sex abstinence. Dalam relasi romantis, pilihan tersebut bisa dikomunikasikan dengan pasangan dan perlu dihormati, tanpa memberikan tekanan untuk berhubungan seksual.
Namun, pemahaman ini perlu didukung oleh pendidikan seks komprehensif, untuk memahami seksualitas dan perkembangan remaja secara psikologis, biologis—mencakup sistem reproduksi dan kesehatan reproduksi, serta cara remaja memahami lingkungan sosial. Sayang, pendidikan seks belum masuk dalam kurikulum formal khusus di sekolah.
Sebenarnya pemikiran soal pernikahan anak sebagai solusi untuk menghindari zina, masih berlaku di berbagai tempat—seperti Lampung Tengah dan Indramayu. Dalam peluncuran riset International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) (2024) soal dispensasi pernikahan usia anak pada akhir September lalu disebutkan, kekhawatiran orang tua jika anaknya berzina, merupakan salah satu alasan perkawinan anak masih terjadi di kedua daerah tersebut.
Pandangan itu dipengaruhi oleh norma agama, sosial, dan budaya yang kemudian menimbulkan stigma di masyarakat. Selain itu, sulit bagi orang tua memutus rantai perkawinan anak karena ini merupakan sesuatu yang lazim. Menurut Duta Generasi Berencana (Genre) Siti Nurhasanah, kondisi ini dipertebal oleh beban ekonomi, membuat orang tua ingin mengalihkan tanggung jawab mengurus anak kepada menantu.
“Orang tua di sana (Indramayu) juga rata-rata lulusan SD. Makanya mereka menyarankan anaknya bekerja, dibandingkan sekolah,” ujar Siti saat menghadiri peluncuran diseminasi riset INFID.
Alasan lainnya adalah kehamilan tak diinginkan, sudah berhubungan seksual, dan relasi kuasa antara orang tua dan anak. Ketimpangan itu terjadi saat orang tua mendorong anaknya untuk menikah, supaya bisa bekerja sebagai buruh migran, karena salah satu persyaratannya berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah.
Terlepas dari orang tua yang mendesak anak untuk menikah, putusan hakim juga berperan penting dalam mengabulkan dispensasi nikah.
Temuan INFID bilang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 soal Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, belum tersosialisasi secara menyeluruh. Akibatnya, pemangku kepentingan belum memahami sehingga sulit untuk mengimplementasikan. Ada juga yang dipengaruhi unsur “mendesak” untuk sejumlah kasus: Hamil di luar nikah, khawatir akan berzina, saling mencintai, dan sudah bertunangan.
Selain itu, miskonsepsi konsep dan prosedur pemberian rekomendasi dalam PERMA, yang dipahami sebagai pemberian dukungan pernikahan. Biasanya, rekomendasi dipahami opsional karena ada klausul “dapat” dalam PERMA.
Misalnya di Pengadilan Agama Indramayu, tidak ada rekomendasi dalam putusan dispensasi pernikahan, sebagaimana dianjurkan dalam PERMA. Tapi, Pengadilan Gunung Sugih, Lampung Tengah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk memberikan rekomendasi setelah assessment.
Kemudian, independensi hakim dalam memutuskan perkara. Ini dipengaruhi oleh perbedaan struktur dan karakteristik kasus, menyangkut kepentingan terbaik anak. Contohnya saat menangani suatu kasus, hakim mempersiapkan “kepentingan anak” mengacu pada termohon dispensasi. Namun, di kasus berbeda, hakim memaknai “keputusan terbaik anak” sebagai bayi di dalam kandungan—jika kasusnya adalah hamil di luar nikah.
Lapisan-lapisan ini yang tak dilihat oleh pasangan TikTokers Zizan dan S maupun keluarganya. Mereka mengesampingkan usia S, dan memandang pernikahan sebagai penyempurnaan agama. Bahkan, kesiapan S untuk menikah diukur berdasarkan pemikiran kuat dan bijak yang S miliki, serta ilmu pranikah yang sudah disiapkan meski belum dewasa.
Sayangnya, mereka tak menyadari, keputusan ini bisa berdampak besar karena banyaknya audiens di media sosial yang menjadi pengikut mereka.
Baca Juga: Penyebab Tingginya Perkawinan Anak di Indonesia
TikTokers Tak Sadar Punya Audiens Besar
Di media sosial, netizen mengecap Gus Zizan dan S dengan sebutan “influencer” karena followers keduanya mencapai ratusan ribu. Studi Glossary of platform law and policy terms (2021) pun mengategorikan influencer berdasarkan jumlah pengikutnya—ada yang nano, mikro, dan mega. Biasanya para influencer menjaga relasi dengan pengikutnya, dengan memperhitungkan konten yang dipublikasikan.
Dengan kapasitas yang dimiliki, influencer memakai pengaruhnya untuk mempromosikan tujuan mereka—seperti dijelaskan dalam laporan Remotivi. Tujuan itu bisa berupa produk, atau mengadvokasi pandangan sosial. Dan keberhasilan mereka memanfaatkan pengaruhnya ditentukan oleh jumlah followers, like, dan engagement.
Hal itu menggambarkan influencer—atau TikTokers—seperti Gus Zizan, S, dan keluarga mereka bisa memengaruhi perspektif pengikutnya soal perkawinan anak. Terlebih mereka cenderung menormalisasinya.
Sebab, yang dikhawatirkan adalah dampaknya: Meningkatkan angka perkawinan anak—walaupun pada 2022 PUSKAPA Universitas Indonesia mencatat, jumlah dispensasi perkawinan anak semakin menurun pada 2020-2022, yakni 53,66 persen dari 41 putusan pada 2022. Mengingat sebagian masyarakat masih melanggengkan norma agama, sosial, serta budaya untuk melatarbelakangi perkawinan anak. Dan kejadian ini bisa menjadi pembenaran untuk mendorong perkawinan anak.
Lalu, upaya apa yang bisa dilakukan supaya perkawinan anak tidak semakin dinormalisasi?
Baca Juga: Bahagia Selamanya yang Semu: Perkawinan Anak Tingkatkan Depresi Perempuan
Intervensi yang Perlu Dilakukan
Idealnya, besarnya audiens di media sosial membuat influencer atau TikTokers menyadari dampak yang muncul dari setiap unggahan. Apalagi jika menyangkut value yang dimiliki, setidaknya influencer merasa bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikan.
Namun, untuk menekan perkawinan anak, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Karena itu, INFID menyarankan beberapa upaya yang bisa dilakukan. Pertama, Mahkamah Agung (MA) menurunkan aturan PERMA ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), agar lebih operasional dalam mengatur posisi rekomendasi, makna kepentingan terbaik anak, dan standarisasi indikator mendesak.
Kedua, menyosialisasikan regulasi perkawinan anak bagi pemangku kebijakan. Ketiga, pemerintah lebih berkomitmen dalam meningkatkan kemampuan analisis gender, pada pejabat tingkat daerah dan pusat. Termasuk melakukan anggaran responsif gender, untuk memastikan alokasi sumber daya program yang mendukung kesetaraan gender.
Keempat, untuk konteks perkawinan anak di desa, pemerintah desa perlu mengalokasikan dana desa dan membentuk komunitas anak. Ini merupakan upaya preventif dan penindakan tegas terhadap calo dispensasi nikah.
Kelima, organisasi non-profit memantau pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak dan memastikan peraturan tersebut berjalan dengan konsisten. Keenam, orang tua dan guru perlu meningkatkan kualitas pola asuh, sekaligus memberikan ruang bagi anak dalam menentukan keputusan. Ketujuh, tokoh agama memperbanyak khotbah yang adil gender.