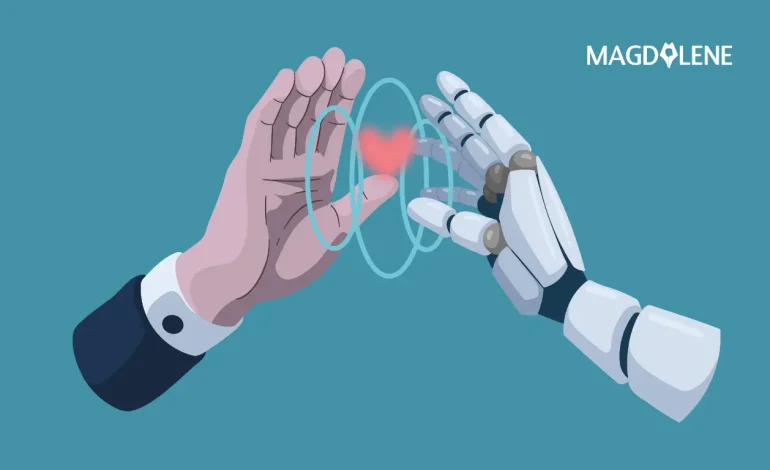Menonton Lagi “Virgin: Ketika Keperawanan Dipertanyakan”, Menonton Kebebasan Di Mata Konservatisme

Di titik klimaks Virgin: Ketika Keperawanan Dipertanyakan (2004), Biyan—tokoh utama yang diperankan Laudya Cynthia Bella—berdiri di hadapan audiens, mengumumkan bahwa dirinya masih perawan. Respons dari hadirin? Helaan napas lega dan tepuk tangan meriah.
Adegan ini tak hanya berfungsi sebagai konklusi dan jawaban atas judul filmnya, tetapi juga semacam kulminasi ideologis yang menggambarkan bagaimana film ini menyusun moralitasnya.
Disutradarai oleh Hanny R. Saputra dan turut dibintangi oleh Ardina Rasti dan Angie, Virgin mengikuti kehidupan tiga remaja perempuan SMA di Jakarta: Biyan, Stella, dan Katy. Ketiganya digambarkan menikmati gaya hidup “gemerlap perkotaan” yang tampil secara klise: budaya konsumerisme yang eksesif, rutin ke diskotik, nongkrong di pusat perbelanjaan, dan terlibat konflik dengan geng sebelah perkara rebutan pria tampan.
Melalui latar ini, dari luar Virgin tampak ingin memotret kebebasan dan eksplorasi hidup khas remaja. Namun, di balik fasad “gaya hidup bebas” itu, tersembunyi sebuah pengukuhan nilai-nilai konservatif, terutama dalam kaitannya dengan seksualitas perempuan.
Baca juga: Praktik Konversi: Upaya Sia-sia yang Menyiksa
Moralitas dan Gagasan Konservatif dalam Film Populer
Dalam film, tiga protagonis utama merepresentasikan spektrum pilihan seksual remaja: Stella telah berpengalaman secara seksual, Angie—satu-satunya yang datang dari kelas ekonomi rendah—”menjual” keperawanannya demi bisa beli gawai terkini, dan Biyan, si protagonis utama, berkomitmen untuk menjaga keperawanannya. Ketika cerita bergulir, keputusan masing-masing karakter pun berujung pada konsekuensi yang sangat berbeda.
Angie hamil dari pria tak dikenal dan menjadi korban kekerasan kliennya. Stella, yang bermimpi jadi selebritas dan rajin mengikuti casting, mengalami penyebaran video intim dan depresi ditekan stigma. Biyan, walau sempat terdesak untuk melepas keperawanannya guna melunasi utang ke seorang mafia setelah ketiganya menghilangkan sebuah mobil mewah, berujung tetap mampu mempertahankannya dan “dihadiahi” dengan pengakuan sosial.
Pola ini bukan tanpa makna. Sebaliknya, ia membentuk narasi yang sangat jelas: seks di luar pernikahan, apalagi yang dilakukan perempuan, harus dihukum, baik secara literal maupun simbolik.
Menurut Noël Carroll dalam Movies, the Moral Emotions, and Sympathy, film memiliki kecenderungan kuat untuk membentuk emosi moral audiensnya. Melalui teknik yang disebut “pre-focusing”, pembuat film mengarahkan simpati atau antipati penonton kepada karakter-karakter tertentu berdasarkan standar moral yang dianggap universal—keadilan, kebaikan, kepatutan.
Dalam Virgin, teknik ini digunakan secara intensif untuk membangun simpati terhadap Biyan dan sebaliknya, menggiring antipati penonton ke arah Stella dan Angie, sebagai karakter-karakter yang menganut nilai-nilai berseberangan dengan Biyan.
Baca juga: Saat Muslimah Tahu yang Dimau: Membaca Lagi Adegan Seks dalam ‘Perempuan Berkalung Sorban’
Salah satu strategi paling mencolok, tentu saja, adalah bagaimana narasi film disusun. Biyan adalah satu-satunya karakter yang punya ruang untuk, secara harfiah, menyuarakan pikirannya, yakni melalui voice over yang muncul saat ia menulis jurnal pribadinya. Layaknya Carrie Bradshaw dalam episode Sex and the City, dengan sebatang rokok di tangan dan laptop di hadapan, Biyan diberi kesempatan merasionalisasikan keputusannya untuk tidak melakukan hubungan seks.
Ia bukan alat naratif semata, melainkan mekanisme untuk membentuk interioritas—kemampuan audiens memahami motivasi internal dan kompleksitas emosional tokoh.
Sebaliknya, Stella dan Angie hanya didefinisikan oleh keputusan mereka untuk berhubungan seks. Alhasil, yang tertinggal hanyalah gambaran dua remaja perempuan yang “tergelincir” pada keputusan bodoh dan menderita karenanya. Di sini, Virgin tidak hanya menarasikan nilai moral; ia menghakimi.
Saya tidak bilang bahwa keputusan Biyan untuk tidak berhubungan seks adalah hal yang buruk untuk ditampilkan. Namun, dalam melakukan hal itu, saat bersamaan film merasa harus menyalahkan karakter yang keputusannya berbeda dengan Biyan. Padahal, via karakter Katy, film ini juga menyinggung isu seputar prostitusi remaja; di mana, secara tak terpisahkan, kelas dan relasi kuasa membuat keadaan makin rumit. Alhasil, saat pilihan hidup Katy tetap diganjar dengan nasib nahas, ada rasa bias kelas dan ketidakpekaan yang terkecap.
Baca juga: Membaca Waktu dan Krisis Iklim dalam ‘Sore: Istri dari Masa Depan’
Konservatisme yang Dibungkus Glamor
Virgin menarik jadi objek kajian retrospektif karena sebagai produk awal millennium—periode waktu yang lekat dengan nuansa “era baru” dan gelombang awal globalisasi—ia menggabungkan dua wacana yang seolah bertentangan: kebebasan remaja urban dan konservatisme seksual. Film ini rilis di tengah tren film Indonesia awal 2000-an yang mengeksplor tema kehidupan remaja kota, seperti Buruan Cium Gue (kemudian diganti menjadi Satu Kecupan), 30 Hari Mencari Cinta, dan Me vs High Heels.
Dalam permukaan, film-film ini menampilkan pemberontakan terhadap nilai-nilai lama, nilai-nilai dari generasi sebelumnya. Tapi, saat ditilik lebih dalam, pada intinya ternyata kebanyakan dari mereka tetap menjaga tatanan moral tradisional.
Dengan kata lain, Virgin bukanlah film yang mencoba menggugat norma sosial, melainkan memperkuatnya dalam bentuk baru yang lebih menarik dan trendi. Keperawanan menjadi simbol moral utama, bahkan nilai tukar bagi penghargaan sosial. Bahwa Biyan mendapat pengakuan dan simbolik “kemenangan” bukan karena keberaniannya mengambil keputusan dalam kondisi sulit, melainkan karena ia tidak mengambil keputusan yang salah (menurut moral arus utama)—menjaga keperawanan.
Sementara itu, isu-isu penting lain seperti prostitusi remaja, kekerasan seksual, dan tekanan ekonomi justru hanya menjadi latar atau pemicu konflik. Tidak ada ruang untuk kritik struktural. Film ini justru mereduksi kompleksitas menjadi soal moral individu.
Yang ironis, Virgin tampak seolah menawarkan pilihan yang beragam kepada perempuan muda. Namun kenyataannya, hanya satu pilihan yang dianggap benar. Dalam masyarakat patriarkal, ini adalah strategi klasik: membingkai satu bentuk perilaku sebagai bebas, namun memberi ganjaran hanya kepada perilaku yang sesuai norma. Pilihan bebas yang semu.
Dengan menampilkan gaya hidup remaja urban yang glamor, film ini seakan memberi izin pada audiens untuk menikmati fantasi “liar” khas kota besar—diskotik, pesta, kebebasan seksual. Namun di akhir cerita, semuanya ditertibkan melalui ganjaran moral.
Film ini menjual fantasi, lalu menyisipkan moralitas dalam bentuk hukuman dan penghargaan.
Dua dekade sejak rilisnya, Virgin tetap relevan sebagai bahan refleksi mengenai bagaimana media memproduksi dan mereproduksi nilai-nilai sosial. Dalam iklim yang tampak semakin terbuka terhadap wacana seksualitas dan kebebasan tubuh perempuan, kita perlu tetap waspada pada bentuk-bentuk konservatisme baru yang diselubungi estetika kebebasan.
Sebab, seperti yang Virgin telah tunjukkan, terkadang bentuk pengekangan paling efektif datang bukan dari larangan eksplisit, melainkan dari arahan simpati dan rasa bersalah yang ditanamkan secara subtil melalui media populer.