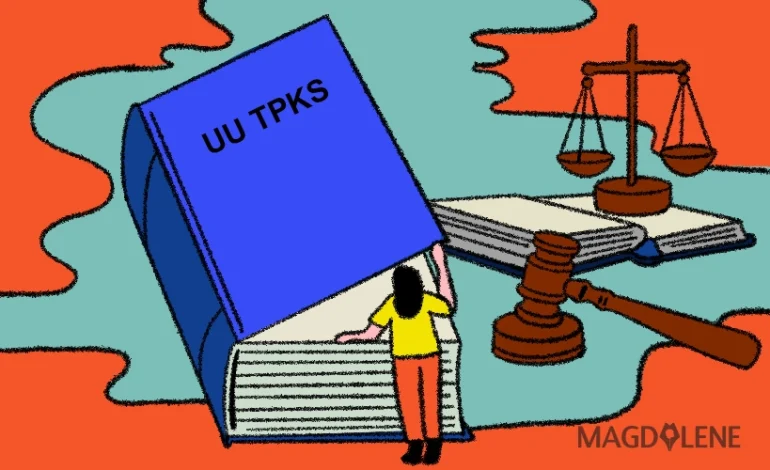Single Mom “By Accident” Is Not A Real Thing!
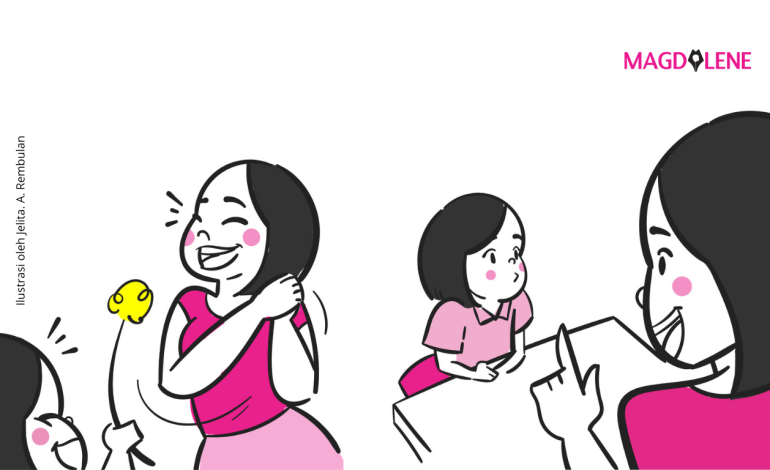
Buat saya yang hampir menginjak usia setengah abad, istilah “married by accident” atau MBA bukan hal yang asing. Saya tumbuh di lingkungan keluarga Jawa yang konservatif, di mana seksualitas perempuan adalah topik tabu. Kata “MBA” yang melekat sejak kecil akhirnya tak pernah berasosiasi dengan gelar akademis di kepala saya, melainkan hukuman sosial karena “terlanjur hamil”, alias sebuah aib yang harus ditutup rapat-rapat.
Sampai suatu hari, seorang perempuan yang tak saya kenal mengirimi saya DM di Instagram. Ia memperkenalkan istilah baru: Single Mom by Accident (SMbA), katanya, sebagai lawan dari Single Mom by Choice (SMbC)—istilah yang saya pakai di salah satu unggahan saya.
Menurutnya, perempuan yang hamil di luar nikah dan memilih melanjutkan kehamilannya adalah SMbA, bukan SMbC. Ia menyatakan keberatan karena unggahan saya disebut menyebabkan akun Instagram-nya “dikepung” warganet yang menyebutnya pelaku zina. Ia merasa saya, tanpa sengaja, merugikan perempuan-perempuan seperti dirinya.
Sebentar, maksudnya gimana, ya?
Baca juga: Bahagia dan Kejar Mimpi Pasca-Bercerai: Cerita Tiga Perempuan
Sedikit mundur ke belakang, saya sempat mengunggah opini soal kehamilan Erika Carlina yang sempat viral. Saya mengapresiasi keberanian perempuan—bukan cuma Erika—yang tetap mempertahankan kehamilan tidak terencana (KTD) meski tanpa pernikahan. Bagi saya, poin utamanya adalah soal agensi dan pilihan.
Saya tidak sedang menormalisasi “seks bebas” atau hubungan seks berisiko. Saya sedang menegaskan pentingnya agensi perempuan. Bahwa seorang perempuan berhak memilih untuk tetap hamil tanpa perlu menikah demi “menutup malu” atau “mengurangi dosa”. Yang menggelitik saya, saya bahkan tidak mengenal perempuan yang DM saya ini. Tapi dia begitu yakin unggahan saya telah membuat akunnya jadi sasaran warganet. Aneh juga, ya?
Tapi yang lebih mengusik adalah bagaimana ia berusaha mengatur narasi saya, sambil tanpa sadar merendahkan perempuan lain. Kurang lebih begini inti pesannya (sudah saya parafrasekan):
“Saya ini solo mother by choice. Saya jalani IUI di Eropa, beli donor sperma dari bank sperma internasional. Bukan bermaksud menggurui, tapi mungkin lebih baik cari bahasa lain. Karena hamil di luar nikah itu bukan by choice, itu by accident.”
Saya langsung berkerut membaca kata “IUI”, “Eropa”, dan “bank sperma internasional”. Jadi maksudnya, istilah Single Mom by Choice hanya sah digunakan oleh perempuan yang punya anak lewat prosedur medis mahal dan legal seperti dia? Sementara perempuan yang hamil di luar nikah (termasuk korban kekerasan seksual) tidak berhak memakai label yang sama?
Benarkah?
Bagi saya, agensi menjadi ibu tunggal tidak ditentukan dari cara hamilnya—apakah lewat inseminasi buatan, adopsi, atau hubungan seksual. Intinya adalah, keputusan sadar untuk tetap melanjutkan kehamilan dan membesarkan anak sendiri, tanpa pasangan.
Kehamilannya mungkin tidak direncanakan. Tapi menyebutnya “kecelakaan” sama saja dengan menafikan pilihan dan kekuatan perempuan dalam mengambil keputusan besar atas tubuh dan hidupnya. Istilah “by accident” justru bisa dipakai untuk merendahkan ibu lain yang “caranya beda”.
Coba pikir dulu baik-baik. Bagaimana dengan perempuan yang ditinggal suami saat sedang hamil? Yang menjadi korban pemerkosaan? Yang mengadopsi anak? Yang mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua dari keponakan atau kerabat yang ditinggal wafat?
Baca juga: Ngobrol Soal Janda Bareng Politisi Luluk Nur Hamidah: Ternyata Memang Tak Seseksi Stigmanya
Kalau semua pengalaman itu kita simplifikasi sebagai “accident”, kita sedang menghapus kenyataan tentang patriarki, relasi kuasa, dan ketimpangan akses. Kita sedang menyamakan pengalaman yang kompleks hanya berdasarkan cara hamilnya.
Menjadi Single Mom by Choice bukan keistimewaan yang hanya boleh dipakai oleh perempuan dengan privilese tertentu. Ini soal keberanian mengambil keputusan besar, hidup dalam stigma, dan bertahan tanpa dukungan pasangan.
Kalau kamu merasa label SMbC hanya cocok untuk perempuan seperti kamu—yang prosesnya legal, medis, dan terstruktur—mungkin masalahnya bukan pada label. Tapi pada kebutuhan validasi yang belum selesai.
Perempuan sudah cukup sering dihakimi oleh masyarakat. Jangan kita tambah luka itu dengan saling menghakimi sesama perempuan. Kalau kata keponakan saya, “Plis banget jangan ngadi-ngadi demi validasi.”
Baca juga: Anjuran Suswono Janda Kaya Nikahi Pengangguran: Sudah Seksis, Objektifikasi Pula
Hargai keberanian perempuan lain, meskipun kisah hidupnya berbeda. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang bagaimana kamu punya anak, tapi tentang bagaimana kamu memilih menjalani hidupmu, dengan kepala tegak.
Untuk semua sobat perempuan, seperti yang selalu saya tulis di Instagram: Be kind. Stay kind. Kita tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih tinggi. Jangan lupa, cek privilese sebelum menghakimi.