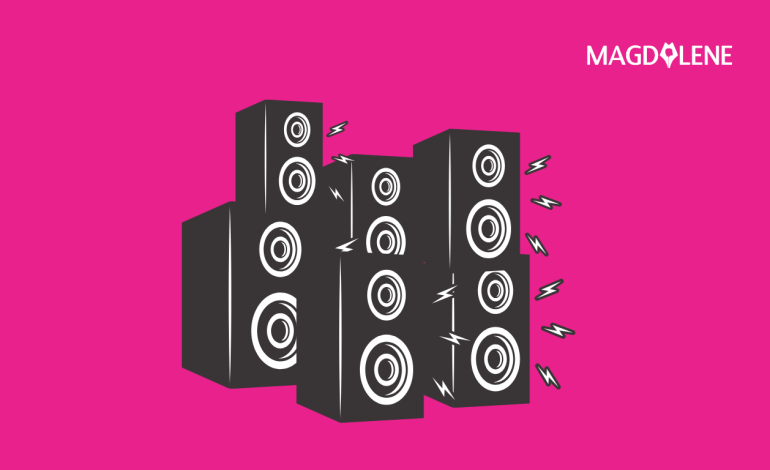Gara-gara Tambang, Tak Ada Lagi Jawa di Masa Depan

Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Sebanyak 151,59 juta jiwa atau sekitar 56,1 persen dari total 284,4 juta jiwa penduduk negara kita bermukim di sana.
Namun, jumlah penduduk yang besar tidak sebanding dengan daya dukung lingkungannya. Meski menjadi lumbung padi dari setengah produksi beras nasional, hanya 5,9 persen dari total air nasional yang tersedia di pulau ini.
Sementara itu, kerusakan lingkungan terus memburuk, terutama akibat perluasan tambang di wilayah karst dan pesisir. Pertambangan menyebabkan penyusutan lahan, mempercepat penurunan muka tanah, dan meningkatkan risiko banjir rob serta tenggelamnya wilayah pesisir.
Pulau Jawa mengalami krisis ekologis yang serius akibat ketimpangan antara jumlah penduduk yang sangat besar, ketersediaan air yang minim, dan tekanan industri ekstraktif seperti pertambangan.
Situasi ini membuat kita patut bertanya, apakah Pulau Jawa masih layak dihuni dalam 10–20 tahun ke depan?
Baca juga: Kisah Mereka yang Mengais Rupiah dari Timah
Ancaman Nyata Tambang di Pulau Jawa
Krisis lingkungan di Pulau Jawa bukan hanya ancaman masa depan, melainkan masalah serius yang sudah terjadi sekarang. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 bahkan mencatat bahwa tutupan lahan dan ketersediaan air di Jawa akan terus menurun hingga mencapai sangat terbatas bahkan langka.
Sebanyak 34 kota/kabupaten pesisir di Jawa tergolong sangat rawan bencana, diperparah oleh kombinasi penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut.
Sebagai contoh, Jakarta dan Semarang sedang menghadapi laju penurunan tanah 1-15 cm per tahun. Di luar Jawa, laju penurunan tanah terjadi secara bervariasi antara 1-8 cm per tahun.
Peningkatan muka air laut setinggi 50 cm yang bersamaan dengan penurunan tanah berpotensi menggenangi kawasan padat penduduk secara permanen di pesisir kota di Jakarta maupun pantai utara Jawa (pantura).
Sementara itu, 92 persen pasokan air baku masih bergantung pada air permukaan yang mudah terpengaruh cuaca dan musim.
Krisis makin parah akibat ekspansi tambang, terutama di kawasan karst yang berperan vital sebagai penyangga cadangan air. Salah satu contohnya adalah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Rembang, Jawa Tengah.
Peta citra satelit selama 2013 – 2024 memperlihatkan area bukit kapur alami Watuputih sudah berubah menjadi kawasan industri semen. Aktivitas penambangan mengganggu pada sistem resapan dan aliran air tanah.
Studi CELIOS menunjukkan bahwa total kerugian akibat aktivitas tambang dan industri semen di CAT Watuputih mencapai Rp35,9 triliun selama periode 2014 hingga 2025. Angka ini mencakup kerusakan lingkungan, kehilangan air bersih, dampak kesehatan, serta hilangnya fungsi ekosistem.
Studi membuktikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang tidak sebanding dengan kerugian lingkungan, sosial, dan fiskal yang ditimbulkannya.
Hal yang lebih ironis, kerugian ini tidak pernah ditanggung oleh pelaku usaha. Warga sekitar harus menerima kerusakan lingkungan tanpa kompensasi yang tidak pernah menjadi bagian dari perhitungan kebijakan publik.
Perusahaan untung besar, sementara masyarakat dan lingkungan yang menanggung kerusakannya.
Kasus tambang pasir di pesisir Yogyakarta menunjukkan pola serupa. Tambang merusak sumber air bawah tanah dan memperparah kekeringan yang sudah kronis.
Tambang pasir di wilayah ini menimbulkan kerugian lingkungan sekitar hingga Rp2,58 triliun per tahun. Namun, data menunjukkan bahwa 85 persen tambang di wilayah ini tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Sebanyak 86 persen di antaranya pun tidak punya Kepala Teknik Tambang. Sekitar 14 persen izin tambang memiliki kesalahan informasi cadangan dan luas lahan yang fatal, misalnya angka yang tertera di dokumen resmi perizinan tidak sama dengan realitas di lapangan. Sepanjang 2019–2024, ditemukan setidaknya lebih dari 60 temuan pelanggaran.
Baca juga: Warga Torobulu dan Mondoe di Lumbung Nikel: Janji Kesejahteraan, Berbuah Kemiskinan
Jawa Enggak Bisa Lagi Ditambang
Pemerintah menetapkan Jawa sebagai koridor ekonomi berbasis inovasi, riset, dan teknologi, bukan zona industri ekstraktif. Jadi, kegiatan pertambangan jelas bertentangan dengan arah pembangunan dan harus segera dihentikan.
Moratorium izin tambang secara hukum bisa dilakukan oleh presiden lewat Instruksi Presiden (Inpres).
Hal serupa pernah dilakukan lewat Inpres Nomor 5 Tahun 2019 untuk menghentikan izin di hutan primer dan gambut.
Dengan kondisi dan arah kebijakan saat ini, moratorium pertambangan di Jawa tidak hanya sah secara hukum, tapi juga wajib secara etis dan ekologis. Analisis CELIOS diolah dari berbagai sumber (ESDM, BPS, dan Pemda), total IUP/WIUP se-Jawa dan Madura mencapai 2.195.
Krisis ekologis di Pulau Jawa bukan sekadar isu lingkungan. Ia adalah persoalan keadilan, tata kelola sumber daya, dan perlindungan hak asasi manusia.
Instruksi Presiden menjadi langkah hukum paling cepat dan efektif untuk menghentikan sementara pemberian izin tambang—tanpa perlu menunggu revisi peraturan perundang-undangan.
Langkah ini bukan hanya tindakan administratif, melainkan juga bentuk konkret penegakan prinsip kehati-hatian, perlindungan hak dasar warga, dan pembangunan yang konsisten dengan kebijakan jangka panjang.
Bersamaan dengan itu, pemerintah harus menata ulang strategi pembangunan agar selaras dengan krisis iklim dan kebutuhan rakyat.
Lingkungan harus dipulihkan dan kita perlu menggeser fokus ke ekonomi restoratif yang tidak merusak. Hanya dengan begitu, Pulau Jawa masih bisa dihuni dan menjadi wajah masa depan Indonesia.
Muhamad Saleh, Researcher in Law and Regulatory Reform, Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Ilustrasi oleh Karina Tungari