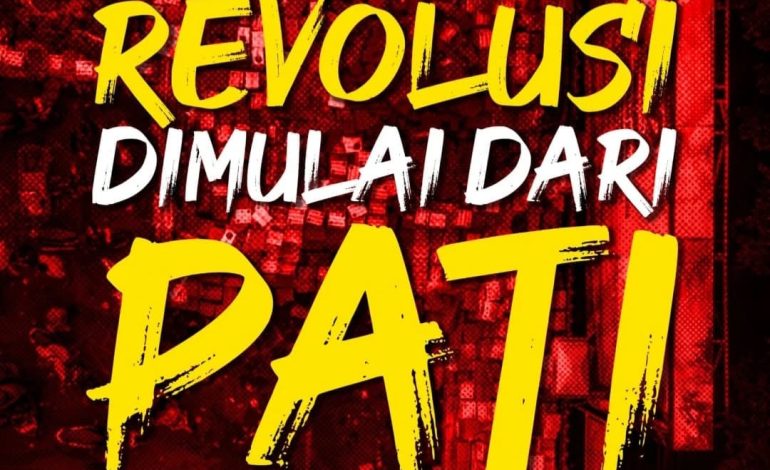Menggugat Standar Cantik bagi Perempuan dengan Disabilitas Netra

Saya perempuan dengan disabilitas netra. Meski tidak sepenuhnya kehilangan penglihatan, kondisi mata saya secara fisik tidak dianggap “normal”. Di usia 30-an, saya telah melewati banyak kegelisahan soal penampilan dan soal identitas saya sebagai perempuan dengan disabilitas penglihatan.
Karena saya pernah melalui masa-masa penuh keraguan itu, saya merasa penting membagikan pengalaman ini. Sebab saya yakin, banyak perempuan muda lain—dengan atau tanpa disabilitas—pernah bergulat dengan pertanyaan tentang tubuh, nilai diri, dan apa makna cantik di mata masyarakat. Kita semua adalah produk dari konstruksi sosial yang menempatkan kecantikan sebagai syarat kesempurnaan perempuan.
Baca juga: Annisa Emery Manik: Perempuan Tuli Penggerak Advokasi Gender Inklusif
Ketika beranjak remaja, orang-orang merasa bebas mengomentari penampilan saya. Kalimat seperti, “Gigimu rapi, hidungmu mancung, sayang, matamu bergerak ke sana ke mari,” sering saya dengar. Ungkapan seperti ini disampaikan oleh siapa saja: tetangga, kerabat, dan teman sebaya. Semakin mereka merasa akrab dengan saya, semakin berani mereka menyatakan betapa anehnya mata saya. Seolah-olah bentuk mata saya adalah kesalahan yang pantas disesali.
Sebagai perempuan dengan disabilitas netra, komentar semacam ini menyakitkan. Tak hanya di masa remaja, bahkan hingga saat ini, setelah saya telah menjadi pendeta dan dipercaya melayani jemaat, perasaan itu terkadang masih muncul. Dulu, saya sering terjaga malam-malam, takut menghadapi dunia keesokan harinya. Yang saya khawatirkan bukan aktivitas berat, tapi pertanyaan: “Kenapa matamu begitu?”
Kerap saya menatap cermin dalam keputusasaan sambil meraba setiap bagian dari wajah tirus ini. Saya bertanya-tanya, mungkinkah karena mata saya, lelaki enggan mendekat? Mungkinkah karena ini saya belum menikah? Kalimat menyakitkan seperti itu sering terucap dari mulut saya sendiri.
Waktu remaja, keinginan saya untuk dianggap cantik begitu kuat, bahkan terkesan obsesif. Saya kerap bertanya kepada orang-orang, termasuk laki-laki, apakah saya cantik. Kini, saya merasa pertanyaan itu sangat menyedihkan. Sebab saya tahu, setiap kejujuran yang mereka berikan bisa menjadi luka baru buat saya.
Beberapa teman menyarankan saya merias wajah—memulas mata dan pipi agar “terlihat cantik.” Tapi saya tak habis pikir. Bagaimana mungkin saya harus menonjolkan bagian wajah yang selama ini justru ingin saya sembunyikan? Bola mata saya yang tidak bisa fokus, yang bergerak tak tentu arah, harus diperjelas dengan perona mata? Apakah itu artinya saya harus mengejar standar kecantikan perempuan non-disabilitas yang jelas-jelas tak bisa saya capai?
Baca juga: Tantangan Mobilitas Perempuan Disabilitas di Jakarta
Kecantikan yang tak ramah bagi penyandang disabilitas
Setelah berdiskusi dengan banyak teman perempuan, saya mulai memahami bahwa kecantikan bukanlah sesuatu yang netral. Ia dibentuk oleh masyarakat—oleh media dan budaya. Kecantikan adalah konstruksi sosial yang sarat diskriminasi.
Saya pun bertanya: apa sebenarnya definisi perempuan cantik? Jawabannya membuat saya tercengang. Ternyata, cantik artinya utuh secara fisik—terutama wajah. Lalu bagaimana dengan kami, perempuan dengan disabilitas netra, yang sejak awal dianggap “tidak sempurna”?
Orang sering mengatakan, selama wajah tidak “cacat”, bagian tubuh lain bisa ditoleransi. Tapi pada kami, mata adalah wajah. Maka perbedaan pada mata kami—entah bentuknya tidak simetris, terbuka sebelah, tidak ada bola mata, gerakannya tak terkendali, atau tak bisa fokus—langsung membuat kami didefinisikan sebagai “buruk rupa”.
Masyarakat kerap sulit memahami ekspresi wajah kami. Mereka bertanya-tanya: apakah kami sedang menyimak? Melamun? Sedih? Bahagia? Tidur? Dan karena mereka tidak bisa menebak, kami pun dianggap aneh—padahal hanya kami sendiri yang tahu apa yang kami rasakan.
Konstruksi ini bukan hanya berasal dari budaya populer, tapi juga dari tafsir keagamaan dan nilai politik. Alkitab mencatat dalam Imamat 21:16-24, bahwa para imam yang cacat badannya—buta, lumpuh, bercacat muka dan berbagai cacat lain—tidak boleh mendekat ke mezbah untuk memberikan persembahan karena mereka dianggap najis. Interpretasi sempit akan menggunakan ayat ini sebagai stigma bagi orang dengan disabilitas, apalagi jika dia perempuan. Bahkan ketika tubuh kami bisa berfungsi secara utuh dan sehat, kami tetap dianggap kurang, dianggap tak bisa apa-apa.
Saya sering bertanya: mengapa kecantikan begitu lekat dengan sorot mata? Mengapa tubuh yang berbeda langsung dianggap tak menarik? Selama konsep cantik masih diukur dari visual yang “sempurna”, selama itu pula kami—perempuan dengan disabilitas penglihatan—akan terus tersingkir dari definisi cantik.
Baca juga: ‘Aku Perempuan Unik’, Saat Perempuan Difabel Wujudkan Kesetaraan Lewat Seni
Menemukan kecantikan dari dalam
Budaya, agama, dan politik telah lama membentuk pandangan bahwa orang dengan disabilitas bukanlah manusia yang “utuh”—apalagi jika ia perempuan. Dalam kerangka ini, kami tak hanya dianggap jauh dari cantik, tapi juga dianggap tak mampu, tak berdaya, dan tidak layak menentukan hidup kami sendiri.
Selama standar kecantikan bergantung pada penampilan mata dan kesan fisik yang bisa dilihat, diskriminasi akan terus terjadi. Sudah waktunya kita menggeser cara pandang. Bahwa cantik bukan soal sorot mata, simetri wajah, atau kulit mulus. Tapi soal kejernihan pikiran, ketenangan batin, nada suara yang hangat, serta kelembutan hati yang terpancar dari tindakan dan kata-kata.
Itulah yang saya rawat dalam diri saya. Saya belajar mencintai jati diri saya sebagai perempuan dengan disabilitas penglihatan. Saya mungkin tak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan dan memahami dengan lebih dalam. Mungkin saya buta mata, tapi saya berusaha untuk tidak buta hati.
Sudah saatnya kita mengakhiri pencarian pengakuan dari luar soal kecantikan lahiriah. Karena pada akhirnya, kecantikan yang paling penting adalah yang kita cintai dalam diri sendiri. “I love myself “
Yohana Maitimu adalah pendeta perempuan dengan disabilitas netra. Ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Disabilitas Netra Indonesia (Pertuni) Maluku dan aktif dalam pemberdayaan komunitas.