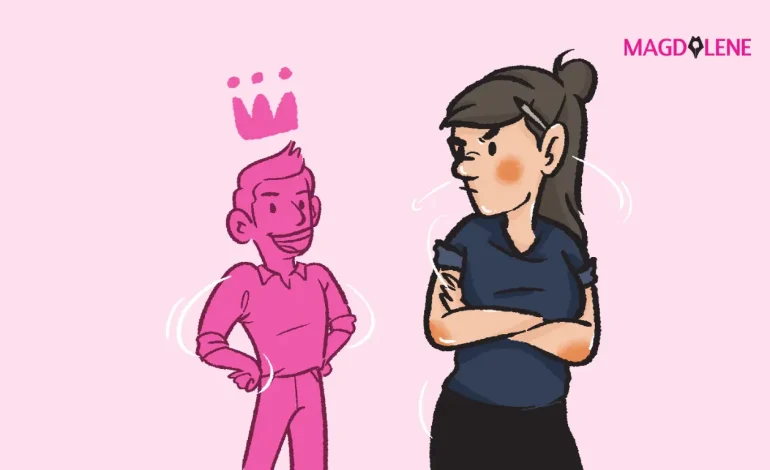MBG di Mata Ibu: Anak Dipaksa Menelan Tanpa Rasa Aman

“Basi itu seperti apa, Ma?”
Anak saya bertanya sebelum berangkat ke sekolah. Hari itu ada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia bukan sedang mencari definisi “basi” melainkan rasa percaya.
Saya pun bukan ahli gizi cuma seorang ibu. Setiap hari saya hanya menimbang satu hal sederhana: Satu suapan yang masuk ke perut aman, aman atau tidak? Sebab buat saya, nyawa anak bukan angka di tabel, dan rasa aman bukan bonus, tapi hak anak sekaligus tanggung jawab negara.
Sejak awal 2025, kabar keracunan yang diduga terkait MBG terdengar beruntun dari berbagai daerah. Jumlah kasus mungkin berbeda-beda, tetapi benang merah gejalanya mirip. Anak mual dan muntah di kelas, antrean panjang di puskesmas, dapur sekolah yang ditutup sementara, hingga penyelidikan yang masih berjalan. Setiap kali, selalu ada penjelasan resmi bahwa persentase kasus keracunan kecil dibanding total porsi yang dibagikan. Namun di rumah, statistik itu punya wajah, ya wajah anak kami sendiri.
Baca juga: Perempuan Pukul Panci, Desak Penghentian Program MBG Sekali Lagi
Transparansi yang Hilang di Meja Makan
“Ma, besok kami dikasih makan apa, ya? Adek takut.”
Saya tidak bisa menjawab. Sebagai orang tua, kami tidak pernah diberi tahu siapa yang memasak, di mana dapurnya, apa menunya, jam berapa dimasak dan tiba di sekolah, serta bagaimana pengawasannya. Saya bahkan tidak tahu apa yang akan disuapkan ke mulut anak saya besok, apalagi memastikan aman atau tidak. Informasi itu tidak sampai ke kami. Di sekolah, yang diumumkan hanya satu hal: Bawa sendok.
Anak-anak diminta membawa sendok dan kepatuhan untuk menelan.
Saya berpesan, “Kalau makanannya basi, jangan dimakan ya, Nak.”
Anak saya balik bertanya, “Basi itu seperti apa, Ma?”
Di hari lain ia bercerita, “Tadi nasinya keras, sayurnya enggak berasa.”
Saya menenangkan, “Kalau begitu dan kamu tidak suka, jangan dimakan.”
Ia menjawab pelan, “Mana berani, Ma. Kami direkam video oleh guru.”
Saya tidak menyalahkan guru sebab mereka bisa jadi bekerja dalam tekanan dan keterbatasan informasi. Namun merekam anak saat makan tanpa persetujuan yang jelas dan ruang penolakan, membuat mulut terasa asing bagi makanan sendiri.
Saya mengapresiasi sekolah kami. Kepala sekolah menjawab WA saya dengan penjelasan bahwa sampai hari ini tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Guru-guru tidak memaksa jika anak ragu, bahkan ikut mencicip jika aroma meragukan. Itu ikhtiar perlindungan di ujung hilir.
Namun agar anak tenang, orang tua butuh dua hal sederhana, yakni ruang aman untuk menolak di momen nyata dan informasi singkat sebelum jam makan. Pada usia SMP, keputusan menelan bukan cuma urusan gizi tapi soal harga diri, otonomi tubuh, dan rasa percaya.
Baca juga: Kalau Perempuan Turun ke Jalan, Artinya MBG Memang Sudah Gawat
Biaya Kecemasan
Di rumah, kecemasan punya biaya, hanya saja kita tak menuliskannya di tabel anggaran. Jam kerja orang tua yang hilang untuk mengantar anak ke puskesmas. Ongkos transportasi mendadak, obat yang harus dibeli, paket data untuk mencari info darurat. Belum lagi jam belajar yang terpotong, hari absen yang menumpuk. Waktu emosional yang terkuras lantaran menenangkan anak yang takut makan lagi, sekaligus meyakinkan diri sendiri bahwa besok akan baik-baik saja.
Malam-malam kami sepi tapi gelisah. Kami orang tua membuka grup WA, mengecek ulang bekal, mengendus sisa bau di omprang, berharap tidak ada tanda yang mencurigakan.
Saya teringat Katrine Marçal, penulis buku “Who Cooked Adam Smith’s Dinner?” (2012) yang mengembalikan dapur ke dalam hitungan. Di saat negara rajin menghitung yang tampak, seperti porsi dan persentase, tetapi mereka menggratiskan kerja perawatan, ketakutan, dan kepercayaan. Kita bilang semua baik-baik saja karena tabelnya rapi tapi rasa takut tidak ikut dijumlahkan.
Sesungguhnya, kekhawatiran orang tua bukan fiksi media sosial. Di Serdang Bedagai, kampung kami, meski bukan sekolah anak saya, rumah-rumah menahan napas, seperti menunggu giliran kabar buruk. Di grup warga, pesan pendek berkelebat, “Sudah terjadi di tempat kita.” “Sekolah anakmu bagaimana?”
Baca juga: Makan Bergizi Gratis, Janji Manis Realitas Amis
Setop MBG
Sebagai ibu, kewenangan saya sederhana, yaitu memilih apa yang masuk ke mulut anak saya. Hari ini saya memilih bekal dari rumah yang lebih sederhana, sehat, dan aman. Dari pilihan kecil itu, saya menuntut pemerintah: Hentikan MBG. Audit, perbaiki, dan pastikan standar keselamatan baru jalankan lagi.
Kalau negara sungguh berpihak pada anak, jangan jadikan sekolah lokasi uji menu. Hentikan dulu, perbaiki dulu. Kami para orang tua menuntut transparansi 4W1H untuk orang tua (siapa, di mana, apa, kapan & bagaimana), dapur yang dapat diaudit, jalur pengaduan yang bekerja, daftar bahan dan sumbernya yang diberitahukan paling lambat sehari sebelumnya, serta hak anak untuk menolak tanpa dipermalukan. Gizi bisa diajarkan tapi percaya tumbuh ketika yang takut didengarkan, bukan ditegur, apalagi direkam.
Anak saya kini paham “basi” versi kamus. Yang belum beres adalah “aman” versi kami di rumah. Setiap menerima omprang, anak saya bertanya, “Boleh dimakan enggak, Ma?”
Duh Gusti, rasa aman seharusnya bukan undian harian. Itu hak anak dan tugas negara.
Peralatan bisa dibeli. SOP bisa ditulis. Sisanya satu pekerjaan negara: Jadikan rasa aman sebagai standar yang diaudit dan dianggarkan, bukan harapan orang tua. Sampai itu nyata, hentikan MBG. Anak kami bukan bahan uji menu.